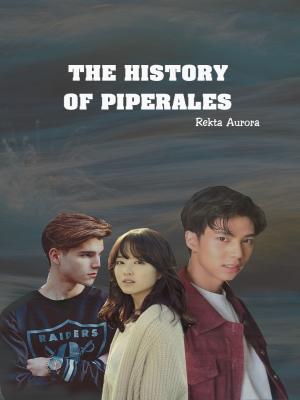Mia duduk di kokpit jet eksperimental dengan harness lima titik melingkari tubuhnya. Di sekelilingnya, panel kontrol berkedip warna-warni dalam irama yang presisi. Angka-angka digital bergerak cepat—menunjukkan kecepatan, tekanan kabin, dan sudut serang. Semuanya tampak sama persis seperti video kanal Youtube aerodinamika yang selalu ia tonton setiap hari minggu. Tapi kini semua itu hidup. Nyata.
Suara mesin menderu berat dari belakang, getarannya menjalar sampai ke punggung. Mia kembali mengulas senyum lebar. Bahagia. Bahkan ketika helm penerbangan yang terasa kebesaran itu membatasi pandangannya, ia masih bisa melihat ujung sayap pesawat yang berkilat diterpa cahaya matahari.
Bau logam hangat dan sedikit jejak kabel terbakar menguar di udara—bukan aroma yang menyenangkan, tapi bagi Mia, ini wangi kemenangan. Ia menatap layar yang menunjukkan grafik suhu nozzle dan distribusi tekanan pada sayap.
“Jet siap take off dalam sepuluh detik,” suara sistem otomatis terdengar. Mia menggenggam tuas kendali dengan kedua tangan. Tangannya gemetar sedikit karena antusias yang memuncak. Dan ketika mesin mendorong tubuhnya ke belakang, Samar-samar Mia mendengar sesuatu yang familiar—suara sumbang, datar, dan berulang-ulang.
“Roti... Roti... Roti hangat! Dua ribuan, eeeenak!”
Mia terkejut. Dunia jet itu buyar dalam sekejap, dan ia terlonjak bangun. Ah, mimpi rupanya.
Langit-langit kamarnya yang gelap terlihat lagi, bersama bintang-bintang glow in the dark yang menyala redup. Suara napasnya masih memburu. Ia mengucek mata, lalu menatap jam dinding.
Pukul 06.32 pagi.
“YA AMPUN!” pekiknya.
Mia melompat turun dari tempat tidur. Kokpit jet eksperimental mendadak tergantikan oleh realitas yang jauh lebih mendesak: ia kesiangan.
***
Pukul 07.25 pagi, Mia baru saja turun dari bis yang sesak oleh pedagang pasar. Ia terlambat. Dengan langkah cepat dan terburu-buru ia melewati gang kecil, jembatan, dan kebun pisang sebelum akhirnya sampai di halaman belakang sekolah. Apel pagi sebentar lagi selesai. Gerbang belakang terbuka. Seorang pria paruh baya memakai setelan PNS dengan peci hitam terlihat melewati gerbang tersebut sambil menengok ke arah kanan dan kiri.
Mia yang menyadari ada Pak Seto sedang berpatroli segera menyembunyikan diri di belakang rumpun pohon pisang. Ternyata dia tidak sendiri. Di rumpun pisang sebelahnya ada dua siswa lain yang sedang menyantap roti hangat—terlihat dari kepulan asap tipis yang keluar setelah digigit. Mia mengenali mereka sebagai anak kelas tetangga. Namanya Fahri dan Sofyan.
“Apa?” tutur Fahri tanpa suara, hanya gerakan mulut saja dengan tatapan tajam. Tidak lupa juga ia memperingatkan Mia untuk tidak melaporkan mereka. Mia cuma mengangguk. Lagi pula siapa yang mau mengadu? Yang ada dia juga akan kena.
Terdengar suara salam terakhir dari sepiker sekolah, tanda apel telah selesai. Mia segera melangkahkan kaki melewati gerbang belakang, berbelok ke kantin, dan akhirnya sampai ke perpustakaan. Untungnya Bu Hera—penjaga perpustakaan—belum ada di kursinya. Mia melipat tas punggungnya dan mengendap masuk ke dalam perpustakaan. Tujuannya adalah rak buku mata pelajaran bahasa arab.
Rencana menyelinapnya terselamatkan dengan jadwal piket ambil buku. Bel tanda jam pelajaran pertama berbunyi. Sebelum masuk kelas, terlebih dahulu ia menyembunyikan tasnya di sudut ruangan dekat tumpukan koran-koran lama—tempat teraman karena jarang ada yang ke sana sebelum jam istirahat.
Sekarang ini adalah pelajaran Bahasa Arab yang diampu Bu Asih. Guru tua legendaris itu tidak akan menginterogasi terlalu dalam, kalau pun ketahuan hukumannya hanya mengulang bacaan surah Ad-duha sebanyak lima kali. Itu mudah. Dia sudah hafal diluar kepala. Mia mulai tenang, langkahnya ringan setelah melewati kantor guru dan mendapati sosok Bu Asih masih duduk di kursinya sambil menyesap segelas teh.
Langkah Mia memelan begitu mendekati ruang kelas 10 IPA-1. Ada yang aneh, pintu kelasnya tertutup rapat. Apa dia salah lihat? Ah, tidak mungkin. Pasti ini cuma taktik teman-temannya agar tidak di tegur Pak Seto—Guru BK.
Ceklek!
Begitu knop pintu berputar, daun pintu bercat coklat itu terbuka, nampaklah seorang perempuan seperempat abad dengan kerudung hitam dan lipstik merah menyala sudah berdiri di depan. Bu Kartika. Mia menelan ludah. Prediksinya meleset jauh. Semua pasang mata memandang ke arahnya, membuat nyali Mia menciut seketika.
“Kamuflase yang klasik, Islamia,” sarkasmenya begitu melihat sampul buku paket yang di dekap Mia.
Mia mengulum bibir. “Ma... maaf, Bu. Boleh masuk?” tanyanya dengan nada gugup.
Bu Kartika tersenyum, namun dimata Mia, senyum itu lebih mirip seringai. Guru dengan julukan killer itu sangat tidak suka dengan keterlambatan. Tepat waktu adalah visinya.
“Untuk kali ini saya maafkan karena waktu kita tidak banyak, silakan duduk, “ perintahnya.
Mia menghela napas panjang, masih dengan tangan gemetar ia mengucapkan terima kasih dan menyalami Bu Kartika sebelum menghampiri tempat duduknya yang berada di barisan tengah. Kali ini dirinya bisa lolos, tapi entah dengan hari esok. Dari yang Mia lihat, Bu Kartika sangat tidak toleran dengan siswa yang terlambat. Alasan klasik seperti tidak ada angkutan, macet, rumah jauh sangat tidak diterima. Sebab Beliau hafal alamat hampir semua murid kelas 10 IPA 1 sampai 5.
Mia menyikut Azro, teman sebangkunya, meminta penjelasan. Gadis berkacamata itu menuliskan jawabannya di sebuah note kecil yang memang khusus mereka gunakan untuk komunikasi ketika sedang ada guru yang mengajar.
“Pindah jam, Bu Kartika mau ada urusan.”
Belum selesai Mia membaca catatan itu, terdengar ketukan pelan di pintu kelas.
Semua kepala serempak menoleh. Bu Kartika yang sedang menyiapkan materi ciri-ciri teks eksplanasi menggunakan infografik, berhenti sejenak.
Pintu terbuka, memperlihatkan sosok wanita tinggi sedikit berisi dengan jilbab biru laut—Bu Yulia, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Satu atau biasa disingkat MANSA.
“Permisi, Bu Kartika. Maaf menginterupsi sebentar,” ujarnya dengan suara tegas.
Di belakangnya berdiri seorang siswa laki-laki yang langsung menarik perhatian seluruh kelas. Seragam putih abu-abunya tampak rapi, bahkan setrikaannya masih melipit sempurna. Rambutnya hitam ikal, dipotong model undercut yang bersih di sisi kanan dan kiri. Kacamata bening membingkai mata monolidnya, dan sebuah tahi lalat kecil di batang hidung menambah kesan khas pada wajahnya yang tenang dan penuh percaya diri.
“Silakan, Bu,” sahut Bu Kartika.
Bu Yulia melangkah masuk dan berdiri di samping murid laki-laki tersebut. “Selamat pagi, perkenalkan ini Zaryn Al Ghazali. Dia ini pindahan dari SMAIT Jakarta. Kalian mungkin sudah dengar sedikit tentang Zaryn—tahun lalu dia memenangkan lomba esai nasional dan debat Bahasa Arab tingkat provinsi. Kami harap kalian bisa membantu Zaryn beradaptasi.”
Mia menyipitkan mata, memindai penampilan siswa baru itu dari atas ke bawah. Sejujurnya, sedikit cupu. Tapi tidak untuk Azro. Gadis itu bersandar ke bahu Mia, kemudian berbisik sambil tersenyum, “Ganteng ya? Lihat deh senyumnya.”
“Cupu,” sahut Mia dengan nada ketus.
Azro memanyunkan bibir, tak terima. “Kamu tuh pasti ngomong gitu karena tadi denger Bu Kepsek nyebut dia pernah menang lomba debat sama esai Bahasa Arab, kan? Iri ya? Atau kamu takut?"
Mia mengangkat bahu. Tidak peduli. Bagi Mia, kedatangan Zaryn seperti gelombang interferensi destruktif—alih-alih membawa semangat baru, malah justru gangguan yang membuat posisinya sebagai peringkat satu terancam.


 manusiatepisungai
manusiatepisungai