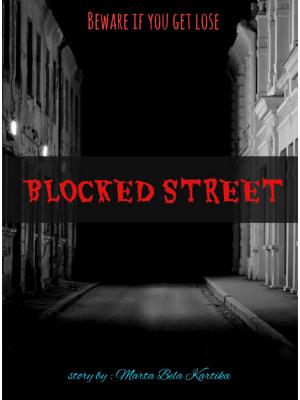Pukul enam pagi, rumah Harry yang tampak sunyi dari luar menyimpan badai di dalamnya. Suara piring pecah baru saja terdengar dari dapur, disusul makian kasar yang menusuk pagi.
“Berapa kali Papa bilang? Kalau potongnya miring begini, mana enak dilihat!” Tiyo membentak sambil menunjuk sepotong wortel yang tergeletak di talenan, terpotong runcing dan tak beraturan. Wajahnya memerah, napasnya berat seperti bom yang tinggal meledak.
Harry berdiri kaku di depannya, menahan marah dan takut dalam satu tarikan napas. “Maaf, Pa ... aku—”
Tepukan keras mendarat di sisi wajah Harry sebelum ia selesai bicara. “Jangan alasan! Kamu pikir hidup bisa dijalanin cuma pakai maaf? Mau kamu jadi apa nanti, hah? Kayak ibumu yang kerjanya cuma ngeluh?”
Harry memejamkan mata. Sudah terlalu sering ia mendengar kata-kata itu. Tentang ibunya yang sudah lama pergi karena tak tahan. Tentang dirinya yang, menurut Tiyo, terlalu lemah, terlalu pendiam, terlalu ... rusak.
“Aku cuma ... belum bisa rapi,” gumamnya.
“Belum bisa rapi, belum bisa bangun pagi, belum bisa lulus ikut kompetisi apapun! Kamu tuh gagal, Har! Anak laki-laki itu nggak cengeng! Kamu tahu kenapa Maureen itu ...!”
Harry menoleh cepat, penuh kemarahan dan luka. “Jangan bawa nama dia!”
Tiyo terdiam sesaat, seperti baru menyadari sesuatu. Namun, bukan rasa bersalah yang muncul di wajahnya, melainkan senyum miring penuh sinis. “Kau pikir dia istimewa? Dia cuma bikin kamu lemah!”
Seperti itu saja, Harry mengerti: tidak ada tempat aman, bahkan di dalam rumah sendiri.
Tiyo mengambil rokok dari saku dan menyalakannya, lalu meninggalkan dapur tanpa peduli sayatan kecil di jari Harry.
Pemuda itu menunduk, menggigit bibir sampai terasa darah. Ada bekas luka lama di pelipisnya yang belum sepenuhnya pudar.
Harry berdiri di sana dalam sunyi, hanya ditemani suara kipas tua dan aroma ampas kopi basi. Tangannya bergetar, tetapi bukan karena takut. Bukan juga karena sakit. Namun, karena sebuah kesadaran lama: dirinya memang selalu diposisikan sebagai kesalahan.
Ia mengambil wortel lain dan mulai memotong lagi, lebih pelan. Lebih presisi.
ꕤꕤꕤ
Hari itu di sekolah, gosip mulai mengalir seperti aliran sungai yang tak terbendung.
“Katanya, Maureen punya hubungan rahasia sama seseorang ....”
“Iya, dan tau nggak? Dengar-dengar, dia suka diem-diem ketemuan sama cowok yang sekarang masih deket sama adiknya.”
“Siapa, sih? Jangan-jangan si Harry itu? Dia kan agak aneh.”
Maura menatap mereka dari kejauhan, telinganya menangkap potongan kalimat-kalimat itu. Ia meremas tali tasnya. Sejak Maureen meninggal dan berita soal buku harian itu bocor ke beberapa murid lewat “seseorang” yang tak bertanggung jawab, pandangan orang-orang mulai berubah. Namun, yang lebih aneh, semua gosip seolah-olah diarahkan ke satu nama, yaitu Harry.
"Katanya udah ada yang mulai diperiksa gara-gara buku harian Maureen..."
"Serius? Siapa?"
"Katanya si H itu Harry, temennya Maura dari SMP. Cuma itu doang clue-nya."
"Jadi ... Maureen pacaran sama dia? Dan dia yang bikin Maureen ...?"
Gosip menyebar seperti api membakar tumpukan kering. Nama Harry mencuat begitu cepat, bahkan saat belum ada yang tahu kebenarannya.
Nana hanya diam saat teman-teman sekelasnya mulai berbisik. Ia pernah melihat Maura dan Harry ngobrol dengan canggung di taman sekolah waktu SMP. Mungkin ada benarnya.
Seorang siswi dari kelas sebelah menghampirinya dengan ekspresi penasaran bercampur simpati pura-pura.
"Maura! Maaf, ya, tapi ... soal Harry itu bener?"
Maura mengernyit. "Maksudmu?"
"Ya itu. Dia yang ada ... di buku harian Maureen, kan? Yang namanya H itu?"
Jantung Maura mencelos.
ꕤꕤꕤ
Di lorong belakang kelas, Maura duduk bersandar pada dinding. Buku harian Maureen tergenggam erat dalam tasnya. Ia tahu betul siapa “H” dalam buku itu. Namun, juga tahu bahwa Maureen menulis inisial lain—A.D.—untuk sosok yang lebih menyakitinya.
Harry memang bagian dari masa lalu mereka, tetapi ia bukan alasan di balik kematian Maureen.
Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari Harry:
“Ada gosip aneh. Semua orang lihat ke arahku hari ini. Maura ... kamu tahu kenapa?”
Maura tak bisa langsung membalas. Rasa bersalah dan amarah berkecamuk bersamaan. Ia tahu ini salah satu rekayasa. Namun, siapa yang menyebarkannya?
Ia membuka kembali lembaran terakhir buku harian itu, yang kini mulai terlihat rusak di bagian pinggirnya. Di sana, seperti bisikan, Maureen pernah menulis:
“Kadang aku merasa ... tak ada yang benar-benar tulus menyayangi. Bahkan kamu, H, hanya tahu bayanganku, bukan aku yang sebenarnya.”
Maura memejamkan mata. Ia harus bicara dengan Harry. Ia harus tahu seberapa besar luka yang telah terbuka karena diamnya terlalu lama. Maura tak tahu harus percaya siapa. Namun, satu hal yang pasti, semuanya semakin kabur, dan kebenaran justru semakin tertutup oleh suara-suara yang terlalu banyak.
ꕤꕤꕤ
Di rumah, Seno mengetuk pintu kamar Maura. Ia berdiri diam di ambang pintu kamar, memandangi Maura yang masih memegangi halaman terbuka dengan mata yang tak berkedip.
“Maureen sering menggambar seperti itu, ya?” tanyanya pelan, seperti seseorang yang mencoba memanggil kenangan yang telah terkubur.
Maura mengangguk pelan, lalu menjawab, “Iya, tapi tidak semua orang bisa membaca maksudnya.”
Seno mendesah, lalu menatap lantai sejenak sebelum berkata, “Papa ... bukan ayah yang sempurna, Maura. Tapi sekarang Papa ingin tahu lebih banyak. Tentang apa yang kalian sembunyikan waktu itu. Tentang Maureen. Apa maksud dari semua ini?”
Maura memejamkan mata sejenak. Pertanyaan itu seperti pisau tumpul: tidak menyakitkan karena tajam, tetapi karena menekan luka yang belum pulih.
“Aku juga belum tahu, Pa,” katanya. “Tapi dia menyimpan sesuatu. Bukan cuma rasa sakit ... tapi semacam rencana. Atau sinyal. Langit Kedua itu bukan cuma gambar. Itu ... semacam pintu.”
Seno mengangguk pelan, walau wajahnya tetap menyiratkan kebingungan. “Kamu percaya semua ini akan menjawab kenapa Maureen pergi?”
Maura menoleh padanya. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia melihat mata ayahnya yang tak disembunyikan oleh pekerjaan dan tekanan. Hanya mata seorang lelaki yang kehilangan anak—dan takut kehilangan satu anak lagi.
“Aku harus percaya,” jawab Maura. “Karena kalau tidak, aku takut ... aku juga akan hilang seperti dia.”
Seno diam. Udara di antara mereka berat, seperti tertahan oleh semua hal yang tak sempat diucapkan.
“Kalau kamu butuh bantuan, ngomong ke Papa. Bukan cuma tentang gambar ini, tapi tentang apa pun yang kamu rasakan. Papa selalu ada di sini.”
Maura menunduk. “Terima kasih, Pa.”
Dalam keheningan itu, sebuah ikatan yang pernah longgar terasa menguat. Bukan karena semuanya jadi jelas, tetapi karena mereka mulai mengakui: kehilangan ini terlalu besar untuk dipikul sendiri.


 chococeanic
chococeanic