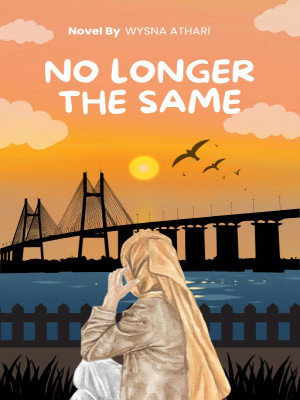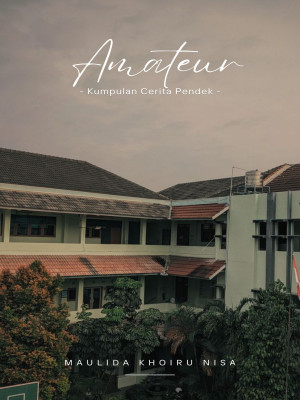Bab 21
Kejadian Aneh
Lala mengetuk ruangan praktik Dokter Krisna. Tidak ada jawaban. Apakah ruangannya kosong? Lala memutuskan untuk memutar handel pintu dan mencoba membukanya. Bisa. Ternyata, ruangan itu tidak dikunci. Dokter Krisna sedang duduk di belakang mejanya. Lala mendekat dan duduk di kursi kayu cokelat di depan meja Dokter Krisna.
Lala melihat dr. Krisna sedang mengetik sesuatu dengan cepat di komputernya. Lala memperhatikan jari-jari Dokter Krisna yang seperti ketukan musik rap itu. Lala bertanya-tanya dalam hati, “Sebenarnya, apa yang ia ketik? Apakah itu ada hubungannya denganku?”
Lala ingin melihat apa yang sedang dr. Krisna ketik, tetapi Lala tidak bisa. Layar komputer itu menghadap ke dr. Krisna yang duduk di seberang Lala. Lala hanya bisa melihat kabel-kabel yang menyembul dari belakang komputer, entah kabel apa saja. Sambil menahan debar jantungnya, Lala memberanikan diri bertanya, “Apa sebenarnya yang sedang Anda ketik itu, Dok?”
Dr. Krisna menghentikan jari-jemarinya yang berada pada keyboard. Ia menurunkan kacamatanya dan memandang ke arah Lala. Lala berharap ia akan mendapat jawaban dari dr. Krisna. Namun, dr. Krisna diam seribu bahasa.
“Apakah itu ada hubungannya dengan penyakit saya? Sudah ada penelitiannya kah? Apakah penyakit saya bisa disembuhkan? Apakah saya akan harus meminum obat seumur hidup?” tanya Lala lagi.
Lagi-lagi dr. Krisna diam seribu bahasa. Matanya seperti akan melotot keluar. Urat-urat berwarna kemerahan terlihat di bagian bola matanya yang berwarna putih. Lala berpikir, “Ini pasti karena aku tidak memberinya uang.”
Lala merogoh saku bajunya, lalu saku celananya. Kosong. Umpatnya, “Sial! Aku tidak mempunyai uang sepeser pun. Oh, di mana Mama? Aku harus meminta uang kepadanya.”
Lala memutuskan untuk keluar ruangan dan meninggalkan dr. Krisna meskipun sesi terapi belum berakhir. Mama sudah mendaftarkannya sejak jauh hari dan hari ini adalah jadwalnya. Lala mencari-cari Mama di luar ruangan, tetapi Lala tidak menemukan Mama di mana-mana.
Lala masuk dan keluar dari setiap ruangan yang berada di rumah sakit itu, termasuk kamar mandi. Mama tetap tidak ada. Bahkan bau parfumnya pun tidak tercium. Seorang petugas berseragam putih memarahinya ketika Lala masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan berkas-berkas.
Tiba-tiba, Mama sudah ada di belakang Lala sambil membawa bungkusan. Lala mengetahuinya ketika ia berbalik menghadap ke pagar rumah sakit.
“Hayo? Ternyata, kamu merindukan Mama juga kan? Kamu tidak bisa hidup tanpa Mama?” goda Mama. Sudut mulut kirinya terangkat sedikit.
“Mama dari mana?” tanya Lala, cemas. Sudut-sudut bibirnya tertarik ke bawah.
“Mama membeli makanan sebentar,” sahut Mama. Ia mengangkat bungkusan di tangannya tinggi-tinggi. Lalu, ia menurunkannya sedikit sehingga bungkusan itu berada tepat di depan hidung Lala. Lala menghirup baunya yang sedap. Tiba-tiba, ia merasa lapar.
“Ya sudah, Ma. Ayo kita pulang!” ajak Lala.
“Sebentar. Dokter tidak memberimu obat?” tanya Mama. Lala hanya menggeleng. Ia malas berkata-kata lagi. Ia tak ingin menceritakan kejadian yang dialaminya barusan di ruang dokter kepada Mama.
“Tidak bisa begitu. Setidaknya, kamu harus mendapatkan resep yang harus ditebus,” tegas Mama. Ia tergopoh-gopoh ke ruang dokter seraya melemparkan bungkusan makanan ke dada Lala. Beruntung, Lala bisa menangkap bungkusan itu sehingga isinya tidak berhamburan ke mana-mana.
“Lihat! Mama tidak seperti kamu. Mama berhasil mendapatkan resep obat. Ayo mengantri di apotek.” Mama bangga.
“Jelas saja. Mama kan punya uang,” batin Lala.
Mama dan Lala menuju ke apotek. Setelah menyerahkan resep kepada petugas farmasi, Mama mengajak Lala duduk di bangku kayu coklat panjang. Di sebelah Lala, sudah duduk seorang wanita berambut cepat dengan lipstik merah menyala.
“Siapa yang sakit, Mbak?” Mama memulai pembicaraan.
“Adik saya,” kata mbak itu.
“Mbak sedang mengambilkan obat untuknya?” tanya Mama lagi.
“Iya,” sahutnya.
Lala mengeluarkan novelnya dari tas hitam besarnya dan disodorkannya novel itu kepada mbak itu. Mata mbak itu berbinar dan tanggapnya, “Ini dikasihkan ke saya? Gratis?”
Lala menggeleng. Lalu, ia berkata, “Saya menjualnya.”
Lala tidak tega memberikan novel itu secara gratis karena ia sudah susah payah menulisnya. Lagipula, uang untuk membeli laptop, dan membayar listrik serta kuota belum balik modal. Tambahan lagi, ia harus membayar biaya berobat yang saat itu belum dikover BPJS.
Mbak itu terlihat kecewa. Ia mengembalikan novel itu kepada Lala seraya berkata, “Saya tidak telaten membaca. Ini tidak bisa dibaca sekali duduk.”
“Bisa, karena novel ini terbagi dalam bab-bab. Harganya juga murah,” bujuk Lala.
“Tidak. Tidak bisa.” Mbak itu bersikeras.
Lala menyerah. Ia memasukkan kembali novelnya ke dalam tas. Toh, ia sudah mendapatkan royalty meskipun hanya sepuluh persen. Ia berpikir, “Mengapa berjualan buku lebih susah ketimbang berjualan makanan? Bukankah buku juga berguna? Makanan memang bisa mengandung nutrisi untuk tubuh, tetapi bukankah buku adalah nutrisi untuk otak?”
Lala teringat kepada orang-orang yang berkata kepadanya ketika ia menawari mereka buku, “Hobi saya makan, bukan membaca. Makanan penting, tetapi buku tidak penting. Tidak makan bisa mati, tetapi tidak membaca tidak akan mati.”
Lala teringat kepada neneknya yang tidak pikun karena hobi membaca. Ia bertanya dalam hati, “Benarkah membaca itu tidak penting?”
“Ayo, La! Kita pulang,” ajak Mama.
“Sudah dapat obatnya, Ma?” tanya Lala, heran. Ia tidak menyadari ketika Mama beranjak dari sisinya dan mengambil obat itu.
“Kamu ini. Dari tadi melamun saja,” gerutu Mama.
Mama berlalu menuju ke pemberhentian bus. Lala mengikutinya dari belakang. Mereka segera naik bus ketika bus yang menuju ke arah rumah mereka datang.
Tak disangka, seorang pria yang merupakan pasien rawat jalan rumah sakit tadi ikut naik ke dalam bus bersama dengan seorang ibu tua berkerudung. Pasien itu duduk di sebelah Lala dan mengajaknya bicara. Katanya, “Aku ini sakit, tapi otakku masih jalan. Aku suka membuka internet dan website. Pekerjaanku adalah membenarkan apa saja yang salah di internet dan website itu. Aku juga mempunyai website pribadi. Ini alamatnya.”
Pria berambut keriting, bertubuh gempal, dan mengenakan kaos oblong lusuh itu menyodorkan secarik kertas yang berisi kode-kode. Lala menyimpannya ke dalam tasnya. Mungkin, pada suatu waktu, ia akan membutuhkannya.
Ibunya bercerita, “Anak saya ini insomnia. Kalau sudah bekerja, ia tidak ingat tidur. Saya tidak tega membangunkannya setiap kali ia tertidur tidak peduli kapan pun. Tidurnya sangat jarang. Saya jadi berempati pada orang yang kena insomnia juga.”
Lala juga sering tidak bisa tidur, tetapi ia lebih memilih untuk diam saja. Ia takut disuruh meminum obat tidur. Ia tidak menyukainya. Lagipula, ide-ide selalu datang berhamburan saat malam di mana ia tidak bisa tidur.
Akhirnya, Mama mengajak Lala turun dari bus. Celetuk Lala, “Ma, aku lupa menawarkan novel kepada orang itu.”
“Tidak apa-apa,” timpal Mama.


 juliartidewi
juliartidewi