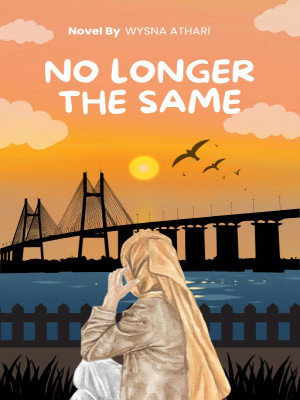Peringkat antar IPS dan IPA tentu dibedakan. Selama lima semester ini, Phiko baru menyadari, bahwa tiga orang tertinggi tidak pernah berubah. Phiko, Bela, Mahen. Bahkan Phiko baru sadar bahwa Mahen, si anak band yang sempat disukai kakaknya itu merupakan salah satu dari orang terpintar jurusan IPS. Phiko mengobrak-abrik dokumen yang dimilikinya. Phiko menemukan sebuah map berisi sertifikat. Mulai dari sertifikat peserta lomba, piagam penghargaan, hingga kejuaraan. Terselip di sana lembaran foto.
Setiap semester, sekolah akan mengadakan acara kecil yang bertujuan untuk mengumumkan siswa-siswa terbaik. Phiko memiliki empat cetakan foto dari masing-masing semester. Berisi tiga murid terbaik IPS dan tiga murid terbaik IPA, mereka sama-sama menunjukkan piagam penghargaan.
Sekali lagi, Phiko tekejut, sebab Vino berada di tiga murid terbaik jurusan IPA. Hanya saja dari keempat foto tersebut, Vino selalu berganti-ganti posisi—menandakan dirinya tidak konsisten dalam peringkat. Berbeda dengan jurusan IPS yang empat semester itu dalam posisi yang sama..
“Gak hidup kali lo waktu itu,” sindir Vino, saat Phiko menyampaikan terkesimanya kepada Vino. Meski setiap tugas Phiko yang kerjakan, tapi Vino ternyata pintar sampai bisa menduduki peringkat terbaik.
“Padahal, di foto itu kita satu panggung. Kenapa gue gak sadar ya?” Phiko menggeleng tak percaya. Ia menjajarkan keempat foto di atas mejanya. “Lo beneran pinter, No?”
Vino mendelik. “Lo beneran mati, Phi.” Lantas Vino menghadapkan tubuh ke meja belajarnya.
Berdebu pula meja belajar ini. Vino
membersihkannya. Vino hanya memakainya ketika mendekati ujian. Ia berjuang untuk nilainya pada saat ujian saja. Selebihnya, tugas-tugasnya, ia akan limpahkan kepada Phiko. Lagipula, anak itu juga mau-mau saja. Sekarang, Vino sedang berhadapan dengan meja belajar, tandanya ujian untuk semester lima sudah di depan mata.
Biasanya Phiko gila-gilaan membuka buku, internet tentang pelajaran, dan membeli buku kumpulan latihan soal dari Bapak atau tetangga toko Bapak. Namun, kali ini Phiko justru sibuk membuka dokumen yang sekiranya akan memberi petunjuk siapa yang hendak melukai keluarganya.
“Kalau Finna, dia masuk ranking gak, No?”
“Wah, lo bener-bener mati, sih, Phi. Waktu acara semester, sebenernya apa yang ada di pikiran lo, hah? Guru nyebutin sepuluh besar anak terbaik dari IPA sama IPS loh.”
“Gue serius, No.”
“Gue juga!”
Phiko memajukan mulutnya kesal. Ia mempertipis jarak kursi yang tengah didudukinya dengan meja, menatap kagum terhadap foto yang ada di tangannya.
“Finna ada di urutan empat. Selalu di urutan empat.”
Phiko membulatkan mulutnya sambil mengangguk-angguk. Gadis itu juga pintar.
“Daripada gue, kalian ternyata lebih hebat. Selama ini, kalian kerja, tapi masih bisa ngimbangin waktu buat belajar. Ya, walaupun lo gak pertahanin ranking lo, tapi lo selalu bertahan di tiga besar. Gue kagum.”
Vino tersenyum sombong. “Jelaslah.”
“Anak-anak Bapak ternyata pinter semua, pasti Bapak bangga sama kita. Pasti Ibun juga bangga sama kita.”
Vino mengangguk-angguk. “Pasti, pasti.”
“Kira-kira semester ini gue bisa jadi satu terbaik lagi gak ya? Nilai-nilai gue banyak yang hancur. Tapi kalau menurun, sedangkan Finna yang naik, gue bakal tetep terima kok.”
Vino sudah selesai membersihkan meja belajar. Ia mengambil tablet yang teronggok di dalam laci selama berbulan-bulan—hanya dipakai untuk belajar. Lantas memulai belajarnya.
“Tapi, kalau gue gak ada di panggung nanti, kalian berdua jangan malu, ya?”
“Iya, bawel! Udah, sekarang belajar aja! Udah mau jam sembilan juga. Kalau lo ngomong terus, kapan belajarnya?”
Phiko tersentak saat Vino memarahinya. Ia paham sekarang. Mungkinkah selama ini, beginilah rasanya dimarahi oleh orang yang sedang fokus belajar? Phiko selalu melakukannya kepada Vino dan Finna. Aneh, jadi terbalik begini.
Vino memakai headphone di kepala. Membuka buku catatan kosong, menyalin apa yang ia tangkap melalui tayangan video menggunakan tangan kirinya. Vino resmi menjadi manusia kidal. Makan, minum, menulis, dan beraktivitas segalamnya menggunakan tangan kiri. Tulisannya memang belum sebagus itu, tapi cukup jelas terbaca oleh dirinya sendiri.
Saat Phiko hendak terlarut ke dalam materi, sebuah tepukan lembut mendarat di bahunya. Beruntung Phiko tidak terkejut. Finna berdiri di belakangnya sambil menatap sendu, menunjukkan layar ponselnya.
“Bantuin aku. Ini gak ada subtitle-nya. Jadi aku bingung dia ngomong apa. Video-video lain juga subtitle-nya ngawur.”
Phiko memerhatikan video yang sedang disaksikan Finna. Materi sejarah. Sedangkan yang akan Phiko pelajari sekarang adalah matematika. Meskipun mereka sekelas, tapi keduanya memiliki fokus mata pelajaran yang berbeda. Namun, Phiko bersenang hati menolong kakak tulinya.
“Ambil kursi,” kata Phiko dengan bahasa isyarat. Finna langsung bertepuk tangan kegirangan.
Mengidap gerd sekaligus autoimun secara bersamaan sangatlah tidak mudah untuk Phiko. Ia tak bisa lagi begadang suntuk untuk memperdalam materi. Alhasil, ia terpaksa membatasi waktu belajarnya sampai jam sepuluh saja, sementara kakak-kakaknya masih berkutik dengan buku pelajaran. Walau sudah membatasi waktu, makan dengan teratur, dan berolahraga ringan, bukan berarti penyakit itu tidak menyakitinya.
Hari ini adalah hari ketiga Phiko menginap di rumah sakit, dan esok adalah hari pertama ujian. Bagaimana caranya berakting sembuh supaya dokter bisa memulangkan dirinya hari ini? Phiko menatap nanar ke arah jendela kamar rawat.
Ruangan ini sepi, sunyi. Hanya ada suara dari pasien sebelahnya di balik tirai yang sedang bermain ponsel, menggulir media sosial. Keluarga Phiko mungkin sedang dilanda kesibukan. Bentar lagi tahun baru, banyak orang membutuhkan daging sapi, maka Bapak sedang rajin-rajinnya mengurus ternak. Bapak sudah lebih sukses dan banyak uang sekarang, ia bahkan merekrut pegawai untuk mengurusi kandangnya. Sapi-sapi juga makin lama makin banyak, ada pula yang berhasil berkembang biak di kandang itu. Kakak-kakaknya tak lagi memikirkan pekerjaan. Mereka tertarik untuk kuliah saat Phiko tak henti-henti memuji kepintaran mereka—yang bahkan baru Phiko sadari sekarang. Maka mereka lebih fokus untuk belajar sampai mengikuti kelas tambahan. Tidak resmi, hanya sebuah perkumpulan pelajar di sekolahnya yang sama-sama berambisi.
Pintu kamar terbuka, menarik perhatian Phiko dari buku di tangannya.
“Permisi.”
Suara lembut itu, bukan suara Finna. Suara kakaknya lebih serak dan berat, tidak terkondisikan juga karena Finna tak dapat mendengar suaranya sendiri. Tak lain dan tak bukan, sudah pasti Bela.
Tebakan Phiko benar. Gadis berkacamata itu menyingkapkan tirai dan masuk ke bilik Phiko. Melempar senyuman kepada Phiko.
“Udah makan?” tanya Bela sebagai sapaan.
Phiko menutup buku, mengangguk pelan. “Tadi pagi, sebelum Bapak pulang.”
Bela tertunduk sambil tersenyum. Ia memeluk sebuah tas kecil di tangannya. Mungkin berisi makanan. Dan Bela agak kecewa karena Phiko sudah makan.
“Kamu bawa apa?”
Akhirnya Bela bersemangat lagi. Tunggu dulu, Phiko sudah mulai menaruh rasa kepada gadis itu, tapi masih tak berani mengungkapnya. Terlalu cepat, menurutnya. Namun, ia sudah mengkode, salah satunya mengubah gaya panggilan dengan aku-kamu. Padahal, kepada Finna saja masih gue-lo.
“Tadi, di kos aku sempet masak. Aku bawain buat kamu. Aku juga beli buah dari minimarket depan.” Senyuman Bela menurun. “Tapi, dimakannya nanti aja, takut kekenyangan.”
Phiko menggeleng lemah. Ia mencari tombol hidrolik untuk meninggikan sandaran brankarnya.
“Makanan tadi baru aja dimuntahin, sekarang perutku kosong lagi.”
Mata Bela membesar, antara senang sekaligus khawatir karena tubuh Phiko tidak bisa mencerna makanannya dengan baik.
“Kamu harus sembuh ya, Phi.” Bela menarik meja makan untuk pasien, meletakkan tas di atasnya.
“Masakanmu wangi, Bel.”
Pipi Bela bersemu merah. “Makasih. Dimakan, Phi. Aku buatnya–”
“Penuh cinta, ya?” Phiko mengambil sendok yang diberikan Bela.
Ujung mata Bela berkedut. Gombalan kuno, tapi ia menyembunyikan kegelian di hatinya itu dengan senyum manis. Mungkin, suatu hari Bela bisa menyarankan Phiko untuk berguru kepada seseorang perihal cinta, supaya tidak terlalu jamet. Sebab cinta yang alay selalu membuat hati Bela tergelitik.
Bela tak lagi tinggal di toko Bapak, tapi ia tetap bekerja di sana. Berkat penghasilannya, Bela bisa menyewa sebuah kamar kos yang terletak tak jauh dari pasar.
“Kamu kenapa nggak ikut Klub Belajar hari ini? Besok ujian lho, mereka juga lagi belajar di taman kota,” ujar Phiko, setelah berusaha menelan makanan di mulutnya. “Finna sama Vino ada di sana.”
Bela menggeleng pelan. Dirinya menarik kursi agar bisa duduk di dekat Phiko. Gadis itu lalu mengeluarkan buku dari dalam tas. “Aku mau belajar bareng kamu.”
Ada debar tak karuan di dada Phiko, tapi bukan karena penyakitnya kambuh. Inikah debaran cinta? Phiko tak tahu seperti apa bentuk cinta. Apakah cinta itu berbentuk? Phiko tidak pernah belajar perihal itu.
“Kamu hari ini pulang, kan?”
“Mungkin iya.”
“Nanti aku mau bantu dan anterin pulang.”
Phiko sedikit tersedak, dan Bela dengan sigap mengambilkan minum. “Nggak usah, buat apa anter aku pulang? Nanti Bapak bakal ke sini lagi, aku bakal pulang bareng Bapak sama kakak-kakakku.”
Senyuman Bela kembali memudar. Ah, Phiko baru saja salah bicara. Finna bilang, perasaan perempuan itu sensitif sekali, apalagi jika berbicara dengan seseorang yang mereka sukai. Phiko menepuk mulutnya.
“Maaf, Bel. Aku cuman, cuman takut kamu kelelahan. Kalau anterin aku, kamu pasti harus pergi lagi ke kosan kamu. Jangan sampai kamu malah sakit karena aku. Aku gak mau.”
Bela menggeleng, masih menyembunyikan wajah dari Phiko. “Aku nggak pernah merasa lelah kalau berkaitan sama kamu, Phi.”
Phiko menggigit bibir bawahnya. Finna juga sempat memperingati, jika perempuan itu keras kepala. Phiko menggeserkan meja makan, menyentuh kepala Bela. Lelaki itu juga menyelipkan helaian rambut Bela ke belakang telinganya.
“Jangan marah, Cantik.”
Bela hanya diam saja. Meski Phiko tahu, hati Bela berdegup cukup kencang, hampir terdengar di telinganya.
Sekali lagi, perempuan keras kepala. Sore itu, dokter memperbolehkan Phiko pulang. Dan Bela bersikukuh ikut mengantarnya pulang. Beruntung
Bapak meminjam mobil milik Pak RT, jadi si triplets ditambah seorang gadis bisa diangkut sekaligus dalam satu waktu.
“Bel, makan malam di sini aja. Pulangnya biar Bapak antar nanti malam,” saran Bapak begitu mereka tiba di rumah.
Bela menatap keempat orang di depannya bersamaan. “Memangnya ... tidak apa-apa?”
“Siapa yang larang?” Bapak mengulurkan tangannya. “Ayo, sini. Bantu Bapak memasak bersama Finna.”
Bela mengulum senyum di bibirnya. Mengangguk halus. Finna yang bisa membaca situasi, merangkul Bela, menariknya sampai ke dapur.
Suasana hangat membalut rumah itu sore ini. Bapak memasak ayam kecap, pergedel kentang dan sayur bayam.
Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun silam, kursi-kursi di meja makan berbahan kayu itu terisi penuh. Bapak memperbolehkan Bela duduk di kursi istrinya. Deretan makanan masakan Bapak, Finna dan Bela tersuguhkan. Wangi khas rempah dari gulai ayam, rolade asam manis, dan sambal menyeruak ke ruang makan. Raut wajah bahagia tak terhapus dari mereka semua, terutama Bela.
Semenjak papanya sakit, Bela tak pernah lagi tahu rasanya makan bersama keluarga. Jangankan makan yang enak, asal bisa makan nasi saja sudah cukup baginya. Untungnya, berkat usaha joki tugas, setiap hari dirinya bisa memberi makan kepada papanya.
“Dimakan, Bela,” ujar Bapak. Bapak menyadari Bela hanya terdiam sambil tersenyum menatapi si triplets.
Bela mengangguk segan, lantas mulai menyuapkan makanannya ke dalam mulut. Tak sadar air mata membasahi pipi tirusnya.
“Tadi, waktu makan, kenapa nangis?”
Pipi Bela bersemu saat lelaki yang tengah berjalan beriringan di sebelahnya ini bertanya. Phiko ternyata memerhatikan Bela selama makan malam.
“Aku ... cuman inget Papa, Phi. Dari kecil, aku nggak pernah ketemu Mama. Sewaktu besar, aku harus lihat Papa yang sakit kronis. Tapi, aku tadi bahagia bisa makan bareng keluargamu.”
Selesai makan tadi, Phiko berinisiatif mengantarkan Bela untuk pulang ke kosannya. Padahal Bapak sudah berniat mengantarkan, tapi Phiko bersikukuh. Lagipula Vino juga ikut, ia akan menjaga Phiko jikalau lelaki yang baru pulang dari rumah sakit itu kenapa-napa. Namun, sebelum pulang, Bela meminta ingin diantar ke rumahnya yang dulu. Tempat di mana Bela tumbuh dan berkembang sedari lahir. Rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan papan tipis. Karena rumahnya terletak di dalam gang—lebih sempit dari jalan menuju rumah Phiko—, Vino memilih menunggu bersama motornya di depan sana.
“Ibuku juga ternyata udah gak ada, Bel.”
Pandangan Bela tertarik. Ia sedikit terkejut.
“Ibuku yang kamu tau selingkuh itu, bukan ibuku. Tapi sahabat ibu kandungku. Ibu kandungku sakit, autoimun. Waktu melahirkan kami, ibuku pendarahan dan beliau meninggal. Ibu udah punya firasat, jadinya beliau ingin Bapak menikah dengan sahabatnya, supaya aku dan kakak-kakakku tidak kehilangan figur Ibu.”
Bela tentu saja tahu tentang kabar ini, kabar ibu Phiko selingkuh. Ia mengetahuinya dari Finna langsung saat awal-awal Bela penasaran tentang sosok seorang Phiko. Gadis berambut panjang yang kini diikat ekor kuda itu menatap wajah Phiko dari samping. Ah, Bela baru menyadari, pipi gembul Phiko kian memudar, tersisa rahangnya yang tegas. Sama seperti papanya.
“Kebohongan terbesar dunia kepadaku adalah menganggap wanita jahat itu adalah ibu kandungku,” ujar Phiko, disertai senyum menyeringai. Bodohnya ia tidak menyadari sedari awal tentang masalah ini. “Kalau kamu?”
Bela membesarkan mata saat Phiko menatapnya hingga pandangan mereka bertemu. Ia buru-bur mengalihkan wajah. Di depannya kini terlihat sebuah lahan kosong, bertimbun kayu dan beberapa sampah. Kedua tangan Bela mengepal secara tak sadar.
“Kebohongan terbesar dunia kepadaku ... mungkin, saat mengira kalau Papa bakal sembuh.”
Phiko menatap reruntuhan rumah itu dengan nanar. Entah mengapa hatinya ikut sakit melihat hal ini. Phiko bisa membayangkan jika dirinya berada di posisi Bela, tapi tak yakin akan sekuat itu. Bela memiliki surat tanahnya, Bela memiliki surat kepemilikan rumah itu. Bisa saja Bela menuntut para warga di sini kepada yang berwajib. Tapi, beginilah Indonesia. Bela bisa kalah dengan uang.
“Kalau udah lulus, aku mau masuk fakultas hukum, Phi. Aku mau nuntut orang-orang sini buat balikin tanah aku dan Papa.” Bela mengeluarkan sesuatu dari ranselnya. Seikat bunga. Ia letakkan bunga cantik tersebut di dekat reruntuhan rumah, seperti meninggalkan jejak kenangan masa kecilnya di tempat terakhir ia bersama keluarga.
Bela kembali berjalan mendekati Phiko. Di bawah rembukan yang terang, Bela termenung menatapi reruntuhan itu. Ingatannya dilempar kembali pada masa di mana ia baru pertama kali bisa melangkah, Papa pernah bercerita. Air mata menetesi pipi Bela. Suara tawa Papa menggema di telinganya. Bela mulai resah. Rasa rindu itu sungguh menyiksa.
Phiko menaikkan tangan, menyentuh punggung Bela. Ia mengusap pelan punggung bergetar itu, berharap akan tenang seiring waktu.
“Nanti kamu bisa beli tanah dan rumah yang lebih besar untuk ayahmu, Bel.”
Bela mengangguk-angguk. Ia menghapus air matanya dengan cepat, tidak enak pula harus menangis di depan orang yang disukai.
“Ayo, kita pulang, Phi,” ucapnya disertai senyum hangat.


 thisadciel
thisadciel