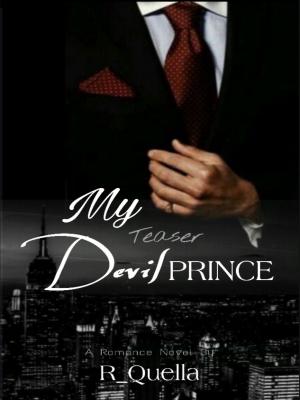Waktu berjalan cepat, tiba-tiba saja sudah tiga bulan berlalu sejak Shafa memutuskan akan mendekati Dirga. Ujian Tengah Semester Pertama juga sudah terlewati, rasanya cepat sekali. Ghea sendiri tidak terlalu memperhatikan perkembangan hubungan Dirga dan Shafa karena fokus mempersiapkan ujian. Tapi melihat Shafa selalu tersenyum sumringah setiap habis belajar bersama Dirga, ia yakin pendekannya keduanya berjalan lancar.
“Ghe.”
“Hmm?”
“Lo yakin gue nggak bakal ditolak?”
Ghea memutar kepalanya cepat ke arah Shafa di sebelahnya. Matanya melirik cewek itu dengan pandangan sinis. “Shaf … ini kayak bukan lo yang biasanya deh. Lagi kesurupan kunti depresi kah?”
“Iya,” timpal Shafa asal sambil nyengir.
Ghea lanyas menghadap Shafa dengan gerakan tidak sabar. “Sekarang gue tanya sekali lagi. Selama proses pedekate berkedom ‘belajar bareng’ kemarin apa ada masalah?” tanyanya dengan suara selirih mungkin. Mengingat mereka berada di kelas, sedang orang yang dibicarakan duduk tidak jauh dan sedang bercanda.
“Enggak.”
“Apa Dirga pernah marah atau nolak setiap lo yang minta diajarin?”
Shafa menggeleng.
“Yaudah, berarti nggak ada masalah.” Ghea menepuk bahu Shafa pelan.
“Itu kan soal belajar, Ghea.” Bahu Shafa melorot lemah. “Gue nggak pernah ngajak dia selain soal belajar. Jadi gue nggak yakin dia bakal mau diajak ngafe bareng. Pake alasan mau berterimakasih udah dibantu, tetep aja gue galau. Pasti bakal keliatan banget kalo gue suka sama dia.”
“Emang itu niatnya?” Ghea bertanya dengan nada hati-hati. “Nanti—“
“Bagaimana rasanya saudari Ghea?”
Ghea dan Shafa sontak tersentak berbarengan. Firzha, teman sekelasnya yang terkenal paling banyak tingkah itu tiba-tiba saja sudah berdiri di depannya sambil menyodorkan bulpen mendekati mulut Ghea. Berpura-pura itu adalah mic.
“Rasanya apa? Rasa roti?” Ghea bertanya bingung. “Gue sih tadi beli rasa selai sirsak.”
Firzha berdecak. Mengarahkan bulpen ke mulutnya sendiri sebelum berbicara. “Saudari Ghea ini sangat rendah hati sekali ya,” ujarnya. Lengkap dengan nada ala-ala MC kondang ibukota. Cowok itu kembali menyorkan mic dadakan ke Ghea.
“Apasih, Zha.” Ghea menepis bulpen dari depan mulutnya. Kenapa tiba-tiba ada wawancara dadakan gini? Tidak mau! Ghea tak dibayar untuk ini.
Tapi Firzha tidak menyerah. Cowok itu kembali mengarahkan mic jadi-jadian ke mulut Ghea. “Bagaimana rasanya menjadi juara satu paralel berturut-turut?” cetusnya dengan penekanan di setiap kata.
Nah, Ghea baru paham. “Rasanya juara satu … rasanya ya—“ Pertanyaan Firzha memunculkan gelombang kehebohan yang bersahutan. Semua mata memandangnya dengan rasa ingin tahu dan ekspektasi tinggi. Mungkin bertanya-tanya apa ada rahasia untuk meraihnya. Membuat ucapan Ghea semakin terbata. “… rasanya sama aja sih.”
“WIH KELASSSS!” seru Firzha yang disambut sorak sorai teman-teman sekelasnya. Sambil bertepuk tangan dan tertawa-tawa. Apa ia lucu?
Keringat dingin muncul di pelipis Ghea. Ia menelan ludah, berusaha menetralkan kegugupan dan bersikap sesantai mungkin. Sudut-sudut bibirnya tertarik paksa. “Rasanya jadi juara? Nggak ada rasanya lah. Tapi kalo lo tanya apa efek samping jadi juara? Kepala gue hampir botak karena stress,” guraunya.
Tapi jawaban Ghea sama sekali tidak memuaskan siapa pun. Pertanyaan demi pertanyaan muncul secara kontinu. Bertanya tentang tips dan trick Ghea, juga jadwal belajarnya. Menganggapnya merendah untuk meroket, sampai mengatai Ghea pelit ilmu. Sangking banyaknya pertanyaan, ia sampai bingung harus menjawab yang mana untuk mejelaskan kesalahpahaman. Tapi boro-boro bisa menjelaskan, telinganya saja mulai berdenging karena cecaran bertubi-tubi.
Cuma pukulan beruntun di papan tulis yang menghentikan suara-suara itu. Dandi, ketua kelasnya, menggeleng-gelengkan kepala tidak habis pikir melihat keributan yang terjadi. Pandangannya lantas terarah ke Ghea. "Ghea sama Dirga, kalian dipanggil ke ruang Kepala Sekolah. Sekarang," tegasnya.
Dirga dan Ghea kontan saling melempar pandang sebelum kembali menatap Dandi dengan bingung. Tidak hanya mereka berdua, tapi seluruh kelas pun ikut bingung.
Dahi Ghea mengernyit. “Ngapain?” mendengarnya bertanya, ia bisa melihat wajah Dandi juga sama bingungnya.
"Lah? Mana gue tau?" cowok itu balik bertanya sambil menaikturunkan bahunya cepat.
Ghea terdiam bingung sampai tidak sadar Dirga sudah bangkit dari tempat duduknya. Cewek itu masih berusaha mengingat-ngingat kesalahan apa yang ia perbuat dalam tiga bulan ini? Apa persaman masalahnya dengan Dirga, hingga mereka berdua dipanggil bersamaan?
“Wih, gue tau!” Mulut ember Firzha kembali memekik. Cowok itu mengangkat tangannya ke atas dengan sikap dramatis. Seolah pahlawan perang yang mau berpidato untuk mengobarkan semangat perjuangan. “Dirga kan sering olimpiade di sekolah lamanya tuh. Jadi bakal ada duo maut yang ngelibas anak-anak SMA Nusantara di olimpiade!”
Sorak-sorai teman sekelasnya langsung menyahuti seruan Firzha. Ghea semakin ingin bisa melipat tubuhnya seperti trenggiling dan menggelinding keluar dari kekacauan ini. Ia bersumpah ingin menambal mulut cowok itu dengan semen.
“Nggak mungkin lah,” cetus Shafa tiba-tiba. Cewek itu bangkit dan berkacak pinggang. “Ghea tuh paling males kalo disuruh ikut olim. Eh—bukan maksud gue ngeremehin lo, Ghe. Sumpah bukan!”
Ghea merutuk dalam hari, ucapan Shafa malah sama sekali nggak membantunya. Ia tersenyum kikuk. “Lo bener kok, Shaf. Gue emang males.”
“Iya. Ngapain pula ya?” Firzha melipat tangan di dada dan berpikir keras. Merasa hipotesanya tadi memang bermasalah. “Ghea kan rangking satu paralel terus. Mau masuk univ nggak pake tes juga bisa, cuma modal nilai rapot. Ngapain ribet ikut olimpiade lagi?”
“Betul! Pinter juga lo!” Shafa mengacungkan jempolnya.
“Mau apa pun alasannya.” Dirga sudah berada di depan Ghea dan mengetuk meja cewek itu pelan, dua kali. Ia lantas menatap Ghea sambil mengisyatkan dengan kepala untuk mereka segera keluar. “Kita tetep dipanggil kepala sekolah.”
Ghea menghela napas dan bangkit. Cewek itu langsung menyelonong keluar lebih dulu dan mengiraukan Dirga. Apa-apaan cowok itu tiba-tiba sok kenal dan ikut memerintahnya? Ditambah pakai cara mengetuk meja dua kali? Isyarat macam apa itu? Muak sekali rasanya, cowok itu selalu berusaha sok keren dari dulu dan ingin dicap dewasa.
“Gue ada salah sama lo?” tanya Dirga tiba-tiba, berjalan dengan jarak satu meter di belakang Ghea. Kedua tangannya di dalam saku.
Ghea menghela napas. Untung saja koridor memang sepi, jadi ia bisa membalas. “Emang lo ngerasa ada salah sama gue?”
“Enggak.”
“Yaudah. Clear, kan?”
Dahi Dirga berkerut samar. “Kenapa lo sensi mulu sama gue?”
“Gue PMS.”
“PMS kok tiga bulan. Itu PMS atau fermentasi eco-enzyme?”
“Lo nyamain gue sama sampah organik?” balas Ghea tanpa menoleh sedikit pun.
Dirga berdecak. “Nggak usah berusaha ngeles terus, Ghea. Akui kalo lo emang—“
“—benci sama lo?” Ghea tiba-tiba berbalik dan bersedekap. Ia memandang Dirga lurus-lurus. “Itukan yang mau lo denger? Gue benci sama lo. Sekarang gimana? Lo udah puas? Udah dapet validasinya?”
Dirga juga otomatis berhenti berjalan. “Lo nggak bisa diajak ngobrol.”
Ghea mendengkus setengah tertawa. “Oh, lo pengen ngobrol sama gue? Kenapa?” Cewek itu memiringkan kepalanya menunggu jawaban.
Cowok itu diam. Menatap Ghea balik dengan bibir terkatup rapat.
Meski sudah berpisah delapan tahun, Ghea selalu tahu kalau Dirga punya sifat menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Ia menolak berbohong bahkan sejak masih kecil. Sifat yang positif bukan? Jadi Ghea tahu, sikap diam cowok itu berarti jawaban. Ia sudah menebak kalau Dirga tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu tapi tetap melemparkannya. Secara tidak langsung Dirga memilih diam daripada membenarkan pertemanan mereka.
“Kita harus ke kepala sekolah,” kata Dirga sambil berjalan melewati Ghea. Suaranya berubah dingin.
Ghea tersenyum, memang ini tujuannya. Supaya Dirga sadar, bahwa kepeduliannya palsu, terlalu dipaksakan hanya untuk ingin menang berdebat darinya.
Ghea ingin Dirga mengakui itu meski cuma dalam hati.


 foraminao
foraminao