Dirga terengah-engah mencoba menyamakan langkahnya dengan Bumi dalam perjalanan menuju sekolah. Tubuh gempalnya bergetar setiap kali ia memaksa langkah lebih cepat.
“Bumi… tunggu kenapa sihh…” keluhnya, setengah menyeret napas.
Bumi hanya berjalan seperti biasa—tenang, tangan terlipat di dada, seolah tak mendengar penderitaan saudaranya.
“Heh… lo kemarin belum cerita. Lo ngomong apa aja sama Raka?” desak Dirga, napasnya memburu.
Tanpa melambat, Bumi menjawab datar, “Nggak ngomong apa-apa. Si sampah itu mau ngerekrut gue masuk gengnya. Gue tolak.”
Langkah Dirga goyah. Wajahnya berubah cemas. “Terus… reaksi dia gimana?”
Bumi menyunggingkan senyum kecil. “Dia bilang dia bakal bikin hidup gue di sekolah nggak tenang.”
Ia tertawa pelan setelah mengatakan itu—tawa ringan, seolah Raka baru saja menyampaikan lelucon paling absurd yang pernah ia dengar.
Tapi Dirga tidak ikut tertawa. Matanya justru semakin khawatir.
“Bumi, gue nanya sama Bagas. Selama ini Raka sering ngerjain anak-anak di sekolah, tapi dia nggak pernah dihukum.”
Bumi melirik sekilas. “Maksud lo?”
“Bokapnya polisi. Pangkatnya lumayan. Ibunya, orang Disdik. Guru-guru nggak ada yang berani negur. Soalnya terakhir kali ada guru yang negur, guru itu langsung dimutasi.”
Langkah Bumi tetap stabil, tapi rahangnya mengeras. Tatapannya lurus ke depan.
Dirga makin panik. “Makanya… lo jangan terlalu frontal sama dia. Inget, jangan bikin masalah—”
“Iya, gue tau,” potong Bumi, cepat dan tajam.
Mereka melewati pagar sekolah. Pagi itu lorong sekolah di lantai 1 masih sepi. Dari sana, mata mereka langsung tertuju ke arah lapangan.
Raka dan gengnya sedang mengerubungi seorang anak kelas X. Tas anak itu disobek terbuka, isinya dilempar ke kubangan air di pinggir lapangan. Tawa puas membahana. Anak itu berdiri kaku, matanya merah, tapi tak berani bergerak. Teman-temannya hanya melirik dari jauh—lalu cepat-cepat berpaling, pura-pura tak tahu.
Bumi tetap berjalan. Tak melambat, tak berhenti.
Saat melewati sisi lapangan, ia menoleh sekilas.
Tatapannya bertemu dengan Raka.
Dingin. Datar. Tak ada kemarahan. Tak ada rasa takut.
Raka menyipit. Rahangnya mengeras.
Tapi Bumi hanya memalingkan wajah, kembali menatap lurus ke depan, lalu terus berjalan—seolah di sana tak ada yang layak ia perhatikan.
***
Setelah pelajaran Geografi, jam pelajaran kedua hari itu adalah Matematika bersama Pak Erhan.
Belum juga guru itu masuk, suasana kelas X-E sudah diliputi ketegangan. Satu per satu murid menunduk di atas buku masing-masing, membaca ulang halaman rumus, berharap mereka tidak dipanggil ke depan kelas.
Bumi duduk tenang di kursinya. Tubuhnya sedikit membungkuk, matanya menyapu deretan angka dan simbol. Pensilnya bergerak cepat dan presisi, menyelesaikan soal demi soal tanpa ragu.
Di sebelahnya, Sophia tampak gelisah. Beberapa kali ia melirik ke arah Bumi—ragu, lalu buru-buru memalingkan wajah. Seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi urung setiap kali keraguan mencengkeramnya.
Bumi menyadari tatapan itu. Ia mengangkat kepala pelan, menatap Sophia dengan ekspresi datar. Mata hitamnya seperti kabut dingin—tak berbunyi, tak tergoyahkan.
Sophia terperanjat. Seperti anak kecil yang tertangkap basah mengintip, ia nyaris tersedak napasnya sendiri. Namun, dengan suara pelan dan jari sedikit gemetar, ia memberanikan diri menunjuk buku Bumi.
“Itu… salah. Harusnya begini,” bisiknya.
Ia mulai menjelaskan langkah-langkahnya. Suaranya kecil, tapi runtut. Bumi tidak menanggapi. Tatapannya hanya berpindah sejenak ke bukunya, lalu kembali ke wajah Sophia. Tidak ada komentar. Tidak ada anggukan.
Sunyi menggantung di antara mereka.
Sophia buru-buru menunduk, berpura-pura menulis sesuatu. Jemarinya tampak gugup, seolah berusaha menyembunyikan jantung yang terlalu keras berdetak.
Beberapa detik kemudian, suara gesekan halus terdengar. Bumi mengambil penghapus dan, tanpa sepatah kata pun, memperbaiki jawabannya—menyesuaikannya dengan penjelasan Sophia.
Lalu, pintu kelas berderit.
Pak Erhan masuk.
Seisi kelas langsung membeku. Tak ada satu pun yang bersuara. Bahkan napas pun terasa ditahan.
Langkah Pak Erhan terdengar berat saat ia menuju meja guru. Ia membuka beberapa buku, lalu mengambil sebatang kapur dan mulai menulis di papan tulis. Setiap goresannya membelah keheningan, meninggalkan serpihan putih di udara.
Tak ada tanya jawab. Hanya suara kapur yang menggores dan degup resah belasan dada remaja yang menunggu giliran dipanggil ke depan kelas.
Kemudian, ia membuka buku absen.
Suara kertas dibalik terdengar seperti ledakan kecil dalam sunyi.
Pak Erhan terus memanggil murid satu per satu, menyuruh mereka mengerjakan soal di depan kelas. Mereka yang selamat kembali ke tempat duduk dengan wajah lega. Mereka yang gagal, dipajang di depan kelas seperti seorang pesakitan yang hina.
Matanya terus menelusuri daftar nama. Hingga akhirnya—
“Bumi.”
Bumi mengedip pelan. Lalu bangkit dari kursi. Langkahnya tenang, bahunya santai, ekspresinya tak berubah.
Seisi kelas memperhatikannya dalam diam. Tegangan di udara seperti listrik sebelum badai.
Bumi berdiri di depan papan tulis.
Pak Erhan menuliskan soal menggunakan kapur. Fungsi dan pertidaksamaan. Tak terlihat rumit, tapi jebakannya halus.
“Kerjakan,” perintahnya.
Bumi menatap soal di papan. Mirip dengan soal yang ia kerjakan tadi. Ia mulai menulis. Kapur di tangannya bergerak mantap, meninggalkan jejak putih yang rapi. Metode yang ia pakai adalah versi Sophia. Sistematis. Efisien.
Selesai, ia meletakkan kapur dan berbalik menghadap kelas.
Pak Erhan memperhatikan papan tulis. Keningnya berkerut.
“Kenapa kamu pakai cara ini?”
“Lebih cepat,” jawab Bumi.
“Ini bukan yang ada di buku.”
“Ya.”
“Jadi kenapa kamu yakin cara kamu benar?”
Bumi tidak langsung menjawab. Ia menatap Pak Erhan. Dalam. Diam. Seolah sedang menelusuri sesuatu yang tak terlihat.
Pak Erhan melipat tangan. “Jawab.”
Bumi mengangkat bahu. “Soalnya sudah selesai. Jawabannya benar. Langkah-langkah saya logis. Apa ada yang salah, Pak?”
Pak Erhan diam. Matanya kembali ke papan. Tak ada reaksi.
Bumi terus mengamatinya. Kedipan yang terlalu cepat. Gerak kepala yang sedikit mundur. Tatapan bingung yang segera ditutupi.
Dia tidak tahu caranya.
Pak Erhan hanya tahu cara di buku. Ia menghafal. Bukan memahami.
Dan sekarang, ia tak punya jawaban.
“Kalau Bapak bersedia,” ucap Bumi, lembut tapi tajam, “bisa tunjukkan di mana letak salahnya?”
Pak Erhan menatapnya. Rahangnya mengencang.
Bumi tersenyum tipis. Senyuman yang datar… tapi menusuk.
“Saya enggak paham, Pak. Bisa tolong jelaskan? Itu tugas Bapak kan… Membuat saya paham?”
Hening.
Beberapa murid di bangku belakang menahan napas.
Lalu—
Kriiinggg.
Bel istirahat pertama pagi itu berbunyi. Panjang. Seperti gong pembebasan.
Pak Erhan menoleh cepat ke arah jam dinding, seolah mendapat pengampunan dari langit. Ia langsung menutup bukunya dengan suara tek yang terlalu keras.
“Duduk semuanya,” ucapnya singkat, nyaris tergesa.
Tangannya sibuk merapikan buku-buku yang bahkan belum benar-benar berantakan. Ia mengambil kapur, penghapus, dan absen seperti sedang menyelamatkan diri dari badai. Tatapannya sempat menyapu ke arah Bumi—sekilas saja. Lalu cepat-cepat berpaling, seperti seseorang yang takut ketahuan sedang berbohong.
Langkahnya menuju pintu nyaris terburu-buru. Tumit sepatunya terdengar berisik di lantai, tidak seperti biasanya yang tenang.
Ia tidak berkata apa-apa. Tidak menegur. Tidak menutup pelajaran.
Hanya pergi.
Menjauh dari Bumi.
Menghilang dari konfrontasi yang hampir saja memalukan dirinya di depan murid-murid.
Bumi mengangkat alis tipis. Ia berbalik, berjalan pelan kembali ke tempat duduknya. Langkahnya terdengar jelas di antara diam yang membatu.
Ia duduk. Menyilangkan tangan. Wajahnya tetap tenang.
Murid-murid lain mulai bergerak, tapi tak satu pun yang bicara. Mereka hanya menatap Bumi. Dengan ekspresi baru.
Takjub. Kagum. Mungkin juga takut.
Bumi tetap datar. Tapi di balik wajah tenangnya, ia tahu satu hal pasti:
Pak Erhan bukan ancaman.
Hanya bayangan besar yang kosong di dalam.
***
Di jam istirahat pertama, Bumi biasa berkeliling sekolah. Langkahnya tenang, matanya awas. Ia menyusuri lorong demi lorong, mengamati tiap sudut seperti sedang memetakan wilayah kekuasaannya. Dinding yang kusam, kamar mandi tersembunyi di balik tikungan—semuanya ia perhatikan. Tidak ada tempat yang terlalu remeh untuk luput dari catatannya.
Ketika bel masuk pelajaran hampir berbunyi dan pelajaran olahraga akan segera dimulai, Bumi berniat kembali ke kelas untuk berganti pakaian. Tapi sesuatu menarik perhatiannya.
Di ujung lorong lantai tiga, ia melihat sebuah pintu besi dengan teralis. Di baliknya, tampak tangga sempit yang menjulur ke atas. Pintu itu digembok.
Bumi mendekat, penasaran. Ia menyentuh gemboknya sebentar, lalu tanpa ragu mengambil peniti kecil yang ia sematkan di dada seragamnya—pengganti kancing yang hilang sejak pagi. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan lorong kosong.
Lalu mulai mengutak-atik gembok itu dengan tenang.
Klik.
Gembok terbuka.
Ia melepasnya, membuka pintu perlahan, dan menaiki anak tangga satu per satu. Tangga itu berujung pada sebuah pintu kayu. Bumi mendorongnya.
Angin menyambutnya segera. Rambutnya terangkat pelan. Ia tertegun.
Rooftop.
Tempat itu jelas sudah lama tak terjamah. Dipenuhi tumpukan kursi kayu tua, lemari-lemari lapuk, dan beberapa perabot berdebu yang ditinggalkan begitu saja. Tapi udara di sana... lebih bersih. Lebih hidup. Dan, yang paling penting, lebih sepi.
Bumi berjalan mendekati pagar pembatas. Dari sini, ia bisa melihat seluruh sekolah. Atap-atap merah, halaman tengah, dan siswa-siswa yang lalu lalang seperti semut dari kejauhan. Ia menarik napas panjang, menikmati sunyi dan ketinggian.
Tempat ini... akan menjadi teritorinya.
Setelah beberapa menit di atas, ia memutuskan untuk turun kembali. Ketika melintasi lorong menuju kelasnya, ia melihat anak-anak perempuan baru keluar dari kelas, berceloteh sambil membawa pakaian olahraga mereka menuju toilet.
Begitu masuk ke ruang kelas, aroma keringat menyergap. Anak-anak laki-laki mulai mengganti seragam putih abu-abu mereka dengan kaus olahraga sekolah. Obrolan ringan mengisi udara.
Bumi berjalan menuju mejanya dengan langkah tenang. Ia membuka tas, mencari pakaian olahraganya.
Dahinya mengernyit.
Tidak ada.
Ia meraba laci mejanya sampai ke dalam. Kosong.
Pakaian itu seharusnya ada. Ia yakin sudah memasukkannya tadi pagi di rumah.
Bumi menoleh perlahan. Matanya menyapu teman-temannya yang masih tertawa, masih bicara santai sambil menarik kaus masing-masing. Matanya menyipit tajam. Napasnya pelan, tapi berisi kecurigaan.
Seseorang berusaha mengerjainya.
Mereka sedang memulai permainan yang berbahaya.
Dan mereka akan menyesal melakukannya.


 dwyne
dwyne





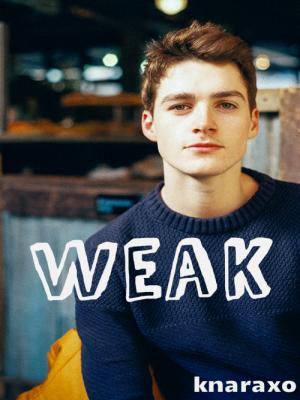





suka dengan bagaimana kamu ngebangun ketegangan di awal, adegan di toilet itu intens, tapi tetap terasa realistis. Dialog antar karakter juga hidup dan natural, terutama interaksi geng cewek yang penuh nostalgia masa SMA; kaset AADC dan obrolan ringan itu ngena banget.
Comment on chapter Pandangan Pertama