Pagi itu sebelum pelajaran dimulai, Dirga menatap lembaran kertas jadwal pelajaran yang baru saja dibagikan sekolah di hari pertama masuk. Ia menelusuri deretan mata pelajaran yang tertera, lalu berhenti pada baris hari ini. Matematika. Ia menghela napas panjang. Hari ini langsung ada dua mata pelajaran yang paling mampu membuat kepalanya berdenyut menanti: Matematika dan Fisika.
Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari koridor lantai tiga. Sejumlah siswa—mayoritas kelas X dan XI—yang tadi duduk santai di bangku panjang koridor, berhamburan kembali ke kelas masing-masing. Wajah mereka pucat dan panik, seperti baru saja melihat hantu.
Dirga refleks berdiri. Ia melirik ke luar jendela, mencoba mencari tahu apa yang membuat mereka setakut itu. Tidak ada apa pun di luar sana. Ia lalu menoleh ke arah Bagas yang tengah panik menyembunyikan tumpukan komik ke dalam plastik hitam, lalu mendorongnya jauh ke laci meja.
“Ada apaan sih, Gas?” tanya Dirga, bingung.
Bagas hanya melirik sekilas ke arah jendela, seolah takut ucapannya terdengar orang lain. Ia menunduk sedikit dan berbisik, “Pak Erhan.”
Dirga mengernyit. “Siapa?”
“Guru Matematika. Sekarang dia ngajar kelas X sama XI. Kata kakak gue, dia killer banget…”
Dirga menelan ludah. “Se-sekiller apa?”
“Dia tuh bisa tiba-tiba nyuruh lo maju ke depan ngerjain soal susah. Kalau enggak bisa, langsung dimarahin. Di depan kelas. Kalau lo ketahuan ngobrol? Disuruh keluar,” kata Bagas dengan wajah cemas.
Dirga menanggapi dengan alis terangkat. “Bukannya kaya gitu biasa aja, ya?”
Bagas menggeleng cepat. “Nggak, Ga. Ini orang beda. Dia suka semena-mena. Kalo dia nggak suka sama lo, lo bisa dihukum asal aja.”
Dirga merasa perutnya mulai mual. “Dia ngajar di kelas mana aja?”
“Di kelas kita... kelas X-C, X-E…”
Mata Dirga membulat. “X-E?”
Bagas mengangguk pelan. “Iya. Emang kenapa?”
Dirga tidak langsung menjawab. Tapi dadanya mulai sesak. Bukan karena takut pada guru galak. Tapi karena satu orang lain—Bumi.
Masalahnya, Bumi paling tidak suka kalau ada orang yang merasa lebih berkuasa dari dia. Dan mereka sudah berjanji. Tidak akan membuat masalah lagi.
***
Pak Erhan masuk ke kelas X-E dengan langkah berat dan sorot mata tajam yang langsung meredam udara di dalam ruangan. Suasana mendadak hening, seolah seluruh kelas menahan napas. Hanya satu orang yang tetap tenang: Bumi. Ia duduk di bangku belakang, tangan terlipat di dada, wajahnya datar seperti batu.
Pak Erhan membuka pelajaran pertamanya di kelas itu tanpa menyentuh materi. Ia mulai bercerita tentang dirinya sendiri—bagaimana ia dulu berjuang menjadi guru, dari kampus mana ia berasal, betapa sulitnya hidup di masa lalu, dan bagaimana anak-anak zaman sekarang sudah kehilangan moral dan disiplin. Ceramah itu panjang, penuh nada meremehkan, dan tidak satu pun siswa berani menyela.
“Sekarang, saya mau tes kalian sedikit,” katanya tiba-tiba.
Seisi kelas menarik napas. Mereka saling bertukar pandang cemas. Yang merasa belum belajar terlihat panik dan buru-buru membuka bukunya dengan tangan gemetar.
“Hari ini tanggal berapa?” tanya Pak Erhan tenang, seolah menikmati kepanikan samar di hadapannya kini.
“Tanggal tiga belas, Pak,” jawab seseorang di barisan depan.
Pak Erhan menyeringai kecil. “Absen tiga belas, maju ke depan.”
Farid—si anak kutu buku yang duduk di barisan paling depan—terperanjat. Dengan tubuh kaku, ia berjalan ke papan tulis, matanya melirik soal di buku Pak Erhan dengan cemas.
“Kerjakan,” kata Pak Erhan datar.
Farid mencobanya. Tapi tidak satu pun angka di kepalanya mau bergerak. Tangannya gemetar. Kapur hampir jatuh dari jari-jarinya.
Pak Erhan menunduk sejenak, lalu berkata dengan suara yang awalnya ramah, “Coba saya bantu, ya.”
Namun tiba-tiba—
“MASA BEGINI AJA NGGAK BISA?!”
Bentakannya meledak seperti bom. Satu kelas melompat dari kursinya. Farid mematung di tempat. Matanya membelalak ketakutan.
“Berdiri di sana! Jangan duduk dulu!” perintah Pak Erhan.
Farid bergerak mundur ke sisi papan tulis, berdiri seperti pesakitan di pengadilan.
Di bangku belakang, Bumi tidak terlihat kaget seperti yang lain, tetapi rahangnya mengeras.
Matanya menyipit tajam, menatap pria itu. Ini orang enggak bener, pikirnya.
Tapi ia hanya memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia ingat janjinya. Ia tidak akan buat masalah.
“Absen tiga puluh tiga,” kata Pak Erhan lagi.
Sophia yang sedang menunduk dalam, tersentak kaget,. “I-iya, Pak,” suaranya nyaris tak terdengar.
Dengan langkah ragu, ia maju. Pak Erhan memberinya soal. Matanya mengamati Sophia seperti seekor predator yang menunggu mangsanya terpeleset.
Namun berbeda dengan Farid, Sophia bisa mengerjakan soal itu.
Pak Erhan tampak tidak senang. “Darimana kamu tahu jawaban itu?” tanyanya. Nadanya mencurigai alih-alih menguji.
Sophia menelan ludah. Suaranya bergetar, tapi ia bisa menjelaskan dengan runut tahapan penyelesaian soal yang ia kerjakan.
Ia dicecar lagi dengan dua-tiga pertanyaan tambahan, tapi Sophia menjawab semuanya. Rahang Pak Erhan mengeras, sebelum akhirnya ia mengangguk dingin. “Duduk.”
Satu per satu, nama acak dipanggil dari daftar absen. Sekitar sepuluh siswa kini berdiri di depan kelas. Pak Erhan melipat tangan di dada, berdiri seperti jenderal, berkata pada semua murid yang duduk di hadapannya.
“Minggu depan, kalau kalian masih bodoh seperti ini, kalian bakal saya hukum. Kalian semua jadi contoh hari ini,” katanya sambil mengangguk singkat pada sepuluh siswa yang dipajang di depan kelas.
Lalu, tanpa ekspresi, ia berkata, “Jalan jongkok keliling koridor lantai tiga. Sepuluh kali.”
Seisi kelas terdiam. Anak-anak yang dipajang hanya bisa menunduk, lalu mulai berjalan jongkok keluar kelas dalam diam.
Di bangku belakang, Bumi tetap diam. Tapi matanya tak berpaling dari sosok Pak Erhan.
Tatapannya dingin. Tajam. Penuh penilaian.
Dia bukan guru, pikir Bumi. Dia tiran.
***
Begitu bel istirahat berbunyi, Dirga segera bangkit dari kursinya dan tergesa menuju kelas X-E. Napasnya masih terengah saat ia mengintip ke dalam ruangan—dan langsung menemukan Bumi, yang baru saja berdiri dari kursinya dengan kotak makan siang di tangan.
“Ngapain lo ke sini?” tanya Bumi datar, melintasinya tanpa berhenti.
Dirga buru-buru mengikuti dari belakang. “Lo tadi ada Matematika sama Pak Erhan, kan?”
Bumi hanya menggumam pelan sebagai jawaban.
Dirga meliriknya takut-takut. “Lo… lo nggak bikin masalah, kan?”
Bumi menghentikan langkah. Pelan, ia menoleh. Tatapannya tajam, menohok, membuat Dirga menelan ludah.
“Jadi lo ke sini cuma buat ngecek gue bakal bikin keributan atau enggak?” tanyanya datar. “Lo pikir gue sebodoh itu?”
Dirga menggeleng cepat, panik.
Tanpa berkata lagi, Bumi kembali melangkah. Namun baru beberapa langkah, seorang siswa berjaket hitam tiba-tiba berdiri menghalangi jalannya.
Bumi mengangkat pandangan, tetap dengan wajah tanpa ekspresi.
“Nama lo Bumi, kan?” tanya si cowok.
“Mau apa?” sahut Bumi singkat.
“Lo dipanggil Raka ke lapangan.”
Dirga sontak membeku. Raka? Kakak kelas yang kata Bagas suka ngerjain anak baru itu?
Bumi menatap si cowok beberapa detik sebelum mengangkat bahu santai dan mulai berjalan mengikuti. Tapi tiba-tiba Dirga meraih tangannya.
“Jangan pergi,” desisnya panik.
Bumi mengernyit. “Apa lagi?”
“Kata temen gue, Raka itu anak kelas XII yang suka ngerjain orang. Kalau lo dikerjain gimana?”
Bumi malah tersenyum kecil. “Menarik.”
Ia lalu menyodorkan kotak makan siangnya ke Dirga.
“Beliin gue es teh di kantin. Taruh di meja kelas gue,” ucapnya santai, lalu berbalik dan pergi, mengikuti si cowok tanpa menoleh.
Dirga hanya berdiri mematung dengan kotak makan siang Bumi di tangannya. Kepalanya terasa ringan, seperti kehilangan keseimbangan.
Masalah apa lagi yang bakal dia buat sekarang?
***
Raka memanggil Bumi ke pinggir lapangan—tepat di bangku semen tua yang teduh di bawah pohon rindang. Tempat itu sudah seperti markas kecil bagi geng Raka. Di situlah mereka biasanya berkumpul, bercanda, merokok diam-diam, atau sekadar memamerkan siapa yang paling berkuasa.
Bumi datang sendirian. Langkahnya tenang, tapi penuh waspada. Ia berdiri tak jauh dari bangku itu, tubuhnya tegak dengan tangan terlipat di depan dada, wajahnya datar nyaris beku.
Raka berdiri dan mendekatinya, senyum tipis tersungging di wajahnya. “Nama lo Bumi, kan? Gue Raka.” Ia menyodorkan tangan.
Tatapan Bumi hanya menyapu tangan itu sekilas sebelum kembali menatap mata Raka. “Langsung aja. Gue enggak biasa basa-basi,” sahutnya dingin.
Alis Raka berkerut, tapi ia hanya mendengus pelan. “Masih kelas sepuluh… tapi nyali lo gede juga.”
Tak ada reaksi dari Bumi. Diam. Seperti batu.
“Oke,” lanjut Raka. “Gue denger gimana lo ngalahin temen-temen gue kemarin. Lo kuat juga. Lo bakal cocok sama kita.”
Bumi menatap mereka semua. Tak butuh waktu lama untuk menilai siapa mereka: bocah-bocah sombong yang merasa berkuasa hanya karena selalu bergerak dalam gerombolan.
“Gue enggak tertarik,” katanya datar. Ia berbalik hendak pergi.
Namun baru beberapa langkah, salah satu anak buah Raka—yang berdiri di sisi bangku—berteriak, “Songong banget lu, anak baru!”
Bumi menoleh perlahan. Tatapannya menghantam balik, tajam dan dingin, seperti pisau yang menempel di leher. Anak itu langsung diam. Mulutnya mengatup sendiri. Entah kenapa, lututnya tiba-tiba terasa lemas.
Raka tertawa kecil. “Santai, Yo. Nanti lo buat dia takut beneran.”
Bumi mengangkat alis, ekspresinya tetap dingin.
Raka menatapnya dalam-dalam, mencoba menakar keberanian bocah yang berdiri di hadapannya. Ia melangkah lebih dekat, lalu menepuk bahu Bumi.
“Gue kasih lo waktu buat mikir. Gue yakin lo bisa bikin pilihan yang bagus.”
“Dan kalau gue tetap bilang enggak mau?” tanya Bumi.
Senyum Raka melebar, tapi dingin. “Hidup lo enggak bakal tenang di sini.”
Bumi melirik tangan Raka yang masih bertengger di bahunya. Ia menyipitkan mata, lalu mencondongkan tubuhnya perlahan.
“Terakhir kali ada yang maksa gue…”
Ia menatap Raka lurus, tanpa emosi.
“…mereka pulang pakai kursi roda.”
Hening sejenak.
Lalu Bumi bicara lagi, lebih pelan, nyaris seperti geraman.
“Kalau lo enggak mau ngerjain ujian akhir dari ranjang rumah sakit… jangan ganggu gue.”
Mata Raka seketika berkedip. Ada sesuatu dari suara itu—dari cara Bumi menatapnya—yang membuat napasnya tertahan sepersekian detik. Tapi ia buru-buru menguasai diri.
“Singkirin tangan lo,” kata Bumi pelan, nyaris berdesis.
Tangan Raka turun perlahan dari bahunya. Gerakannya enggan, tapi tak bisa dihindari.
Bumi menatapnya sekali lagi—tegas, tajam, penuh peringatan. Lalu ia berbalik dan berjalan pergi.
“Songong banget dia. Kita kerjain aja, Ka!” umpat salah satu anak buah Raka dengan gusar.
Raka diam sesaat. Matanya masih menatap punggung Bumi yang perlahan menghilang di antara kerumunan lapangan.
Lalu ia mendengus pelan. “Gue pengen tau… berapa lama dia bisa bertahan di sini.”


 dwyne
dwyne




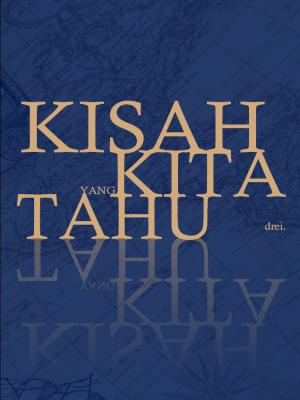






suka dengan bagaimana kamu ngebangun ketegangan di awal, adegan di toilet itu intens, tapi tetap terasa realistis. Dialog antar karakter juga hidup dan natural, terutama interaksi geng cewek yang penuh nostalgia masa SMA; kaset AADC dan obrolan ringan itu ngena banget.
Comment on chapter Pandangan Pertama