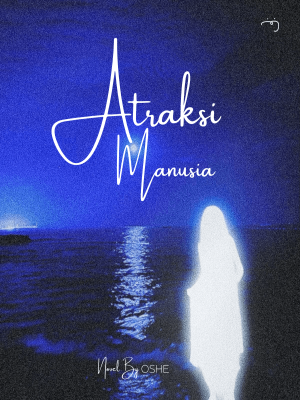# Email 003 – 25 Desember 2022
To: in_ara@email.com
Subject: Rumah yang tak lagi ramah
Ra,
Aku... aku gak tahu harus mulai dari mana.
Aku menulis ini dari halte, duduk sendiri dengan tas ransel setengah kosong. Malam ini aku pergi.
Iya, Ra. Aku akhirnya keluar dari rumah itu. Tempat yang seharusnya menjadi ruang tumbuh, justru berubah jadi medan bertahan. Dua bulan aku mencoba menyesuaikan diri, tapi setiap harinya terasa makin menyesakkan—hingga akhirnya aku menyerah dan pergi.
Sebenarnya sejak Papa meninggal, aku merasa tidak perlu pindah bersama Ibu. Aku pikir aku sudah cukup besar untuk hidup sendiri. Tapi saat Ibu datang dengan wajah sendunya, memelukku erat, hangat sekali—aku terenyuh. Aku luluh. Akhirnya, aku ikut tinggal bersamanya.
Ironisnya, malam ini, Ibu jugalah yang mengeluarkanku dari rumah itu.
Tadi malam mereka bertengkar lagi—lebih keras dari biasanya. Piring pecah. Teriakan. Kata-kata kotor. Aku yang biasanya menutup telinga, akhirnya keluar kamar ketika mendengar tangis Dinda. Ia menjerit-jerit, berusaha melerai dengan suara kecil yang gemetar. Kupeluk dia erat-erat. Kucoba menenangkannya. Dan saat itu juga aku berkata:
“Udah cukup! Kalian sadar gak sih Dinda denger semuanya? Dia ketakutan! Bisa gak sih kalau mau berantem, jangan di depan anak kecil?! Kalian tuh udah dewasa, harusnya punya malu!”
Dan kamu pasti tahu, Ra, ending-nya seperti apa.
Orang itu bukannya sadar, malah melampiaskan amarahnya. Aku dipukul. Didorong. Dicaci maki. Sampai akhirnya aku jatuh tersungkur. Kulihat wajah orang itu begitu puas menyaksikanku menderita. Ia menendangku dan keluar dari rumah. Ibu... Ibu hanya berdiri melihatku sejak tadi. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Ia mendekat dan dengan suara pelan bergetar berkata,
“Nak, kamu pergi dulu aja ya dari rumah ini. Kamu tinggal dulu di rumah teman.”
Aku tidak menjawab. Hanya diam, air mata menetes perlahan tanpa kusadari. Tapi cepat-cepat kuhapus. Aku berdiri perlahan, mengambil barang-barang seadanya ke dalam satu-satunya tas yang kupunya. Ibu berdiri di depan pintu, berjaga-jaga agar aku tidak berpapasan dengan orang itu.
“Ibu sudah pesankan taksi,” katanya pelan.
Aku masuk ke dalam mobil itu. Dan entah kenapa, ketika Pak Supir bertanya aku mau ke mana, aku menjawab: “Ke kampus aja, Pak.”
Karena aku benar-benar gak tahu harus ke mana lagi. Tak ada tempat lain. Pak Supir sempat menyarankan ke rumah sakit, tapi kutolak sambil tersenyum tipis,
“Gapapa, Pak. Ini mah gak seberapa kok.”
Sesampainya di kampus, aku berjalan ke halte. Duduk. Sendirian. Entah menunggu siapa atau apa.
Aku membuka kotak P3K dari tasku, mulai membersihkan luka-luka kecil yang bisa kujangkau. Satu per satu. Betadine perih. Tapi tidak lebih dari hati yang terasa nyeri—nyeri yang tak bisa kuobati.
Air mataku mengalir deras. Bukan karena sakit fisik, tapi karena semua ini seharusnya tidak terjadi. Aku tahu mungkin Ibu seperti itu agar aku aman dari orang itu. Tapi entahlah, rasanya aku malam ini aku ingin menangis saja.
Aku duduk merenung. Ada tujuh jam lagi menuju pagi. Tapi sepertinya aku akan tetap di sini. Ironis, ya. Halte terbuka seperti ini justru terasa lebih aman daripada tempat yang seharusnya disebut rumah.
Ra, kalau suatu hari kamu membaca surat ini lagi, semoga kamu sudah berada di tempat yang aman. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara hati. Tempat yang membuatmu bisa tidur tanpa rasa waspada. Tempat yang tidak membuatmu bertanya-tanya, "Besok aku bakal disakiti lagi atau tidak?" Tempat pulang. Bukan tempat bertahan.
Ra, kamu tahu kan ini tanggal berapa? 25 Desember. Malam Natal.
Orang-orang mungkin sedang berkumpul di ruang keluarga, menikmati cokelat panas, menyanyikan lagu-lagu Natal, atau sekadar tertawa bersama. Tapi aku di sini, duduk di halte, dengan tubuh memar dan hati yang hancur. Ironis, ya... hari yang katanya penuh cinta kasih, justru menjadi malam paling menyedihkan dalam hidupku. Malam Natal yang seharusnya hangat, justru terasa lebih dingin dari biasanya.
Aku belum tahu akan ke mana setelah ini. Tapi satu hal yang pasti: aku tidak bisa kembali ke sana.
Doakan aku kuat, ya.
Inara, yang akhirnya memilih pergi.


 dalamparagraf
dalamparagraf