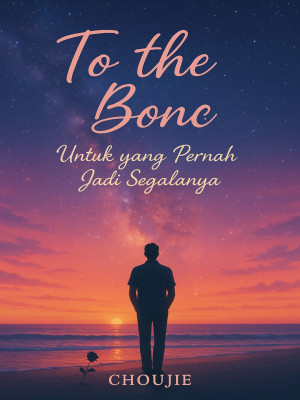“Kalau aku hilang dan tidak ada yang mencariku, berarti aku memang tidak pernah ada.”
___Arsya Abiseka G.
______________________________________________________________________________________________
Suara tawa mengejek membangunkannya dari mimpi panjang.
Arsya membuka mata, kepala masih berputar karena sisa obat. Yang pertama dia lihat bukan langit-langit putih rumah sakit yang sudah familiar, tapi wajah-wajah asing yang menatapnya dengan mata penasaran. Belasan anak berkumpul melingkari ranjangnya seperti menonton pertunjukan sirkus.
"Lihat, dia bangun!"
"Kurus banget. Botak lagi."
"Pasti anak buangan. Jelek, makanya nggak ada yang mau. Dia juga mungkin anak nakal."
Suara-suara itu menghantam telinganya sekaligus. Tapi yang lebih buruk—pikiran mereka ikut berdengung di kepalanya.
“Dia pasti lemah.”
“Kita apakan dia hari ini?”
“Mainan baru.”
Arsya mencoba duduk, tapi dunia bergoyang. Efek obat membuatnya mual dan pusing. Dia menutup mata rapat-rapat, berharap semua suara bisa hilang.
"Hei, kenapa diam aja?"
"Dia takut kita, ya?"
Semakin banyak anak yang datang mendekat. Ruangan yang sempit makin sesak. Napas Arsya mulai pendek.
"Pergi," bisiknya lemah.
Gelak tawa meledak. "Dia minta kita pergi! Dengar itu!"
"Dia pikir dia siapa? Raja?"
"Si Botak aneh."
"Anak buangan."
Setiap kata yang mereka ucapkan hanya berisi hinaan. Arsya menekan telapak tangan ke telinga, tapi pikiran mereka tetap mengalir masuk.
“Dia belum terima kalau dibuang makanya marah-marah.”
“Dia pasti masih berharap ada yang datang jemput.”
“Dasar bodoh!”
"HENTIKAN!" Arsya berteriak sekuat tenaga.
Tapi yang dia dapat justru tawa lebih keras.
Sesuatu dalam dada Arsya pecah. Tangannya meraih bantal dan melemparkannya ke arah anak-anak. Mereka menghindar sambil tertawa.
"Wah, dia ngamuk!"
"Ayo, ayo! Bikin dia makin marah! Biar dia tau diri."
Arsya melempar apa saja yang bisa dia raih. Gelas plastik, sandal, bahkan seprai. Tangan kecilnya bergerak tanpa kendali, didorong amarah dan frustrasi yang meluap.
"Pergi kalian! Pergi!"
Seorang anak laki-laki yang lebih besar—mungkin umur sepuluh tahun—melangkah maju dengan senyum jahat. "Kamu mau ngusir kita? Ini rumah kita, bukan rumah kamu."
"Iya, kamu yang harus pergi dari sini!"
"Tapi kemana? Kamu kan udah dibuang!"
Suara tawa mengejek terdengar lagi.
Anak itu mendorong bahu Arsya, tidak keras tapi cukup untuk membuatnya terhuyung. Arsya mendorong balik, lebih kuat, hingga si anak terpeleset ke belakang.
Tubuh anak itu menabrak seorang bocah kecil yang sedang bermain balok di pojok. Bocah itu terjengkang, balok-baloknya berserakan, lalu menangis sejadi-jadinya.
Hati Arsya mencelos. Dia tidak ingin menyakiti siapa-siapa.
Tapi terlambat. Si anak besar bangkit dengan wajah merah. "Sekarang kamu udah bikin masalah!"
Dia menerjang Arsya. Keduanya jatuh ke lantai, bergulat. Tangan si anak mencengkeram telinga Arsya dan menjewer keras-keras.
"Argh!" Arsya membalas dengan menjambak rambut lawannya, kedua tangannya mencengkeram erat.
"Lepas! Lepasin rambutku! Sakit, lepas!"
"Kamu duluan yang lepas!"
Mereka berguling-guling di lantai sempit. Beberapa anak mencoba memisahkan, tapi malah ikut terjatuh. Yang lain berteriak memanggil pengurus.
Arsya sudah kehabisan tenaga, tapi sesuatu membuatnya bertahan—mungkin keputusasaan, mungkin ketakutan. Saat lawannya mulai unggul, Arsya panik dan menggigit tangan yang mencengkeram telinganya.
"AAAHHH!" si anak berteriak dan refleks menendang perut Arsya.
Tendangan itu menghantam persis di tempat lukanya masih belum sembuh. Tubuh Arsya terlempar dan tergelincir masuk ke kolong ranjang.
Rasa sakit meledak di perutnya. Arsya meringkuk, lutut ditarik ke dada, napas tersengal-sengal. Tapi yang lebih mengerikan—pemandangan dari bawah kolong ini.
Kaki-kaki anak-anak berlarian. Suara teriakan. Persis seperti malam penculikan itu.
Kilatan ingatan menyerbu. Dia tiba-tiba kembali berada di bawah ranjang rumah sakit, mendengar langkah kaki asing yang datang mengambilnya. Tarikan tangan kasar. Jarum suntik. Wajah-wajah menyeramkan.
Dadanya sesak. Telinga berdengung. Keringat dingin mengalir membasahi dahi.
"Nak, kamu terluka?" Suara pengurus panti terdengar jauh, seolah dari ujung terowongan. "Keluarlah dari sana, biar kita lihat."
Arsya tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku ketakutan.
"Mbak, bagaimana ini?" Kania, pengurus muda, berbisik cemas. "Ibu sedang ke balai desa melaporkan anak ini."
"Ah!" Fatma, pengurus yang lebih tua, menepuk jidat. "Ada obat yang ditemukan bersamanya waktu itu. Mungkin obat rutinnya."
Mendengar kata 'obat', Arsya bergidik. Obat yang diberikan penculik bukan untuk menyembuhkan. Dia tahu itu.
"Kita tidak boleh sembarangan kasih obat," kata Kania ragu.
"Tapi dia kesakitan. Anak-anak lain juga ketakutan lihat dia begini."
Fatma berlutut dan mengulurkan tangan ke kolong. "Nak, keluar dulu. Kakak mau bantu."
"Nggak..." suara Arsya parau. "Nggak mau..."
Dengan susah payah, Fatma menarik tubuh Arsya keluar dan memangkunya. "Tenang dulu. Atur napasmu. Nanti Kakak kasih obat biar tidak sakit."
Arsya menggeleng lemah. Dadanya makin sesak, napas makin pendek. Dia merasakan bahaya—bahaya yang sama seperti malam penculikan.
"Enggak mau, tolong buang…Tolong..." bisiknya hampir tak terdengar.
Tapi siapa yang akan menolongnya di tempat asing ini?
Mata Arsya mulai buram. Tubuhnya lemas. Dalam kepanikan, dia melakukan hal yang bahkan dia sendiri tidak mengerti—dia memanggil dengan seluruh jiwa raganya.
“Tuhan... tolong aku... kirimkan siapa saja…”
“Dokter Nata…”
“Kakek…”
“Siapa saja yang bisa nolong…”
***
“Kakek….”
Pak Damar tersentak dari tidurnya. Jantungnya berdetak kencang. Suara itu… bukan mimpi. Terlalu nyata. Terlalu dekat.
Ia duduk, mendapati dirinya sendirian di ruang kerja kecil rumah kayu yang mereka sewa di pinggiran kota Tokyo. Lampu meja menyala redup. Di luar, angin malam meniup gorden tipis.
Hari itu panjang—persiapan ulang tahun dan senyum palsu. Tapi sekarang, semua terasa sunyi. Hampa.
"Arsya... kamu barusan memanggil Kakek?"
***
Di panti asuhan yang jaraknya puluhan kilometer, Arsya akhirnya kehilangan kesadaran dalam pelukan Fatma. Tapi untuk sesaat sebelum gelap menelannya, dia merasakan kehangatan—seolah ada seseorang, di suatu tempat, yang mendengar panggilannya. Seseorang yang juga memanggil namanya.
Dia terlihat tenang dalam tidurnya.
Tapi malam belum selesai. Dan takdir belum memutuskan di pihak siapa ia berpihak.


 hanyaselingan
hanyaselingan