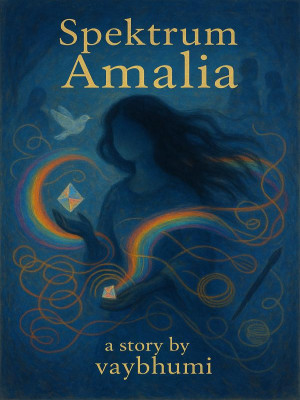"Sabar itu nggak nyembuhin semuanya, tapi bisa bikin kita tetap kuat sampai semuanya selesai."
___ Pramudya Rajendra
___________________________________________
Sinar senja merayap melalui jendela, melukis garis jingga samar di dinding kamar. Arsya duduk di tepi ranjang, jari-jari dinginnya masih menggenggam ponsel Rajendra. Layarnya mati—sunyi dari kedipan notifikasi, kosong dari sapaan pesan. Hanya pantulan wajahnya yang buram terlihat di sana.
Mungkin lupa, bisik lirih dalam hatinya. Atau... memang aku tidak diinginkan?
Arsya menggeleng pelan. Seperti awan gelap, pikiran-pikiran buruk mulai berarak di benaknya. Padahal, saat Rajendra pertama kali datang membawa kabar itu, hatinya terasa hampa, tidak ada kebahagiaan yang muncul di sana. Dia justru bingung bagaimana menanggapi hal tersebut.
Saat sendiri banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya “Emang aku beneran pengin pulang? Ketemu Kakek? Kayak yang diminta Bunda? Atau aku cuma nggak enakan aja karena udah ngerepotin terus?”
Tapi semakin dipikirkan, perasaan tak berdaya di tubuhnya yang delapan tahun itu perlahan mengubah bingung menjadi secercah harap. Harap yang mewarnai mimpinya. Sebuah keluarga utuh dengan suara obrolan hangat dan tawa yang nyaman didengar.
“Semoga Kak Jendra cepat dibalas,” pintanya dalam hati. “Setidaknya... aku ingin melihat wajah mereka. Orang yang melahirkanku, yang mungkin... dulu pernah mencintaiku.”
Namun harapan itu kian dipengaruhi rasa cemas, karena setiap kali Arsya mencoba bertanya, jawaban Rajendra hanya berisi kemungkinan ‘Mungkin pesan Kakak masuk pesan rahasia di keluargamu’ atau ‘Mungkin mereka belum sempat membuka pesanmu, karena sibuk mencarimu di luar?’
Arsya tahu Rajendra hanya bingung saat dia bertanya, dan upayanya berkilah justru memperburuk suasana hatinya “Sibuk nyari aku di luar? Padahal aku di sini, kan… sudah dijasin lewat pesan” Arsya menggigit ujung bibir bawahnya. Kata ‘folder rahasia’ dan ‘sibuk’ itu pelan-pelan berubah jadi arti lain di kepalanya. Mungkin aku nggak penting.
Bahkan hingga tiga hari setelah pesan itu dikirim, mimpinya masih sama. Kehangatan keluarga menguar dari meja makan yang penuh dengan aroma hidangan lezat. Namun, begitu kelopak matanya terbuka, kamar rumah sakit yang menyambutnya, tidak ada aroma yang menggugah selera, hanya bau obat-obatan yang menusuk hidung.
Sepi dan sendiri, kedua hal itu membungkam ilusi kehangatan alam mimpi dengan kenyataan pahit. Itu cuma mimpi. Setiap kali matanya tanpa sengaja melirik ponsel yang tergeletak bisu di nakas, sesak di dadanya kembali hadir, seolah ada tangan besar yang meremas dadanya. Membuatnya bernapas pendek-pendek, seperti habis berlari jauh tanpa berhenti.
Arsya menelan ludah dengan susah payah, namun tidak ada kelegaan yang datang. Kerongkongannya terasa seperti digosok amplas, seiring dengan bayangan wajah-wajah asing yang dia bayangkan menjadi keluarganya, berkelebat di benaknya. Matanya menatap segelas air di nakas—disiapkan Kak Alin sebelum ia pergi. Dengan tangan gemetar, Arsya meraihnya, seteguk cairan dingin menyentuh bibirnya… detik berikutnya—
“Kamu sudah dibuang!”
Raungan keji dalam benaknya mencabik sunyi. Gelas terlepas dari cengkeramannya, membentur lantai keramik dengan bunyi nyaring, lalu terburai menjadi serpihan tajam. “Lihat! Mereka tak peduli sedikit pun!” Suara itu kembali menyerang, gerombolan bisikan jahat di kepalanya kian riuh.
“Mereka nggak baca pesanmu.”
“Kalau kamu memang dicari... harusnya waktu itu, mereka langsung buka.”
“Kamu nggak penting. Nggak pernah penting. Kamu itu cuma___”
“Diam!” pekik Arsya, kedua tangannya menutup kedua telinga, berusaha membungkam serbuan kata-kata menyayat dari benaknya. Tapi suara-suara itu terus menembus. Telinganya terasa panas, kepalanya berdenyut, dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ketika gaung itu mereda, barulah ia menyadari pecahan gelas berkilauan di lantai.
Napasnya tercekat. “Aduh, kenapa kubuang? Kak Alin pasti repot membersihkannya.” Dengan tergesa, Arsya turun dari ranjang. Jari-jari telanjangnya bergerak mengumpulkan beling-beling tajam. Karena pikirannya masih berkecamuk, gerakannya ceroboh.
“Aw!”
Setitik darah merah merembes dari ujung telunjuknya. Luka kecil itu terasa perih, namun tusukan emosi di dadanya jauh lebih menyesakkan, hingga air mata tak tertahankan mengalir di pipinya. “Bunda…” lirihnya. Ia tak tahu pasti mengapa bibirnya menyebut nama itu, namun sosok hangat dalam mimpinya selalu menyambutnya dengan panggilan itu.
“Aku kena pecahan kaca, Bunda… tanganku berdarah. Ini sakit banget Bunda. obati… aku… sakit.” Isak tangis pilu kemudian memenuhi ruang sunyi, tubuh Arsya bergetar di balik kedua tangannya yang menutupi wajah, ia meringkuk di lantai yang dingin.
Di balik pintu, Rajendra dan Alin saling mencuri pandang. Napas mereka tertahan ketika tangisan itu terdengar. Tanpa sadar, tangan Alin mencengkeram lengan Rajendra—kuku-kukunya meninggalkan bekas merah. Rajendra menatap gagang pintu, rahangnya mengeras, menahan dorongan untuk menerobos masuk.
“Kamu... nggak ada jaga malam kan?” bisiknya, suara serak oleh air mata yang ditahannya. Dia menyeka sudut matanya dengan punggung tangan. “Pulang saja. Biar aku yang temani dia malam ini.”
Rajendra menghela napas panjang, pandangannya tak lepas dari gagang pintu yang masih digenggamnya erat. “Yakin?” tanyanya sekali lagi, suara rendah penuh keraguan. “Dia lagi... dia lagi nggak baik-baik saja, Lin.”
“Justru karena itu!” jawab Alin mantap. Dia menarik napas dalam-dalam. Namu, seolah diingatkan atas sesuatu, dia kemudian bertanya “Eh, ponselmu kan masih sama Arsya, ya? Kayaknya dia butuh istirahat, deh. Aku khawatir kondisinya makin nggak karuan karena belum ada respons juga dari keluarganya.” Dia melirik ke arah pintu. “Ayo kita masuk bareng… kamu ambil poselmu tapi,” tangannya menahan Rajendra, “biar aku yang pertama, oke?”
Mereka mengangguk bersamaan, sebuah kesepakatan tanpa kata terbentuk di antara tatapan itu. Rajendra mengetuk pintu tiga kali - pelan tapi pasti. “Arsya, kami mau masuk ya?” Suaranya berusaha tenang meski jemarinya gemetar membuka pintu perlahan.
Arsya tampak salah tingkah dan rona malu menjalari wajahnya saat dua perawat yang sigap menghampirinya melihat jejak air mata. Ia berujar lirih, "Gelasku kesenggol tadi." Alasan yang sebenarnya kurang meyakinkan, mengingat serpihan kaca dan sisa air yang lebih dekat ke ranjangnya. Namun, kedua perawat itu tidak mempermasalahkannya. Alin dengan cekatan membersihkan noda darah di lengan Arsya dan memberinya obat, sementara Rajendra sigap mengambil tempat sampah dan memunguti pecahan kaca yang berserakan.
"Sakit, ya? Sampai nangis ," tanya Alin lembut, sambil menempelkan plester bergambar dinosaurus.
"Nggak kok, cuma… " Arsya menggantungkan kalimat, matanya menerawang ke jendela.
“Cuma?” usapan Alin pada tangan Arsya terhenti. Matanya menatap lurus anak itu. dia terlihat seolah terpojok dengan tatapan Alin
sementara suara alin terdengar oleh Arsya. Dia berharap Arsya tidak bertambah sakit dengan menyembunyikan apa yang dia rasakan hari ini. suara penuh keraguan Arsya terdengar “Iya, sakit banget”
“Yang sakit ini?” Alin menunjuk jari yang dibalut.
“Atau di sini?” Ujung jarinya berpindah ke dada Arsya, di atas degup yang belum tenang.
sekali lagi, pertanyaan Kak Alin seolah tepat sasaran. Arsya menggeleng cepat. "Cowok nggak boleh nangis… " katanya, tapi air mata malah jatuh deras.
“Nggak papa nangis, Dek…” Alin membelai rambut Arsya lembut.
“Kesedihan itu kayak awan mendung. Kalau ditahan terus, bisa jadi hujan deras yang nyakitin banyak orang.”
Ia menarik napas, membiarkan kata-katanya meresap.
“Mending keluarin sekarang, lewat air mata. Biar hatimu nggak penuh. Biar lega, kayak tanah yang akhirnya disiram hujan. Dia kotor, tapi dia juga hidup lagi.”
Alin memeluknya lebih erat. “Banjir bukan karena hujan—tapi karena kita nggak pernah kasih jalan buat airnya keluar.”
Akhirnya Arsya meluapkan semuanya, bahunya sampai bergetar dalam pelukan Alin. Setelah cukup tenang, dia kemudian mengurai pelukan.
Arsya diam sejenak, pikiran kak alin juga tidak memaksanya segera menceritakan sesuatu, setelah menarik napas, Arsya akhirnya memulai bercerita “Kak… kalau emang mereka nggak suka aku, kenapa aku dilahirkan?”
Alin mengernyit, tidak menyangka Arsya akan berpikir demikian, “Sebentar, menurutmu mereka begitu? Nggak menginginkanmu?”
"Iya… mungkin itu sebabnya pesanku nggak dibalas. Mungkin aku memang dibuang… " Arsya menggigit bibir. "Sebelum kecelakaan, aku juga sendirian. Sekarang pun… tetap sendirian. "
Mata Alin memerah, suara pikirannya sedikit kacau, Alin ingin memintanya sabar. tapi tidak mungkin memintanya bersabar saat dia sedang merasakan duka
“Arsya… dengerin Kakak.”
“Kamu ada di dunia bukan karena kesalahan siapa-siapa. Bahkan kalau ada yang menolakmu... itu karena mereka belum belajar cara mencintai dengan benar.”
Kalimat terakhir Alin mampu menyita perhatian Arsya ‘belum belajar cara mencintai dengan benar’ ditambah dengan suara hati Alin ‘semua orang pasti pernah berbuat salah,’
"Iya, Kakak tahu, kamu sedih sekali sekarang." Alin mengangguk paham. "Tapi Dek, coba bayangkan kalau kamu punya mainan kesayangan yang hilang. Seperti... robot superhero atau mobil remote control yang kamu sayang banget."
Arsya terdiam sejenak, matanya masih basah tapi mulai tertarik dengan cerita Alin.
"Terus kamu cari ke mana-mana, sampai kasih pengumuman bahwa siapa yang menemukan akan dapat hadiah. Tapi tiba-tiba, banyak anak yang bilang menemukan mainanmu, padahal sebenarnya mereka bohong dan cuma mau hadiahnya saja. Mereka datang ke kamu setiap hari dengan mainan yang mirip tapi bukan punyamu. Coba kakak tanya, bagaimana perasaanmu saat itu?"
"Pasti sebel..." gumam Arsya pelan.
"Nah, betul! Lama-lama pasti kamu capek dan bingung, kan? Bahkan mungkin kamu jadi ragu-ragu kalau ada yang benar-benar menemukan mainanmu. Mungkin keluargamu juga merasakan hal yang sama. Mereka dapat banyak pesan dan telepon dari orang-orang yang ngaku sebagai kamu, tapi ternyata bukan."
Arsya mengangguk perlahan, mulai memahami.
"Mungkin mereka sedih dan bingung, sama seperti kamu sekarang. Arsya mau memberi mereka kesempatan sebentar lagi?"
"Hmm..." Arsya terlihat berpikir.
“Arsya…” panggil Rajendra, dia sudah selesai membereskan pecahan gelas di lantai, bahkan sudah siap untuk pulang, karena datang dengan menenteng tas. Dia mendekati Arsya berjongkok di hadapannya. “Kita belajar lebih sabar, ya?” Pintanya, nada suara Rajendra terdengar lebih lembut dari biasanya. “Kakak tahu kamu capek. Tapi kita coba tahan dikit lagi, ya? Sabar itu nggak nyembuhin semuanya, tapi bisa bikin kita tetap kuat sampai semuanya selesai.”
Arsya tidak menjawab. Matanya menatap ke ujung selimut yang kusut di pangkuannya.
“Sebagai gantinya...” Rajendra melanjutkan, “malam ini Kakak coba ke alamat rumahmu. Yang di poster itu. Kakak selesaikan malam ini, dan usahakan besok pagi udah ada kabar. Gimana?”
Arsya mengangguk pelan, tapi anggukan itu terasa seperti refleks, bukan kesepakatan.
Di dalam kepalanya, badai tak reda. Ia tahu mereka sedang berusaha. Ia tahu Alin dan Rajendra bukan musuhnya. Tapi tahu bukan berarti menerima. Yang bisa dia lakukan malam ini... hanyalah diam. Menahan.
Sabar—kata itu terdengar indah kalau diucapkan orang lain, tapi rasanya seperti batu di kerongkongan kalau harus dilakukan sendiri.
Kalau boleh memilih, Arsya ingin berlari sendiri ke alamat itu. Berdiri di depan rumah itu dan menunggu sampai seseorang membukakan pintu, berkata "Maafkan kami." Tapi ia tahu tubuhnya masih lemah. Ia tahu belum saatnya. Jadi ia memendam itu dalam-dalam, bersama tangis yang sudah kehabisan air mata.
Nanti, kalau kesempatan itu datang, dia akan cari sendiri. Tapi malam ini, ia hanya menggenggam sisa harapan seperti menahan napas terlalu lama di dalam air. Dan entah sampai kapan ia bisa terus menahan.
***
Malam merambat pelan di balik jendela rumah sakit, menelan detak jantung Arsya yang masih tersisa. Di tempat tidurnya, ia menatap langit-langit, mencoba menahan desakan untuk bangkit. Alin baru saja tertidur setelah menenangkannya saat mengigau dari mimpi buruk, genggaman tangan Alin memang sudah sedikit melonggar, tapi sedikit pergerakan Arsya mungkin bisa membangunkannya. Akhirnya Arsya mencoba memejam sekali lagi, dengan harapan tidak mengulang mimpi yang sama.
Sementara itu, di sebuah rumah megah yang diterangi lampu kristal, malam justru terasa lebih pekat. Nohan berdiri di depan ruang kerja kerja Aswan, setelah dipersilakan masuk, Nohan langsung menuju meja kerja tempat bosnya sedang duduk dengan wajah dingin terpantul layar ponsel. Udara di ruangan itu terasa berat, dipenuhi aroma tembakau mahal dan ketidakpastian.
"Akhirnya kau menyempatkan diri," desis Aswan tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponsel. Ritme ketukan kukunya di meja kayu eboni serupa detak jam siksaan.
"Ada laporan menarik tentang... anak itu?"
Nohan menelan ludah. "Anak yang Bapak tabrak?" Getar suaranya menggema di ruang ber-AC ini bagai senar biola tua yang rengat.
Barulah Aswan mengangkat kepala. Matanya menyipit, sinar lampu meja membelah wajahnya menjadi dua bagian - separuh terang dengan senyum tipis, separuh gelap dengan rahang mengeras. "Kondisinya?"
"Mulai pulih," jawab Nohan singkat.
Keringat dingin merayap di tulang rusuknya.
"Pulih," ulang Aswan sambil menyenderkan badan ke kursi kulit. Suaranya mendayu seperti guru yang mengeja kata untuk murid bodoh. "Lalu kapan kau pindahkan ke panti?"
Nohan mengepal buku jari di balik punggung. "Bukankah Dokter Nata yang—"
"Benar! Serahkan pada Nata!" sela Aswan tiba-tiba. Jarinya menunjuk foto Arsya di layar ponsel. "Biarkan si dokter idealis itu mengurus sampah sampai akhir." Senyumnya melebar.
Nohan tercekat. Instingnya berbisik ini permainan kucing-tikus. "Berarti... tugas saya selesai?”
“Anggap saja begitu, tapi…” Aswan menyapu layar ponsel dengan ibu jari. Gambar Arsya tergantikan oleh dokumen notaris. "Duduk," perintahnya dengan nada yang mendadak ramah.
Pak Nohan mengikuti, duduk di seberang Pak Aswan dengan punggung kaku. Senyum tipis terkembang di wajah Pak Aswan saat ia menekan tombol di telepon mejanya.
"Bawakan dua kopi Kintamani," ucapnya pada seseorang di ujung saluran. Ia beralih pada Nohan. "Kau harus mencoba kopi ini. Biji langka dari lereng timur gunung. Harganya empat juta sekilo, tapi rasanya... sepadan dengan harganya."
Nohan menatap cangkir porselen yang dibawakan tak lama kemudian seperti menatap racun yang disuguhkan dengan senyuman. Aroma kopi yang pekat mengisi ruangan, kontras dengan ketegangan yang tak terucap.
"Aku baru saja mendapatkan laporan, kamu nanti bisa cek isinya," ujar Pak Aswan membuka pembicaraan. Ia menyesap kopinya dengan nikmat sebelum melanjutkan. "Sebelum itu... aku ceritakan sesuatu yang menarik."
Pak Aswan menatap lurus mata Pak Nohan, tatapannya menggali jauh ke dalam jiwa yang gemetar di hadapannya.
"Kamu tahu, belakangan Chalita senang saat aku bacakan cerita, ada dongeng menarik yang masih aku rahasiakan darinya. Tentang seorang raja yang mendapati musuhnya bangkit dari kubur." Suaranya mengalun seperti beludru yang menyembunyikan pisau. "Aneh... raja itu benar-benar yakin dengan kisah kematiannya, tapi... kenapa dia punya kesempatan bangkit lagi? Harusnya dia sudah membusuk di dalam tanah, dagingnya dimakan cacing dan perutnya digerogoti tikus. Harusnya lidahnya sudah membeku selamanya."
Jemari Aswan mengetuk meja dengan ritme yang tak beratura
"Tapi yang paling menakutkan, Nohan, bukanlah orang mati yang bangkit kembali. Yang paling mengerikan adalah pengkhianatan dari tangan kanan yang selama ini menyembunyikan pisau di balik punggungnya yang selalu menunduk pada raja. Sang Raja mencurigainya, namun masih mengasihi bawahannya. Dia pikir belas kasihan adalah kebijaksanaan. Tapi apa yang didapat sang raja? Kudeta. Tikaman dari bayang-bayang. Dan akhirnya... sejarah mencatat raja itu bukan sebagai pahlawan. Tapi bodoh."
Pak Aswan meletakkan cangkirnya dengan hati-hati, seolah takut meninggalkan retakan pada porselennya yang sempurna.
"Aku berencana mengajarkan dongeng ini pada Chalita begitu dia cukup umur," lanjutnya dengan suara lembut seorang ayah. "Pelajaran berharga tentang kepercayaan dan... konsekuensi." Matanya tak lepas dari wajah Nohan yang semakin memucat. "Menurutmu, berapa umur yang tepat untuk memahami cerita seperti itu, Nohan? Delapan? Sepuluh? Lima belas?"
"Kau tidak usah ketakutan seperti itu, Nohan... aku tahu kau orang yang setia, bukan begitu?"
Nohan mengangguk ketakutan, menelan ludah yang terasa seperti pecahan kaca. Sebulir keringat dingin menuruni pelipisnya.
"Setia sebagai anjing penjaga, Pak," akhirnya Nohan bersuara, suaranya hampir berbisik. "Tapi bahkan anjing penjaga kadang merasa kasihan pada pengemis di depan pagar."
Sesuatu berkilat di mata Aswan—entah kemarahan atau ketertarikan—sebelum senyumnya kembali terukir sempurna.
"Nah, kisah itu sudah selesai," Aswan mengakhiri dengan tawa ringan yang tak mencapai matanya. Ia mendorong sebuah amplop coklat ke arah Nohan. "Sekarang bukalah amplopnya. Selesaikan tugas yang aku cantumkan di sana."
Tangannya yang sempat mundur kembali bergerak maju, menepuk pundak Nohan dengan gestur kebapakan yang terasa seperti cap api di kulit. "Aku selalu memilihmu untuk tugas penting, Nohan. Karena aku percaya padamu. Seperti keluargaku sendiri."
Pak Nohan dengan gemetar membuka amplop, matanya membulat sempurna. Foto Arsya saat di rumah sakit. Foto kedua, anak itu dalam pangkuan kakeknya yang dia yakini tersimpan dengan baik di tempat yang hanya dia dan—Seolah ada lampu terang yang menyala—"Andi," gumam Pak Nohan.
Keterkejutannya belum usai melihat bukti transfer uang 3 tahun ke belakang, dan hasil tes DNA dengan nama tertulis Arsya. Dan hasil 100% cocok dengan keluarganya yang saat ini masih hidup.
"Tanpa aku jelaskan, kau tahu laporan di sana bisa membahayakan nyawa seseorang," Aswan memutar cangkir kopinya dengan gerakan malas. "Dan kau juga pastinya sudah tahu, bukan, caranya menyelamatkan orang yang sekarat itu?" sindirnya, mata tajamnya tak pernah meninggalkan wajah Nohan yang memucat.
Kopi mahal di cangkir Nohan masih tak tersentuh, uapnya mengepul perlahan seperti roh yang melayang pergi.
Ketika uap terakhir kopi itu lenyap, Nohan bangkit. Kursinya menggeretak pelan, suaranya terbelah oleh deru nafasnya sendiri. Di antara kepergian uap dan langkah pertamanya, ada sesuatu yang mengkristal: keputusan yang harus dibayar dengan berat.
Pak Nohan melangkah keluar dari ruangan Pak Aswan dengan kaki terasa berlumpur, seolah diseret oleh gravitasi yang melipatgandakan bebannya. Lorong panjang menuju lift terasa seperti jalan setapak menuju tiang gantungan.
Rasa putus asa mengalir dalam dadanya, pekat seperti tinta hitam yang meresap ke setiap sudut jiwanya. Di dalam tadi, dia bahkan tidak sanggup membela diri, seluruh tubuhnya kaku, seolah dibelit oleh ular yang siap meremukkan tulang-tulangnya bila ia berani bergeming. Bagi Pak Nohan, bosnya adalah sosok ular itu, menekannya, mendorongnya ke pinggir jurang agar dia mau bergerak menyelamatkan diri sendiri dengan menghancurkan orang lain.
Pikiran itu membuat perut Pak Nohan bergejolak. Asam lambungnya naik, membakar kerongkongan. Pak Aswan selama ini mengintainya. Dia mengetahui rahasia yang disimpan rapat-rapat selama tiga tahun. Pak Nohan tahu, jika dia gagal kali ini, Pak Aswan tidak akan ragu mengubur Nohan bersama arsip-arsip tua jika sesuatu bocor keluar.
Ia mengeraskan hatinya—atau setidaknya berusaha. Tak ada pilihan lain. Arsya harus dijauhkan dari rumah sakit ini, dari Dokter Nata, dari siapa pun yang mungkin mempertanyakan masa lalu anak itu. Arsya harus menghilang, tapi bukan dalam arti harfiah. Melenyapkan nyawa anak itu bukan sesuatu yang sanggup ia lakukan—tak pernah sanggup, bahkan dulu—tapi membuatnya tak ingat lagi semua yang terjadi di sini adalah satu-satunya jalan. Entah bagaimana, Arsya harus dibuat lupa. Lebih lupa dari sekarang.
Saat tiba kembali di ruangannya, tangannya gemetar meraih ponsel. Layarnya menampilkan kontak yang sebenarnya sangat tidak ingin ia hubungi. Sejak mengurus kasus Arsya tiga tahun lalu, di luar jam kerjanya dengan Pak Aswan, dia banyak bertemu orang-orang dengan moral seumpama debu—mudah terbang ke mana arah angin kekuasaan bertiup. Jiwa-jiwa tanpa batas kemanusiaan, bahkan ada di antara mereka yang menikmati penderitaan orang-orang yang mereka buat sekarat.
Berbeda dengan Andi—yang direkrut karena masih berada dalam lingkar pekerjaan yang sama—dua orang ini berasal dari tempat yang tak ingin diingat Nohan terlalu lama. Ia mengenal mereka bukan lewat Pak Aswan, dan bukan pula dari jalur kerja yang resmi.
Beberapa tahun lalu, saat kebiasaan buruknya masih belum jinak dan meja judi menjadi tempat pelarian, seorang kenalan memperkenalkannya pada dua sosok yang katanya “bisa menyelesaikan masalah tanpa banyak bicara.”
Waktu itu Nohan hanya menanggapi dengan tawa sinis saat mabuk, tapi nama-nama itu tetap melekat. Dan kini, saat hidupnya kembali berada di ujung tanduk, ia terpaksa meraih potongan masa lalu yang seharusnya sudah ia kubur.
Yang membuatnya sedikit tenang: Pak Aswan tak pernah tahu tentang mereka. Tak mungkin. Jika sampai tahu, berarti semua harapannya memang sudah hancur dari awal.
Kali ini, Nohan bertaruh dengan sisa-sisa hidupnya—dan semua uang yang masih ia simpan.
Jarinya yang gemetar akhirnya mengetikkan pesan:
"Bisakah kita bertemu? Aku butuh bantuan. Aku akan bayar kinerjamu dengan seluruh hasil kerja kerasku."
Pesan terkirim, dan Pak Nohan menatap layar ponselnya dengan sorot mata kosong. Ia merasakan sesuatu terenggut dari dalam dirinya—sesuatu yang tak akan pernah kembali. Mungkin itu adalah sisa-sisa kemanusiaan yang masih ia pertahankan selama ini.
Dia termenung sejenak, jemarinya mengusap wajahnya yang terasa sepuluh tahun lebih tua dalam sehari. Meskipun tak akan secerdik rencana-rencana Pak Aswan, ia tahu ia harus bertindak cepat. Teleponnya bergetar—balasan datang lebih cepat dari yang ia harapkan.
"Berikan alamatnya, kami akan siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tidak perlu ragu. Melenyapkan seseorang adalah perkara mudah”
“Jangan sakiti dia.” Tangannya berhenti di atas keyboard. Jantungnya berdetak kencang, seperti ingin ikut bicara. Tapi jari-jarinya—pengecut seperti dirinya—menekan tombol hapus.
Seketika, bayangan Arsya yang tersenyum polos saat memberikan kue pada petugas kebersihan rumah sakit membayang di pelupuk matanya. Wajah kecil yang tak tahu apa-apa tentang kerasnya dunia. Tentang kekejaman orang-orang seperti dirinya.
Pak Nohan menelan gumpalan pahit di tenggorokannya. Matanya terpejam, dan untuk pertama kalinya sejak pekerjaannya dengan Pak Aswan dimulai, ia merasa air mata menggenang di sudut kelopaknya.
"Maafkan saya," bisiknya entah pada siapa—pada Arsya, pada dirinya sendiri, atau pada tuhan yang mungkin sudah lama berhenti mendengarkannya.


 hanyaselingan
hanyaselingan