“Nggak semua orang bisa diselamatkan. Kadang, yang bisa kita lakukan cuma tetap ada di situ, meski kita enggak tahu apa fungsinya.”
Atha pernah membaca kalimat itu entah di mana. Mungkin dari salah satu buku yang ia pinjam diam-diam dari perpustakaan sekolah. Atau dari layar ponselnya saat malam-malam tak bisa tidur, menelusuri forum-forum sunyi yang membahas tentang orang-orang seperti Niko—yang tidak menghilang dari dunia, tapi menghilang dari dalam dirinya sendiri.
Sudah hampir tiga minggu sejak ia pertama kali datang ke rumah itu bersama Dero. Sejak mereka ditolak untuk masuk ke kamar Niko—ruang yang dulunya mungkin penuh ambisi dan nada, tapi kini hanya menyisakan gema kosong.
Atha belum tahu apakah yang mereka lakukan selama ini berhasil. Tapi ia tahu satu hal: berhenti bukan pilihan. Kalau ia menyerah, tak akan ada yang tersisa untuk Niko, bahkan mungkin untuk dirinya sendiri.
Dan sore itu, seperti banyak sore lainnya yang mulai terasa serupa, dia kembali berdiri di depan pagar itu. Kemeja pramukanya masih bau asap dan debu sekolah. Tapi tak apa. Ia tidak ke sana untuk jadi sempurna.
Atha ke sana untuk jadi nyata.
Langkah Atha terhenti di depan pagar rumah itu. Dia melihat, cat putihnya mulai mengelupas di bagian bawah, tergurat lumpur kering bekas hujan semalam. Jendela lantai dua terbuka sedikit, seolah mengintip dunia luar tanpa benar-benar ingin melihatnya.
Ia menekan bel. Sekali. Dua kali.
Tak lama, pintu depan terbuka. Seorang wanita paruh baya berdiri di ambang pintu, mengenakan blus hitam rapi dengan bros perak mengilap di kerahnya. Rambutnya disanggul ketat, bibirnya merah tua, dan tatapannya seperti suara piano tua—tajam dan nyaring, meskipun tak mengeluarkan satu nada pun. Seorang itu terlihat seperti hendak bepergian.
“Sendirian sekarang?” suaranya datar.
“Iya, Tante. Saya cuma mau—“
“Kalau hanya untuk melihat-lihat, lebih baik tidak usah. Niko sedang tidak bisa diganggu.”
Atha menunduk sedikit, menggenggam tali ranselnya erat-erat. “Saya enggak cuma mau lihat, Tan. Saya… cuma pengin bantu.”
“Apa menurutmu, bantuan itu berarti datang setiap minggu dan duduk diam di kamarnya?” Wanita itu menyilangkan tangan di depan dada. Suaranya tidak meninggi, tapi ada nada penolakan yang lebih tajam dari bentakan mana pun.
Atha tidak sempat menjawab. Di belakangnya, suara langkah sepatu menghentak batu kerikil—Dero, muncul seperti biasa tanpa aba-aba. Ia menyender santai di tiang pagar, mengangguk singkat ke arah sang ibu.
“Tante, saya juga mau bantu,” katanya singkat, lalu menoleh ke Atha. “Gue bilang lu jangan berangkat duluan,” bisiknya kemudian.
Ibu Niko menatap keduanya bergantian. Ada kekesalan samar di sudut bibirnya yang menegang.
“Anak saya bukan objek eksperimen,” ucapnya pelan, “Saya tidak butuh simpati remaja sok peduli yang bahkan belum tahu artinya krisis kejiwaan.”
Dero melangkah maju. Untuk pertama kalinya, Atha mendengar suaranya terdengar dewasa. Penuh tekanan, tapi tenang.
“Kami tahu kami bukan ahli. Tapi tante juga tahu, Niko nggak bisa sendirian terus. Kita enggak bisa pura-pura dia baik-baik aja. Dan kalau semua orang cuma nungguin profesional yang belum tentu datang, terus siapa yang nemenin dia hari ini?”
Ibu Niko terdiam. Matanya menyipit. Tapi tak ada bantahan.
“Kami enggak akan ganggu. Kami enggak akan maksa. Kami cuma mau duduk, Tan. Duduk, dengerin, atau diem bareng dia. Itu aja. Setidaknya Niko gak ngerasa sendirian.”
Hening sejenak. Lalu napas berat terdengar.
“Di lantai dua saja, dia udah dipindah ke kamarnya lagi,” ucap wanita itu akhirnya, melepas napas panjang seperti menyerah pada sesuatu yang tak ingin ia akui.
“Kalau dia teriak, kalian keluar.”
“Baik, Tan.”
“Dan jangan menyentuh barang-barangnya.”
“Ngerti, Tan.”
Wanita itu membukakan pintu lebih lebar. “Saya dan suami akan keluar kota lagi malam ini. Urusan sosial.”
Atha hanya mengangguk. Dia tahu itu bukan informasi, tapi peringatan. Mereka akan sendirian.
Begitu mereka naik ke lantai dua, Atha sempat menoleh ke belakang. Ibu Niko berdiri di bawah tangga, menatap mereka seperti wasit pertandingan yang enggan meniup peluit.
Sesaat kemudian, pintu kamar Niko ada di depan mereka lagi. Dunia yang remuk dan hening, menunggu untuk dibuka.
Pintu kamar terbuka perlahan, disambut aroma lembap dan sisa-sisa wewangian kayu manis yang nyaris tenggelam oleh udara basi. Tirai tebal menjuntai rapat menutupi jendela. Cahaya yang berhasil menyusup pun tampak malu-malu—pucat dan redup. Lampu tak dinyalakan.
Kamar itu bukan lagi ruang istirahat. Ia telah menjelma jadi sarang. Berbeda jauh dengan pertama kali Atha masuk sekitar dua bulan lalu. Di dinding, ratusan kertas menempel. Sebagian berupa sketsa tangan kasar—wajah-wajah tak selesai, bentuk tubuh yang melengkung aneh, pulpen hitam yang ditekan terlalu keras hingga kertasnya bolong.
Beberapa lainnya dipenuhi tulisan acak. Kata-kata yang seperti ditulis dalam tidur: “Nggak ada siapa-siapa di sana.” “Gue masih hidup, kan?” “Bunyi-bunyi itu dari mana?” “Berisik banget.”
Niko duduk di kursi kayu dekat jendela. Kepalanya condong sedikit ke samping, seperti sedang mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Matanya kosong. Tak berkedip. Di tangannya, sehelai kertas kusut diremas tanpa sadar.
Atha menarik napas pelan. Ia duduk di ujung ranjang, membuka buku kecil dari dalam tas—sampul lusuh dengan ilustrasi klasik. Tanpa aba-aba, ia mulai membaca.
Suara Atha rendah dan dalam, hampir berbisik.
“Nik, ini gue ada cerita bagus. Gue bacain, ya?” Sesekali Atha melihat ke arah Niko yang masih kosong pandangannya. Dia menarik napas dan mulai membaca, “Pada zaman dahulu, di hutan paling sunyi di dunia, tinggal seekor burung yang tidak pernah bernyanyi...”
Dero duduk di lantai, menyandarkan punggung ke lemari, gitar akustik bersandar di pangkuannya. Ia mulai memetik senar, iringan sederhana—tiga akor minor yang berulang, seperti mantra.
Niko tak bereaksi. Ia tidak menoleh. Tidak bersuara.
Hanya sesekali, bibirnya bergerak pelan. Seolah sedang bercakap dengan udara. Kadang gumaman pelan terdengar, tak jelas artikulasinya. Sekali waktu, ia tertawa kecil. Entah pada apa.
Atha melanjutkan membaca, meski suaranya mulai goyah di beberapa kalimat. Remaja itu tahu betul bahwa Niko tidak sedang menyimak. Tapi ia terus membaca. Ia harus, agar tidak sepi.
Dero menghentikan petikan gitarnya mendadak. Tangannya menggantung di udara, lalu turun pelan. Ia menyandarkan kepala ke lemari dan memejamkan mata.
“Gue nggak tahu ini ada gunanya apa enggak,” gumamnya lirih. “Tapi setidaknya kita di sini.”
Atha tidak menjawab. Ia membalik halaman, menatap kalimat berikutnya, lalu kembali membaca.
Niko tiba-tiba menengadah. Gerakan itu kaku, seperti boneka yang diangkat paksa. Ia memandang Atha lama sekali. Bukan tatapan mengenali. Bukan benci. Bukan takut. Hanya kosong.
Dan di detik yang terasa tak berkesudahan itu, setetes air mata jatuh dari ujung matanya. Tanpa ekspresi. Tanpa suara. Ia bahkan tidak menyeka pipinya.
Atha berhenti membaca. Ia menutup buku itu perlahan. Dero menatap ke arah Niko, tapi tidak berkata apa-apa.
Sunyi menggantung di antara tiga remaja itu. Suara gitar Dero telah berhenti beberapa menit lalu, menyisakan hanya desir angin yang merambat lewat celah jendela dan detik jam dinding yang terdengar seperti gema di lorong kosong. Atha menutup buku cerita yang tadi dia bacakan, menatap sampul lusuhnya sejenak sebelum mendongak dan melirik Niko.
Remaja itu masih duduk di kursi, wajahnya tertutup sebagian oleh rambutnya yang tak terurus. Tatapannya menerawang, seakan melihat sesuatu jauh di luar jendela, di tempat yang bahkan bukan bagian dari dunia ini. Helaan napasnya dangkal. Tangannya—lurus dan pucat—menggenggam lutut sendiri, sesekali bergoyang ke depan dan ke belakang perlahan, seperti anak kecil yang mencoba menenangkan dirinya sendiri.
Atha bergeser sedikit. “Niko,” ucapnya pelan, nyaris seperti berbisik. “Lu masih inget cerita tadi? Yang soal anak kecil di dalam hutan? Gue lanjut, ya?”
Tak ada reaksi.
Dero berpindah duduk di ujung tempat tidur dekat Atha, tangan masih menggenggam leher gitar akustik kecil yang kini terdiam. Ia memalingkan wajah. Frustrasi, lelah, dan cemas membentuk kerutan di dahinya.
“Atha, udah. Orang itu enggak denger,” gumam Dero lirih.
Tapi Atha menggeleng, tak mau menyerah. Ia membuka kembali buku itu. Suara Atha mulai mengisi ruangan. Pelan, ragu-ragu, tapi lembut. Kata-kata mengalir seperti sungai kecil yang mengikis batu.
“...dan di hari ke tujuh, sang anak berdiri di ujung jurang, menantikan suara ibunya yang tak pernah datang...”
Niko bergerak.
Tiba-tiba, cepat dan tak terduga. Kursi bergeser dengan bunyi melengking. Tangannya menghantam meja kecil di samping jendela, menjatuhkan gelas dan pulpen. Dia berdiri dan berteriak—suara melengking yang datang dari perut, dari tempat terdalam yang penuh amarah dan kesakitan.
“BERHENTI!” teriaknya, suara serak dan parau. “Berisik! BERISIK!”
Atha terkejut, buku hampir terjatuh dari tangannya. Dero refleks berdiri, menaruh gitar di lantai dan berjalan cepat ke arah Niko. Tapi Niko lebih cepat—ia menyambar bantal dan melemparkannya ke arah dinding. Lalu rak kecil penuh CD musik yang langsung ditendangnya dengan keras. Disusul lengan kirinya yang digigit sendiri—keras, sampai kulitnya memerah.
“Nik, berenti, Nik! Ada kita di sini! Gue, Atha, sama Dero!” Atha berseru, berdiri tapi tak mendekat.
Niko mundur, memegangi kepalanya, berulang-ulang mengguncang tubuh sendiri. “Gak mau denger lagi... Gak mau! Jangan suruh gue main! Jangan... jangan...!”
Dero menatap Atha—wajahnya pucat, mata lebar. Tapi ia bergerak cepat. Ia membuka lemari kecil dan menarik selimut tipis, lalu bersama Atha, mereka mendekat perlahan.
“Gue selimutin dia ya?” Dero berbisik.
Atha mengangguk panik.
“Bro, ini cuma kita,” gumam Dero ke arah Niko sambil meraih lengannya pelan. “Gak ada panggung. Gak ada suara. Cuma kita. Lu aman.”
Dengan usaha yang canggung tapi penuh kehati-hatian, mereka membungkus tubuh Niko dengan selimut, seperti memeluk luka yang tak kelihatan. Dero mulai menyenandungkan lagu pelan—nada minor yang terdengar seperti lullaby yang kehilangan kata-kata.
Niko mulai mereda. Tubuhnya masih gemetar, tapi ia tak lagi melawan. Kepala bersandar ke bahu Atha, napas terengah, mata basah.
Atha menahan tangis. Saat ia mendongak, matanya bertemu mata Dero. Tak ada kata yang keluar. Tapi dunia mereka seolah runtuh bersama-sama dalam diam.
Akhirnya, Niko berbisik, nyaris tak terdengar, “Maaf... gue... gue enggak kuat denger suara itu lagi...”
Dan saat ia menutup mata, air mata jatuh satu per satu. Atha memeluknya, dan kali ini ia tak mencoba kuat. Sedangkan, Dero menatap lurus ke dinding kamar yang penuh lembaran notasi musik—beberapa disobek setengah, beberapa dicoret tinta hitam.
Di sanalah letak sumbernya, pikirnya. Musik. Tempat luka itu lahir dan terus berdarah.
Niko masih menggeliat di bawah selimut yang membungkus tubuhnya. Napasnya tersengal, tak teratur, seperti seseorang yang baru saja bangkit dari mimpi buruk dan belum kembali ke dirinya. Ia memegangi rambutnya sendiri dengan kedua tangan, bergumam dalam suara serak yang tak bisa dipahami.
Entah yang dilakukan oleh Atha dan Dero ini benar atau salah, yang pasti mereka tidak tahu bagaimana cara untuk menanganinya, dan, mereka kaget.
Atha duduk di lantai tak jauh darinya, punggungnya bersandar ke kaki ranjang. Matanya masih merah, kemejanya kusut karena sempat berusaha menahan Niko. Sesekali ia menoleh, memastikan Niko tidak melukai dirinya sendiri lagi. Tapi tak ada lagi jeritan. Tak ada lagi bantingan.
Dero duduk di sisi lain, lututnya dilipat, gitar akustik kecil yang sempat ia pakai tadi kini tergeletak di lantai, senarnya bergetar samar oleh angin kipas. Ia tidak lagi bicara. Sorot matanya tajam tapi kosong—campuran marah, sedih, dan bingung.
Ruangan kamar itu pengap. Tirai masih tertutup. Lampu kecil di pojok kamar berkedip pelan, membuat bayangan-bayangan di dinding bergerak seperti sosok lain yang ikut mengawasi.
Dalam hening itu, Atha memutuskan untuk bicara.
“Nik... enggak apa-apa. Udah tenang, ya?” Suaranya setipis bisikan.
Tak ada jawaban.
Tapi tubuh Niko mulai gemetar lebih pelan. Tangannya jatuh ke sisi ranjang. Tatapannya menembus langit-langit, tapi kali ini tanpa kegilaan, tanpa ketegangan. Hanya letih. Letih yang tak manusiawi.
Dero berdiri pelan, lalu meraih selimut tambahan dari kursi. Ia mendekat, menutupi tubuh Niko yang kini mulai terkulai, matanya mulai mengerjap berat.
“Niko,” gumamnya. “Tidur aja dulu, ya.”
Mata itu tidak menoleh. Tapi kelopak matanya menutup perlahan. Nafasnya panjang, satu-dua kali, lalu teratur. Tubuhnya rileks, masih bergetar kecil, tapi tidak lagi melawan.
Atha dan Dero saling pandang. Tak ada senyum, tak ada kemenangan. Hanya napas lega yang terlalu berat untuk disebut melegakan.
Mereka menunggu satu-dua menit, memastikan bahwa Niko benar-benar tertidur. Lalu berdiri pelan, berjalan menuju pintu kamar yang terbuka setengah. Mereka keluar tanpa suara, menutup pintu perlahan seperti menutup dunia yang baru saja retak.
Dan begitu pintu itu menutup, seluruh emosi yang tertahan tadi akhirnya jatuh. Berat. Tanpa bentuk.
Tangga rumah itu terasa sempit dan dingin, padahal hanya dua remaja yang mendudukinya. Suara-suara dari kamar lantai dua telah menghilang, berganti dengan keheningan pekat yang tak nyaman. Di bawah cahaya lampu redup di lorong atas tangga, Atha duduk dengan lutut dipeluk, dagu bertumpu di lipatan lengannya sendiri. Tubuhnya sedikit membungkuk, seperti berusaha menyusutkan dirinya ke dalam lubang yang tak ada.
Di sebelahnya, Dero bersandar ke dinding, kepala tengadah, mata menatap langit-langit yang tak menyuguhkan jawaban. Keringat dingin masih melekat di pelipisnya. Jemarinya gemetar sedikit, tapi bukan karena takut. Bukan juga karena lelah. Sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak bisa disebutkan.
Tak ada yang bicara selama beberapa menit.
Bahkan napas pun terdengar seperti beban.
Atha membuka suara lebih dulu. Suaranya parau dan berat, seperti baru melewati badai. “Kalau ada orang lain yang tadi lihat... mereka pasti mikir kita gila,” katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri.
Dero tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu mengusap wajah dengan kedua tangannya. Lelahnya tidak fisik. Lelahnya seperti tumpukan tahun yang tiba-tiba diturunkan ke pundaknya.
“Lu kenapa enggak ikut ninggalin?” tanya Atha kemudian, masih tidak menoleh. “Pas Niko... kayak tadi.”
“Karena lu juga enggak ninggalin,” jawab Dero tanpa jeda. Lalu menarik napas dalam, menunduk, menyandarkan sikunya ke lutut. “Dan... gue juga takut. Tapi bukan takut sama dia.”
Atha menoleh perlahan.
“Gue takut kalau enggak ada yang tetap tinggal buat dia. Buat kita.”
“Ternyata lu bisa baik juga, ya, Der.”
Hening. Hening yang lebih keras dari teriakan tadi.
Atha menunduk lagi. Matanya merah. Tapi ia tidak menangis. Sudah terlalu kering.
“Kenapa gue ngerasa... yang sakit bukan cuma dia?” katanya.
Dero terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya menjawab. “Karena lu juga punya luka. Gue juga.”
Nada suaranya datar. Bukan karena tak peduli, tapi karena kejujuran itu datang tanpa baju, tanpa tameng. Polos dan menyakitkan.
Atha tertawa. Kecil, getir. Lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan.
“Kita ngapain sih... kita ngapain...?” gumamnya di balik telapak tangan.
“Gue juga nanya itu,” kata Dero. “Setiap malam.”
Lalu mereka terdiam lagi. Tapi kali ini, bukan karena tak ada yang bisa dikatakan—melainkan karena keduanya tahu, rasa sakit mereka tak butuh banyak kata. Dia cukup duduk di antara mereka, seperti teman lama yang akhirnya datang menagih.
Beberapa menit kemudian, Dero berdiri, menghela napas panjang. “Gue tidur sini aja, ya. Lu balik, Tha. Lu udah cukup hari ini.”
“Gue gak bisa tinggalin Ni—,”
“Niko gak sendirian, ada gue. Gue gak pulang, udah lu balik, istirahat. Mental lu, semuanya harus lu perhatiin juga. Jangan bikin repot semua orang.” Meski kata-kata Dero masih tidak jauh berubah dengan gaya sarkasnya, tersirat kepedulian yang cukup dalam pada sosok di sampingnya.
Atha menengadah, menatap Dero sejenak, lalu mengangguk.
Dia hendak kembali masuk ke kamar Niko, tetapi diurungkannya. Remaja itu akhirnya menuruni tangga yang terasa seperti berjalan dari dunia lain. Dunia yang hanya terdiri dari luka, suara, dan kenangan yang hancur. Di luar, malam tampak sepi. Langit mendung menyembunyikan bintang-bintang. Lampu jalan memantul samar di aspal basah sisa hujan siang tadi.
Langkah Atha menyusuri jalan pulang dengan lambat. Udara malam menusuk, tapi tidak sedingin yang ia kira. Atau mungkin tubuhnya sudah terlalu beku dari dalam.
Sesampainya di rumah, ia membuka pintu kamarnya, lalu menutupnya kembali perlahan, seolah khawatir akan membangunkan sesuatu.
Ia duduk di ranjang. Lama menatap ke arah jendela. Lalu mengambil ponsel. Layarnya menyala, putih terang di tengah gelap. Jarinya bergerak pelan. Ia membuka catatan dan mulai mengetik.
“Apa boleh kita hancur bareng-bareng, asal jangan saling ninggalin?”
Kata-kata itu menggantung di layar ponsel. Ia tak menekan simpan. Tak pula menghapus.
Ia hanya menatapnya.
Dan dalam diam itu, Atha tahu satu hal: besok mereka akan kembali.
Meski takut. Meski lelah.
Karena tidak ada pilihan lain, selain tetap tinggal.


 harrisradcliffe
harrisradcliffe


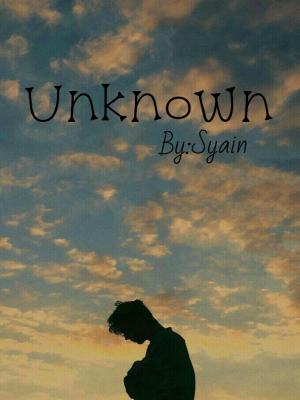







arrghhhhh. aku bacanya ikut frustrasiiiiiii
Comment on chapter BAB 3: TIDAK LAYAK BERTAHAN