Terlalu jahat jika dengan gamblang menyebutkan bahwa ruangan dengan cat tambok putih yang sudah kotor itu adalah kandang ayam. Tetapi, bukan tidak bersih lagi, pemandangan di ruangan Kelas 13 ini benar-benar seperti kapal karam di palung terdalam puluhan tahun. Tidak ada aroma menyengat bau mengganggu hidung memang, hanya saja noda-noda membandel di lantai terlihat jelas seolah-olah menjadi corak seni abstrak.
Saat langkah pertama Atha mendarat di ambang pintu yang terbuka lebar dengan deritan kuat, tidak ada satu mata pun yang memerhatikannya, dia bisa jamin itu. Dia melihat ke sekeliling ruangan, menelisik setiap sudut dan bagian-bagian yang bisa dijamah oleh mata sayunya.
Hatinya gelisah, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk pertama kali di kelas itu. Menengok kesana kemari mencari kursi kosong yang bisa dia tempati. Namun, hasilnya nihil, Atha tidak dapat menemukan satu tempat pun yang kosong. Bukan karena jumlah muridnya yang terlalu banyak sehingga penuh, tetapi karena memang hanya tersedia delapan kursi meja lipat saja.
Cukup lama suasana canggung itu menggelayut di hadapan muka Atha, sampai akhirnya ada satu orang berjalan dengan kasar sembari menyenggol Atha bilang, “Ambil kursi lu sendiri di gudang penyimpanan, kalo lu mau duduk.”
Masih dengan ransel hitam dan pakaian putih abu-abu rapinya, Atha malah terlihat kikuk. Butuh waktu setengah menit untuk dia akhirnya bergerak pergi dari kelas tersebut dan berjalan sambil mengutuk dalam hati menuju gudang penyimpanan.
Astaga, kenapa canggung banget, ish, ayolah, gak boleh kayak orang bodoh, Atha!
Belum juga Atha membuka pintu gudang penyimpanan, dari luar dia mendengar suara geretan kursi di dalam, yang tidak lama kemudian membentuk wujud seorang lelaki lain keluar dari tempat tersebut.
Mukanya tidak familiar, tetapi senyuman yang diberikan oleh remaja berambut french crop itu lebar. Atha hanya membalas singkat.
“Mau ambil kursi meja juga?” tanya remaja itu, langkahnya baru selesai dan dia hendak menutup pintu.
“Iya, nih.”
“Ya udah ambillah, gue tunggu. Ntar kita bareng ke kelasnya.” Tidak terdengar seperti tawaran, tetapi Atha langsung menyetujuinya. “Kelas tiga belas, kan?” lanjutnya.
Atha masuk ke gudang penyimpanan, dan memilih kursi meja mana yang sekiranya masih layak dipakai.
“Iya,” jawabnya singkat.
Remaja diambang pintu itu pun terdiam, dia mengernyitkan dahinya, dan menggerakkan mata seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Atha menyadari kalau orang tersebut sesekali melihat ke arahnya, kemudian ke arah lain, kemudian ke arahnya lagi. Seperti orang kebingungan.
Setelah selesai memilih kursi meja yang paling belakang posisinya, Atha pun turut keluar dari gudang penyimpanan. Dia berjalan mendekati sosok yang sedari tadi kebingungan.
“Ayo, keburu bel,” ajak Atha.
Tidak banyak bicara, keduanya bergegas menuju Kelas 13.
Setelah menunggu sampai bel masuk berbunyi, Atha bisa menyimpulkan kalau ternyata hanya ada sepuluh siswa saja di Kelas 13 ini, termasuk dirinya. Soal kuantitas bukanlah masalah besar baginya, tetapi bagaimana caranya dia bisa bertahan di lingkungan dengan suasana canggung ini?
Wajar, ini baru hari pertama, Atha, gak usah neko-neko, gak usah mikirin yang enggak-enggak. Dalam hatinya terus-menerus membatin.
Bahkan, remaja tadi yang membawa kursi dari gudang pun keberadaannya kini entah di mana. Hanya tersisa kursinya saja yang diletakkan di dekat Atha.
Jika semua orang berpikir kalau di ruang Kelas 13 tersebut sunyi, itu adalah kebohongan dan kesalahan besar. Justru kelas tersebut adalah kelas terberisik yang pernah Atha datangi. Pikirannya yang masih kacau, ditambah kegaduhan tak terelakkan di dalam kelas membuat Atha sebenarnya ingin pulang saja. Namun, dia ingat dengan janjinya kepada orang tua untuk tetap mengikuti program remedial lanjutan apa pun kondisinya.
Mencoba mendistraksi pikirannya, Atha mengeluarkan ponsel dari saku kanan celana abu-abunya. Lelaki dengan warna kulit kuning langsat itu mulai menggulirkan keypad ponselnya, menekan beberapa menu seperti galeri, daftar musik, sampai akhirnya mendarat di aplikasi pesan instan. Melihat-lihat grup kelas yang dia arsipkan, membaca isinya yang ternyata sedang membahas soal lowongan kerja dan kehidupan pasca sekolah.
Luka hati Atha semakin terbuka lebar, dia benar-benar merasakan sakit tapi tak berdarah yang teramat sangat. Air matanya sukar untuk dibendung, hingga akhirnya beberapa detik kemudian menetes.
“Lha, cowok masa nangis, kenapa lu?” Suara tersebut benar-benar mengagetkan Atha. “Coba gue liat.” Tanpa aba-aba remaja cowok tersebut mengambil ponsel hitam miliknya.
Atha yang tidak terima langsung mencoba merebut kembali. Dia berdiri dengan paksa, tetapi hal itu malah membuat pahanya terpentok kursi meja yang ukurannya memang hanya pas-pasan saja. Atha kembali terduduk dan menahan sakit, tetapi emosinya semakin terbakar.
“Balikin hp gue!”
“Wih, lagi BBM-an sama ayang, nih? Diputusin?” Remaja tidak sopan tersebut menatap layar ponsel Atha sambil sesekali menghindar dari rebutan Atha. Suasana kelas yang tadinya bising dengan kesibukan masing-masing, kini riuh fokus antara Atha dan cowok jail itu.
“Woy, woy, udahlah … Udah pada gede juga,” dari belakang, satu orang menggebrak kursi mejanya. “Balikin hp dia, Zal.”
Hanya dengan kalimat tersebut, seorang menyebalkan yang ternyata namanya Rizal itu langsung dengan mudah menyerahkan ponselnya kepada Atha. “Ah, gak seru lu, Der.”
“Lagian lu ngapain ambil-ambil hp dia? Sok jago lu?” Remaja yang duduk di paling belakang itu berbicara sembari memejamkan mata.
Tidak ada perlawanan dari Rizal, keriuhan tersebut pun usai. Dan tepat tidak lama dari itu, seseorang masuk mengenakan pakaian dinas harian hari senin. Sosok itu Atha ketahui, tetapi tidak dia kenali. Atha sering melihatnya saat upacara, tetapi dia tidak pernah mendapatinya di ruang guru atau di tempat tata usaha.
Tanpa salam, tanpa permisi, tanpa tanda. Tiga ‘tanpa’ tersebut menggambarkan kemunculan pria berkumis tipis itu di dalam kelas. Perawakannya kurus, tidak terlalu tua, tidak juga terlalu muda. Umur kisaran tiga puluh awal, dengan gaya rambut rapi, dan warna kulit terang, sosok tersebut dinilai masih bisa lebih tegas lagi dari penampilannya.
“Pagi, Anak-anak. Ke mana ini satu?” tanyanya dengan nada yang kurang ramah, matanya langsung tertuju pada kursi kosong di samping Atha. Sedangkan, Atha hanya menatap sosok di hadapannya sembari menggeleng pelan. Ya, Atha duduk di paling depan dekat dengan meja guru.
Siswa-siswa yang lain pun tidak ada yang menjawab untuk beberapa saat. Namun, seseorang di pojok belakang tertawa kecil, suara ringannya menggema cukup jelas di antara suasana kelas yang tidak sepenuhnya hening. Rizal, yang sedari tadi sudah bikin onar, langsung nyeletuk.
“Paling masih tidur, Pak. Masih mabok semalem kayaknya.”
Beberapa anak lainnya tertawa. Atha tidak. Pak guru itu juga tidak.
“Kalau memang tidak bisa ikut kelas dengan baik, saya bisa bantu urus surat pengunduran diri. Gampang, kok.”
Seisi ruangan langsung hening membungkam.
“Tidak ada pengantar. Saya langsung saja. Ini kelas remedial akhir. Kelas untuk orang-orang yang gagal. Tidak usah tersinggung, itu kenyataan. Tapi dari kegagalan itu, saya mau lihat siapa yang masih bisa bangkit. Atau tetap tenggelam.”
Atha merasa jantungnya menegang sesaat. Suarasosok di hadapannya terdengar sangat datar, tapi punya bobot yang berat. Kata-katanya menyakitkan, tetapi juga seperti tamparan yang gak bisa dihindari.
“Nama saya Narya Kurniawan. Bisa kalian panggil Pak Narya. Saya wali kelas kalian sampai remedial ini selesai. Kalau selesai. Saya tidak akan banyak ikut campur urusan pribadi kalian, dan kalian juga jangan banyak menuntut dari saya. Simpel.”
Ia menaruh satu map tebal di atas meja guru, kemudian menyisir rambut klimisnya pelan dengan tangan.
“Jadwal pelajaran, peraturan kelas, dan sistem penilaian ada di sini. Saya tidak akan ulang dua kali. Hari ini hanya pengantar. Mulai besok, kegiatan belajar akan berjalan sesuai jadwal. Kalau mau tetap duduk di sini sampai akhir, atur diri kalian masing-masing.”
Setelah beberapa menit bicara tanpa arah dan hanya menjelaskan hal-hal teknis soal jadwal, Pak Narya akhirnya keluar dari kelas tanpa mengucap salam ataupun penutup. Pintu tertutup kembali, dan suasana kelas langsung berubah riuh seperti sedia kala. Suara tawa, teriakan, hingga lagu dari speaker bluetooth kecil di pojokan saling bertabrakan, seperti enggan memberi ruang untuk keheningan.
Atha duduk diam. Jemarinya menggenggam ponsel yang tadi nyaris diambil paksa. Ia mencoba menenangkan degup jantungnya yang belum sepenuhnya stabil. Baru hari pertama, dan ia sudah kehabisan tenaga.
Belum lama, suara pintu dibuka lagi.
Seseorang masuk dengan langkah sedikit berat. Ransel disampirkan di satu bahu, rambutnya terlihat berantakan seperti belum sempat disisir, dan wajahnya lelah, seperti habis disedot semua energi positif di dunia. Remaja itu melirik sekilas ke arah bangku-bangku kelas, lalu berjalan santai ke arah bangku kosong di sebelah Atha.
Itu adalah anak dari gudang penyimpanan tadi pagi. Dan kursi kosong itu adalah kursi yang tadi dia bawa bersama Atha.
Niko namanya.
Tidak banyak yang melirik atau peduli. Harus mulai terbiasa, di kelas ini, kehadiran satu orang seperti tidak berarti apa-apa.
“Abis dari ruang BK,” katanya, menurunkan ranselnya dan duduk. “Ternyata formalitasnya ribet juga, padahal mah udah jelas gue ditempatin di sini.” Padahal tidak ada yang bertanya dan menyapanya.
Atha pun hanya melirik sekilas. Dia masih enggan terlibat dalam percakapan panjang.
Niko bersandar santai, membuka botol minum dari ranselnya dan meneguknya pelan. Setelah beberapa detik keheningan, dia bersuara lagi, kali ini nadanya agak heran.
“Eh, eh, tapi gue masih penasaran sih. Lu ... Atha Pradana, kan?”
Atha langsung menoleh. Matanya menajam. Nama itu terlalu formal untuk disebut sembarangan apalagi oleh orang baru.
Niko nyengir sedikit. “Gue gak sok kenal, tenang aja. Tapi nama lu tuh sering banget lewat. Ranking dua paralel satu angkatan, anak IPA suka ikutan olimpiade, ketua bidang akademik OSIS, aktif seminar ... apalagi, ya?”
Atha tetap diam, tapi matanya memicing. Tersinggung? Mungkin. Atau sekadar lelah mendengar kenyataan yang dulu pernah jadi identitasnya.
“Gue anak IPS,” lanjut Niko. “Makanya gak pernah ketemu. Kita beda dunia. Gue juga gak pernah nongol di kegiatan sekolah. Gue cuma dateng, absen, cabut. Gue aktifnya di luar. Band.”
Dia pun bersandar, menatap langit-langit. Dan, lagi-lagi masih tidak ada yang bertanya pada dia soal apa saja pencapaiannya.
“Band gue lumayan. Manggung dari cafe ke event. Musik doang yang bikin gue ngerasa hidup. Tapi ya… mungkin itu juga yang bikin gue gak lulus, haha, Waktu ujian nasional kemarin gue malah lagi di luar kota buat gigs kecil. Udah deh, otomatis dicoret.”
Atha menatap ke depan. “Berarti lu gak niat dari awal.”
“Bisa dibilang gitu.” Niko tidak terlihat menyesal. “Tapi bukan berarti gue gak peduli. Gue Cuma ... gak cocok aja sama sistem mereka. Lo juga, kali?”
Atha menghela napas. Berat. “Gue jatuh karena satu kesalahan. Terlalu fatal buat dimaafkan sama sekolah,” katanya pelan.
“Skandal? Lu ngehamilin anak orang?” tanya Niko asal-asalan.
“Gila lu. Udah, gak penting,” potong Atha cepat. Nada suaranya tidak marah, tapi cukup tegas untuk menghentikan pertanyaan lanjutan.
Niko mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara lebih rendah, “Oke, oke. Gak maksa. Tapi gila juga, sih. Anak secerdas lu bisa nyangkut di tempat ini. Jadi, ada harapan juga buat kita-kita yang ‘keliatannya’ bego.”
Atha tidak membalas. Tapi dari caranya menunduk, bisa dilihat dia sedang berpikir—tentang banyak hal, mungkin juga tentang apa yang baru saja didengar.
Niko kembali meneguk airnya, lalu menyenggol pelan siku Atha.
“Tenang aja, bro. Dari ceritanya, kelas ini emang gila, tapi ya kita udah di sini. Jadi, mending kita gila bareng.”
Atha akhirnya tersenyum tipis. Sedikit, tapi cukup untuk menutup hari itu dengan sesuatu yang bukan beban. Tapi sebelum senyum itu benar-benar mengendap, dari pojok ruangan terdengar suara Rizal—pelan tapi cukup jelas karena di ruangan tersebut hanya ada sepuluh orang saja.
“Oy, Nik. Tau nggak, tuh anak...”
Niko menoleh.
“…katanya sih, dia yang dulu bikin soal ujian sekolah bocor.”
Atha sontak menegakkan punggungnya.
Hening. Suasana yang tadinya masih riuh perlahan mencair jadi sunyi penuh bisik. Beberapa pasang mata langsung melirik ke depan, ke arah Atha dan Niko. Sebagian memasang ekspresi penasaran, sebagian lagi—sinis.
Niko menatap Atha lekat-lekat. Wajahnya tak lagi santai. Kali ini ada sedikit keraguan, meskipun cepat disembunyikan.
“Beneran?” bisiknya, tak sebercanda tadi.
Atha tidak menjawab. Dia menghela napas, pelan. Tangannya gemetar dan disembunyikan di bawah meja. Dia benci perasaan ini—dilihat, dinilai, dibicarakan. Semua orang seperti punya cerita tentangnya, tapi tak satu pun dari mereka benar-benar tahu.
Bel istirahat pun berbunyi, tetapi Niko belum beranjak. Dia hanya menatap Atha dalam diam. Bukannya ingin ikut-ikutan menyudutkan, tapi rasa ingin tahunya terlalu besar untuk ditahan. Ada banyak pertanyaan di kepalanya, dan Atha adalah teka-teki yang terlalu mengganggu untuk dibiarkan.
“Gue nggak percaya gituan sih,” gumam Niko akhirnya, mencoba meredam suasana yang mendadak terasa dingin. “Kalau orang sepintar lu mau nyontekin anak-anak, buat apa juga dia capek-capek jadi pengurus OSIS?”
Atha tidak menjawab, tapi bola matanya bergerak, melirik ke arah Niko seperti ingin mengatakan sesuatu. Sayangnya, suara dalam dirinya lebih nyaring dari apapun yang ingin dia ucapkan.
Lu percaya atau nggak, tetep aja gue udah jatuh di mata semua orang.
Satu per satu siswa yang jumlahnya bisa dihitung jari pun keluar, ada yang ke kantin, ada yang hanya duduk di selasar depan kelas sambil memutar musik dari ponsel, dan ada juga yang sembunyi-sembunyi membawa rokok ke toilet belakang kelas.
Atha bergerak perlahan, mengambil botol minum dari ranselnya dan menyandarkan punggung ke kursi. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba mengatur napas, lalu membukanya kembali hanya untuk menemukan Niko masih memperhatikannya.
“Lu kenapa sih?” tanya Atha, suaranya datar.
Niko mengangkat bahu. “Gue cuma ... penasaran.”
“Penasaran sama orang gagal?”
“Penasaran kenapa orang kayak lu ada di sini.”
Atha nyaris ingin tertawa, tapi yang keluar hanya gumaman miris. “Kadang lu gak perlu nyari tahu kenapa seseorang jatuh. Lu cuma perlu pastiin jangan ikut nginjek mereka pas jatuh.”
Niko diam. Ia tidak menyangka kalimat seberat itu keluar dari mulut cowok yang bahkan tadi pagi masih terlihat seperti boneka baru dikeluarkan dari etalase toko.
“Lu tahu nggak?” Atha kembali bicara, tapi kali ini pandangannya lurus ke depan, kosong. “Gue bahkan gak yakin masih bisa percaya sama diri gue sendiri.”
Mendengar itu, Niko benar-benar terbungkam. Dia mulai beranjak dari duduknya, dan pergi meninggalkan Atha sendirian di dalam kelas. Tidak, Atha tidak sendirian, dia berdua dengan seseorang yang membela dirinya dari kejailan Rizal tadi pagi. Dero namanya.


 harrisradcliffe
harrisradcliffe

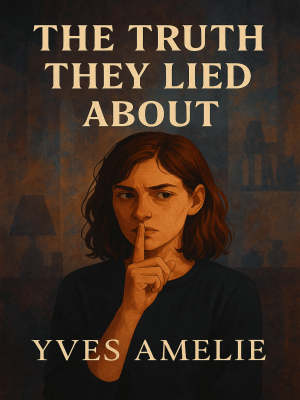





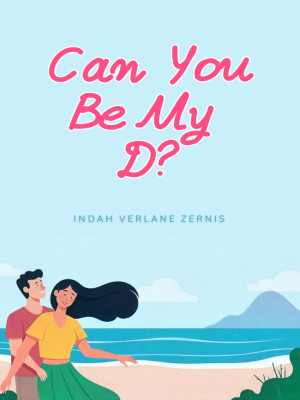
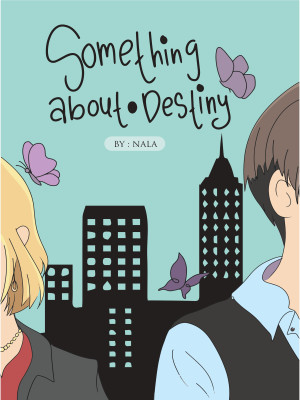
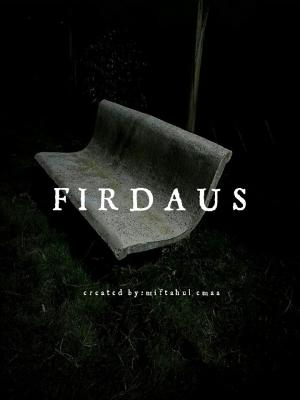
arrghhhhh. aku bacanya ikut frustrasiiiiiii
Comment on chapter BAB 3: TIDAK LAYAK BERTAHAN