Ersa menepis tangan Binar, ketika pemuda itu coba menolong.
'Masa ini karma, sih?' Ersa bertanya pada dirinya sendiri.
Hanya perkara mengatai Binar lemah ... tahu-tahu pandangannya berputar-putar dan menjadi gelap untuk sesaat.
Tahu-tahu ia sudah tergeletak di atas paving. Mau bangun sendiri sulit. Ia benci terlihat lemah. Kenapa juga harus begini saat ada Binar? Kelihatan lemah di depan musuh, sama sekali tidak elit.
Mungkin Binar masih keturunan dukun. Makanya malati.
"Udah bagus Binar mau nolong! Lo lagi lemah gitu masih sok banget!" Jena kembali mencak-mencak mewakili isi hati Binar.
Ya ... Binar sebenarnya juga kesal. Tentu saja. Tapi di saat seperti ini, hatinya yang lembut itu tetap merasa tidak tega.
Ia mengulurkan tangannya lagi. Menarik tangan Ersa, membantu Ersa duduk dulu setidaknya.
"Lo demam, Sa. Tangan lo panas. Mending istirahat di dalam, ada kasur kok. Mungkin nggak senyaman kasur lo di rumah, tapi setidaknya lebih nyaman dari paving. Ada AC-nya juga kok."
Memastikan Ersa duduk dengan tegak, Binar berlutut di depannya, dalam posisi membelakangi Ersa.
"Mau ngapain lo?" Ersa mendorong punggung Binar.
Binar meringis, dorongan itu mengenai jajaran sumber pegal dan nyeri tubuhnya.
"Bisa nggak sih, nggak usah barbar? Tangan lo nggak ada akhlak, dari tadi ringan banget sama Binar!" Jena kembali mencak-mencak. Tak terima Binar terus disakiti.
Jena memegangi dua tangan Ersa, lalu dengan sengaja menelangkupkan pada leher Binar di depannya. Memanfaatkan kondisi Ersa yang sedang lemah. Ia tahan punggung Ersa supaya tidak berusaha berontak lagi.
"Lemes begitu tapi songongnya bukan main!" Jena tak henti-hentinya menggerutu pada Ersa.
"Gue nggak kenal sama lo, ya. Jangan ngomel terus sama gue!" Ersa lama-lama kesal dengan keberisikan Jena.
"Lo nyakitin Binar. Siapa pun yang nyakitin Binar, harus siap lawan gue!" Jena memang selalu berada di garda terdepan dalam membela Binar.
"Udah, Jen ...!" Binar jadi ikut pening, Jena dan Ersa malah ribut sendiri.
Binar berusaha koorperatif bekerja sama dengan Jema, yang masih memegangi badan Ersa dari belakang. Binar cukup susah berdiri, sebab Ersa ternyata berat.
***
"Nih dikunyah dulu. Terus buburnya dimakan." Binar menyerahkan nampan berisi bubur dan tablet kunyah pereda asam lambung.
Ersa hanya bergeming. Ia tidak lagi berontak, tapi malah diam seribu bahasa. Terlihat dari sorot matanya ... banyak hal yang sedang Ersa pikirkan.
"Tahu lagi sakit kenapa berangkat?" Binar duduk di pinggiran ranjang.
"Bukan urusan lo," jawab Ersa akhirnya.
"Harusnya ke rumah sakit aja. Minta obat yang paling manjur. Sayang punya bokap tajir, kalau duitnya nggak dimanfaatkan semaksimal mlungkin."
"Bisa diem nggak?"
Binar terkekeh. "Agak heran sebenarnya, lo bisa sakit juga, Sa."
"Gue juga manusia kalau lo lupa."
"Baru tahu lo manusia. Gue pikir selama ini batu."
"Nggak usah mulai!"
"Bercanda, Sa. Jangan serius-serius amat jadi manusia!"
"Kita nggak seakrab itu buat saling bercanda."
"Kalau gitu mulai sekarang kita coba lebih akrab. Lagian kita satu sekolah ... satu kelas pula ... wajar kalau kita berteman akrab. Malah aneh kalau bersikap layaknya musuh. Padahal kita sebenarnya nggak ada masalah."
"Sorry, gue menolak. Nggak ada minat akrab sama lo."
Binar lagi-lagi terkekeh. Ersa benar-benar tak berniat menyembunyikan rasa tak sukanya pada Binar.
"Sebenarnya kenapa, Sa? Kenapa lo kayaknya benci banget sama gue?" Binar akhirnya ada kesempatan menanyakan apa yang membuatnya penasaran.
"Nggak perlu ada alasan buat benci orang. Pokoknya lihat lo bawaannya benci."
"Nggak mungkin, lah. Pasti ada alasannya."
Ersa membuang pandangan ke arah lain.
"Lo tuh beruntung, Sa. Orang tua lo ada uang buat bayar bimbel mahal. Lo punya fasilitas lengkap. Lo punya akses mudah buat segala urusan. Jujur gue iri. Lo harus bisa bikin orang tua lo bangga. Mumpung masih punya orang tua. Kalau gue wajar iri sama lo. Secara lo punya segalanya. Harusnya gue yang benci lo saking irinya. Eh ... ini malah kebalikannya. Alasan lo benci sama gue ... nggak mungkin karena iri juga, kan? Mana ada yang bisa dijadikan sumber iri dari gue?"
Binar menertawai dirinya sendiri.
Ersa masih diam. Padahal benar tebakan Binar. Ia benci pada Binar memang karena iri.
Bukan karena harta benda, atau pun kemewahan lain yang berhubungan dengan materi. Hanya karena Binar selalu lebih unggul dalam hal prestasi. Yang pada akhirnya membuat Ersa dituntut harus bisa mengalahkannya. Dan Ersa ... belum mampu melakukannya.
"Kalau gue jawab beneran karena iri gimana?" Ersa balik bertanya.
Yang membuat Binar kembali tertawa kecil. "Lo udah mulai bisa bercanda ya sekarang. Perkembangan bagus."
"Apa gue kelihatan lagi bercanda?"
Binar terdiam. Ersa memang tidak terlihat sedang bercanda.
"Memangnya apa yang bikin lo iri, Sa? Kerjaan gue di warung soto? Kerjaan gue di sini? Atau kerjaan gue bantu jualan pecel tumpang? Atau ... iri gue nggak punya orang tua? Kalau soal asam lambung, masa lo iri? Kan lo juga punya!"
Ersa mengernyit. Apa benar Binar bekerja sebanyak itu? Apa benar Binar tidak punya orang tua?
Tapi Ersa sama sekali tak berminat adu nasib dengan Binar. Langsung ia utarakan saja intinya. Biar Binar tahu sebenarnya apa masalahnya.
"Ranking 1 paralel," jawab Ersa singkat, padat, dan jelas.
"Oh ... jadi itu. Lo harusnya nggak perlu iri soal itu. Soalnya gue memang harus ranking 1. Gue bukan orang kaya. Biaya SPP sekolah kita mahal. Mana gue mampu bayar, jika tanpa beasiswa? Kalau prestasi gue turun, bisa-bisa beasiswa dicabut. Lo enak, nggak perlu mikir uang SPP!"
"Asal lo tahu ya, Bin. Hidup gue selama ini menderita karena lo."
"Kok bisa?"
"Ya bisa! Gara-gara gue selalu kalah dari lo, ayah gue menjelma jadi Genderuwo. Gue dituntut supaya bisa ngalahin lo. Supaya nggak bikin dia malu. Dia maunya gue ranking 1 paralel. Biar nggak ada kecacatan profil, sebagai penerus perusahaannya!"
Binar belum menjawab apa pun. Masih membiarkan Ersa untuk meluapkan segalanya. Ia pun bersedia untuk mendengar semuanya. Supaya masalah di antara keduanya ada harapan untuk dapat solusi.
"Gue nggak pernah istirahat. Gue nggak pernah bisa main kayak anak muda pada umumnya. Gue juga mau bebas. Gue nggak mau kehilangan masa muda!"
Binar masih bergeming. Sesederhana itu keinginan Ersa. Eh ... tidak sederhana juga, sih. Yang sebenarnya juga merupakan keinginan Binar.
Bisa bebas menikmati masa muda, seperti orang lain pada umumnya.
"Kalau memang itu mau lo, gue bisa kok merelakan beasiswa gue," jawab Binar akhirnya.
Gantian Ersa yang bergeming. Ersa menatap Binar lekat-lekat.
"Tapi lo juga harus tanggung jawab. Bayarin uang SPP gue!"
Ersa tak kunjung menjawab. Pikirannya sedang sibuk mempertimbangkan ucapan Binar.
"Perkara gini doang, tapi lo sampai benci gue bertahun-tahun, Sa. Harusnya lo bisa ngomong baik-baik. Kita cari solusinya."
"Sebenarnya harga diri gue agak tercoreng. Lo sengaja ngalah demi gue bisa ranking 1. Tapi nggak apa-apa, lah. Masa muda gue lebih berharga. Dari pada gue terus dituntut sempurna sama bapak gue sendiri. Ya udah kalau lo mau ngalah dengan sukarela. Ini keuntungan besar buat gue. Bayar SPP lo doang mah kecil!"
Binar mengangguk mengerti. "Ya udah. Mulai sekarang gue nggak akan terlalu berusaha keras. Gue sebenarnya juga udah cape."
Binar beranjak dari sana. "Itu obatnya buruan dikunyah. Buburnya dimakan. Gue balik ke depan, nerusin kerjaan. Oh, iya. Itu nggak gratis, ya. Soalnya gue ambil apa-apa di minimarket juga bayar. Nggak ada jatah karyawan."
"Astaga ... berapa sih harganya? Bubur instan doang sama promah!"
"Harganya emang nggak seberapa. Tapi gue setengah mati dapetin duit segitu!"


 sheilandak
sheilandak



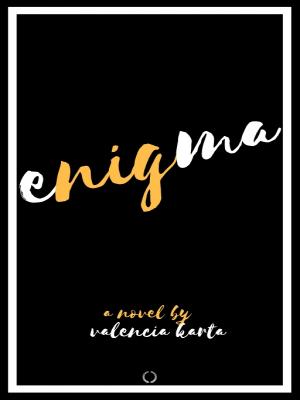






Gak di next kak?
Comment on chapter Hari Pembagian Rapor