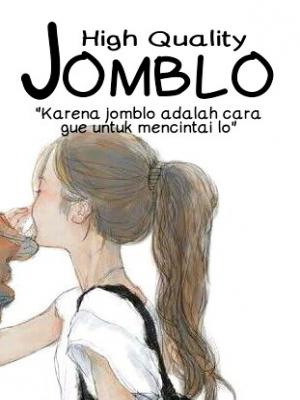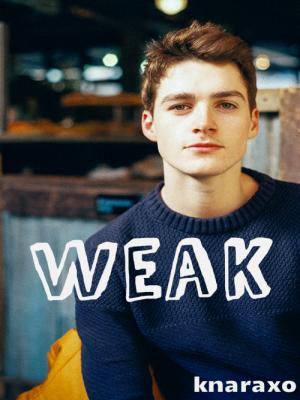“Makanannya enak, Tante. Terima kasih sudah ajak saya makan bersama. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu, Tan.” Anbi berpamitan dan menyalami Mama dengan sopan, tak lupa pamit pada Hima, Rosa, bahkan Hanif yang lagi-lagi cengegesan.
Aku berdiri dan membuka pintu, mengantar cowok yang memasang jaket denimnya hingga depan gerbang. Aku memanggilnya untuk bicara sejenak dan tetap memikirkan kalimat yang tepat untuk kata terima kasih atas bantuannya beberapa hari lalu.
“Makasih udah antar gue.” Aku mengepalkan tangan, melirik Anbi untuk melihat reaksinya. Lantas, mataku hanya fokus pada liontin ruby di dada cowok itu. “Itu … gue belum sempat berterima kasih waktu lo bantu di tangga sekolah,” kataku gugup. Kutatap wajahnya yang menahan senyum dan mukaku menghangat untuk melanjutkan, “makasih atas bantuannya, Anbi.”
Segera kupalingkan wajahku. Ditatap seperti itu membuat jantungku berdebar duakali lipat lebih cepat. Dan, respons Anbi Sakardja adalah tawa. Apa dia mengejekku?
“Kalau gitu, besok jangan muter jalan buat ke kantin,” katanya sambil tertawa. Aku menutup wajahku malu. Jadi, Anbi tahu aku melakukan hal merepotkan itu untuk menghindarinya? Sungguh memalukan.
“Soal itu ….” Aku tak ingin melepaskan tangan dari mukaku. Rasanya malu sekali, sungguh. Akan tetapi, tangan hangat Anbi meraih tanganku sehingga mata kami saling bertemu. Senyum jahil di wajahnya tergantikan dengan senyum yang melembut.
“Gue pamit. Sampai besok, If.”
Nama kecil itu terasa asing di telingaku, tetapi aku menyukainya. “Hati-hati, An.” Dan ia melebarkan senyumnya. Lantas, aku tersadar akan tangannya yang masih memegang tanganku. “Ini modus juga?”
Anbi justru mengeratkan genggamannya dan tertawa. “Haha, ketahuan.”
***
Melewati IPA 5 adalah tantangan terbesar tahun ini. Perkataan cowok penghuni kelas itu membuatku menahan napas kala melewati koridor. Tak lain karena siulan jenaka beberapa murid cowok yang mengingatku jatuh dari tiga anak tangga, dan julukan ‘Cewek Tangga’ berkumandang setiap aku lewat.
“Malu banget,” keluhku tak tahan setelah berbelok dari ruang Konseling, lantas memasuki area ramai kantin. April hanya tertawa di sampingku setiap kami lewat kelas itu. Tiga hari aku menahan perasaan malu ini.
“Hei,” sapaan itu membuat kami mendekat ke meja di mana Anbi Sakardja tengah makan siang. Dan, ia tidak sendiri. Panji dari klub band ada di sana dan tersenyum lebar padaku. Entah mengapa, aku bisa menebak apa yang akan ia bicarakan.
Setelah perkumpulan tiga hari lalu dan setiap kami tak sengaja bertemu, Panji selalu mengingatkan untuk bergabung dalam band dengan kata ‘sedikit memaksa’ dilontarkannya. Aku selalu menunda jawaban. Masih memikirkannya. Dan, semakin lama dipikirkan hanya membuatku bertanya-tanya, “Apa yang membuatku takut untuk kembali bermusik?”
Semalam aku sempat membicarakannya bersama Kakakku yang kembali meledek perihal uang yang nominalnya disebutkan dalam bahasa ‘gocap’. Tak tersinggung, aku menanyakan keputusanku untuk kembali memainkan musik.
“Gue pendukung lo nomor satu kalo balik main gitar,” ujarnya dengan semangat, sampai bangkit bersila di kasurku. “Gue pengin denger lagi lo main, Faa.”
Senyumku terbit. Aku memandang buku di meja belajar hanya agar mataku yang berembun tak terlihat oleh Hima. Hatiku tersentuh dan perasaan lega melahapnya. Hima kembali merebahkan diri memandang plafon kamar yang perlu dicat ulang seraya mengembuskan napas panjang.
“Lo masih kecewa sama keluarga kita, Faa?” tanyanya, aku terdiam. “Pasti lah ya. Gitar kesayangan lo diancurin Bapak dan Mama juga ambil uang buat pengobatan Bapak, terus Rosa yang kurang ajar juga bakar buku-buku musik lo. Dan malaikat di rumah ini tuh cuma gue, Faa. Lo mau gabung?”
Tawa Hima membuatku meringis. Hela napas Kakakku kembali terdengar dan ia menjelaskan, “Jangan khawatir Mama ambil uang lo diem-diem lagi … yang ini biar gue urus buat pengobatan Bapak. Kalau Bapak ikut hancurin gitar lagi … biar gue beliin deh. Ditambah Rosa yang sok cakep, biar gue pukul aja biar tau rasa.”
Aku mengedipkan mata dan sebutir air membasahi buku. Aku menahan napas agar isak tangisku tak terdengar, tetapi rasanya percuma setelah Hima kembali bicara lembut. “Lo jangan berhenti bermimpi, Faa. Jangan kalah sama kecewa. Cukup gue aja.”
Berulang kali kuhapus air yang membasahi pipi, mataku tak kunjung reda membasahinya. Meski isak tangisku yakin terdengar telinga Hima, ia membiarkanku seolah tak melihat apa-apa. Namun, aku paham sekali bahwa ia hanya memberiku waktu.
“Lagian lo nggak bener-bener berhenti ‘kan, Faa? Gue tahu lo diem-diem kumpulin uang buat beli gitar lagi.”
Meski demikian, aku masih ragu untuk bergabung band saat Panji tetap sedikit memaksa. Alasan seperti ini mungkin membuat Panji berhenti, “Gue nggak punya gitar, Kak.”
Panji menertawakan. Aku meminum teh botolku dan tersedak saat Anbi tiba-tiba satu jengkal dari wajah. “Kenapa?” bisikku. Dan, Anbi ikut berbisik di telingaku, “Lo habis nangis? Kenapa?”
Seketika itu sekujur tubuhku merinding dan memanas sehingga aku menutup wajah. Bagaimana bisa ia menebak dan sasarannya tepat. Dekat dengan Anbi Sakardja memang membuatku perlahan mati dengan senjata bernama malu ini.
“Yudis punya dua gitar. Dia nggak bakal keberatan buat pinjamin satu. Jadi, apa yang membuat lo ragu buat gabung?”
Aku bergeser sedikit untuk menjaga jarak dari Anbi. Apa ini waktu yang tepat untuk membulatkan tekadku yang ragu-ragu? Aku mengembuskan napas sebelum bertanya, “Apa yang membuat lo bertahan buat main musik, Kak? Padahal sekolah nggak mendukung dengan kasih ruang khusus.”
Panji terkekeh. Ia tersenyum lebar seolah ada kebanggaan sendiri. “Ini penting, wahai junior tersayangku. Lo butuh seseorang untuk dijadikan alasan. Gue nggak menyarankan itu harus pacar, karena motivasinya cuma sementara. Paman gue pernah bilang, main musiklah untuk seseorang. Jadi, apa lo punya seseorang itu, Iffaa?”


 azzmifaitsmiddielah
azzmifaitsmiddielah