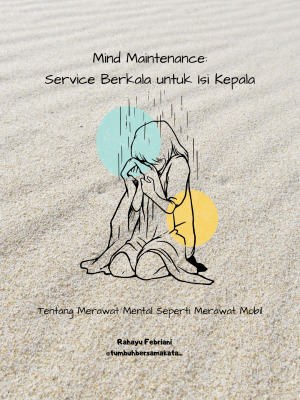“Rasakan berbagai emosi untuk menjadikannya sebagai pengalaman di masa mendatang. Jangan takut untuk merasakan emosi pahitnya dalam pertemanan, keluarga, atau bersama pasangan. Semua emosi selalu memiliki pesan tersendiri untuk diperbaiki.”
Hanya baru beberapa kali pertemuan, tetapi aku selalu terkesan pada cara bicaranya yang lugas, gestur tubuhnya yang menyebarkan aura positif, ditambah mimik wajah yang ramah. Namun, aku kagum pada orang tua yang memberikan nama Indah Fitri pada wali kelasku.
“Ikatan dengan sesama manusia itu rumit. Akan selalu ada kondisi dimana kalian harus memustuskan untuk bertahan atau meninggalkan.” Ia melanjutkan pembicaraan yang selalu dilakukannya sebelum memulai kelas pagi. Aku senang mendengarnya, tetapi murid di bangku belakang menghela napas berat. “Seiring berjalan waktu dan kalian bertumbuh menjadi dewasa … kalian akan memahami rasa pahit itu.”
Aku mengangguk-angguk. Sepertinya orang dewasa senang mengatakan istilah memahami saat usia kami layaknya mereka. Saudariku juga menyatakan hal serupa.
“Namun, ada satu hal yang bisa mengatasi hal itu. Kalian penasaran?”
Aku tertawa dalam hati, antusias dengan nada lemah kawan sekelas itu cukup lucu. Bu Indah tak melunturkan senyumnya di wajah, beliau tetap menyampaikan, “Keberanian. Perasaan itu sangat berharga. Untuk memilih bertahan atau pergi dari seseorang, pasti memiliki resiko menyakiti atau tersakiti. Maka, menjadi berani sangat berperan penting disituasi ini.”
Aku meringis. Kuakui bahwa diri ini tak memiliki sikap berani seperti yang dibicarakan. Menolak pun, rasanya masih kelu kuucap. Payah, rutukku dalam hati. Situasi ini membuat kepalaku menoleh ke bangku kedua pada sisi kiri. Seorang perempuan yang keningnya kemerahan oleh jerawat tampak cemberut memangku dagu.
Aku menghela, tak senang memikirkan hubungan kami. Dia Usa, teman sebangku kala kami masih semasa putih biru selama satu tahun. Selama itu pula kata teman mengitari hubungan kami. Setidaknya itulah bagiku. Mungkin, menurut Usa yang temannya berada di mana-mana, aku hanyalah satu mahkluk yang tak perlu diperhatikan.
Pernyataan tersebut menjadi lebih kuat kala ia meminta, “Lo bisa pindah tempat duduk sama Zia, nggak? Soalnya temen gue Dewi mau sebangku. Lagian tahun lalu, lo selalu sama gue.”
Jadi, kusimpulkan bahwa kami bukanlah teman. Sejak saat itu, aku tak ingin bersitatap bahkan menghindarinya yang selalu bersama teman-temannya. Mengapa aku begitu sakit hati dan merutuk setiap kali melihatnya? Apa karena Usa adalah teman pertamaku?
Anehnya, perempuan berjerawat itu—maaf mengatakan hal seperti itu, tetapi mulutku menjadi nakal jika bersangkutan dengannya—mengatakan hal yang cukup lucu kala jam istirahat di SMAN 2 Dharma ini—SMADHA.
“Lo mau sebangku sama gue nggak, Faa? Kayaknya gue nggak bakal betah sama dia yang bau badan. Mending lo sama gue aja deh,” tawarnya yang tak terdengar menawar, bagiku.
Apa ini pertanda untuk mulai melangkah menjadi berani seperti yang Bu Indah sampaikan pagi ini? Harus berani. Aku tak ingin menjalin hubungan pertemanan dengan Usa lagi.
“Maaf, Usa, nggak bisa.” Aku bersorak dalam kalbu. Kata itu cukup memakan waktu agar aku bisa menjawab Usa yang saat itu pula mendecak tak senang. Apa perempuan berjerawat ini merasa tersakiti atas penolakanku? Anehnya, aku menikmati jika memang demikian.
Jahat banget.
“Iffaa, lo mau makan di kantin nggak? Eh ….”
Itu teman sebangku, April Lia. Datang dari pintu kelas dan terhenti saat melihat Usa di tempat duduknya. Sementara, Usa segera berdiri dan berkenalan dengan April santai. Kami masih terhitung siswa baru di sekolah ini.
“Bareng aja kalau mau ke kantin. Koridor IPA 5 rame banget sama cowok. Makanya gue balik lagi biar ada temen lewat, hehe.”
“Koridor yang ada tiga anak tangga itu?” tanya Usa, lalu dijawab April cengegesan, “Iya. Kalau jatuh di sana pasti malu seumur hidup, tuh.”
Kudengarkan mereka saat keluar kelas. Koridor selalu ramai pada jam ini, aku takkan berkomentar. Murid berseragam sama hilir mudik membawa kantongan dari arah kantin di balik ruang Bimbingan Konseling/Penyuluhan. Berbincang perihal makanan lezat dari kantin, lingkungan sekolah, atau teman-teman di kelas.
“Lo jangan jalan di belakang. Di depan aja, sini.”
Aku sempat membeo, tetapi menurut saat ditarik Usa untuk berada di depannya. Aku tak terbiasa, justru di belakang adalah tempat semestinya. Tinggal selangkah untuk menuruni tiga anak tangga di koridor IPA 5 yang tiap sisinya ramai oleh siswa. Langkahku terhenti saat April memberitahu, “Tali sepatu lo lepas, mending benerin dulu.”
April dan Usa menghentikan langkah memberiku waktu seraya bercengkrama menunjuk seseorang di lapangan. Aku hendak membenarkan ikatan tali sepatu, tetapi punggungku terasa didorong. Disebabkan oleh tali sepatu yang terinjak kaki sendiri membuat langkahku tak benar. Mataku terpejam. Aku pasrah saja jika momen jatuh dari tiga anak tangga ini akan menjadi topik menyenangkan saat reuni tiga tahun mendatang.
“Astaga.”
Aku mengenali suara Usa yang histeris. Sedangkan aku menyiapkan diri untuk merasakan keramik putih yang meninggalkan jejak kaki sepatu berdebu entah siapa pemiliknya. Namun, aroma kayu yang mirip wangi buku-buku lama di perpustkaan masuk indra penciumku. Aku tak merasakan dinginnya lantai melainkan pergelelangan tangan seseorang yang hangat dan sedikit kering. Samar tetapi kudengar debar jantung seorang yang membuatku terperanjat kaget oleh sentuhannya di pinggangku.
“Lo baik-baik aja?”
Suaranya jelas sekali adalah seorang lelaki. Aku segera membenarkan posisiku berdiri untuk tak membebaninya dengan tubuhku. Satu kesalahan, aku hampir terjungkal jika tangan itu tak segera kembali merengkuh pinggangku. Aku tak ingin mendongak menatap pemilik aroma asing ini sebab wajahku memerah.
Kondisi macam apa ini? Aku ditelan oleh perasaan bernama malu. Orang di sekitar terdengar bersiul-siul menggoda, aku mematung tak percaya pada situasi yang membuat wajahku seperti terbakar. Sekarang apa lagi? teriakku karena ia menahan tangan saat aku sendiri ingin enyah sejauh mungkin dan berharap kami tak dipertemukan kembali. Ia justru berjongkok dan menalikan tali sepatuku.
Apa yang kulakukan adalah menutup wajahku yang yang sudah seperti kepiting rebus. Rasa malu membuat akal sehatku tak bekerja dengan benar. Tanpa sepatah kata, langkahku meninggalkan sekerumunan manusia itu yang menggoda.
“Bodoh,” gumamku.


 azzmifaitsmiddielah
azzmifaitsmiddielah