Lara dan Sera berjalan beriringan menuju rumah Sera. Lara sedikit tersenyum, meskipun senyumnya itu terasa samar. Ia memandang rumah Sera dengan hati yang bimbang. Rumah itu sangat sederhana. Beberapa cat temboknya terkelupas, dan pagar kayu yang sedikit miring membuatnya tampak seperti rumah yang sudah lama tidak terawat.
Namun, ada satu hal yang membuat Lara tak bisa berhenti memandang—di tembok ruang tamu, ada sebuah foto keluarga yang tergantung dengan rapi. Foto itu menggambarkan Sera tersenyum bahagia, berdiri bersama seorang pria yang tampak seusia Ayahnya, seorang wanita yang tampak seusia Ibunya, serta nenek dan kakek Sera. Mereka semua tersenyum lebar, begitu penuh kebahagiaan.
Lara menatap foto itu, matanya sedikit berkilat. "Kenapa mereka bisa sebahagia itu?" pikirnya, merasa ada sesuatu yang begitu asing dan sekaligus mengharukan. "Kenapa aku nggak pernah punya foto seperti itu?"
Lara merasa iri. Ia bahkan tak pernah memiliki foto keluarga yang hangat seperti itu. Foto keluarganya yang terakhir, dan pertama kali, hanya ada satu—saat Satya berusia dua tahun. Itu pun, jika dilihat dengan seksama, Lara tampak seperti bayangan yang terabaikan. Ia hanya ada di samping, sedikit di belakang, seakan-akan tak ada tempat bagi dirinya. Bahkan, jika bisa, mungkin saja bagian tubuhnya bisa dihapus dari foto itu.
Foto keluarganya hanya memperlihatkan senyum Ayah, Ibu, Luna, dan Satya. Sementara dirinya, hanya bisa menahan tangis yang hampir tumpah di tengah senyum mereka.
Sera yang melihat Lara diam, kemudian tersenyum canggung. “Maaf ya, Lar. Rumah aku emang jelek, hehe.” Sambil berkata begitu, Sera menyajikan teh hangat dan beberapa camilan ringan di meja.
Lara kembali tersenyum, meskipun senyumnya masih sedikit kaku. “Enggak kok, malah aku salfok sama foto itu. Itu keluarga kamu ya?” tanyanya sambil menunjuk ke arah foto di dinding.
Sera berbalik melihat ke arah yang ditunjuk Lara. “Iya, itu diambil setahun sebelum Mama sama Papa kecelakaan,” jawab Sera dengan nada yang tiba-tiba berubah datar, seakan-akan kehangatan yang ada dalam foto itu tak bisa bertahan lama.
Lara terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ekspresi Sera berubah, matanya mulai berbinar dengan air mata yang hampir jatuh. Lara merasa canggung, bingung bagaimana harus merespons. “Oh…” itu saja yang bisa keluar dari mulut Lara. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi melihat ekspresi Sera yang begitu rapuh, Lara memilih untuk diam.
Beberapa waktu lalu, Lara tak jadi dijemput Ayahnya. Ia berjalan dengan langkah ringan, meskipun hatinya berat. Pandangannya kosong, pikirannya melayang entah ke mana. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan Sera yang sedang mengayuh sepeda tuanya, baru saja selesai berbelanja di pasar. Lara tahu, Sera mungkin bisa mengerti, bahkan tanpa perlu banyak kata.
“Eh, kamu udah liat grup?” Sera tiba-tiba bertanya, memecah keheningan yang sempat menyelimuti mereka.
Lara mengernyitkan dahi, bingung. “Emang ada apa?”
“Tugas kelompok, Ra. Kelompoknya kita diubah.” Sera menjelaskan, melirik Lara dengan mata yang sedikit cemas.
Lara sedikit terkejut. “Ha? Kenapa diubah?” tanyanya dengan nada tak percaya.
“Bu Meri nggak suka kalau kita cuma berdua. Jadi dia satuin kita sama kelompok Zea. Biar kita berlima, jadi lebih banyak orang,” jelas Sera dengan sedikit terburu-buru, seperti ingin mengakhiri topik itu.
“Habislah…” kata Lara pelan, matanya menatap ponselnya seolah berharap ada keajaiban. Ia tidak terlalu suka jika harus bekerja dengan orang yang belum terlalu dekat, apalagi dengan Zea yang selalu sibuk bergantung padanya dan gengnya juga.
Tiba-tiba, ponsel Lara bergetar. Ada panggilan dari Ayahnya. Lara menghela napas berat. Ia tahu ini bukan panggilan yang baik.
Dengan tangan sedikit gemetar, ia menjawab panggilan itu. “Iya, Ayah?”
“Lara!” suara Ayah terdengar keras dan penuh amarah. “Kenapa kamu belum pulang? Ayah ke sekolah, kamu nggak ada di sana! Udah sore, kamu nggak kabar! Lagi ngapain kamu?”
Ayah bilang tak jadi menjemput, tapi ia akhirnya ke sekolah karena khawatir Lara tak juga pulang. Ketika tahu Lara tak ada di sekolah, Ayah makin marah.
Lara menghela napas dalam, menahan emosi yang mulai meluap. “Ayah, aku di rumah temen,”
“Apa? Jangan mentang-mentang Ayah gak jadi jemput kamu bisa keluyuran gini?!” Ayahnya terdengar semakin marah. “Kamu pikir kamu bisa terus kayak gini? Udah sore, Lara, kamu harus pulang sekarang!”
Lara merasa hatinya semakin sesak. “Iya, Ayah,” jawabnya pelan, meskipun dalam hatinya, ia merasa terjebak dalam rutinitas yang tak pernah bisa ia selesaikan dengan baik.
Setelah menutup telepon, Lara melihat ke arah Sera. “Duh, kalau kerja kelompok di rumah aku aja gimana? Gara-gara telat pulang hari Minggu kemarin, aku nggak dibolehin keluar tau,” ucapnya dengan nada memelas.
Sera mengangguk dengan cepat. “Iya, nggak masalah kok. Kita kerja kelompok di rumah kamu aja.”
Lara merasa sedikit lega. Setidaknya, dia tidak harus menghadapi kemarahan Ayahnya lebih lama lagi. Tapi ia tahu, meskipun Sera menyarankan itu, di rumah nanti tetap saja akan ada pertengkaran yang menunggunya.
*****
Sesampainya di rumah, Lara langsung disambut dengan suara Ayahnya yang menggelegar. “Lara! Kamu kenapa? Udah sore gini baru pulang? Kamu itu ngerti nggak, Ayah ini khawatir!” Ayahnya sudah tidak bisa menahan emosinya lagi.
Lara menundukkan kepalanya, hanya bisa mengunci pandangan ke lantai. “Maaf, Ayah,” ucapnya pelan.
“Apa? Maaf? Itu yang kamu ucapin setelah bikin Ayah khawatir? Kamu pergi seenaknya tanpa kabar! Kapan kamu ngerti kalau ada aturan yang harus diikuti di rumah ini?!” suara Ayahnya semakin tinggi.
Lara merasa dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia hanya ingin sedikit merasakan kebahagiaan, tapi tak bisa. Rasanya tak ada kata yang bisa mengubah keadaan ini.
“Lara! Kamu nggak tahu apa yang Ayah dan Ibu rasakan? Selalu begini, Lara! Selalu! Ayah capek ngomong sama kamu!” Ayahnya akhirnya melemparkan kalimat itu, membuat Lara merasa semakin kecil.
Lara tak bisa berkata apa-apa lagi. Matanya terasa panas, dan ia menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang, Ayahnya tak akan mengerti. Hanya ada kesunyian yang menenggelamkan dirinya.
“Ke kamar sekarang!” perintah Ayahnya dengan tegas.
Lara berjalan menuju kamarnya dengan langkah pelan, merasa setiap kata yang keluar dari mulut Ayahnya membekas dalam hatinya. Ia ingin sekali berteriak, mengungkapkan apa yang dirasakannya, tetapi mulutnya terasa terkunci.
Di dalam kamar, Lara duduk diam di tepi ranjang. Suara teriakan Ayahnya masih terngiang-ngiang di telinganya, membuat kepalanya terasa berat. Ia terdiam lama, menatap lantai yang dingin seolah mencari jawaban dari kebisuan.
Perlahan, tangannya meraih buku catatan kecil yang selalu ia sembunyikan di bawah bantal—satu-satunya tempat di mana ia bisa bicara tanpa takut disela. Buku itu sudah penuh dengan coretan rahasia, puisi-puisi lirih yang tak pernah dibacakan pada siapa pun.
Tangannya gemetar saat menggenggam pulpen. Ia menarik napas pelan, lalu mulai menulis
Aku rumah yang selalu sunyi,
Dindingku keras, pintuku terkunci.
Aku ada, tapi tak pernah dimiliki,
Seperti bayangan yang tak dipedulikan pagi.
Mereka bicara, aku mendengar,
Tapi tak satu pun suara untukku benar.
Aku bernafas, tapi seolah salah,
Dalam rumah ini, aku selalu kalah.
Tapi hari ini aku melihat cahaya,
Di rumah tua yang penuh tawa.
Di sana, senyum tak perlu alasan,
Dan luka tak perlu penjelasan.
Lara meletakkan pulpennya. Ia mengusap air mata yang jatuh tanpa izin. Hatinya masih nyeri, tapi setidaknya malam ini ia tak sendirian dalam pikirannya. Ada kata-kata yang menemaninya, dan ada bayangan Sera yang membuat dunia terasa sedikit peduli padanya.


 yourassiee
yourassiee
















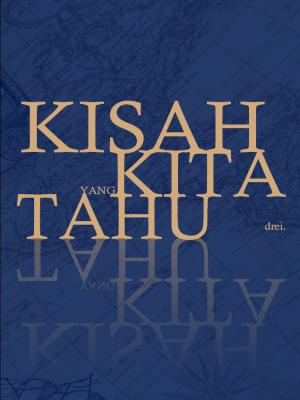

@pacarmingyuu, ahaha, maaf aku sensi, abisnya komennya menjerumus banget, aku kepikiran punya salah apa, dikomen juga aku jelasin, aku harap aku salah, kalau beneran aku salah, aku minta maaf ya😔😔🙏🩷
Comment on chapter 3 - Aku ingin berubahthank you udah berkenan komen juga, have a great day🩷🙏