Lara berdiam di kamarnya. Sepi. Hanya suara desau pelan dari AC tua yang meneteskan air di pojok langit-langit. Udara kamar dingin, tapi dadanya tetap sesak.
Ia tengkurap di atas kasur, kakinya selonjor ke belakang dan bergoyang pelan-pelan di udara. Tangan kirinya menyangga dagu, sementara tangan kanan sibuk menulis dengan pulpen hitam yang tintanya nyaris habis. Kertas-kertas berserakan di sekitarnya—beberapa penuh coretan marah, beberapa cuma sebaris lalu dicoret keras-keras.
Di balik tumpukan bantal yang sengaja ditinggikan, terselip buku catatan kecil yang sampulnya berwarna coklat mulai mengelupas. Di situlah Lara menyimpan semua yang tidak bisa ia ucapkan. Semua yang tidak boleh diketahui siapa pun.
Ia sedang menulis puisi. Lagi.
Menulis adalah satu-satunya tempat ia bisa bernapas, di rumah yang terlalu sempit untuk perasaan. Rumah yang dinginnya bukan cuma dari AC, tapi dari suara-suara keras yang setiap hari melukai.
Tak ada yang tahu tentang buku itu. Tidak Luna, tidak Satya. Tidak pula orang tuanya yang sibuk dengan urusannya. Apalagi teman-teman di sekolah yang hanya mengenalnya sebagai 'anak baik', 'pendiam', dan 'nggak pernah bikin masalah'.
Tapi di buku itu, Lara bukan siapa-siapa. Dan juga semuanya. Ia bisa marah, bisa menangis, bisa berteriak tanpa suara.
Hari ini, ia menulis puisi yang agak berbeda. Judulnya Aku Ingin Jadi Jahat. Jantungnya berdetak lebih cepat saat menuliskannya. Seperti sedang menuliskan dosa—padahal cuma menulis puisi. Tapi bagi Lara, kalimat itu lebih jujur dari semua ‘aku baik-baik saja’ yang ia ucapkan setiap hari.
Aku Ingin Jadi Jahat
Aku lelah menjadi boneka,
Tersenyum dengan luka yang tak pernah bisa aku ungkapkan.
Mereka bilang aku baik,
Tapi tak ada yang tahu bagaimana rasanya dipaksa
Menjadi sesuatu yang bukan aku.
Lara menatap puisinya lama. Ada sesuatu yang mengganjal di dada—bukan sedih, tapi juga bukan lega. Rasanya seperti baru membuka luka yang selama ini dibalut paksa agar terlihat indah.
Tiba-tiba suara pintu dibuka paksa dari luar.
"Kak Lara!"
Luna. Suara itu seperti palu godam yang menghancurkan dunianya seketika. Lara langsung panik, menyambar buku catatannya dan menyelipkannya cepat ke bawah bantal. Detak jantungnya seperti drum perang. Ia duduk tegak, wajahnya gugup.
Luna berdiri di depan pintu yang setengah terbuka. Mata adiknya itu langsung menyipit curiga.
"Nyembunyiin apa lo?"
"Bukan apa-apa kok," jawab Lara cepat. Terlalu cepat. "Kenapa?"
Luna langsung masuk ke kamar tanpa izin, seperti biasa. Ia duduk di tepi kasur dengan santai. "Gue mau pinjem dress merah muda lo itu, dong. Yang kemarin lo beli."
Dress itu. Lara langsung kaku.
Itu satu-satunya barang yang Lara beli dari hasil tabungannya sendiri. Ia belum sempat memakainya. Dress yang bagi Lara terlalu cantik untuk di pakai, terlalu sayang. Dan dress itu semacam harapan kecil bagi Lara. Mungkin Lara akan pakai nanti. Nanti, ketika ia berhasil menjadi dirinya yang baru, yang penuh percaya diri, tanpa kebohongan lagi.
"Itu..."
"Kenapa?" Luna menaikkan alis, nadanya mulai mengancam.
"Gak boleh!" jawab Lara cepat, seperti menahan sesuatu yang hendak meledak. Ia memejamkan mata, menunggu ledakan dari adiknya. Tapi... sepi.
Luna diam sejenak. Wajahnya mengeras. Ia bangkit berdiri, lalu berjalan keluar kamar tanpa suara. Justru itu yang membuat Lara panik.
Ia tahu, kalau Luna diam... itu pertanda buruk.
Segera setelah Luna pergi, Lara loncat dari kasur dan berlari ke pintu, memutarnya cepat, mengunci. Jantungnya berdetak kencang. Ada firasat buruk—dan benar saja.
Beberapa menit kemudian, suara langkah berat mendekat. Lalu pukulan keras di luar pintu. Disusul suara dua orang sekaligus, suara yang ia kenal terlalu baik, tak lain adalah Lusi dan Leo, orang tuanya.
“LARA! BUKA PINTUNYA SEKARANG!”
Suara Lusi, Ibunya, meledak seperti pecahan kaca yang menghantam jantung. Pedih, tajam, dan berulang. Disusul suara Leo, Ayahnya—lebih berat, lebih dingin, tapi tak kalah mematikan. Bagaikan palu godam yang menghantam kepala tanpa ampun.
"Apa-apaan kamu?! Nolak permintaan adek kamu kayak gitu? Hah?! Cuma dress doang, Lara pelit banget! Luna sampai nangis gara-gara kamu! Kamu puas, hah?!" suara Lusi melengking, penuh kemarahan.
"Kamu itu Kakaknya, Lara! Kakak apaan yang gak bisa ngalah? Baru punya dress satu aja udah ngerasa paling istimewa ya?! Kamu pikir kamu siapa?!" Leo menyusul, nada suaranya seperti cambuk, keras dan dingin.
Luna diam sejenak. Wajahnya mengeras. Ia bangkit berdiri, lalu berjalan keluar kamar tanpa suara. Justru itu yang membuat Lara panik.
"Asal kamu tau ya!" Lusi kembali, suaranya naik dua oktaf. "Anak Baik itu harusnya tak pernah menolak! Apa lagi untuk hal-hal kecil seperti ini! Dari kecil, saya didik kamu agar jadi Kakak yang bisa ngalah, bisa ngerti, jadi anak baik yang benar-benar sempurna!"
"Cuma anak gagal yang gak bisa nyenengin keluarganya sendiri!" Leo ikut menyerang. "Kalau bukan karena tanggung jawab, sudah saya buang kamu dari lama!"
Lara menahan napas. Tak ada balasan, tak ada pembelaan. Hanya air mata yang mengalir pelan, dan tubuh yang perlahan menggigil dalam diam. Bahunya bergetar, tak tahu apakah karena dingin… atau karena luka yang tak terlihat.
BRAK!
Pintu itu terbuka keras. Dentumannya memantul di dinding kamar, membuat Lara tersentak. Ia mundur panik, kaki terantuk ranjang, lalu jatuh terduduk ke lantai. Pinggulnya menghantam ubin dingin, siku kirinya terbentur lemari kecil. Perih menjalar pelan, tapi tidak berdarah.
Kepalanya terbentur dinding—cukup keras untuk membuat pandangannya berkunang. Ia diam, terengah, tubuhnya bergetar.
Air mata mengaburkan penglihatannya, tapi ia masih bisa melihat siluet Ayahnya berdiri di ambang pintu.
Tegap. Diam.
Matanya menatap tajam, tapi bukan amarah yang Lara tangkap—melainkan sesuatu yang samar. Ketegangan di rahangnya, jemari yang mengepal lalu mengendur. Seperti ada yang hendak disampaikan, tapi tertahan di batas bibir.
Namun tetap, tak ada langkah mendekat. Tak ada tangan yang terulur.
Lara hanya bisa duduk di lantai, menggigil di bawah cahaya lampu kamar yang dingin. Terluka bukan hanya oleh benturan, tapi oleh jarak yang tak pernah dijembatani.
Lusi menoleh pada Luna di belakang. Suaranya ringan, terlalu tenang untuk keadaan seperti ini. “Luna, udah, ya. Nanti Ibu beliin yang lebih bagus dari punya Kakak. Yang lebih cantik. Biar Luna nggak sedih lagi.”
Lara mendengarnya—jelas. Seolah suara itu tertancap di dadanya.
Ia memeluk lututnya erat, menahan gemetar dan isak. Sakit di tubuhnya tak seberapa dibandingkan rasa sesak di dada. Luka-luka kecilnya tak berdarah, tapi hatinya seperti koyak dari dalam.
Di saat ia tersungkur, satu-satunya hal yang orang tuanya pikirkan hanyalah Luna. Bukan dirinya.
Ia merasa seperti bayangan di sudut ruangan—tak terlihat, tak dianggap.
Dalam kepalanya, sebuah suara kecil yang selama ini berbisik pelan... kini berteriak.
Aku ingin jadi jahat.
Kalau menjadi anak baik artinya harus selalu mengalah… Kalau menjadi baik artinya tak pernah punya tempat di hati siapa pun…
Lara tidak ingin lagi.
Matanya menatap lurus, kosong. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai menyala. Bukan harapan. Tapi tekad.
Buku catatannya masih ada di bawah bantal—disembunyikan seperti dirinya sendiri. Tapi tidak untuk lama lagi.
Ia akan menulis lagi. Tapi kali ini, bukan untuk merayu pengertian. Ia akan menulis untuk melawan. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, meski hanya lewat kata-kata. Karena kalau tak ada yang ingin mendengarnya...
...ia akan bicara lebih keras.
Meski harus jadi jahat.


 yourassiee
yourassiee









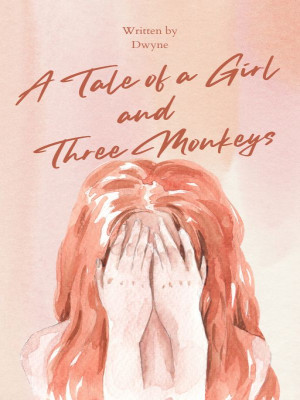





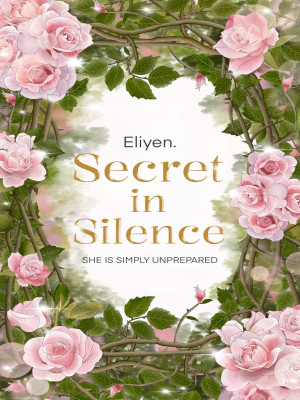


@pacarmingyuu, ahaha, maaf aku sensi, abisnya komennya menjerumus banget, aku kepikiran punya salah apa, dikomen juga aku jelasin, aku harap aku salah, kalau beneran aku salah, aku minta maaf ya😔😔🙏🩷
Comment on chapter 3 - Aku ingin berubahthank you udah berkenan komen juga, have a great day🩷🙏