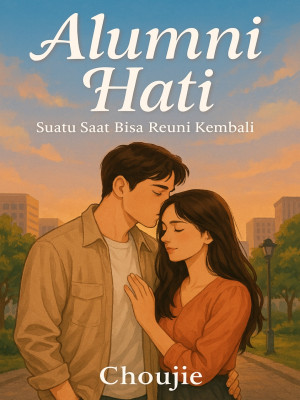Senja perlahan-lahan memancarkan warnanya di Kayseri saat langit diwarnai jingga dan keemasan. Sore itu suasana di suatu daerah sekitar 30 KM dari pegunungan Erciyes menjadi hidup oleh suara lantunan ayat suci Alquran yang merdu di Masjid Bürüngüz menjelang adzan maghrib, saat angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah yang baru dibasahi hujan. Sore hari menampakkan kabut keemasan dari beranda sebuah rumah kecil tempat seorang pemuda duduk dengan tenang. Tangannya yang kuat dan terampil mengukir tasbih dari kayu zaitun yang indah. Ia menyentuh setiap potongan kayu dengan perhatian yang mendalam seolah-olah setiap goresan membutuhkan pesan spiritual untuk disampaikan.
Pemuda itu bernama Mustafa Ghaziy, tubuhnya tinggi sekitar 185 cm, bahunya yang lebar dan postur tubuhnya yang percaya diri melengkapi penampilannya. Keturunan Anatolia terlihat melalui kulitnya yang sedikit gelap dengan highlight keemasan. Rambut hitamnya yang kuat terpotong rapi dengan gelombang halus di atas dahi yang memadukan esensi keanggunan dengan pesona maskulin. Matanya yang berwarna cokelat gelap memiliki daya tembus seperti elang yang secara bersamaan mempesona dan melukai. Garis keturunan Ottoman terlihat dalam bentuk hidung yang lurus dan tegas yang dipadukan dengan lengkungan lembut bibirnya yang penuh yang meningkatkan daya tariknya.
Mustafa mewarisi bakat pertukangan kayu dari kakeknya yang membuatnya menjadi pengrajin tasbih kayu di Kayseri. Sepanjang hidupnya yang berusia dua puluh delapan tahun, ia mendedikasikan diri untuk kesederhanaan yang menghubungkan toko pertukangan kayunya dengan masjid yang terletak di tengah kota. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa di balik penampilannya yang damai, Mustafa diam-diam berdoa terus-menerus memohon ketetapan untuk dirinya.
Dari tempat yang tidak jauh, seorang wanita tua duduk di kursi kayu anyaman di rumahnya yang sederhana untuk memperhatikan Mustafa. Dia adalah ibunya, Fatma Ghaziy. Sang ibu sangat memahami perasaan anaknya, tetapi berulang kali gagal membujuknya untuk memulai hidup baru. Mustafa tetap setia pada keyakinannya bahwa segala sesuatu terjadi persis seperti yang Allah tetapkan. Meskipun selalu khawatir, Fatma terus berdoa agar keinginan Mustafa segera terkabul.
Malam itu, Mustafa kembali ke bengkelnya setelah menunaikan shalat Isya di masjid. Tangannya kembali memahat kayu-kayu itu, tetapi pikirannya melayang ke kenangan masa lalunya. Dulu ia hampir menikah dengan wanita yang dicintainya. Namun, takdir berkata lain. Setelah meninggalkan Kayseri, gadis itu menetap di kota lain sehingga Mustafa memilih untuk menepis semua pikiran tentang asmara. Yang tersisa di hatinya hanyalah doa-doa yang dipanjatkannya dalam diam.
Mustafa menyelesaikan tasbih terakhirnya hari itu sambil melirik serpihan kayu yang telah ia haluskan. Ia menatap partikel kayu yang telah dilunakkan itu sambil merasakan bagaimana rasanya saat terjepit di antara ujung jarinya. Ia menutup matanya sejenak setelah mengingat do'anya yang tak kunjung mendapatkan jawaban.
"Ya Allah," gumamnya lirih. "Jika memang ini adalah ujian, berilah aku kesabaran. Jika ini adalah takdir, berilah aku keteguhan hati. Dan jika ini adalah jalan yang telah Engkau tetapkan, bimbinglah aku untuk menerimanya dengan ikhlas."
Malam semakin larut, dan doa-doa itu kembali mengudara, menembus langit Anatolia yang sunyi.
***
Seorang perempuan puluhan kilometer jauhnya dari Kayseri menempati meja dengan buku-buku peradaban Islam yang memenuhi permukaannya. Langit malam Jakarta mulai menggelap melalui jendela apartemennya. Cendekiawan muda Ayra Safiyyah mengakhiri bukunya sambil menghela napas panjang dan dalam. Selama beberapa bulan terakhir ia terus-menerus mengalami kegelisahan terhadap hidupnya. Sebagian dari dirinya tampaknya tengah mencari potongan-potongan jawaban karena ia merasa ada sesuatu hal penting yang hilang.
Ayra terus merasakan ada pesan penting yang belum tersampaikan dari ayahnya setelah kematiannya. Kecintaan terhadap sejarah Islam membentuk karakter ibunya yang sering berbagi cerita tentang perjalanannya ke negara-negara yang kental dengan sejarah Islam. Anatolia, Turki, menjadi lokasi yang paling sering dirujuknya karena ia menyebutkannya berkali-kali karena banyaknya ulama dan sufi hebat di negeri ini.
Di meja kerjanya, tergeletak sebuah buku tua lusuh dengan sampul cokelat yang terbuka di salah satu halamannya. Tulisannya sedikit memudar, tetapi satu kalimatnya menonjol dengan kuat "Jika ingin menemukan jawaban, pergilah ke negeri para ulama."
Ayra mempelajari kata-kata itu cukup lama. Ia tahu pesan ini bukan sekadar teks biasa karena ada sesuatu yang penting untuk ditemukan dalam kata-katanya. Ada tujuan tertentu yang perlu ia kejar di sana. Tempat yang jauh dari rumahnya mungkin akan mewujudkan doa-doanya yang belum terjawab. Malam itu juga akhirnya ia membuat pilihan yang pasti. Tangannya yang gemetar membuka laptopnya untuk mencari tiket pesawat Turki. Detak jantungnya yang cepat menandakan bahwa keputusan ini akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Ketakutan dan keraguan ada dalam dirinya, tetapi keyakinannya tentang bepergian lebih kuat daripada kekuatan-kekuatan yang berlawanan ini.
Ayra menutup laptopnya setelah memastikan tiket pesawatnya sudah dibelinya benar. Penerbangan ke Istanbul tinggal tiga hari lagi. Ayra menatap langit Jakarta yang mulai menebal sambil menarik napas dalam-dalam. Perasaan campur aduk muncul di hatinya antara rasa lega dan khawatir dengan harapan yang tidak dapat ia pahami.
Keesokan paginya, Ayra memulai proses persiapan keberangkatan. Dari sudut kamar, Ayra mengambil tas travel lalu mulai meletakkan perlengkapan pakaiannya beserta buku catatan dan tasbih kayu pemberian ayahnya. Ia menggenggam tasbih itu sebentar lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam koper sambil mengusap lembut butiran kayu tasbih itu.
Suatu pagi saat sarapan, Ayra memberanikan diri untuk menyampaikan rencana perjalanannya ke Turki kepada ibunya. Ayra mendekati ibunya perlahan-lahan sambil mengutarakan rencananya untuk mengunjungi Turki, membuat meja makan keluarga menjadi sunyi.
Hamidah tiba-tiba menghentikan garpunya di udara saat hendak makan. "Turki?"
Kata Turki terngiang di telinga Ayra saat ia menatap ibunya dengan tatapan ragu. "Iya, Bu. Saya merasa perlu ke sana. Dengan penjelasan yang cermat, Ayra mengungkapkan perasaannya tentang kehadiran yang diyakininya menunggunya di Turki. "Aku yakin ada sesuatu yang menungguku di tanah Anatolia itu Ibu" ungkap Ayra.
Sesaat hening berlalu sebelum Hamidah menarik napas dalam-dalam. "Ayahmu memang sering membahas Turki, apalagi wilayah Anatolia. Tapi, bukan berarti kamu harus kesana nak." Tutur Hamidah khawatir, sebab setelah suaminya Ferhat Kiray meninggal dunia, hanya putrinya-lah satu-satunya keluarga yang ia miliki saat ini, sehingga baginya sangat berat untuk berpisah sama putrinya barang satu detik pun. Apalagi Turki, negeri yang ratusan kilometer jaraknya dari Jakarta. "Apakah kamu yakin ini keputusan yang tepat?'' tanya Hamidah memastikan.
Ayra mengangguk mantap. "Aku tidak mengerti apa yang akan aku temukan di sana, Bu. Tapi, aku percaya jalan yang aku pilih ini terasa berbeda dari sekadar keinginan sesaat. Aku merasa terpanggil untuk pergi kesana," tutur Ayra.
Hamidah menatap putrinya penuh perhatian yang dalam sebelum dia tersenyum lembut. Dengan pikiran yang mantap, Ibu hanya akan berdoa agar yang terbaik datang kepadamu.
***


 diary_azra
diary_azra