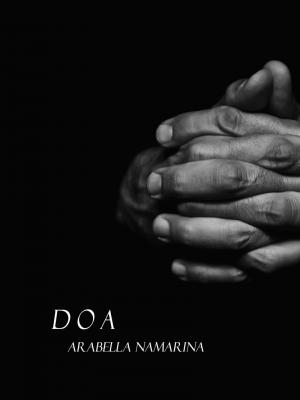Tembang kuno Jawa dilantunkan, samar-samar mengisi hampa udara di ruang teras belakang rumah. Mbok Miyem kerap bersenandung untuk menghibur tuannya. Tangan kurus berkeriputnya menyisiri rambut gadis jelita yang duduk membelakanginya.
“Sejak Ibu sering ritual sakral, Samara sering mimpi buruk. Mungkin kepikiran hal-hal aneh tentang kegiatan Ibu sekarang ini,” ucap gadis itu.
Sejenak Mbok Miyem berhenti bernyanyi. Ia mengernyit seraya balas berkata, “Leh weleh, Ndoro, jangan memikirkan yang aneh-aneh. Ilmu Kejawen bukan ilmu sing aneh kok.”
Samara membalikkan badan dan menyahut, “Kalau memang bukan ilmu yang aneh, kenapa Ibu sampai sebegitunya?”
Mbok Miyem mengerucutkan bibir kecilnya. Ia nampak bingung bagaimana harus menjelaskan.
Samara lanjut menggerutu, “Bakar-bakar dupa, sesajen di mana-mana, meditasi sampai tengah malam. Menurutku itu semua terlalu berlebihan.”
Kala Samara duduk membelakanginya lagi, Mbok Miyem lanjut menyisiri rambut cokelat tua panjangnya.
“Kejawen meniko kan ilmu kepercayaan turun temurunnya orang Jawa,” tutur Mbok Miyem. “Ibunya Ndoro kan masih kuat darah Jawa nya—”
“Terserah Mbok deh mau mikir apa, kalau menurutku sih tetap aneh,” ujar Samara yang tetap kukuh pada pemikirannya sendiri.
Si Mbok berkemben itu pun hanya terkekeh mendengarnya menggerutu kesal.
Samara menyudahi pembicaraan dan beranjak dari lantai teras berwarna merah delima itu. Sebelum meninggalkan si Mbok, ia memberitahunya, “Dan satu lagi; Mbok enggak perlu panggil-panggil aku Ndoro. Aku bukan putri keraton kok.”
Si Mbok hanya mesem-mesem saja seraya mengangguk patuh.
Samara segera memasuki rumah yang pintunya bersebelahan dengan ruang makan dan dapur. Mengingat ucapan si Mbok, rumah ini kental akan nuansa Jawa yang kuno. Mulai dari perabotan, pajangan-pajangan antik, semuanya menggambarkan rumah adat Jawa.
Semasa taman kanak-kanak, Samara pernah tinggal di rumah tua ini. Baru setahun belakangan, Samara dan ibunya kembali tinggal di kampung halaman. Sebelumnya ia menempuh masa pendidikan sampai kuliah di Jakarta. Mbok Miyem yang diamanahkan menjaga rumah di sini.
Ketika ia berada di sini, terkadang rasanya bagai lintas waktu ke masa lalu. Nuansa mistis juga terasa menyelimuti arsitekturalnya yang kuno. Ibunya memang menyenangi segala hal yang bernuansa Jawa kuno. Mbok Miyem yang merawatnya sedari kecil pun sudah tak asing dengan pemandangan di rumah ini.
Bahkan Mbok Miyem yang sehari-harinya memakai kemben—seolah sedang mengabdi pada putri-putri keraton. Tak bosannya si Mbok memanggil ibunya yang bernama lengkap Larasati Kusuma Wijaya itu dengan panggilan akrab; Gusti Laras.
Nama Gusti sendiri dalam kebudayaan orang-orang Jawa diperuntukkan untuk darah ndalem[1] yang kedudukannya masih tinggi di keraton. Apalagi ketika memanggil namanya, Mbok Miyem selalu menghormatinya secara berlebihan. Samara resah tiap kali si Mbok memanggilnya dengan sebutan Ndoro. Terbiasa hidup dilingkungan metropolis membuatnya bersikap seperti anak gaul Jakarta pada umumnya. Makanya ia merasa tak pantas kalau disandingkan dengan putri Solo.
Pajangan-pajangan antik dan arsitektural bangunan di sini memang terkesan seperti rumah ningrat. Namun tak lantas membuat Samara meyakini bahwa ia berasal dari keluarga berdarah biru. Sedangkan mendiang ayahnya, Bung Pierre Utomo seorang profesor sejarah budaya. Kawan-kawan lamanya akrab memanggilnya Bung, karena sosoknya yang sangat bersahaja. Walau bukan dari kalangan bangsawan, beliau orang terpandang di kota Solo.
Setelah ia lulus sekolah dasar, ayah Samara meninggal dunia. Itulah faktor yang membuat ibunya memutuskan pindah dari Solo ke kota metropolis. Samara belum sempat mengenal ayahnya lebih akrab. Tumbuh kembangnya lebih banyak ia dapat dari kasih sayang sang ibunda. Karena kedekatannya dengan sang ibu, mereka selalu bersama semasa tinggal di Jakarta.
Kini usianya menginjak 22 tahun. Setelah lulus kuliah tahun kemarin, Ibunya mengajaknya kembali ke Solo. Beliau ingin melanjutkan usaha pakaian batik dan jajanan Solo yang selama ini ditekuninya.
Sepulangnya ke tanah kelahiran, ibunya memang rajin menjalankan usahanya. Namun tiga bulan terakhir ini, beliau malah lebih sering melakukan ritual-ritual sakral. Entah ada mimpi dadakan apa yang diterimanya, sampai-sampai hampir melupakan kesibukan di dunia nyata.
Samara merasa hubungan dengan ibunya mulai renggang. Frekuensi komunikasi di antara mereka pun semakin hari semakin berkurang. Ia justru berpikir ritual-ritual yang dilakukan ibunya bisa membawa pengaruh tak baik.
Dalam tiga bulan terakhir ini juga, ia sudah mengamati sikap aneh ibunya. Samara yang tak memahami kepercayaan Kejawen, menganggap kegiatan ibunya terlalu berlebihan.
Pagi-pagi itu, seperti biasa, Samara suka memperhatikan kegiatan ibundanya. Dari balik tembok rumah, ia mengintip kegiatan ibunya di teras luar. Ibunya tengah duduk bersimpuh sambil memegang beberapa dupa. Di hadapannya ada meja berisi piring-piring sesajen bunga, kendi-kendi air, dan tempat dupa yang asapnya mengepul di udara.
Setelah beberapa saat ibunya nampak menyudahi acara ritual, Samara menghampirinya. Ia langsung menyeru kesal, “Bu, mau sampai kapan kayak begini?”
Sambil beranjak dari lantai, wanita bersanggul dan berparas ayu itu menengok padanya. Ia tak tampak terkejut dengan kehadiran anaknya yang blak-blakan mengonfrontasi. Malahan beliau tersenyum lembut.
“Samara, Ibu harus menjalani ini demi kebaikan,” ucap wanita berusia lima puluh tahunan itu. Lalu beliau meletakkan dupa yang dibawanya ke atas meja.
Samara terkekeh tak percaya. “Kebaikan untuk siapa sih, Bu?” Sesekali ia mencuri pandang ke meja sesajen di belakang ibunya sambil berbicara, “Mending Ibu berhenti bakar-bakar dupa dan meditasi enggak jelas begini. Lagian masih banyak hal lebih penting yang ibu bisa urus di tempat kerajinan.”
Sang ibunda menghampirinya lebih dekat dan berkata, “Samara, ada hal-hal yang kita yakini, tidak selalu urusannya dengan duniawi.”
Seketika itu, Samara tertunduk membisu. Tiap kali ia mendengar suara berwibawa ibunya, ia tak sanggup untuk membantah. Walau dalam hati, tetap ia tak setuju.
“Kalau soal rezeki sudah ada Gusti Allah yang mengatur. Kamu tidak perlu meributkannya,” pungkas ibunya. “Apa yang Ibu lakukan sekarang ini, biarlah menjadi urusan Ibu dengan Gusti Allah. Kamu sendiri lebih baik fokus apa yang kamu mau lakukan setelah lulus kuliah.”
Mendengar nasihat ibunya, Samara semakin menunduk.
“Apa kamu sudah tahu mau ngapain setelah lulus?” tegur Ibunya, suaranya tetap mendayu lembut khas orang Solo.
Samara kembali menatapnya dan menggelengkan kepala. “Belum tahu, Bu.”
Tiba-tiba ibunya memeluknya dan berkata, “Ibu bangga kamu bisa lulus dengan nilai cumlaude,” lalu ia melepas pelukannya dan menambahkan, “itu artinya Ibu tidak gagal mendidik dan memeliharamu.”
Samara tersenyum bahagia bisa merasakan pelukan hangat ibunya. Rasanya sudah lama sekali ia tak mengobrol dengan sang ibunda seperti ini.
“Tapi jika Ibu boleh sarankan, kamu bisa bantu-bantu Ibu di tempat kerajinan. Lebih bagus lagi kalau kamu bisa meneruskan usaha Ibu,” ujar ibunya yang kala itu memakai kebaya cokelat dan jarik. Sedangkan Samara berpakaian sederhana dengan kaos putih dan rok modern panjang bermotif batik.
“Samara sih setuju saja mau nerusin bisnis Sendang Laras,” ucapnya sambil tersenyum lebar. “Kapan Ibu mau anterin aku berkunjung ke toko?”
Ibunya berujar, “Nanti ya, setelah Ibu sudah selesai—
Samara langsung memotong sinis, “Ritualnya?”
Sang ibunda menarik nafas dalam. Ketika topik tersebut kembali diungkit, suasana di antara mereka kembali kaku. Ditambah pembawaan Samara yang suka moody, memperkeruh keadaan.
Sang Ibu kembali menengoknya dengan tatapan teduh, “Samara, sudahlah—”
“Aku enggak mau sampai Ibu melupakan kehidupan nyata Ibu di sini,” ujar Samara, mencoba mengingatkannya. “Sembahyang boleh-boleh saja asal enggak keluar jalur kayak gini. Kita hidup di dunia yang nyata, Bu.”
“Sampai kapan kamu mau mendebat Ibu?” pungkasnya, kali ini terdengar tegas. “Cukup kamu ketahui, usia Ibu jauh lebih matang darimu. Ibu tahu apa yang Ibu lakukan.”
Samara tetap ingin membantahnya, “Tapi—”
Ibunya melipir meninggalkannya masuk ke dalam rumah. Tak mau lagi beliau berdebat panjang lebar yang hanya memperkeruh suasana.
Samara merasa gagal meminta ibunya berhenti menggiati acara tersebut. Tak mudah membuat kepercayaan ibunya goyah. Akhirnya ia hanya bisa cemberut sepanjang hari.
[1] Darah Ndalem: keluarga inti raja Solo sampai grad keturunan kelima.


 keefe_rd
keefe_rd