Siang ini mami sungguh berbahagia. Wanita itu, meski sudah melewati usia empat puluh lima, sepatu hak tinggi bukan suatu masalah baginya. Kakinya masih mantap melangkah, tidak goyah. Sambil merangkul anak laki-lakinya (dan satu-satunya) –yang dengan wajah malas dan senyum yang memelas, terlibat dalam tanya-jawab formalitas dengan rekan-rekan mami yang tampak borjuis. Acara syukuran ini terbilang megah untuk merayakan kelulusan Ares dari seleksi masa percobaan tiga bulan sebagai Junior Graphic Designer pada salah satu perusahaan telekomunikasi. Tenda seperti acara pernikahan berwarna putih-emas berdiri gagah di halaman belakang rumah, kurang pelaminan saja. Aku duduk bersama orang-orang terbaik. Tidak hanya Ibu dan Marwa, teman-teman kami juga menghadiri undangan. Ada Bu Dewi dan Pak Rully, Trisna dan Tyas, juga Galih dan Fahmi. Kami semua terkikik melihat bagaimana Ares dibawa kesana kemari dengan lemas, seperti layangan yang ditarik tanpa angin.
“Kurang Pak Yahya, nih!” celetuk Bu Dewi dengan wajah sedih yang dibuat-buat.
“Eh! Telpon, yuk! Video call!” kataku sambil mengeluarkan handphone. Semua yang di meja itu setuju dan tampak semangat. Kecuali Tyas, Galih dan Fahmi yang memang jarang ke kost-ku dulu sehingga tidak begitu tahu Pak Yahya. Tyas berdiri, memberikan kursi untuk Bu Dewi agar duduk lebih dekat denganku. Telepon tersambung.
“Selamat tahun baru!” ucap kami serempak.
Hari ini memang masih dalam minggu pertama awal tahun. Pak Yahya tampak gembira dan hampir meneteskan air mata melihat kami duduk bersama. Dalam panggilan itu, Zahara, anak Pak Yahya, yang juga ikut bergabung, tampak tumbuh dengan cantik. Aku udah SD kelas tiga, katanya, dan badannya semakin berisi. Aku masih ingat, dia yang kurus sering bermain ke kost sore hari untuk mengunjungi ayahnya yang bekerja. Sebagaimana khas anak TK, dulu dia berkulit gelap dan bau matahari, lengkap dengan rambut yang jika tidak lepek, pasti megar. Kini kulitnya lebih cerah, rambutnya yang panjang sebahu itu tampak terawat, hitam mengilap. Pada panggilan video itu, dia cukup cerewet berbicara, lucu.
Bu Dewi memamerkan makanan yang sengaja dipesan Ares darinya untuk hidangan acara ini. Sedangkan ibuku banyak diam, sesekali tertawa jika memang ada yang patut ditertawakan. Pak Rully, dengan suara dan nada kebapak-bapakan, rendah dan berat, saling bertanya kabar dan sepertinya lebih mengkhususkan bertanya bagaimana kehidupan di Sragen. Sesaat telepon akan berakhir, Ares tiba-tiba datang, mengejutkan kami semua yang fokus menatap satu layar. Dia menyapa Pak Yahya dan Pak Yahya menyelamatinya.
“Kerja sing bener, Mas! Mbanggakne wong tuwa!” ujar Pak Yahya.
“Siap, Pak!” Ares mengacungkan jempol.
Dan telepon berakhir.
Ares bergabung bersama kami, dia duduk sambil membuka seluruh kancing kemeja hitamnya, hingga menampilkan kaos putih polos, “Panas,” katanya kemudian.
Lalu dia makan dengan lahap, karena mengaku belum makan apapun sejak pagi. Sambil makan dia mengatakan pada Bu Dewi bahwa makanan ini lebih banyak mendapatkan perhatian daripada dirinya yang memang bintang acara. “Dipuji loh, Bu. Sampai ada yang minta nomor catering-nya,” kata Ares lagi. Bu Dewi kegirangan, Pak Rully juga tampak bangga. Ibu terdengar bisik-bisik pada Marwa mengatakan gudeg ini luar biasa, dan diam-diam sepertinya ingin belajar dari Bu Dewi bagaimana cara membuatnya. Trisna dan Tyas sibuk selfie, keduanya tersenyum manis, walau yang satu tampak berusaha habis-habisan menyamarkan wajah jutek. Galih dan Fahmi sedang menceritakan pekerjaan masing-masing. Tidak hanya bercerita, mereka berlomba menunjukkan pekerjaan siapa yang lebih menantang. Fahmi, yang kini bekerja di sebuah rumah produksi, mengaku lebih sulit bekerja dengan tim daripada hanya mengatur anak buah pada perusahaan yang sudah besar di tangan seorang ayah –menyindir Galih. Aku tertawa melihat tingkah mereka berdua, persis seperti anak SD yang masuk tahun ajaran baru dan memamerkan tas yang masih wangi toko. Semakin wangi dan kaku tas itu, semakin tinggi harga diri anak tersebut.
Sesaat kemudian mereka sudah tidak tampak menarik lagi, sudah akur dan berjalan bersama mengambil minum. Aku hanya duduk sambil melihat-lihat saja, memutar kepala, melemparkan pandangan ke halaman yang meriah ini. Lalu tepat saat pandanganku berakhir di kursi sebelah kiri, Aruna di sana, duduk, menatapku sambil tersenyum seperti biasa. Rambutnya dihiasi bando beludru merah muda. Aku membalas senyumannya dengan dada berdebar pula.
“Ambil buah, yuk!” katanya, dan suara itu berhimpitan dengan suara dari arah belakang. Suara Tyas.
Aku menoleh, Tyas berdiri sambil memegang punggung kursi yang aku duduki. Saat menoleh lagi ke bangku kiri, Aruna sudah pergi. Aku menelan ludah, untuk sesaat merasa gundah.
“Yuk!” aku menyahut sambil berdiri. Dan tidak duduk di sana lagi setelah kembali hanya untuk menghindari ilusi.
-oOo-
Saat aku masuk ruangan, Tyas sedang duduk berhadapan dengan Bu Eka, satu-satunya akuntan di Midas Creativity, sebuah agensi digital marketing milik Pak Adimas yang dipercayakan kepadaku untuk dikelola. Februari ini adalah bulan ke delapan Midas beroperasi. Aku menyapa mereka sebelum duduk. Tidak lama Bu Eka meninggalkan meja Tyas dan duduk pada kursi di hadapanku. Sudah menjadi kegiatan rutin sejak empat bulan lalu –sejak Bu Eka bergabung bersama kami membantu pembukuan dan penyusunan laporan keuangan– bahwa setiap jam Midas mulai beroperasi ia akan melaporkan pembukuan harian kepada aku dan Tyas.
“Bagaimana, ada yang perlu aku tahu?” tanyaku, berusaha untuk mengikuti pembicaraan mereka sebelumnya. Bu Eka mengangguk, lalu mulai menjelaskan situasi. “Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama mengenai anggaran untuk iklan baru yang akan kita produksi. Kita perlu memastikan semuanya tetap dalam batas yang telah ditetapkan sebelumnya, jangan sampai budget overrun.”
Tyas menambahkan, “Ada beberapa pengeluaran yang perlu diverifikasi.”
Aku mengangguk, memahami pentingnya detail yang mereka bahas sambil memeriksa berkas yang diperlihatkan Bu Eka, “Oke, nanti aku sama Tyas periksa ulang alokasi anggarannya. Terima kasih, Bu.” Bu Eka keluar ruangan. Aku dan Tyas merencanakan anggaran atau membahas hal-hal lain yang dirasa perlu untuk kepentingan Midas, termasuk manajemen karyawan (yang masih empat orang). Tyas, yang memang lebih sering berada di kantor, mempunyai lebih banyak waktu untuk memperhatikan bagaimana tim bekerja. Dia mengeluhkan satu pegawai yang bertanggung jawab mengelola akun media sosial klien terpantau tidak cepat menanggapi respons audiens.
“Nurunin engagement. Bisa-bisa brand distrust, Kak!” Tyas berdecak kesal, “ini untung Pak Dahlan belum komplain aja!” katanya lagi. Pak Dahlan adalah salah satu klien yang memercayakan pengelolaan media sosial usahanya yang bergerak di bidang pakan ternak kepada Midas. Usahanya memiliki diferensiasi produk berupa pakan organik dan modernisasi kemasan. Bahkan, desain kemasannya pun dipercayakan kepada Midas. Dapat dikatakan Pak Dahlan adalah pelanggan dengan loyalitas tinggi dan tidak selayaknya menerima pelayanan tidak memuaskan.
“Ya, nanti sebelum pergi gua panggil Satrio,” kataku sambil memeriksa akun media sosial pakan ternak Pak Dahlan dan melihat sendiri bagaimana Satrio tidak responsif terhadap audiens. “Jangan lupa. Catat di buku catatan karyawan masalah si Satrio ini, Yas.”
Tyas mengangguk.
Setelah jam makan siang, aku memanggil Satrio. Dia yang aku ketahui memang menguasai dua bahasa asing selain Inggris, yaitu Korea dan Jepang, mengaku kurang jam tidur sebab harus begadang menyelesaikan pekerjaan sampingan: menerjemahkan salah satu serial live action Jepang yang akan tayang pada situs menonton ilegal. Aku katakan padanya, jika memang ada pekerjaan sampingan, seharusnya dan sepatutnya tidak mengganggu pekerjaan utama. Juga menegaskan padanya bahwa pekerjaan yang dia lakukan tidak hanya berdampak pada Midas tapi juga berimplikasi pada nama baik Pak Dahlan.
“Kerjaan yang lu kerjain ini ibarat ujung tombak untuk dua bisnis, Sat. Lu gak bisa seenaknya, ngantuk terus tidur, lapar terus cabut makan. Semuanya harus dipersiapkan sebelum mulai. Ini kerja, ada tanggung jawabnya, bukan tempat ngetes-ngetes ilmu.”
Satrio, sedari tadi hanya menunduk setelah menjelaskan alasan kesalahannya. Dia meminta maaf dengan sepenuh hati, dan raut wajahnya menunjukkan semburat ketakutan akan diberhentikan. Lalu, dia berjanji akan bersikap profesional dan memberikan hasil pekerjaan yang lebih baik.
Aku mengangguk sambil mempersilahkan Satrio keluar dan kembali pada pekerjaannya. Lalu sekali lagi kembali memeriksa file promosi pada tablet untuk dibawa ke acara konferensi pariwisata dan travel pada salah satu hotel bintang lima. Hal-hal seperti inilah yang membuatku sering meninggalkan kantor sebab harus jeli mengidentifikasi peluang bisnis baru dan memperluas jangkauan pasar agensi.
Konferensi yang aku hadiri itu membuahkan hasil. Minggu ketiga Februari, aku berada di Tangerang bersama Tyas dan Gilang. Dalam konferensi dua minggu lalu itu, aku berhasil mendapatkan kerja sama jangka panjang dengan satu agen pariwisata milik salah satu artis ibu kota. Negosiasi bisnis yang aku dan Tyas lakukan langsung bersama pemiliknya berjalan baik. Keluar dari gedung itu, di dalam mobil yang terparkir di halaman kantor agensi dimana Gilang menunggu, Tyas berseru kegirangan karena Midas mendapatkan penawaran dengan harga yang cukup fantastis. Gilang, yang memang bekerja pada salah satu perusahaan ritel di Tangerang, menyempatkan diri mengantarkan kami (khususnya Tyas) untuk membuat kesepakatan kerja sama dengan agen pariwisata ini. Lalu kami makan siang bersama sebelum aku dan Tyas kembali ke Jatinegara, dimana kantor Midas berada. Di restoran itu lah aku kembali bertemu Gina, dia –tanpa bertanya terlebih dahulu– menarik kursi di sampingku dan duduk. Kami bertiga (aku, Tyas dan Gilang), setelah berpandangan dengan tatapan heran, akhirnya bisa bersikap biasa saja setelah Gina bercerita dengan luwes bahwa dia sudah bekerja di klinik Bu Sarah sejak awal Desember, setelah dua kali gagal.
“Yang pertama dan kedua gagal pas wawancara,” ujarnya dan masih ada sisa-sisa kekesalan pada wajahnya.
Tentu saja, gaya komunikasinya yang tidak terkontrol itu menunjukkan keterampilan interpersonal yang kurang baik. Dan dia, yang sepertinya tidak bisa diam barang semenit saja, kembali menceritakan Aruna yang tidak diketahui oleh siapa pun di klinik.
“Heran. Padahal menurut cerita Mbak Aruna dulu dia hadir, loh, pas pembukaan klinik itu,” kata Gina sambil menyuap mi gorengnya, “juga katanya ikutan bantuin cek kesehatan gratis,” katanya lagi sambil mengunyah.
Tyas sedikit-sedikit melirikku, seperti memastikan bahwa aku sudah biasa-biasa saja saat nama Aruna kembali disebutkan, setidaknya di depan Gina. Dari luar aku terlihat tidak begitu mendengarkan tapi juga tidak bisa menepis bahwa sesuatu dalam diriku terusik. Sejujurnya, sejak melihat Aruna dan Andre bersama di parkiran klinik dulu, Kota Tangerang, walaupun dalam jangkauan, bagiku terasa samar. Aku tidak pernah menginjakkan kaki di kota ini lagi kecuali untuk urusan pekerjaan. Dan ini adalah pertama kalinya sejak tahun lalu.
-oOo-
Senin itu hingga siang adalah hari yang biasa, berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi menjelang Ashar suasana terasa sedikit berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di langit Jakarta. Dengan secangkir kopi di tangan, aku mengetuk tablet, menyalakannya. Setelah beberapa menit memeriksa media sosial Midas, pandanganku tertuju pada sebuah artikel dengan judul yang membuatku tidak jadi menyesap kopi bahkan saat cangkir sudah menyentuh bibir, aku terhenti sejenak.
"Virus Corona Masuk Indonesia, Dua Kasus Positif ditemukan di Depok."
Mataku membesar seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kubaca. Aku tahu tentang virus ini, tentu saja. Selama beberapa bulan terakhir, berita tentang virus yang berasal dari Wuhan, China, ini telah mendominasi berita internasional. Namun entah bagaimana, berita itu terasa jauh, seperti masalah di belahan dunia lain yang tidak akan sampai ke sini. Terlebih beberapa minggu sebelumnya beberapa pejabat negara tampak remeh terhadap virus ini, bahkan Menkes Terawan mengatakan dengan entengnya, “Enjoy aja,” sementara komentar santai yang tumpul empati keluar dari mulut Menhub Budi Karya Sumadi bahwa Covid tidak bisa menginfeksi masyarakat Indonesia sebab terlalu sering makan nasi kucing.
Kubaca artikel itu paragraf demi paragraf. Dua orang terinfeksi, seorang ibu dan anaknya setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang pada klub berdansa. Kumatikan layar tablet dengan sedikit resah dan merokok sambil memandang keluar jendela, melihat hiruk-pikuk jalanan Jakarta yang masih sibuk seperti biasanya. Aku segera menelepon ibu, memberitahukan tentang virus yang baru saja masuk ke negeri ini dan meminta ibu lebih mawas diri. Lalu setelah telepon berakhir, aku memanggil Tyas dan semua pegawai Midas untuk duduk membicarakan masalah dan dampak virus ini terhadap industri yang kami jalani.
Saat pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kantor kami yang biasanya ramai dengan aktivitas mendadak sunyi. Tim kami, selain aku, Tyas dan Bu Eka, terdiri dari desainer kreatif, copywriter, analis data dan manajer proyek, harus dipaksa dengan cepat mampu menyesuaikan diri untuk bekerja dari rumah. Dua minggu awal kami semua belum terbiasa, cenderung kesulitan karena selalu saling koordinasi dan melihat hasil pekerjaan secara langsung. Ini adalah tantangan besar, tetapi bagiku juga peluang untuk menunjukkan fleksibilitas tim Midas kepada Pak Adimas. Selain rutin mengadakan pertemuan online, secara tidak sengaja, bahkan tanpa membuat janji sebelumnya, Tyas dan aku sering bertemu di kantor. Kadang aku duluan datang, di lain hari Tyas. Hal ini membuatku cukup senang, akhirnya bisa bertatapan langsung dengan seseorang saat berbicara. Seperti hari itu, saat lebaran. Selesai sholat Idul Fitri, aku yang bingung karena tidak bisa pulang terkait peraturan pemerintah, justru tidak kemana-mana selain kantor. Mami tidak menerima tamu, ucap Ares begitu. Di kantor, aku hanya menonton serial BBC hingga sore. Saat akan kembali ke kost, Tyas datang. Aku tidak jadi pulang. Hingga malam aku dan Tyas bercerita mengenai hal-hal yang bukan pekerjaan. Tyas mengatakan rindu pada Gilang, juga mengabarkan bahwa pacarnya itu akan melamarnya akhir tahun nanti. Aku juga bercerita hal remeh saja, kebanyakan mengenai film atau sesekali pengalaman di Pulau Siberut tahun lalu.
-oOo-
“New normal,” kata Cak Son sambil terkekeh. Ada sesuatu yang sinis dari cara dia mengatakan frasa itu. Satu sudut bibirnya naik lebih tinggi dari pada satunya. Mbak Sundari datang membawakan sepiring buah potong, kulirik, apel dan pir dalam piring plastik hijau kusam. “Makan, Gam. Jangan dilirik aja …,” canda Mbak Sundari. Aku mengangguk malu. Lalu dia kembali ke dalam gerai buahnya meninggalkan aku dan Cak Son yang duduk di luar.
“Lu segala! Ke sini doang pake masker. Lepas!” Cak Son menatapku dengan jengkel lalu mengambil sepotong pir dan mengunyah dengan cepat.
“New normal,” kataku sengaja membuatnya kesal.
“Kampret!”
Masker kubuka, lalu juga mengambil sepotong pir, mengunyahnya.
“Mereka maksa kita berdamai sama ketidakpastian dan ketakutan,” ujar Cak Son lagi. “Ini, nih …,” dia mengambil maskerku, memegang tali masker seolah jijik hanya menggunakan ujung jempol dan telunjuk, “kayak selimut tipis yang nutupin kerapuhan dunia kita yang terpapar pandemi. Seolah kalau lu pakai ini, lu aman. Kalau lu lupa pakai ini, bersin dikit lu langsung dijauhin se-RW.”
Aku tergelak.
Cak Son, orang yang pernah melihat langsung bagaimana ketidakadilan terjadi di depan matanya hingga berpengaruh buruk pada kesehatan mentalnya untuk waktu yang cukup lama. Juga pernah merasakan bagaimana pemerintah seolah tuli dan buta terhadap konflik antara kaum kapitalis dan petani kecil, dan baru melek jika sudah jatuh korban jiwa. Membuatku merasa bahwa memahami perspektif Cak Son menjadi penting dalam situasi sekarang ini.
“Iya. Tapi ini pencegahan, Cak,” kataku, “yah, upaya biar kita nerima kenyataan pahit juga.”
“Justru kita harus tetap skeptis. Kritis. Gak biarin mereka nipu kita dengan kata-kata manis,” Cak Son menyalakan api untuk rokoknya, “bilang aja dunia lagi sakit, lu pada harus ekstra hati-hati kalau gak mau mati. Gak usah pake ungkapan klise segala. New normal. Taik! Apanya yang normal kalau jalanan sepi begini?” dia diam sebentar, lalu melirikku dengan sorot menekan, “lu juga kemarin lebaran gak bisa pulang, kan?”
Aku mengangguk.
“Mamam tuh masker!” ujar Cak Son kasar lalu mengembuskan asap tebal dari mulutnya.
Lagi-lagi aku terkekeh dan Cak Son yang jengkel melempar maskerku ke tong sampah. Lalu obrolan kekesalan bergulir kepada hal-hal yang sebetul-betulnya normal: membahas pekerjaan. Aku membutuhkan dummy food.
Di tengah-tengah rasa cemas dan stres akibat simpang siur informasi juga terus menerus terpapar berita negatif tentang virus , memasuki kuartal keempat tahun 2020, tidak sedikit orang yang mengalami ketidakpastian finansial akibat kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji, atau penutupan usaha. Bisnis-bisnis yang bertahan juga terpaksa menutup toko fisik mereka karena pembatasan sosial. Lantas kebutuhan digital marketing meningkat tajam. Perusahaan yang bertahan, yang juga sebelumnya ragu untuk terjun ke dunia digital, kini tidak punya pilihan selain memanfaatkan platform online untuk tetap menjalankan usaha. Di sinilah peran kami menjadi sangat krusial. Midas tidak hanya membantu klien-klien lama untuk memperkuat kehadiran mereka secara online, tetapi juga menerima banyak klien baru yang membutuhkan bimbingan dalam merambah dunia digital. Midas sibuk dengan kantor yang sunyi. Kami bekerja terpisah, lagi-lagi. Pada hari-hari lain, setidaknya dua kali dalam sebulan aku akan mengisi seminar online, baik untuk sekolah, kampus hingga UMKM dengan membawa materi mengenai digital marketing. Lalu hari-hari lain saat senggang, aku masih keluar memotret jalanan yang lengang. Juga, saat malam dan mengalami keresahan karena segala macam situasi yang kami hadapi, aku masih menulis surat yang tidak pernah aku kirimkan kepada Aruna. Tidak sering, dalam delapan bulan ini hanya tiga surat saja. Satu surat tepat saat malam hari setelah acara selebrasi yang diadakan mami untuk Ares, dua lagi selama pandemi. Kebanyakan tulisanku berupa kerisauan sendiri terhadap kondisi saat ini, juga beberapa kalimat yang tertulis menggambarkan betapa aku mengkhawatirkannya. Aku masih bertanya-tanya, apakah dia sudah melahirkan, apakah dia masih bekerja sebagai perawat. Kalau iya, bagaimana keadaannya? Televisi dengan berita yang selalu berseliweran mengatakan kurangnya alat pelindung diri. Media sosial juga menggembar-gemborkan hingga viral bagaimana tekanan yang dihadapi tenaga kesehatan. Tidak sedikit dari mereka kelelahan. Kamu harus baik-baik aja, Runa. Kubaca sekali lagi surat-surat yang sudah kutulis untuknya, lalu aku merobeknya dari belakang buku, melipatnya secara bersamaan dan menyelipkannya pada kantong tempat kartu di belakang buku.
Di bulan ketiga belas Midas berdiri, Pak Adimas memutuskan untuk mengubah bentuk badan usaha dari sebuah agensi menjadi CV setelah aku mengatakan akan berinvestasi pada perusahaan ini. Saat itu, baik Pak Adimas maupun Tyas tampak senang. Kini, Midas tidak lagi dimiliki oleh Pak Adimas seorang. Aku, yang telah mengelola Midas, membuatnya tidak hanya bertahan dengan baik, namun berkembang cukup pesat di tengah-tengah pandemi, merasa yakin dengan kemampuanku untuk menangani masa depan perusahaan ini. Tabunganku, hasil bekerja di Midas ditambah tabungan lain dari beberapa komisi yang aku terima dari pekerjaan sebelumnya (termasuk angka dua digit dari Pulau Siberut) telah cukup untuk memiliki sepertiga Midas Creativity. Lalu aku usulkan pada Pak Adimas, karena sudah berubah menjadi CV, sebaiknya Midas didaftarkan pada Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) agar suatu saat bisa mengikuti ajang Citra Pariwara. Wajah Pak Adimas cerah seketika.
Meskipun beberapa hal menggembirakan terjadi, namun kembali aku diingatkan bahwa kita semua—satu dunia—masih dilanda ketakutan dan kecemasan yang sama, dan jauh lebih besar. Jumat siang di minggu terakhir bulan November, Marwa menelepon saat aku, Tyas, dan Bu Eka tengah mengadakan konferensi online. Aku terpaksa mengabaikan telepon Marwa karena kami sedang membahas perencanaan keuangan Midas. Tidak lama setelah itu, handphone-ku bergetar, dan Marwa meninggalkan pesan yang langsung aku baca.
‘Kak! Ibu demam udah dua hari gak membaik’
Aku tahu bahwa resah yang dirasakan Marwa melebihi apa yang ditulisnya. Dadaku berdegup lemah saat membalas pesannya, mengatakan padanya sebaiknya dia membeli alat tes rapid antigen dan segera memberitahukan hasilnya. Setelah mengirimkan pesan pada Marwa, aku mencoba kembali fokus pada konferensi kami.
Setengah jam berlalu. Handphone kembali bergetar. Jantungku berdegup kencang melihat nama Marwa tertera. Aku, yang tiba-tiba gagu saat ingin mengatakan undur diri sejenak dari rapat, hanya bisa menatap cemas layar komputer, membuat Tyas dan Bu Eka sadar –tentu saja karena kepekaan yang meningkat atas situasi gawat yang mendunia– bahwa sesuatu sedang terjadi, dan mereka, tanpa perlu aku katakan, tahu sesuatu itu apa.
“Angkatlah, Gam.” Begitu kata Bu Eka. Aku mengangguk dan mematikan komputer, kemudian bertelepon dengan Marwa sambil mengusap-usap wajah, melampiaskan gelisah.
“Aku pulang,” kataku setelah Marwa berbicara cukup panjang. Entah bagaimana, entah bisa atau tidak aku pulang, mengingat pembatasan perjalanan dan segala peraturan yang menyulitkan yang harus aku hadapi di pos-pos perbatasan, yang aku tahu aku hanya ingin pulang. Ibuku positif Covid bahkan secara mengejutkan Marwa juga terjangkit meskipun tanpa gejala.
Sambil menelepon Tyas, aku mengemas tablet milik Midas dan beberapa catatan lainnya. Melajukan motor secepatnya menuju rumah Pak Adimas, mengatakan akan mengambil cuti juga menyerahkan beberapa pekerjaan kepada Tyas yang akan dia kelola bersama tim selama aku di Bogor, selama yang aku sendiri tidak tahu sampai kapan.
Pak Adimas dengan sangat paham mengizinkan. “Semoga ibu dan adik kamu cepat sembuh, Gam. Sampaikan salam saya,” katanya dengan arif.
“Terima kasih, Pak. Saya akan kembali secepatnya setelah mastiin situasi di rumah membaik.”
Pak Adimas mengangguk, kemudian dia memintaku sekalian mengantar Tyas ke kantor. Aku tidak keberatan karena memang searah.
Tyas turun dari lantai dua, sudah siap dengan jaket kulit dan helmnya.
“Berangkat, Pa,” katanya sambil memeluk Pak Adimas sekilas.
Aku juga bersiap, menarik resleting jaket bomber. Sebelum motor meninggalkan halaman rumah, Pak Adimas berseru, “Hati-hati kalian!”
Motor melaju kencang pada jalanan sore yang lengang. Suara Tyas terbawa angin dan tertelan deru motor. Dia mengulang perkataannya, mengatakan ada beberapa hal yang dia ingin periksa pada komputer kantor. Aku merespons dengan mengangguk saja sebab pikiranku kacau memikirkan ibu dan adikku di rumah. Sesaat kenangan pahit tiga setengah tahun lalu, saat berita bapak meninggal, mengganggu konsentrasiku. Lalu tiba-tiba, aku takut hal yang sama terjadi pada Ibu.
Tyas menepuk pundakku untuk mengingatkan berhenti saat lampu lalu lintas menyala merah.
“Kak, merah, kak,” ucap Tyas agak keras.
Aku ngerem mendadak tepat dibelakang garis zebra-cross. Tidak ada percakapan lagi antara aku dan Tyas sambil menunggu aba-aba lampu lalu lintas. Jalanan lengang. Kota ini walau terang dihiasi lampu jalan dan lampu gedung perkantoran, namun sesuatu membuatnya justru muram. Benar-benar gambaran kota yang sedang bersedih.
Pundakku kembali ditepuk Tyas pelan saat lampu berganti hijau.
“Oh,” aku terkejut karena lamunan yang buyar. Dan kembali melanjutkan perjalanan. Rasanya baru beberapa meter meninggalkan lampu lalu-lintas, suara klakson dari arah kanan menggema seperti teriakan peringatan. Aku menoleh cepat, mataku terbelalak melihat mobil sedan hitam melaju dengan sangat kencang. Napasku tersengal, adrenalin merayap ke seluruh tubuh secepat kilat. Suara teriakan Tyas terdengar dari balik helmnya seiring dengan remasan kuat tangannya pada jaketku. Pada satu tarikan napas aku berusaha lebih laju namun semuanya terjadi begitu cepat. Terlalu cepat.
Brak!!!
Dentuman keras menggelegar seiring tubuhku terbang dan dengan kuat mendarat di aspal. Tiap detik terasa lamban, waktu nyaris berhenti. Pandanganku buram, punggungku terasa kaku sedang kaki kananku luar biasa ngilu. Aku menoleh ke kiri. Di antara celah kaca helm yang pecah, aku melihat Tyas, tergeletak lemah tidak jauh dari motor yang juga tampak penyok, dan … merah. Tyas terbaring dan terlantar dengan banyak warna merah pekat di sekitarnya.
Darah … darah ….
Dengan menggigil aku memaksakan diri untuk bangkit dan tertatih-tatih mendekatinya. Kembali terduduk di sampingnya, berseru seraya mengangkat kepalanya, “Yas! Tyas! Bangun!”
Lehernya lemah tidak menyangga, matanya terpejam dan dia tidak merespons. Jantungku berdetak semakin kencang saat melihat bagaimana darah berlumuran dan menutup seluruh sisi kanan wajahnya, mengalir terus hingga ke leher, meninggalkan jejak mengerikan pada kerah kemeja biru muda yang menyembul dari balik jaket kulit yang sudah acak-acakan, sobek dan terlalu berantakan. Tanganku gemetar saat menekan nadi Tyas pada leher dan pada pergelangan tangannya.
Masih! Masih berdetak, tapi lemah.
Napasku sendiri terasa berat, aku bahkan tahu bahwa napasku sendiri terembus melalui mulut, bukan dari hidung. Derap-derap langkah kaki dan teriakan-teriakan perlahan mendekati kami. Saat itu aku ingin mengangkat Tyas untuk membawanya ke pinggir, saat itu lah aku meringis karena pergelangan tangan kananku tiba-tiba terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Sakit dengan cara yang menyengat. Lalu telingaku berdenging hebat, aku bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan seorang pria paruh baya kepadaku dengan wajah kalut. Dia dan orang-orang di belakangnya terlihat seperti video dengan kualitas rendah: buram dan suara yang patah-patah. Pandanganku gelap dan hitam.
-oOo-
Ibu….
Ibu….
Marwa….
Dingin. Sekujur tubuhku terasa dingin. Mataku perlahan terbuka. Sayangnya kelopakku terasa terlalu berat, aku tidak bisa membelalakkan mata memastikan apakah cahaya yang menyilaukan dihadapanku ini adalah cahaya kematian atau cahaya lampu operasi. Samar-samar terdengar suara monoton dengan tempo teratur, bip bip bip.
Ah, benar. Ruang operasi. Aku belum mati.
Mataku –walau menolak– kembali tertutup. Aku ingin berbicara satu kata saja namun suaraku tertahan oleh sesuatu yang membuatku sangat mengantuk. Pandanganku kembali gelap dan sepertinya ini akan menjadi tidur yang panjang.
-oOo-
Aruna ….
Aruna ….
Aku merasakan tanganmu mengusap wajahku. Juga bibir mungilmu mengecup dahiku. Aku mendengar namaku dalam bisikanmu. Kenapa suaramu bergetar? Apa yang kamu tangiskan?
“Runa?” Pandanganku nanar, lambat laun menjadi jelas dan menatap plafon putih dihiasi lampu menyala terang. Dengan wajah yang masih lurus menghadap langit-langit, mataku bergerak-gerak. Aku mendapati tiang infus lengkap dengan botol infus terpasang pada sisi kanan dan juga tepat di bawah hidungku tertempel selang. Aku tahu, selang oksigen, sebab saat benar-benar menoleh ke kanan, tabung baja biru yang ramping tegak berdampingan dengan ranjangku.
“Gua kayaknya harus manggil optometris,” kata Ares sambil bangkit dari sofa, dia menghampiriku, “Aruna segala. Ares, Nyet!”
Ah … ternyata Aruna tadi cuma mimpi. Cuma mimpi.
“Bentar, gua manggil perawat dulu di luar.” Ares pergi dengan cepat sebelum aku berkata apa-apa, terlebih menanyakan Tyas.
Aku melirik jam dinding pada sudut ruangan yang menunjukkan pukul enam dan sore, sebab samar-samar aku bisa melihat warna langit yang mulai gelap dari balik jendela.
Haus. Aku berusaha bangkit untuk meraih segelas air, namun tiba-tiba aku merasa sakit pada tangan kanan. Pergelangan tangan kananku terasa perih seperti disayat pisau, dan kini goyah menahan beban tubuh. Aku mengamati penyangga berwarna cokelat muda yang membungkus pergelangan hingga telapak tangan. Perlahan-lahan aku mencoba mengangkat tangan—aman. Namun saat mencoba menggerakkan jari-jari, aku tidak bisa. Jariku sama sekali tidak bergerak. Aku kalut. Dengan gugup dan menahan napas mencoba lagi—gagal. Hasilnya sama. Kelima jariku tetap diam, kaku, dan kini hanya bergetar.
Saat aku mulai panik, Ares masuk bersama seorang perawat perempuan dan dokter yang memperkenalkan diri sebagai Dokter Gusman, Spesialis Ortopedi dan Traumatologi. Mendengar spesialisasinya saja, aku tahu apa yang akan keluar dari mulut dokter ini adalah segala sesuatu yang akan membuatku bermuram durja. Aku menatap Ares yang berdiri jauh di belakang perawat. Air mukanya yang tidak kalah keruh itu seakan membenarkan pikiranku tentang muram durja. Dia mengangguk perlahan, seolah berkata kuatlah, kawan.
-oOo-
Saat Dokter Gusman dan perawat sudah pergi, Ares yang masih bersandar pada dinding di sebelah jendela mengatakan bahwa ibuku tahu. Dia juga mengatakan–dengan ketenangan luar biasa yang tidak pernah ditunjukkannya– bahwa ibu dan Marwa, walau positif Covid, tapi dapat dikatakan dalam keadaan yang tidak mengkhawatirkan.
“Nyokap lu bilang, dan katanya juga lu harus tahu kalau udah siuman, dia dan Marwa baik-baik aja. Ibu katanya kayak flu biasa, cuma yah, gak bisa nyium apa-apa sama gak berasa apa-apa lidahnya. Mereka berdua isolasi mandiri di rumah. Pak RT sama orang puskesmas rutin kunjungan, ngasih obat dan vitamin,” Ares diam, “kalau lu udah siap, telpon mereka. Nyokap lu hari ini udah empat kali video call gua mau cek keadaan lu.”
Aku menghela napas.
“Ini hari apa?” tanyaku.
“Minggu. Kecelakaan itu udah lewat dua hari.”
Ares duduk di kursi dan menatapku dengan cara yang tidak pernah kupikir akan diperlihatkannya dalam pertemanan ini—tatapan simpati yang penuh rasa iba. Sayangnya, aku tidak suka.
“Tyas?” tanyaku membuang muka, menghindari sorot mata belas kasihan dari seorang teman.
Ares mengembuskan napas, “Luka di wajah.”
Aku menoleh cepat padanya dengan mata terbelalak.
Anggukan Ares yang sangat dalam itu meyakinkanku bahwa luka pada wajah Tyas bukanlah luka biasa.
“Dijahit. Pipinya dijahit,” kata Ares, bahunya sedikit merosot saat mengatakan itu. Aku terperangah, dan jantungku berdegup tidak teratur.
“Yang lain? Kaki? Tangan?” tanyaku tergesa-gesa.
“Aman. Yah, paling baret-baret kena aspal aja.”
Ares melepas ikatan rambutnya dengan kasar, digaruk-garuknya kepala yang tak gatal untuk menyembunyikan resah, “Tyas malam ini lepas perban bekas jahitan,” katanya kemudian.
“D-dia di kamar mana?”
Kursi roda yang didorong Ares terasa sangat lamban bergerak menyusuri lorong-lorong. Banyak perawat dan beberapa dokter berjalan dengan langkah tegas dan cepat, beberapa tampak seperti biasa, memakai jas putih atau seragam perawat. Sementara yang lain sudah seperti astronot saat mengenakan APD lengkap. Sedang aku, sepanjang roda kursi besi ini menggiling lantai, sepanjang itu juga lah diriku digiling rasa bersalah. Dadaku kembang-kempis. Kalut. Batinku menjeritkan kesusahan hati. Entah dengan rupa yang bagaimana aku menghadapi Pak Adimas dan istrinya setelah membuat paras anak perempuan mereka rusak.
Kamar Tyas, kamar yang berbeda lorong dari kamarku. Walau tidak terdengar suara-suara kesedihan, namun ruangan ini mampu menekan bahuku dengan suguhan kerapuhan. Mata pasangan suami-istri ini penuh perasaan yang lapuk menatap anak perempuannya tertunduk dengan rambut yang biasanya terikat tinggi dan rapi, kini justru terurai, jatuh lemah seolah ikut merasakan keputusasaan si Empunya.
Aku meminta Ares mendorong kursi roda lebih dekat ke ranjang Tyas.
“Yas?” panggilku pelan sambil menurunkan masker.
Tyas melempar wajahnya ke jendela dengan cepat, menghindari tatapanku, “Gua gak apa-apa, Kak.”
Tyas. Dia tidak menangis. Suaranya bahkan terdengar teguh. Tapi, tangannya yang menggenggam erat handphone dengan kamera depan terbuka itu bergetar.
Aku tahu apa yang dia khawatirkan. Dia perempuan. Dan bagi perempuan, paras adalah segalanya. Mereka menjaga wajah seperti menjaga martabatnya.
Aku segera menelungkupkan tangan kiriku pada tangannya yang bergetar, mencoba meredam guncangannya yang terasa di setiap sela-sela jari. Bagiku, kata maaf kini terasa seperti sampah—tidak cukup untuk mengakui dan mengungkapkan perasaan bersalah. Tak ada yang terpecahkan dengan kata maaf; kata itu hanya menambah luka, memperjelas kondisi Tyas yang lemah, dan memperkuat posisiku sebagai orang yang bersalah. Bisa jadi, dia akan menangis setelah mendengar permintaan maafku, dan aku akan semakin tenggelam dalam penyesalan.
“Maaf, Yas,” ucapku, justru mengeluarkan kata sampah itu karena benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa kulakukan dalam tekanan luar biasa ini, pada tempat ini. Dan benar saja, suara tangisan terdengar. Tapi bukan berasal dari Tyas, melainkan dari ibunya. Pak Adimas yang kini merangkul istrinya, menatapku, dan aku bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada setitik kemarahan atau kekesalan terpancar dari matanya yang bijaksana.
Tyas menoleh, menatap lurus, menyaksikan bagaimana ibunya menangisi keadaannya. Aku melihat semburat keangkuhan yang tertoreh pada air muka Tyas.
“Ma, gak perlu nangis. Ini cuma luka,” Tyas berbicara dengan nada yang tegas dan penuh keyakinan. Namun tatapannya mencerminkan sesuatu yang bertolak belakang dengan keangkuhan yang dia tunjukkan. Perasaannya yang memar tersampaikan dengan baik melalui sorot matanya. Dia menoleh padaku, rambutnya yang tergerai itu dia selipkan ke belakang telinga, menunjukkan padaku satu garis yang meremuk dadaku lebih dari apa yang terjadi pada tangan kananku, “Ini hanya luka, bukan apa-apa. Jangan lihat aku pakai muka memelas, Kak,” katanya lagi, suaranya serak.
Dirinya yang menatapku itu tampak buram sebab air mulai menggenangi pelupukku.
Luka itu…
Luka pada wajah Tyas itu …
Satu, kecelakaan terjadi dua hari lalu. Pengendara sedan hitam itu kini meringkuk di sel tahanan dan juga harus membayar sejumlah denda karena kecelakaan lalu lintas itu termasuk tindak pidana, mahasiswa yang dengan sengaja ngebut karena jalanan sedang lengang.
Dua, aku mengalami cedera pada kaki kanan dan pergelangan tangan kanan karena terbentur benda keras. Kaki kanan hanya terkilir dan akan sembuh dalam hitungan hari. Berbeda dengan tangan kananku. Setelah melewati segala macam prosedur pemeriksaan, akhirnya tindakan operasi dilakukan. Operasi kecil pada pergelangan tangan kanan. Tapi menurutku dampaknya cukup besar. Intinya, tangan ini tidak bisa digunakan sekedar memegang pensil atau menggerakkan mouse dengan baik. Aku harus melewati proses terapi fisik untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tangan, tak lupa, obat-obatan. Perkiraan Dokter Gusman, jika rutin melakukan terapi, maka tangan ini akan berfungsi dengan baik setelah tiga bulan. TIGA BULAN!
Tiga, Tyas.
Empat, Tyas.
Lima, Tyas.
Dan …, seterusnya akan selalu Tyas. Selama bekas jahitan cokelat kemerahan yang membelah pipinya itu ada, selama itu pulalah luka di hatiku menganga. Garis yang mempertemukan ekor mata kanan dan ujung bibir kanan itu adalah suatu gambaran nyata bahwa aku, Gamma Aditya, telah berhasil merusak harapan satu perempuan, Tyasworo Adimas.
-oOo-
“Kata Papa …,” Tyas membuka bungkusan makanan, “Kakak gak perlu turun tangan ngambil gambar, atau bikin konten bahkan ngedit juga. Kakak bisa ngasih ide atau masukan. Juga sekedar meriksa kerjaan anak-anak.”
Aku duduk di kasur, melempar pandangan pada meja kerja yang kini tampak sepi, lesu, dan dingin. Sejak pulang dari rumah sakit tiga hari lalu, aku tidak lagi duduk di sana. Dari 365 hari dalam setahun, mungkin 280 di antaranya kuhabiskan di kursi itu. Kini, aku menghindari apa pun yang bisa membuatku kesal dan marah, serta enggan mempertontonkan kelemahanku—setidaknya hingga berbulan-bulan ke depan. Menolak bekerja dengan komputer, aku lebih memilih tablet, sesuatu yang bisa dioperasikan dengan cepat tanpa perlu mouse, tanpa perlu memaksakan tangan kananku bekerja.
“Ayo, Kak. Makan …,” Tyas menyuapiku. Aku membuka mulut dan menerima bubur ayam dari sendok yang Tyas antarkan. Dia mengenakan masker. Kain tipis berwarna hijau muda itu sepertinya lebih berfungsi untuk menutupi luka di wajahnya dari pada melindungi dirinya dari paparan Corona.
“Yas, lu bisa lepas masker …,” ujarku hati-hati.
Tyas menatapku sesaat, lalu menunduk dan mengaduk-aduk bubur ayam dengan canggung, “Ntar ngerusak selera makan,” katanya kemudian.
Berdenyut. Hatiku berdenyut dan perih. Dia berkata seperti itu kepada pelukis yang menorehkan kuas dengan cat darah di sepanjang pipi kanannya.
Aku menggeleng pelan, menelusuri matanya lamat-lamat. Apa yang dia sembunyikan jauh di balik pekatnya warna hitam pada iris matanya, bagiku cukup terlihat dangkal; sebuah kepiluan. Kepiluan itu telah dibendung dengan kuat, hingga hanya ketangguhan yang terlihat.
Aku menarik perlahan tali masker yang terselip pada telinganya, “Bukalah,” kataku nyaris berbisik, “Lu salah. Luka ini sama sekali gak ganggu selera makan gua.” Kemudian aku menyuap sendiri bubur ayam dengan tangan kiri, makan dengan lahap sambil tersenyum melihatnya yang juga tersenyum.
“Gilang,” katanya lagi seturut dengan surut senyumnya, “Gilang bilang ini ganggu selera makan dia.”
Aku terperangah, menaikkan kedua alis tinggi-tinggi, sulit memercayai apa yang baru saja Tyas katakan.
Tyas mengangguk, “Dia … kami …,” kalimat Tyas terbata-bata, “kami gak jadi lamaran. Putus.” Tyas menunduk, mencubit-cubit ujung hidungnya, menyamarkan desiran,“Kami putus, Kak.” Nada bicaranya tidak menuntut, lebih seperti seorang teman yang sedang bercerita kesedihan yang dia rasakan.
Aku menutup kotak bubur ayam dan menaruhnya pada meja kecil yang tersandar di sisi dipan.
Tuhan? Bagaimana ini? Aku benar-benar sudah mengacaukan segalanya untuk Tyas.
“Yas?” panggilku pelan, menunduk berusaha melihat wajahnya yang tertekuk.
“No. I’m all good. Totally fine!” Katanya cepat-cepat menatapku, memaksakan senyuman.
“Maafin gua, ya?”
“Lu salah apa, Kak?”
“Luka ini …, lu sama Gilang ….” Aku diam. Tidak sanggup melanjutkan kata kata putus padanya.
Tyas menyeringai. “Kata Papa, luka ini suatu keberkahan. Gua jadi tahu bahwa Gilang selama tiga tahun ini cuma naksir sama apa yang dia lihat, bukan sama apa yang ada di dalam sini,” katanya lagi. Telunjuknya menusuk dadanya sendiri, “kata Mama, luka ini, jadi acuan terbaik untuk nemuin siapa yang sungguh-sungguh cinta sama aku, luar dan dalam. Aku harus bersyukur. Aku harus bangga. Aku punya semacam filter yang membuat hidupku mudah karena nantinya orang-orang yang berada di sekitar aku adalah orang-orang yang udah benar-benar tersaring. Orang-orang yang tulus.”
Keteguhan Tyas membuatku terkejut. Kali ini dia begitu tampak seperti diriku –jenis manusia yang tidak mengais-ngais rasa iba. Tidak mengemis untuk dikasihani. Tidak suka jika orang lain menganggap kami lemah.
“Ini gak kesalahan kakak. I'm done with your sorrys. Those words are just tearing us apart. Neither of us messed up. The one who did is locked up. We just gotta move on and heal,” dia menatapku dengan bola mata yang bergerak-gerak pendek dan cepat, “Here,” tunjuknya pada penyangga pergelangan tangan kananku, “here…,” pada kakiku, “and here…,” dan berakhir pada dadaku. Telunjuk itu sudah banyak berpindah tempat dalam satu menit belakangan.
Aku mengambil tangannya yang menunjuk dadaku dan menggenggamnya. Dia juga melakukan hal yang sama, dua tangan itu saling menggenggam, saling berbagi kekuatan atas apa yang sudah menimpa kami. Bahkan Tyas sambil mengayun kecil genggaman itu. “We’ll get through this together,” tambahnya lagi.
Aku mengangguk pasti. Sesuatu pada percakapan ini telah membuatku jauh lebih lega. Dia hanya ingin kami berdua tidak mengingat kejadian ini sebagai malapetaka. Dan mungkin juga dia tidak ingin aku, atau orang tuanya, atau siapapun yang dia kenal membahas apa yang menjadi bekas dari kecelakaan itu. Dia, dengan cara paling tidak egois, mengingatkanku bahwa kami sudah dewasa, sudah pada usia dimana diombang-ambing nasib bukan lagi sesuatu yang akan membuat kami merengek-rengek, cengeng dan bersungut-sungut. Dia seolah membisikkan amor fati, amor fati tepat pada benakku.
“Thanks, Yas,” kataku, “thanks.”
Tangan kami yang masih saling menggenggam itu, aku bawa pada pipinya. Dia, dengan punggung tangannya sendiri yang aku gerak-gerakkan, mengusap garis luka pada pipinya.
Tyas tersenyum. Aku tahu, senyum kali ini tulus, sebab tidak hanya bibirnya yang tampak senang, pada matanya terpancar kebebasan. Seolah apa yang mengikatnya telah lepas. Sedang tanganku masih menggerak-gerakkan tangannya, dan mataku hanya menatap pada luka itu saja, pikiranku tidak begitu diam. Aku mengira-ngira seberapa tangguh wanita yang ada di hadapanku ini sebab belum pernah kilatan air mata jatuh barang setetes saja sejak kecelakaan itu terjadi. Aku yakin sekali, kecelakaan kemarin bukan main menghancurkan dirinya, tapi dia juga bukan main kokoh berdiri tegak menghadapi apa-apa yang berbekas dan apa-apa yang melekat, termasuk siapa-siapa yang meninggalkan. Dia, lagi-lagi, dengan cara paling bermurah hati, menyadarkanku bahwa apa yang menjadi kelemahan justru bisa memberi kekuatan baru. Hanya perlu mengalah sedikit saja untuk menyesuaikan sudut pandang, maka masalah akan terlihat berbeda dan terasa jauh lebih mudah.
Lima menit berlalu. Tyas kini membiarkanku makan dengan tangan kiri. Meskipun awalnya bubur ayam itu banyak tumpah, tapi aku yakinkan padanya bahwa aku bisa. Lagipula aku benar-benar tidak ingin merepotkannya. Tidak lama setelah makananku habis, Ares menelepon. Dia sedang mengurusi motorku di bengkel.
“Motor lu udah beres, ntar malem gua anter,” katanya pada sambungan telepon itu.
Lalu telepon itu mati sebelum sempat aku ucapkan terima kasih.
Pukul empat sore, tim Midas akan mengadakan rapat. Aku mengizinkan Tyas menggunakan komputer. Kami akan membahas konten-konten apa dan iklan yang seperti apa yang cocok untuk salah satu klien kami yang memproduksi kertas daur ulang. Aku masih duduk berselonjor di kasur, sudah siap dengan tablet dan aplikasi Zoom.
Tyas juga sudah siap dengan komputer dan memasang kamera tambahan. Dia kini dengan percaya diri membuka masker.
“Gua juga mau ngefilter anak-anak. Gimana reaksi mereka liat gua.” Katanya dengan nada bercanda.
“Kalau ada yang macem-macem, cut aja langsung!” jawabku juga berseloroh.
Tyas tertawa.
Lalu sebelum rapat itu mulai, aku bercerita pada Tyas mengenai buku agenda yang hilang, tidak ada di ransel saat aku kembali dari rumah sakit.
“Apa kececer, ya, pas orang-orang nolongin kita ngemasin barang-barang di jalan?” tanya Tyas.
“Engga, gua inget kok, ransel gua gak kebuka. Gua jalan ke lu itu, gua masih pake ransel.”
Tyas berpikir, “Di rumah sakit kali? Tinggal.”
“Ya, bisa aja, sih. Soalnya pindah-pindah kan. IGD, ruang pemeriksaan, ruang operasi, kamar,” aku mengangguk menyetujui.
“Ntar pas kontrol, tanya aja,” kata Tyas.
Rapat bersama tim berjalan baik. Dengan perbincangan hampir satu jam, kami menemukan ide yang segar. Tyas langsung mencatatnya dan segera membagikan tugas kepada empat orang tersebut. Yang membuat hati Tyas puas dan berhasil mengukir senyuman pada wajahnya tepat setelah layar komputer mati adalah, empat orang pegawai Midas itu tampak sangat khawatir dengan keadaan kami, terlebih kepada Tyas. Tidak satu pun raut wajah mereka yang mengisyaratkan kejanggalan. Mereka bersungguh-sungguh merasa bersimpati. Tyas dengan tegas mengatakan pada mereka, bahwa setelah ini tidak ada lagi pembahasan mengenai luka di wajahnya ataupun cedera pada tanganku. Semuanya mengangguk memahami.
“Gak ada yang di cut, nih!” sindirku pada Tyas.
“Aman! Semuanya orang-orang baik!” Seru Tyas senang.
Langit Jakarta mulai jingga. Tyas bersiap pulang setelah memesankan makan malam untukku. Dia kembali mengenakan masker. Kini aku yakin masker itu memang berfungsi untuk melindungi dirinya dari virus yang secara masif berkeliaran diluar sana, tidak lagi untuk menutupi lukanya.
Aku mengantarnya hingga pintu, melangkah tertatih menggunakan tongkat.
“Gua besok datang lagi. Kita bareng, ya, ke rumah sakit. Gua kontrol, kakak terapi, kan?” tanya Tyas sambil membantuku berjalan.
“Lu besok gak nyetir, kan? Kita naik taksi aja.”
“Ya, rencana gua juga gitu,” katanya sambil melihat handphone, “Papa udah di bawah.”
“Ya. Buruan, gih! Gua gak turun, ya. Sampein salam sama Pak Adimas.”
Tyas mengangguk, dia keluar, “Eh! Kak!” katanya sambil menunjuk satu tas kertas yang tersandar pada dinding sebelah pintu,“ini!” katanya. Dia memungutnya lalu memperlihatkan padaku.
Aku membaca tulisan besar pada tas kertas itu, rumah sakit dimana tempat kami di rawat kemarin, rumah sakit tempat Aruna bekerja dulu.
“Bener, kan? Tinggal di rumah sakit,” kata Tyas sambil mengeluarkan buku agenda bersampul hitam milikku.
“Berarti tadi orang rumah sakit datang nganter ini, ya?” tanyaku heran sambil melongok sedikit keluar, menoleh ke kiri dan kanan lorong. Sepi. Kosong.
“Mungkin. Mungkin dia ngira gak ada orang karena sepi, jadi yah, digeletakin aja,” ujar Tyas santai sambil memasukkan lagi buku itu ke dalam tas kertas dan memberikan padaku.
“Gua balik. Besok jam sebelas udah ready set go, ya!” katanya setengah berlari meninggalkanku.
Jempolku teracung tinggi saat dia berbalik melihatku sebelum turun.
Aku masuk, cepat-cepat menutup pintu dan menguncinya. Menyandarkan tongkat pada dinding dan duduk lagi di tepi kasur. Lalu segera mengeluarkan buku itu dengan cara mencurahkannya, tergesa-gesa dan setengah gugup. Aku mencoba menghirup tas kertas itu, memastikan bahwa aroma yang tercium saat Tyas membuka tas ini tadi bukanlah sebuah kekeliruan.
Benar, hidungku tidak salah. Dari tas ini, aroma masa lalu menguar—strawberry-vanilla milik Aruna.
Aku kembali menghirup tas kertas ini, memejamkan mata. Kenangan mengalir deras, membanjiri ingatan yang dibangkitkan oleh aroma familiar. Dadaku berdegup samar. Setiap helaan napas menghidupkan kembali momen-momen yang mulai samar.
Malam itu sebelum tidur, aku meraih satu kotak bekas sepatu dari laci paling atas lemari, dimana didalamnya tersimpan baju kaos biru Aruna yang dulu dia tinggalkan begitu saja. Tas kertas itu aku simpan bersama baju biru miliknya.
Dia ternyata benar-benar memiliki tempat tersendiri di hati. Ini sudah nyaris dua tahun, waktu yang hampir sama lamanya dengan masa kami bersama dulu. Tapi jauh di dalam diriku, dia masih ada dan masih sama, tetap hidup di satu sudut, mengisi ruang dengan kenangan-kenangan yang tidak lekang.
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden











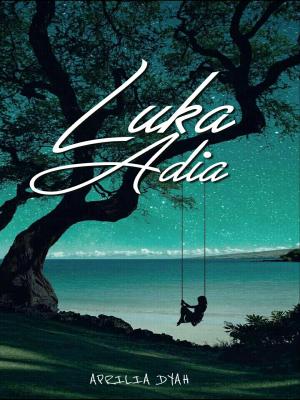

Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)