Masih di bulan Juni, hari-hari terakhir bulan ini. Juga hari kesekian yang terasa panas menyengat hingga kaosku basah berkeringat meskipun Jakarta sudah gelap. Sebuah pesan masuk saat aku memandangi lampu jalan berwarna kekuningan, menyala seolah putus asa di persimpangan gang. Kamar kostku yang baru berada di lantai dua, memiliki beranda mungil yang cukup untuk duduk dua orang saja. Tidak ada pantry, sehingga peralatan makan yang semakin hari semakin bertambah sejak Aruna turun tangan di dapur mini itu dulu, masih tersimpan dalam dus dan sama sekali tidak ada niatku untuk membukanya. Bahkan, karena malas harus membongkarnya untuk mengambil satu piring, satu sendok, dan satu gelas, aku lantas memutuskan untuk membeli yang baru saja. Kamar yang baru ini lebih luas juga dengan kamar mandi yang lebih modern –kering. Aku meraih handphone, membuka pesan itu, dari Tyas.
I’m sorry, Kak. I went too far
Asap putih dari mulutku terembus jauh. Lalu jari-jemariku mulai mengetik membalas pesan dengan setengah hati sebab sudah cukup jengah sejak siang tadi mengatakan padanya bahwa sikapnya yang spontan, yang kemudian memberatkan hatinya bukan suatu masalah.
“Toh, juga gak ada yang berubah,” aku bergumam sendiri.
Sebelum mematikan layar handphone, aku sempat melihat jam, sudah pukul sebelas malam.
Aku masuk, menutup gorden, bersih-bersih, lalu berbaring setelah mematikan semua lampu hingga gelap gulita. Lama-lama pendar cahaya lampu gedung kost tetangga (atau lampu jalan yang putus asa itu) masuk dari kaca bagian atas yang tidak tertutup kain.
Aku meraih bantal, menutup wajahku dengan kasar.
Aku merasa … entahlah. Tidak lepas. Tidak bebas. Begitu terjebak. Begitu terkukung atas apa yang aku tahu dan tidak aku tahu. Terjebak di antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sudah terjadi—tentang kekasihku, Aruna.
Sembilan jam sebelumnya.
“Yas. Selesai ini kita makan dulu. Laper,” bisikku pada Tyas. Dua hari lalu aku diajak bekerja untuk membuat motion graphic sebuah iklan produk susu UHT dan yogurt yang akan tayang in-stream pada youtube ads. Aku pun mengajak Tyas karena mereka membutuhkan seorang scriptwriter. Kami berada di ruang editing bersama seorang sound designer.
Tyas mengangguk cepat sambil melirik sound designer yang dikenal sebagai komentator. Dia laki-laki dengan lidah tajam, mulut pedas. Di tim ini tidak ada yang akrab dengannya, tidak ada yang mau tepatnya. Sok pintar sehingga gampang menyalah-nyalahkan pekerjaan yang bukan bidangnya juga tidak mau menerima kritikan atau saran untuk perbaikan pekerjaannya. Cerewet dan bawel. Mendominasi. Tapi, semua sikap menyebalkan itu akan berakhir saat creative director datang. Dia akan diam menunduk seperti anak anjing yang sedang bermasalah dengan pencernaan. Dan benar-benar menjadi anjing jika dia sudah berusaha menjilat wajah creative director untuk menjadi si Paling Kesayangan. Dia tidak urung meskipun si Tuan tampak tidak acuh.
Setengah jam kemudian, kami keluar studio untuk makan siang (makan sore, karena sudah nyaris pukul tiga). Aku memboncengi Tyas menuju rumah makan cepat saji yang tidak jauh dari studio. Berdiri mengantre cukup lama sampai kami bisa duduk dan makan menikmati ayam goreng dan segelas cola. Makanan kami baru setengah habis, tanpa mendung atau angin, tiba-tiba saja gerimis.
Tyas melongok ke jendela kaca besar di belakangnya yang sudah terkena goresan-goresan air, lalu mengangkat bahunya ringan.
“We gotta hurry kalau gak mau kehujanan,” kata Tyas dengan tenang juga tegas.
“Santai aja. Si Komentator juga katanya bakal lama.”
Lagi-lagi Tyas menaikkan bahu, menyetujui dengan cara paling santai.
Kami lanjut menghabiskan makanan. Tyas sambil bercerita, dan katanya ini sebuah rahasia, bahwa Pak Adimas sepertinya tertarik dengan digital marketing. Tyas sedikit-sedikit tersenyum sambil mengingat-ingat bagaimana ayahnya melakukan riset mengenai bisnis itu.
“Kayaknya …,” kata Tyas lagi, dia berhenti karena meneguk cola, “Papa mau ajak kakak buat bisnis, deh.”
“Oh, ya?” tanyaku hampir tidak percaya setelah kegagalanku –setidaknya menurutku– dalam mempertahankan Gammares, ternyata Pak Adimas masih menaruh harapan. Kali ini, sepertinya ingin membangun perusahaan sendiri.
Tyas mengangguk yakin dan semangat. “Tapi diam-diam aja, ya. Jangan tanya langsung juga.”
“Ya, gak lah! Kepedean banget gua kalau gitu!”
Kami tertawa.
Selang sepuluh menit, makanan dan minuman sudah habis dan kami kenyang luar biasa. Tapi di luar masih saja gerimis .
“Ini bakal lama,” kataku lagi sambil melepas flanel dan menyerahkan pada Tyas, “lu pakai. Lumayan basah sampai studio ntar.”
Tyas menerimanya sambil tersenyum, senyum ledekan, “ Uuuu … A sweet boy is becoming a gentleman!”
Tapi dia lagi-lagi Tyas, bercanda terlihat berbeda jika dia yang melakukannya. Tidak luwes. Senyum ledekannya itu justru terlihat seperti seringai menyeramkan.
Aku tersenyum saja karena menurutku lucu juga. Dia perempuan yang tidak tahu bagaimana terlihat manis. Juga sepertinya tidak berusaha untuk itu. Dia hanya mengurusi apa yang menurut dia penting, jelas sekali bermanis-manis bukan salah satunya. Juga pada wajahnya, terlukis sesuatu, semacam batasan yang membuat kebanyakan orang akan salah paham jika bertemu dengannya untuk pertama kali. Dia cenderung terlihat tidak bersahabat. Tapi begitulah, setiap orang tentu punya cara masing-masing untuk bersosialisasi. Bagi Tyas, sepertinya dia tidak butuh teman banyak, dia hanya butuh orang-orang di sekitarnya memercayainya seperti dia sudah memercayai orang tersebut melalui proses seleksi ‘wajah jutek’.
Sambil menunggunya mengenakan flanel untuk melapisi kaos abu-abunya, aku memeriksa ponsel. Benar saja, si Komentator mengirimkan pesan menanyakan kenapa kami terlambat padahal pekerjaan masih banyak. Aku mendengus kasar.
“Yok!” Sambil meraih tas kanvas selempang miliknya, Tyas berdiri. Badannya yang cenderung tinggi dan tegap untuk ukuran perempuan, membuat flanel itu tampak pas di tubuhnya.
Kami berjalan bersisian menuju pintu. Tyas mengatakan seharusnya tadi kami mengendarai mobilnya saja.
“Kalau gini kan malah kakak yang kebasahan,” ujar Tyas.
“Gak masalah. Lagian kaos hitam gini gak tembus pandang,” kataku menarik sedikit kaos yang kukenakan.
Handphone-ku kembali bergetar, aku merogohnya dari saku celana. Aku mendengus melihat nama si Komentor tertera di layar, sudah jelas dia akan mengomel. Aku bahkan sudah bisa memperkirakan apa yang akan keluar dari mulutnya.
Kalian ini tidak menghargai waktu! Dasar pemalas! Begitulah kira-kira.
Padahal, dia hanya takut sendirian dan juga terlalu gengsi mengakui. Apalagi di hari Minggu begini, tidak ada orang yang bekerja di studio, kecuali kami.
Aku masih saja menatap ponsel saat mendorong pintu kaca untuk keluar. Tiba-tiba, suara seseorang yang dulu setiap hari aku dengar memanggil lengkap dengan nada khas membujuknya.
“Gam?” kata suara itu.
Aku mendongak seketika dan mematung setelahnya, mungkin juga lupa bernapas sebab aku tiba-tiba merasa sesak.
Aruna.
Dia tidak sendirian. Andre yang berwajah makin mulus dan cerah itu berada di sampingnya. Handphone-ku akhirnya tenang dalam genggaman setelah sibuk bergetar.
“Eh …,” Tyas melirikku dengan kikuk yang tidak mampu dia sembunyikan, “Mbak? Apa kabar? Dari mana?” tanyanya sedikit terbata-bata.
Andre menjawab, “Dari dokter kandungan.”
Dia menatapku, tersenyum. Entah untuk pamer atau memang sedang ingin menunjukkan kebahagiaan. Aku tidak terlalu peduli apapun yang sedang dia lakukan, atau yang dia maksudkan.
Tidak terbantah bahwa sesuatu dalam diriku terusik mendengar kata dokter kandungan. Satu sisi diriku ingin berbesar hati, ingin dengan mudah mengatakan selamat pada Aruna, tapi sisi diriku yang lain tahu betul kata itu nantinya akan keluar dengan cara paling aneh juga dengan raut paling menyebalkan. Lalu kedua sisi diriku itu setuju untuk tetap bungkam.
Dari wajah Aruna, tatapanku beralih cepat ke perutnya. Tidak ada yang berubah. Perut itu tidak membesar, atau mungkin tidak terlalu terlihat karena dia … dia masih mengenakan jaket jeans-ku yang kebesaran di tubuhnya itu.
“Mbak Aruna udah hamil?” tanya Tyas sambil menyikutku, menyadarkanku dari momen termangu. Atau … bagaimana wajahku saat ini? Terpana? Terkejut? Panik? Apapun itu asal jangan terlihat memprihatinkan.
“I-iya. Udah …,” jawab Aruna sambil mengelus perutnya.
“Wah? Selamat, Mbak.” Respons Tyas tidak dibuat-buat, bukan suatu kepura-puraan. Bukan juga sebagai usaha agar situasi yang tegang menjadi kendur. Tyas memeluk Aruna. Lalu mengusap-usap perut Aruna setelah meminta izin darinya. Namun Aruna sepertinya tidak terlalu nyaman. Pada sorot matanya, aku tahu dia keberatan.
“Kalian baru selesai makan siang?” tanya Andre kemudian.
“Ya. Udah. Nih mau balik,” jawab Tyas, lagi-lagi melirikku yang tengah menatap Aruna dan perutnya bergantian. Tiba-tiba saja, Tyas menggamit lenganku dengan manja. Aku terkejut tapi karena tidak tahu harus bagaimana, aku menerima saja. Aruna tersenyum melihat Tyas begitu.
“Kalian …,” tanya Andre sambil menatapku tidak yakin, “pacaran?”
“Ya.” Tyas menjawab cepat.
Aku bingung kenapa Tyas tiba-tiba bertindak di luar kebiasaannya yang jujur, tegas dan tidak gampang bercanda. Tapi lagi-lagi aku diam saja, tidak menyangkalnya juga. Aku hanya menatap pada Aruna. Semua pertanyaan tentangnya yang menggantung selama tiga bulan tiba-tiba buyar. Otakku kosong melompong. Namun dadaku disesaki sesuatu yang lain, yang aku juga tidak tahu disebut sebagai perasaan apa. Apa ini? Aku senang karena sepertinya dia dalam keadaan baik, sesuai harapanku tapi saat bersamaan juga merasa tidak begitu senang karena … entahlah, katakan saja hatiku surut. Ada Andre kecil dalam dirinya. Ada Andre kecil sedang tumbuh di dalam tubuh Aruna. Ada Andre kecil yang berenang-renang dalam rahim Aruna. Andre kecil yang beruntung mempunyai ibu seperti Aruna. Andre kecil yang … ah, sudahlah …. Aku tahu, aku cemburu.
“Selamat,” Aruna mengulurkan tangan padaku, “kalian pacaran. Semoga langgeng, Gam.” Kemudian dia mengangkat kedua ujung bibirnya dengan ramah.
Apa? Selamat? Selamat katamu?
Sambil tersenyum kamu ucapkan selamat?
Selamat atas apa, Aruna? Kamu percaya aku bisa menemukan orang lain hanya dalam waktu tiga bulan saja?
Tiba-tiba aku merasa tidak ada arti baginya juga dengan apa yang sudah terjadi di antara kami dua tahun belakangan.
Benar, tentu saja, kamu sudah menjadi istri pria lain. Sedang hamil pula. Untuk apa mengingat kenangan yang mungkin hanya meninggalkan luka?
Tangan Aruna masih menggantung di udara. Saat melihat cincin emas polos melingkari jari manisnya itu lah aku menyadari bahwa cincin dariku mungkin sudah dia simpan jauh atau bisa saja sudah dibuang. Aku menyambut tangannya. Tangan yang dulu biasa aku genggam, tangan yang mengantarkan kehangatan, tangan yang terbiasa mengusap pipiku, terasa masih sama, baik ukurannya, kesannya dan hangatnya. Jantungku berdegup tidak asing, degupan yang selalu ada saat aku berada di dekatnya.
Saat tangan kami sudah terlepas, dia dengan cepat menggenggam tangan suaminya, sepertinya dengan kuat hingga Andre menoleh kepadanya tiba-tiba.
“Kami masuk, ya?” kata Aruna dengan wajah yang –aku tahu– tidak begitu nyaman. Mungkin pertemuan ini, selain tidak terduga, tidak pernah ada dalam rencananya, juga tidak dia inginkan.
Andre, secara tidak masuk akal, justru terlihat bimbang, menoleh pada Aruna dengan alis bertaut. Aruna menarik tangan suaminya, “Ayo … anaknya udah lapar. Perutku keroncongan.”
“Oh, iya. Ibu hamil gak boleh lapar,” kata Tyas sambil membuka jalan, minggir dan mepet ke arahku hingga aku bergeser.
“Makan yang banyak, Mbak. Biar dedeknya sehat,” ujar Tyas yang justru seperti kalimat perpisahan.
“Ya. Pasti,” kata Aruna sambil mendorong pintu.
Dia menunduk setelah melempar senyum ragu-ragu kepadaku, sedang Andre masuk sambil merangkul bahunya. Pintu kaca itu sudah tertutup sempurna.
“All good, Kak?” tanya Tyas sambil melepaskan pagutan tangannya.
Aku menatapnya, diam.
“Maaf gua …” sorot mata Tyas mencari-cari sesuatu pada wajahku, “gua cuma gak mau kakak kelihatan, yah … kayak muram gitu di depan mereka. Kakak gak pantas digituin,” katanya lagi saat kami mulai berjalan menuju motor yang terparkir.
Ternyata ekspresi wajah yang kukhawatirkan justru tampil: memprihatinkan. Cengeng.
“Gak apa-apa. Gua oke, kok,” aku berdeham. “Makasih, Yas.”
Terima kasih karena telah cepat menyelamatkanku dari tatapan iba seorang mantan pacar.
Aku menoleh lagi. Terlihat dari balik dinding kaca, Aruna duduk persis di tempat dudukku tadi. Dia mengusap-usap perutnya yang kini berselimut jaket jeans dengan kasih sayang. Sedang Andre baru saja datang membawa nampan berisi makanan.
Jantungku berdenyut dengan rikuh melihat jaketku seakan mampu memberi kehangatan yang lebih untuk anak dalam perutnya.
Di studio, aku bekerja sambil sesekali termenung, membuat lidah tajam si Komentator benar-benar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini.
“Kalau mau bengong di WC sana!” atau,
“Kalau ngantuk, gak usah kerja!” atau,
“Lelet amat lu bocah! Niat kerja gak sih!”
Dan hal-hal semacam itu yang membuatku ingin menyiram wajahnya dengan kopi panas di genggamanku. Tyas, yang sepertinya paham aku kenapa, menghampiri si Komentator dengan menunjukkan pesan dari creative director yang menanyakan keberadaannya karena tidak bisa dihubungi. Dia tergesa-gesa berlari ke arah ranselnya yang digantung pada pintu ruang rekaman dan berdecak kesal mengetahui baterai handphone-nya habis. Setelah itu, dia sibuk menyalakan ponselnya yang dalam pengisian. Rona wajahnya berubah menjadi lebih pucat saat kembali berusaha menghubungi creative director. Mulut pedas itu menjadi lebih manis dari milkshake strawberry saat berbicara dengan orang yang diseganinya.
Hmm … milkshake strawberry, Aruna.
Susah ternyata ….
Malam ini, aku berbaring dengan kegundahan yang aku benci. Walau sudah seminggu di kost baru, meskipun Aruna tidak ada di sini dan tidak pernah di sini, kenyataannya Aruna selalu di kepala dan di hati. Dia akan selalu terbawa kemana pun aku pergi jika aku tidak mampu memberi batas yang jelas antara harapan, angan-angan dan kenyataan.
Dia punya suami. Dia bahagia. Dia sudah hamil. Dia sedang membina keluarga.
Aku mengucapkan kalimat itu berkali-kali bagai aji-aji ilmu sakti untuk menyadarkan diri sendiri. Lalu kalimat itu selalu aku ulangi lagi beberapa hari kemudian tiap kali jatuh dalam lamunan, setiap kali diam dan setiap akan tidur malam.
-oOo-
“Eh! Si Reren nge-WA, nih!” Ares dengan semangat menunjukkan chat pada handphone-nya. Aku melihat sekilas saja lalu kembali sibuk dengan tes A/B pada satu video yang kukerjakan.
“Dia ngajak nongkrong, traktiran ultah,” kata Ares lagi.
“Kapan?”
“Ntar malem, di bar biasa.”
“Liat ntar, deh. Kerjaan gua belum kelar,” kataku, “menurut lu bagusan mana?” aku menunjukkan video pada Ares dengan dua tone warna berbeda.
Ares mengusap-usap dagunya sambil memperhatikan dengan jeli. “Yang kanan,” katanya.
Aku mengangguk sebab pendapat kami sama.
“Si Reren naksir lu udah lama, tuh! Ya kali lu gak ngeh.” Ares kesal, “Aruna is done, Man!”
“Apa sih bawa-bawa Aruna segala?” aku diam, melihat wajah Ares yang berkerut-kerut, lalu menghela napas, “mantan pacar sama kekasih tuh beda, Nyet! Mantan pacar itu status, tapi selama lu masih punya perasaan sama dia, selama itu juga dia masih kekasih meski udah jadi mantan. Paham lu?”
Ares bengong dengan wajah setengah menjijikkan. Raut berkerut-kerutnya itu berubah menjadi garis-garis menyebalkan, “Heh! Cucunya Socrates lu? Mendadak filsuf! Gak pantes!”
Aku tertawa.
“Jadi gimana, nih? Ikut apa gak nanti acara Reren?” tanyanya lagi dengan nada mendesak.
“Males…”
Malam itu, akhirnya aku dipaksa Ares untuk memenuhi undangan Reren. Aku dan Ares patungan membelikan kado untuk si Empu acara, satu parfum. Di bar, kami minum-minum sewajarnya. Sewajarnya menurut Ares, tapi tidak menurutku. Kami lagi-lagi pulang dalam keadaan setengah mabuk.
-oOo-
Pak Adimas menelepon saat aku di gerai ayam Kak Ami, hanya makan dan berbincang ringan tanpa menyentuh topik pekerjaan. Lalu saat handphone-ku berdering, Kak Ami dengan paham undur diri, dia menyibukkan diri dengan membantu satu-satunya pegawai yang tampak menghitung jual-beli. Gerai Kak Ami tidak besar, dua kontainer yang dimodifikasi sedemikian rupa berdiri di lahan kosong yang cukup luas. Terdapat lima meja bundar lengkap dengan payung lebar, dengan masing-masing empat kursi yang mengelilinginya. Semua warna pada gerai ini senada: oranye dan kuning.
“Ada yang mau saya bicarakan, Gam.” Katanya dari seberang telepon. Dia juga mengatakan akan segera menyusulku. Serta-merta aku teringat cerita Tyas beberapa hari lalu saat kami makan –tentang bisnis yang ingin dibangun Pak Adimas.
Tidak sampai lima belas menit, Pak Adimas datang. Dia memesan minuman dan kudapan ringan, lalu segera duduk di depanku. Kami saling menanyakan kabar. Pak Adimas juga terlihat menikmati ceritaku tentang pengalaman bekerja di Pulau Siberut. Dia juga mengatakan bahwa istrinya sudah semakin membaik. Tidak lagi minum obat, juga sudah tidak menggunakan tongkat. Mereka sekeluarga menyampaikan terima kasih kepada Aruna melaluiku. Lalu dia menanyakan kabar Aruna, aku menjawab dia baik-baik saja, pada umumnya orang akan menjawab seperti itu jika ditanyai kabar untuk sekedar pengantar obrolan.
Saat makanan dan minuman Pak Adimas diantarkan, saat itu juga lah pembicaraan yang sebenarnya dimulai. Ternyata benar, kejadian studio terbakar tidak menyurutkan semangat Pak Adimas untuk tetap mengajakku berbisnis bersama. Dia sudah melakukan riset kecil-kecilan, baik dari rekan bisnis, klien bahkan kepada anaknya sendiri, Tyas, bagaimana pentingnya digital marketing terhadap suatu usaha. Dengan segera Pak Adimas mengeluarkan buku catatan yang sudah lecek dari tas laptopnya. Tangannya sangat semangat membolak-balikkan kertas yang berisi catatan hasil riset. Menurutku, dari tampilan kertas-kertas buku ini yang sudah kusut, berkerut dan lusuh, juga dari banyaknya coretan-coretan tidak teratur dengan pensil dan pulpen, lengkap dengan grafik seadanya, ini sudah bukan riset kecil-kecilan lagi namanya. Catatan ini menunjukkan suatu kesungguhan.
“Saya tahu,” katanya, “kamu pasti jauh lebih paham dari saya.” Pak Adimas tersenyum. “Tapi ini sekaligus memperlihatkan ke kamu kalau saya serius. Saya punya uangnya, kamu punya ilmunya. Bareng Tyas saya rasa ini bakalan berjalan lebih baik dari yang saya kira, “ dia berhenti sejenak, menyeruput es teh, “Gimana, Gam?”
Aku mengangguk-angguk untuk menyamakan antusias Pak Adimas.
“Kapan bisa gerak, Gam?” tanya Pak Adimas seolah yakin aku tidak menolak permintaannya. “Saya gak tahu lagi siapa yang mau saya ajak selain kamu,” kata Pak Adimas membujuk saat aku masih diam saja.
“Oh, ya?” Aku tidak begitu yakin, sebab sedikit banyaknya tahu Pak Adimas punya beberapa klien dari agensi serupa. Tapi sejujurnya, aku senang dia masih mengandalkanku untuk memutar modalnya membangun sebuah bisnis baru. Hanya saja, aku bimbang pencapaianku kelak tidak sesuai dengan target Pak Adimas.
Mencoba menimbang-nimbang, aku membolak-balikkan kertas yang tadi Pak Adimas perlihatkan, pura-pura membacanya.
“Tyas juga berteman sama kamu. Dia juga bilang kamu orang yang bisa dipercaya, bahkan dia bilang kalau dia lebih percaya kamu daripada Gilang.”
“Gilang?”
“Pacarnya. Gilang.”
“Oh.” Aku ingat. Dulu saat minum kopi setelah menemani Tyas membeli buku, dia pernah menyebut nama pacarnya.
“Oke, ya? Ini harus jadi. Sejujurnya saya kasihan sama Tyas harus kerja kesana-kemari,” Pak Adimas menyeruput lagi es tehnya, “walau dia gak pernah ngeluh juga. Dia sama kayak kamu semangat empat lima kalau udah kerja. Kemarin dia bantuin bikin script berita, lho!”
“Iya, Pak. Saya lihat sendiri. Dia kerja sepenuh hati,” kataku sambil mengembalikan buku catatan Pak Adimas. “Kami lagi bikin iklan sekarang.”
“Oh?” Pak Adimas tercengang, “dia gak cerita apa-apa. Padahal saya cukup sering ngobrol sama dia.”
Perbincangan selesai. Pak Adimas memberikan waktu untukku berpikir hingga akhir Juli karena pertengahan Juni kemarin aku baru saja diterima bekerja di satu kantor penerbitan sebagai desainer grafis yang mengerjakan lay out buku dan majalah serta desain sampul buku cetak dan buku digital, menggantikan pekerja sebelumnya yang sabatikal. Pak Adimas pulang setelah membungkuskan makanan untuk anak dan istrinya.
-oOo-
Setiap orang punya cara tersendiri untuk melewati sunyi dan memeluk kesedihan. Dulu, setelah Aruna menghilang begitu saja, mungkin caraku adalah dengan merenungi kesepian, menyendiri hingga rasa sakit itu hampir mengikis habis diriku. Namun kini, setelah bertemu lagi dengannya beberapa waktu lalu, meskipun dengan cara yang mengejutkan dan kurang menyenangkan, aku sadar bahwa tak ada seorang pun yang patut dipersalahkan. Aku sudah berhenti bertanya-tanya, apakah dia sudah menikah atau bahagia. Jawabannya sudah terpampang jelas di depan mata—dia sudah menikah dan bahagia.
Kini aku tidak lagi bergelut dengan diriku sendiri untuk menghadapi kenyataan itu. Aku berdamai dan menerima, sambil berharap waktu akan memudarkannya. Cukup pudar, aku juga tidak ingin kenangan itu hilang sepenuhnya. Dia adalah perempuan yang meninggalkan jejak manis, dan aku ingin tetap menikmati kenangan-kenangan itu suatu hari nanti sebagai bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Mungkin, suatu hari nanti, aku akan menceritakan kisah itu pada anakku saat dia tumbuh remaja dan mulai jatuh cinta. Sebuah cerita khas dari seorang ayah yang bangga karena pernah menjadi pujaan hati seorang perempuan.
Hari-hari bergulir begitu saja dan terasa cepat. Pekerjaanku di penerbitan cukup menyita waktu, banyak desain yang harus selesai dengan deadline berdekatan. Pantas saja desainer sebelumnya meminta sabatikal, pekerjaan yang hanya dilakukan oleh dua orang ini membuat kami nyaris bekerja dua puluh jam sehari. Ya, sampai di rumah kami harus kembali menatap layar komputer. Tapi, aku merasa puas karena kembali sibuk, siang dan malam, pagi dan petang. Aku puas karena aku kelelahan dan bisa tidur malam dengan nyenyak tanpa perlu berlama-lama menatap plafon kamar yang membuat pikiran jauh melayang.
Hari Sabtu seminggu lalu, aku meluangkan waktu untuk membersihkan komputer, menghapus file-file yang tidak diperlukan lagi. Sampailah pada file foto yang aku periksa satu per satu. Aku mendapati banyak foto Aruna dari waktu-waktu di Bogor. Saat aku mengisi seminar, ternyata Ares diam-diam juga memotret Aruna. Bahkan, ada beberapa foto di mana Aruna sengaja berpose dengan latar belakang aku yang sedang memberi materi bersama Trisna. Ada foto dia duduk berselonjor karena kelelahan mengelilingi Kebun Raya Bogor, fotonya bersama ibu dan Marwa saat lebaran. Satu foto yang membuat perasaanku hangatnya masih sama seperti saat mengambil foto ini dulu adalah gambar dia di dapur, memberikan jilbab untuk ibu. Kedua wanita itu saling tersenyum. Meskipun back shot, tapi situasi dan suasana, serta ekspresi mereka mendukung sebuah kehangatan antara ibu dan anak. Tanpa sadar, aku mulai mengedit foto itu. Entah untuk apa, aku juga tidak tahu, yang jelas aku senang melakukannya.
Sejak itu, aku sadar bahwa satu kebiasaan lama mulai terlupakan: memotret jalanan. Kemudian pada akhir pekan berikutnya dan berikutnya, aku menyempatkan diri keluar sambil mengalungkan kamera. Waktu tidak menjadi keharusan, mau matahari sedang menantang atau justru langit mulai kelam, asal memiliki waktu luang aku akan meraih kamera dan membidik lensa pada jalanan. Saat itulah aku bertemu dengan Odah.
Satu malam dengan angin kencang, dia sendirian, duduk meringkuk karena takut mendengar suara petir beserta kilat yang menyambar. Dia ketakutan di bawah kursi kayu yang ditinggalkan di trotoar. Kucing kecil dengan bulu putih-kuning itu sempat menghindar dan memekik saat aku berusaha meraihnya. Wajah mungilnya itu justru terlihat imut saat marah –taring kecil keluar dengan kumis halus yang menukik-nukik. Sebentar-sebentar aku ngikik, mengingat bahwa kucing ini mirip Aruna yang berpikir akan terlihat mengerikan saat marah. Justru yang terlihat olehku adalah suguhan wajah yang menggemaskan.
Aku melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa kucing ini makan, setidaknya membujuknya untuk mendekatiku. Saat menemukan satu warteg yang masih buka, aku berlari kencang ke sana untuk membeli ikan apa saja yang masih tersedia dan kembali membawa ikan goreng yang tidak aku tahu jenisnya. Aku beri ikan goreng pada kucing malang itu, namun dia tidak memakannya. Aku pikir mungkin karena ada sambal yang masih melekat, lantas aku mencucinya dengan air minum yang kubawa. Tetap, dia tidak mau, juga tidak mendekat. Aku sempat hilang akal dan ingin pulang saja karena sudah mulai gerimis, tapi juga tidak tega menatap mata cokelat kucing ini yang penuh pantulan petir.
“Ah! Sial!”
Aku segera mengambilnya, menggendongnya dan dengan harap-harap cemas memasukkan ke ransel berharap kucing ini tidak mati hingga kami sampai di kost nanti. Sambil mendekap tas, aku berlari-lari masuk gang dan tepat sebelum hujan turun lebat aku sudah sampai di kost. Setelah menunggu sekitar sepuluh menit, makanan kucing datang diantar langsung ke pintu kamar oleh ojek online. Aku merelakan satu piring yang baru aku beli untuk kucing itu gunakan makan. Dia makan dengan lahap makanan basah yang baunya menyengat hingga aku nyaris muntah saat membuka bungkusnya.
Besok sorenya, Ares datang. Dia bengong melihat kucing betina yang saat itu belum ada namanya sedang tidur pulas di kursi kerja.
“Lu miara cewek aja gak beres, sekarang coba-coba sama kucing? Yakin nih dia hidup di tangan lu?” tanya Ares yang masih tampak terkejut dengan cara yang menyebalkan.
Aku berdecak, “Kasihan.”
“Dih? Ya, kalau kasihan, mending sekalian lu jadiin nih kamar tempat penampungan hewan.” Ucapan cemoohan itu dia ucapkan berikut dengan raut masam.
“Ya. Udah ada dua hewan juga, kan?”
Ares diam, dia berpikir sebentar sebelum akhirnya mengeluarkan kata-kata kasar sambil menendang bokongku.
Kami tertawa dan kucing itu tampak belum terbiasa mendengar gelegar suara tawa laki-laki dewasa sehingga dia bangun karena terkejut dan berlari ke bawah dipan untuk sembunyi.
Aku sedang menunduk di bawah dipan, mengulurkan tangan untuk membujuknya keluar saat Ares bertanya siapa namanya.
“Belum ada,” kataku, “pusss … pusss …. Sini sama Aa.”
Ares menoleh padaku segera dan aku yang tahu bagaimana reaksinya juga menoleh kepadanya, ingin melihat rautnya. “Idih! Najis! Aa segala!” katanya. Lalu dia bergidik ngeri, menaik-naikkan bahunya dan merinding geli.
Aku lagi-lagi tertawa dan kucing putih-kuning kecil itu sudah dalam pangkuanku saat Ares mengusulkan nama.
“Saodah.” Katanya.
“Hah?”
“Saodah namanya, panggilannya Odah.”
“Perasaan nama kucing orang pada imut, minimal kebule-bulean. Chelsea segala udah kayak klub sepak bola. Giliran di gua, betawi amat. Saodah!” dahiku berkerut sambil memberi pendapat sinis
“Ya kan lu nemunya di tanah betawi!” Ares tampak lebih kesal, dia melirik kucing yang bersandar manja padaku, “lagian nyamain tampang, lah! Yang kebule-bulean itu minimal jenis persia. Nah ini?” dia menunjuk kucing itu, “peranakan apa lu, cing? Paling juga mix Pasar Senen sama Kampung Marlina.”
“Dih? Superfisial! Physically Judgemental!” aku menatapnya tajam, mencemooh. Dia terkikik. Saat-saat seperti ini, dia benar-benar menunjukkan bahwa dia darah daging mami. Membedakan-bedakan berdasarkan apa yang terlihat saja. Aku menunduk melihat Saodah, Saodah mendongak. Kami bertatapan dan bersungut-sungut berdua membicarakan Ares.
Akhirnya, tanpa persetujuanku. Sejak sore itu, Ares memanggil kucing kecil putih-kuning itu dengan Odah dan aku ikut-ikutan karena si kucing pun datang saja ketika dipanggil seperti itu, tidak tampak keberatan. Mungkin memang benar dia asli betawi. Hingga lima hari ke depan, dia akan duduk di meringkuk di pangkuanku saat aku begadang. Hanya lima hari karena setelah itu, Odahku malang, hilang.
Waktu itu, aku yang saat siang menerima komisi mingguan dari pemred, segera menuju pet shop untuk membelikan Odah kalung kerincing dan stok makanan juga satu gaun pink menyala yang menurutku sangat menggemaskan, mengingatkanku pada boneka barbie yang dulu dikoleksi Marwa. Dengan hati riang aku berlari menaiki tangga dan membuka pintu kamar sambil memanggil namanya. Dia yang sudah lima hari terakhir menyambutku datang, hari itu tidak berlari ke arahku. Aku terus memanggilnya namun dia tidak dimana-mana. Hingga aku sadar, jendela tidak tertutup sempurna dan aku perkirakan dia keluar dan melompat. Semua belanjaan atas namanya itu kulempar begitu saja ke kasur dan segera mengelilingi kost sambil memanggil-manggil namanya. Tetangga-tetanggaku terlihat heran dan bertanya Odah siapa. Saat aku katakan kucing –dengan sedikit malu sebenarnya– alih-alih membantu, justru mereka tertawa.
Malam itu, aku sampai memutari gang tapi tidak berhasil menemukannya. Dengan langkah gontai aku kembali ke kost dan mendapati Ares sudah duduk di kursi kerja sambil menyalakan lagu dari tabletnya.
“Kemana lu?” tanyanya heran.
“Odah hilang,” kataku lemas sambil masuk dan menutup pintu. Berbaring tertelungkup di kasur. Menarik dan mengembuskan napas panjang-panjang, meluapkan lelah dan kekesalan karena tidak berhasil menemukan Odah.
Ares mendengus kasar, “kan?” katanya lagi dengan keyakinan yang dia percayai sejak lima hari lalu, “Gak Aruna gak Saodah, pokoknya segala yang bentukannya imut-imut kagak cocok ama lu! Besok-besok piara biawak aja udah!”
Aku diam saja dan masih tertelungkup di kasur. Dengan perasaan bersalah memegang barang-barang yang baru aku beli untuk Saodah, terlebih gaun pink itu. Belum sempat mengenakannya dia sudah hilang. Aku mengesah lemah.
“Muka lu! Gak cocok melankolis!” Ares melemparku dengan tas selempangnya.
“Cuma lu binatang yang bertahan ama gua …,” kataku bangkit sambil melempar kembali tasnya.
Dia tertawa sambil balas menghujat. “Brengsek!”
Sebelum Ares pulang, aku mengemas kembali belanjaan dan menyerahkannya pada Ares untuk diberikan ke Trisna yang memang memelihara kucing sejak lama. Lalu sudah bertekad, tidak akan membawa hewan lain ke kost walau badai sekalipun sebab aku menyadari ternyata perpisahan, bahkan dengan hewan, terasa menyakitkan.
Sejak kapan aku rentan begini?
Satu subuh di akhir Juli, masih duduk di atas sajadah aku menelepon ibu. Tak mungkin bagiku untuk tidak memberitahu ibu mengenai rencana bisnis bersama Pak Adimas yang akan aku setujui jika ibu merestui. Dalam panggilan video itu ibu tampak senang.
“Mungkin kamu memang merasa was-was karena sempat mengalami kemalangan sebelumnya, terlebih Pak Adimas yang akan jadi pemodal, wajar kamu cemas, Nak,” kata ibu dengan tenang, “Tapi kamu lihat? Pak Adimas bahkan gak membahas kejadian kebakaran, dia gak menyinggung itu sama sekali pas bicarain bisnis, kan?” tanya ibu dengan mata berbinar.
Aku mengingat-ingat. Benar. Pak Adimas seolah mengesampingkan perihal studio kebakaran saat berbicara padaku akhir Juni lalu. “Iya, sih, Bu.”
“Nah, dia tahu kemalangan itu, tapi dia gak ngungkit. Justru dia gak nyerah percaya sama kamu, Itu berarti dia benar-benar yakin kalau kamu punya kemampuan, Nak.”
“Gitu, ya, Bu?” tanyaku masih ragu-ragu.
“Iya. Lagi pula kenapa kamu menyebutnya kegagalan? Ibu gak anggap itu kegagalan kalian. Semuanya itu pelajaran yang datang dalam bentuk musibah,” wajah ibu teduh dan aku tenang melihatnya, “buktinya, lihat sekarang, Ares makin mandiri, kan? Dan kamu bisa bangkit setelah belajar mengikhlaskan dan memaafkan.”
Aku banyak mengucapkan terima kasih pada ibu dalam percakapan itu, juga menyelipkan kata rindu yang membuat ibu tertawa dan Marwa yang mendengarnya dari luar kamar, segera masuk. Dia terlihat sudah rapi, mengenakan kemeja putih dan rok panjang hitam. Sudah sebulan dia bekerja –dalam masa percobaan– sebagai akuntan junior di perusahaan logistik. Marwa mengatakan padaku, dia akan membelikan apapun yang aku mau saat dia menerima gaji pertama. Aku katakan aku ingin tablet baru dan dia segera melengos pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku dan ibu terkikik.
Besoknya, aku berbicara dengan pemred di penerbitan. Beliau menerima alasanku berhenti meskipun terlihat berat hati. Saat aku berpamitan dengan rekan kerjaku, dia kesal karena kini harus bekerja sendirian dengan pekerjaan yang banyak dan tenggat waktu yang berdekatan hingga kantor menemukan pengganti baru. “Lu gitu! Kerjaan masih banyak. Desain sampul buku juga. Aduh! Pusing gua!” katanya menggerutu. Meskipun begitu dia senang aku menemukan jalan karir yang lebih baik.
Lalu sorenya, aku, Ares dan Trisna mampir ke toko buku setelah menonton satu film komedi tentang keluarga yang mendadak kaya setelah kepala keluarga yang berpura-pura hidup susah itu meninggal. Keluar dari bioskop, Ares bersusah payah membujuk Trisna karena celetukan spontan yang mengatakan betapa cantiknya Raline Shah selama film itu diputar. Aku masih memilih buku agenda saat Ares merayu Trisna dengan mengatakan akan membelikan novel-novel romansa. Sepertinya langkah itu cukup strategis, sebab keluar dari toko buku, selain tangan Trisna menenteng tas belanja yang penuh novel, tangan satu lagi menenteng Ares yang nyengir girang. Aku yang tidak senang diabaikan lantas ikut menggamit tangan Ares yang membuat Trisna risih dan akhirnya melepas tangan pacarnya. Ares menatapku kesal. Aku pura-pura tidak bersalah, lantas bersiul ringan sambil membuang muka.
-oOo-
Hari ini terasa berbeda. Entah apa. Untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, aku merindukan Aruna, secara berlebihan. Anehnya aku merasa lapang hati karena perasaan ini, tapi karena sangat lapang, justru terasa sepi. Mantra-mantra batasan yang selalu aku sebut –dia punya suami, dia bahagia, dia sudah hamil– saat diam itu bekerja untuk beberapa bulan. Tapi, malam ini, kalimat itu seakan kehilangan kekuatan seperti mantra tukang tenung yang memiliki batas waktu keampuhan. Pukul 11.25, malam. Aku duduk sambil menatap kertas kosong pada bagian belakang buku agenda. Pulpen di tangan berputar-putar di antara jemari. Selain tidak mengantuk, aku juga enggan berbaring. Handphone hening. Lampu jalan di ujung gang itu sudah benar-benar putus hingga pemandangan diluar jendela cukup gelap, membuatku malas duduk di beranda.
Lantas, dari pada kebingungan sendiri atas apa yang aku rasakan, aku melakukan hal yang hampir tidak pernah aku lakukan: menuliskannya. Sebuah surat. Untuk Aruna.
Aruna, kamu apa kabar?
Aku tahu bahwa sudah terlarang rinduku padamu, tapi aku tidak mengelak, malam ini aku rindu secara gila-gilaan. Aku senang tapi juga merasa sedih. Apa ini yang disebut haru? Juga merasa sepertinya ada sesuatu yang membahagiakan baru saja terjadi dengan cara paling meluluhkan hati. Tapi hari sudah gelap, dan juga tidak ada yang berbeda dari hari-hari kemarin. Aku bertanya-tanya, kejadian apa yang aku lewatkan? Apa yang membuatku begitu senang namun sedih sekaligus? Kalau saja, …. kita masih bersama, aku bakal meluk kamu entah sambil tertawa atau sambil menangis. Aku juga bingung.
Aku berhenti menulis. Tadinya, aku ingin mengakhirinya sampai di situ saja. Tapi secara mengejutkan, aku menyukai ini. Aku merasa pengalaman ini nyaris sama seperti saat aku berhadapan dengannya untuk bercerita, untuk menceritakan apa saja. Lalu aku kembali menulis.
Kamu tahu? Gedung kost UPIL itu kayaknya sekarang sudah benar-benar kosong. Aku lewat sana dua hari lalu, kotor banget, banyak daun sampah dan daun kering bertebaran di parkiran.
Gak ada yang seperti Bu Dewi atau Pak Yahya di kost aku sekarang. Tapi seenggaknya kami bertetangga baik-baik saja. Gak ada masalah berarti selain sesekali tetanggaku yang lain, kayaknya dari lantai atas, suka karaokean bahkan dangdutan kalau lagi suntuk. Awal-awal aku risih, lama-lama aku ikutan nyanyi diam-diam di kamar. Hehehe …
Oh! Aku sempat pelihara kucing. Namanya Saodah dipanggil Odah (ya, aku tahu namanya gak lazim untuk kucing. Ares yang ngasih). Dia kucing betina dengan bulu putih-kuning dan … mata yang sama cokelatnya dengan mata kamu. Dia kecil dan lembut. Juga gemesin dan lucu. Dan juga penurut (soalnya waktu makanannya habis dan aku belum beli, dia mau makan tempe pake nasi setelah aku bujuk-bujuk). Tapi, belum genap seminggu dia sudah pergi. Kayaknya bener yang Ares bilang kalau aku gak cocok sama yang bentukannya imut-imut. Kamu dan kucing itu. Segala tentang Saodah adalah segala tentang kamu. Pergi tanpa ingin diketahui lagi.
Runa, akhir-akhir ini aku juga menemukan kebahagiaan yang sama kayak menjalankan Gammares dulu. Empat bulan lalu, aku bermitra bersama Pak Adimas. Dia sebagai pemodal dan dia percaya sama kemampuan aku untuk mengelola bisnis itu. Kalau Pak Adimas bilang, ini jenis usaha kemitraan. Mitra terbatas. Itu katanya. Pak Adimas gak turun tangan untuk gabung di manajemen. Dia sudah sibuk sama pekerjaannya di firma hukum, begitu katanya.
Waktu itu, saat akan bikin akta perusahaan, Pak Adimas minta saranku menamai bisnis ini. Aku pikir dia udah punya nama sendiri, jadi aku yang bingung spontan bilang ‘Midas Creative’. Pak Adimas melongo menanyakan maknanya. Yah, aku bilang kalau Midas itu raja dalam mitologi Yunani yang dikenal mampu mengubah segala yang disentuhnya menjadi emas. Pak Adimas tersenyum puas, lalu kami terkejut setelah sama-sama nyadar kalau huruf dalam kata Midas itu sendiri adalah huruf yang sama untuk menyusun nama Pak Adimas. Dia menepuk pundakku bangga saat itu. Jadilah Midas Creative sebagai Agensi Digital Marketing. Aku yang bertanggung jawab sama keseluruhan operasional dan strategi perusahaan, kayak buat keputusan penting, nentuin visi dan arah Midas Creativity. Kali ini hanya aku dan Tyas, Ares gak ikutan. Pak Adimas kelihatannya keberatan karena dia tahu segimana cerobohnya Ares dulu. Lagi pula, Ares sekarang udah dapat kerjaan. Awal September lalu dia diterima di salah satu perusahaan telekomunikasi. Dan tahu? Mami berencana adain acara syukuran kalau Ares berhasil lolos seleksi sebagai karyawan percobaan! Mami tetaplah mami.
Malam ini aku duduk, menulis untuk kamu karena aku tahu kamu gak di sini untuk mendengarkan. Hari aku menuliskan surat ini adalah hari tanggal jadian kita dulu. Tahun lalu kita gak sempat merayakannya karena aku sibuk mengemasi studio juga kerja untuk Monas. Tahun ini kita gak mungkin merayakannya karena bukan lagi menjadi hari spesial buat kita. Gak pernah kusangka tahun lalu adalah kesempatan terakhir untuk merayakannya. Kita memang udah jauh dari rencana-rencana di tahun-tahun sebelumnya. Kamu kembali ke jalan kamu, and I’ll be me before you.
Hidup nyatanya akan baik-baik saja asal kita mampu menerima. Itu yang aku pelajari setelah kesedihan berbulan-bulan dan beberapa tangisan yang menghancurkan. Aku pelan-pelan bangkit lagi. Lambat laun aku memahami bahwa kebahagiaan itu gak sepatutnya kita gantungkan hanya kepada dan untuk satu orang saja. Aku menemukan semangat baru, Runa. Juga sepertinya kekuatan baru dari energi yang ada di Midas. Aku harap kamu juga gitu.
Belum putus doaku untukmu. Sehat. Tetap bersahaja. Tetap Ceria. Kelak jadilah ibu terbaik, Runa. Dan berbahagialah sebagaimana mestinya, sebagaimana yang aku harapkan.
Desember 08, 2019.
Sebelum menutupnya, aku mengusap-usap tulisanku sendiri.
Sama seperti buku bersampul cokelat dulu, pada buku ini, buku bersampul kulit hitam ini, aku juga menuliskan semua rencana, jadwal dan perkembangan bisnis yang aku pegang. Tak luput beberapa rencana-rencana personal. Namun buku ini masih terasa sepi, tidak ada nyawanya sehingga –mungkin juga karena ingin– aku menulis sebuah catatan privat. Mungkin juga caraku untuk mengingat kembali apa yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir ini, juga sebagai bentuk kebiasaan lama yang belum hilang sepenuhnya –bercerita pada Aruna.
Tidak. Aku tidak berniat mengirimkannya. Aku hanya menulis untuk kemudian dibaca lagi, olehku sendiri. Tidak ingin mengulang kesalahan yang dilakukan Thomas Jefferson yang terus mengirimkan surat cinta dengan tipuan sastrawi kepada kekasihnya yang bersuami, Maria Cosway, hingga hubungan tersembunyi itu diketahui cukup luas, maka suratku jelas sejak awal hanya akan menjadi sebuah diary dalam bentuk surat. Sebuah surat yang tak pernah dikirimkan –a never-sent letter.
Hari sudah berganti, jam di ponsel menunjukkan pukul 12.04 dini hari. Aku merokok di beranda sambil membaca kembali sebuah e-mail yang masuk tadi siang dari salah satu SMA Swasta di Jakarta Selatan berisikan undangan untuk menjadi pembicara tamu pada kelas hari Rabu untuk membagikan pengalaman nyata dunia kerja. Tidak berlarut-larut memikirkannya, aku segera menyetujuinya setelah berbicara setengah jam dengan narahubung yang tertera di e-mail itu. Tentu Pak Adimas tidak keberatan karena aku juga akan memperkenalkan Midas, juga Tyas bersedia bekerja sendirian beberapa jam. Aku menghela napas lega, meyakinkan diri bahwa setelah tahun ini, aku akan fokus pada pencapaian diri.
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden












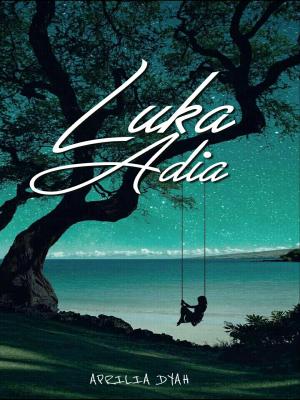
Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)