“Jadi juga, nih, Gammares VisualCraft!” Ares tegak pinggang dengan kepala mendongak melihat signboard kami sedang dipasang. Wajahnya tampak ceria, dia tersenyum bangga. Walau cuaca di luar sungguh menyengat, Ares tetap bertahan berdiri di depan ruko berlantai dua ini, memperhatikan pekerja sambil sesekali menyoraki memberikan semangat. Aku segera masuk saat melihat Pak Adimas datang –seorang notaris, dengan membawa berkas-berkas surat izin usaha kami. Pak Adimas merupakan paman Trisna. Sejak aku dan Ares bercerita ingin membuka bisnis bersama, Trisna dengan cepat menawarkan bantuan pamannya yang bekerja pada lembaga konsultan hukum.
Aku dan Ares akhirnya berhasil menemukan lokasi yang cukup strategis dengan tempat yang cukup baik pada bulan ketiga. Sebuah ruko dua lantai berukuran sedang. Ruko ini terdiri dari tiga deretan, kami berada paling kanan. optik di tengah dan yang paling kiri adalah kantor jasa pariwisata. Tempat ini sedikit lebih jauh dari lokasi rencana awal, tapi itu bukan masalah besar. Kami perlahan mulai mengisi tempat itu, memindahkan alat-alat yang diperlukan, membeli apa-apa yang kurang serta mulai mendekorasi sehingga layak disebut sebuah studio komersial profesional. Aruna dan Trisna terkadang datang membantu, dalam beberapa kesempatan justru mereka bertemu. Memang benar, walau Aruna tidak menyukai saat aku bekerja berdua saja dengan Trisna dulu –event imlek di TMII, justru saat bertemu secara langsung Aruna mampu bersikap tepat, tidak berlebihan. Cukup baik namun juga tidak terlalu ramah. Bisa dikatakan mereka lebih dari sekedar kenalan, namun juga belum bisa dikatakan sebagai teman. Hari-hari itu walau sangat melelahkan, namun di saat bersamaan memberikan kesenangan. Bahkan beberapa malam aku dan Ares tidur di studio untuk fokus mengerjakan dekorasi hingga malam, kami bahkan menggunakan jasa interior. Mengurusi bisnis sendiri memberikan pengalaman baru, banyak hal-hal yang kami tidak tahu dan awalnya terasa ragu, namun kami putuskan untuk terus maju. Bahkan dulu Ares sempat mengatakan jika dalam sebulan tidak juga mendapatkan tempat, dia akan menyerah. Nyatanya mungkin dia lupa atau mungkin semangatnya tidak padam. Lewat sedikit dari batas yang dia tetapkan akhirnya kami menemukan tempat. Ternyata banyak hal yang kami salah perhitungkan, mulai dari alat-alat fotografi hingga perlengkapan dekorasi, semuanya melebihi dari kalkulasi awal. Sehingga beberapa bulan belakangan kami berdua berlarian antara satu pekerjaan ke pekerjaan lain, berlarian dari rumah, kampus, studio, berlarian dari kamera ke komputer. Tentu saja kami tidak lupa dengan tanggung jawab sebagai mahasiswa, menyelesaikan tugas akhir. Nyaris tiga bulan waktu yang kami butuhkan untuk mempersiapkan studio ini termasuk berkas-berkas izin usaha, melewati bulan puasa dan lebaran Idul Fitri.
“Datang ya, Pak. Sabtu besok grand opening, nanti undangannya saya kirim,” aku mengundang Pak Adimas untuk datang ke acara pembukaan yang akan dilaksanakan empat hari lagi. Hanya acara kecil-kecilan, mengundang rekan-rekan kerjasama seperti Pak Purwa dan Bu Mariska, perusahaan garmen yang kemungkinan besar akan diwakilkan oleh Kak Amy dan timnya serta rekan-rekan kami yang lain. Ibu dan Marwa juga akan datang. Ibu terdengar sangat antusias untuk melihat studio ini, berkali-kali ibu melakukan panggilan video jika aku mengatakan sedang berada di studio.
“Saya bakalan datang. Gak perlu kasih undangan segala,” ujar Pak Adimas lalu segera menyeruput kopi yang sudah mulai dingin karena kami berdua tengah fokus membicarakan hal teknis mengenai surat izin.
“Undangan digital kok, Pak. Gak repot”
Pak Adimas mengangguk-angguk. Kami duduk pada sofa di ruang depan. Lantai satu ini kami sekat menjadi dua ruang. Ruang depan berfungsi sebagai penerimaan tamu sekaligus reservasi dan di belakangnya ruang studio kerja. Lantai dua masih belum jelas untuk apa, namun di sana banyak alat-alat dan perlengkapan serta sisa-sisa dekorasi yang kami simpan rapi, sehingga bisa digunakan sebagai studio cadangan jika pekerjaan sedang banyak. Pada lantai dua juga terdapat ruangan untuk kami istirahat atau bahkan mumpuni untuk menginap, kasur dan lemari kecil tersedia di sana. Pada setiap lantai terdapat satu kamar mandi di belakang.
“Wihh, panas banget di luar!” Ares masuk sambil menarik-narik ke depan kerah kaos oblong nya, mengisi angin agar masuk melalui celah leher, Ares mengulurkan tangan bersalaman dengan Pak Adimas, membuat Pak Adimas berdiri untuk menyambut tangan Ares dan duduk kembali bersamaan dengan Ares yang duduk bersisian denganku.
“Sekali lagi selamat buat Gammares. Saya yakin bisnis ini maju. Orang-orang udah pada konsen juga sama digital marketing, jadi perlu banget nih iklan-iklan visual,” ucap Pak Adimas, “Kalau butuh investor, saya siap, nih!” paparnya lagi sambil tertawa. Mendengar itu, Ares langsung melihatku, lututnya menyenggol lututku. Aku tahu apa maksudnya itu, “ntar,” ujarku tanpa suara sambil melihat Ares.
Setelah berbincang sedikit, Pak Adimas pamit. Kami mengantar Pak Adimas hingga pintu –hanya menatap dari balik pintu kaca. Ares melambaikan tangan dengan kekanak-kanakan, “Kok lu cuekin aja tadi sentilan calon investor?” tanya Ares, tangan kanannya masih melambai ke mobil Pak Adimas, menunggu Pak Adimas pergi.
“Yahh, liat dulu lah ini kita bakal gimana. Lagian gua kagak paham keuangan, gimana ntar ngebagiin keuntungannya ke dia. Lu paham?”
“Kagak,” Ares menjawab segera, “eh buset, lama bener ni orang berangkat, pegel tangan gua!” sambungnya kesal, namun wajah nya tetap mempertahankan senyuman –palsu.
Aku menyeringai. “Apek banget lu. Bau matahari!”
“Ah? Masa?” Ares mengendus ke kiri dan kanan dengan mengangkat sedikit pangkal lengannya, “oh iye!” Lalu dia tertawa sendiri. Menyadari dirinya yang telah lama berdiri di bawah sengatan matahari, berkeringat. Saat Ares mandi, aku merapikan studio, menyapu dan memastikan semuanya sudah rapi. Kami sepakat menunggu hingga malam untuk melihat signboard dengan LED menyala.
Aku sedang mengatur sofa saat Trisna masuk, dia baru saja datang, “Gam?” Sapanya. Aku melihat sekilas dari pintu kaca bahwa dia diantar oleh pacarnya. “Nih, gua bawain makan malam, Aruna datang?” tanyanya kemudian.
“Enggak. Katanya lagi belajar bareng temen, dia bentar lagi uji kompetensi,” jawabku segera, “ntar gua bawain aja punya dia.”
“Uji apa?” tanya Trisna lagi.
“Uji kompetensi. Yah, semacam ujian buat dapetin lisensi perawat.”
“Ooh, okelah.”
Trisna mengeluarkan beberapa kotak makanan lengkap dengan sendok dan air mineral.
“Tuh, pacar lu nungguin apa gimana? Kok gak berangkat juga?”
Mobil si dokter muda tidak kunjung pergi dan menutup hampir seluruh pandangan ke jalan.
“Lu ngusir apa gimana?” Trisna ketus.
“Ya enggak, kalau mau di bawa masuk juga gak apa-apa.”
“Bentar lagi juga pergi, tadi gua turun dia lagi telpon, kali masih telponan,” jawab Trisna sambil sibuk menyusun makanan yang dia bawa di meja, sendok-sendok plastik dia tata tepat di atas kotak styrofoam. Benar saja, tidak lama mobil itu pergi tepat saat Ares muncul setelah mandi. Ares tampak senang melihat Trisna datang, “Kamu aku telepon gak angkat.” ujar Ares singkat, lalu duduk di sofa memeriksa apa yang Trisna bawa.
“Aku bareng dia.” Trisna menjawab cepat namun suaranya pelan.
“Oohh…” Ares mengangguk lemah. Lalu membuka tutup botol air mineral dengan kasar dan meminumnya segera, membasahi kerongkongan atau mungkin juga untuk menyirami hatinya yang terbakar. Melihat Ares begitu, Trisna diam saja, duduk pada sofa. Lalu setelah cukup lama diam, Trisna berujar pelan, “Res? Sorry.”
“Sorry buat apa? Haus aja kok,” Ares meremas botol air mineral yang sudah kosong itu. Aku kikuk berada dalam situasi ini di tengah-tengah mereka. Mataku bergerak kanan dan kiri memperhatikan Ares dan Trisna yang tidak kalah kikuk juga. Canggung. Dingin. Hening.
“Wiihhh! Nasi goreng! Favorit gua, nih!” Aku berujar ceria, berusaha membuat suasana kembali riang.
“Makan, makan, makan!” Trisna menimpali.
-oOo-
Aruna mengetuk pintu kamarku siang itu saat aku sedang duduk pada meja kerja, mengerjakan karya tugas akhir. Dia datang dengan membawa laptop dan beberapa buku, salah satunya terlihat sangat tebal, berkisar 600 halaman.
“Aku mau belajar, tapi berisik banget di sebelah,” ujarnya sebal. Wajahnya merengut menunjukkan kekesalan. Gedung kost sebelah sedang direnovasi, sepertinya penambahan lantai. Jendela kamar Aruna tepat menampilkan pemandangan para pekerja yang selalu di sana saat siang dan malam, bergantian. Gedung itu hanya berjarak sekitar lima meter dari kamar Aruna, membuat suara khas renovasi sangat jelas terdengar, dentingan palu, suara teriakan para tukang yang saling memberi koordinasi, dan hal semacamnya. Sudah sekitar seminggu berlangsung, sehingga sering kali saat siang Aruna datang ke kamarku agar lebih konsentrasi belajar. Walau masih terdengar, tapi tentu tidak selantang jika berada di kamar Aruna.
Dia langsung duduk pada sofa, membuka laptopnya. Wajahnya tampak bersungguh-sungguh, matanya bergerak membaca tiap tulisan yang muncul pada layar laptopnya.
“Ujiannya minggu depan, kan?” tanyaku, kembali duduk pada kursi kerja sebab tempat kosong di samping Aruna sudah dipenuhi dengan barang-barangnya, buku-buku dan alat tulis. Aku membawa kursi ini tepat kedepan Aruna.
“Iya, nih…Aku gugup,” Aruna menghela nafas.
“Bisa. Kamu pasti bisa.” Aku mengagetkannya dengan memegang kedua pangkal lengan Aruna dengan wajah meyakinkan bahwa dia pasti bisa, berharap dengan begitu meningkatkan kepercayaan dirinya.
“Do’ain, ya,” Aruna menatapku dengan bagian gelap matanya membesar.
“Pasti.”
Kecupan mendarat pada keningnya dengan cepat dan kuat sebanyak tiga kali, membuat kepalanya memantul.
“Gamma!” pekiknya pelan memintaku segera menghentikan. Lalu kami berdua tertawa.
Aku berdiri, mengambil kunci yang tergantung di balik pintu, melepaskan kunci cadangan yang terkait bersamaaan dengan kunci utama, lalu memberikannya kepada Aruna. “Nih, pegang. Jaga-jaga kalau aku siangnya pergi, kamu bisa masuk. Bebas.”
Aruna sempat ternganga, menatapku sekali lagi sambil menerima kunci itu. “Beneran gak apa-apa?”
Aku mengangguk pasti.
“Aku gak tanggung jawab, ya, kalau nanti ada barang berharga kamu hilang.” paparnya bercanda, sambil menyimpan kunci itu ke dalam kotak pensilnya.
“Apa sih yang berharga? Satu-satunya yang berharga itu cuma kamu, jangan sampai hilang.” jawabku santai sambil duduk memutar-mutarkan kursi kerja, bermain.
“Gak cocok, ah! Kamu gak pantes gombal gitu,” Aruna tertawa sehingga membuatku sadar bahwa selama ini aku memang tidak pernah melemparkan gombalan-gombalan. Aku sampai berhenti bermain putar-putaran pada kursi ini karena menyadari hal itu. Sebenarnya Aruna ini cukup santai, namun aku terkadang khawatir berada di dekatnya, karena tahu-tahu aku berperilaku membingungkan atau mengucapkan kata-kata yang di luar kebiasaan. Aku mengusap-usap tengkuk, malu sendiri. Namun sejujurnya itu bahkan bukan gombalan, yang kuucapkan padanya memang benar, dia memang berharga. Pada beberapa kesempatan Aruna berpikiran buruk tentang dirinya karena banyak hal, terkadang karena fisiknya yang cenderung kecil untuk wanita seusianya, atau saat dia mendapatkan nilai yang tidak sesuai harapannya bahkan beberapa kali karena dia dari panti asuhan –walaupun ini sangat jarang. Aku tahu dan menyadari memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi bagiku segala tentang Aruna terasa istimewa.
Saat Aruna kembali menatap layar laptop, aku justru sibuk melihat buku-bukunya, membaca bagian belakangnya. Beberapa membuatku sakit kepala karena bahkan bagian belakang sampulnya saja sudah banyak menampilkan istilah medis. Lalu mengambil buku yang lainnya, sama saja.
“Nyaris gila aku bacanya,” ujarku tersenyum sinis.
“Sama kayak aku baca buku kamu, pusing. Tapi aku suka.” Aruna membalas. Sambil menyelipkan rambut ke belakang telinga dia tersenyum. Matanya masih setia menatap layar laptop. Dia sungguh penuh perhatian dalam mempelajari tiap jurnal.
Dia pasti bisa. Pikirku.
“Aku tungguin kamu sampai selesai ujian besok. Pulangnya kita makan es krim!” ujarku menyemangati.
“Double!” Seru Aruna dengan semangat.
“Siap!”
Siang itu aku meninggalkannya belajar di kamar karena akan pergi bersama Ares, bekerja pada tim Kak Amy pada pabrik garmen, lalu rencana setelahnya adalah memperkenalkan bisnis kami kepada perusahaan garmen tersebut, sekaligus memberikan undangan acara pembukaan. Kami akan memaparkan kelebihan dan keuntungan jika mereka berkenan bekerja sama dengan kami, mencoba membawa mereka beralih, dengan SDM yang sama mereka akan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk content marketing perusahaan.
Sekitar pukul tujuh malam kami selesai, Kak Amy dan tim terlihat antusias saat kami memperlihatkan profil perusahaan dari tablet Ares. Mereka tertarik dan akan membahas perihal peralihan bersama tim keuangan dan tim marketing. Di parkiran, duduk pada motor masing-masing dan sambil merokok satu dua batang, Ares mengeluhkan bahwa karya tugas akhirnya tidak mengalami kemajuan karena sibuk mengurusi studio, “lu udah berapa persen?” tanyanya mengenai karya milikku. “Yah, tujuh limaan-an lah …,” jawabku santai, menghembuskan asap abu-abu ini jauh. Lalu Ares berkeluh kesah, bahwa sepertinya dia tidak bisa memenuhi janji kepada orang tuanya untuk lulus semester ini. Aku mengatakan padanya bahwa itu semua ada sebabnya, justru orang tuanya akan merasa bangga mengetahui anaknya membangun usaha bahkan sebelum wisuda. Ares hanya mengangkat bahu, menyeringai, lalu menunduk, menatap kedua sepatunya, “Yah, semoga, deh. Lu kayak gak tau papi mami gua aja,” sambung Ares mengetuk-ngetuk ujung rokoknya, membuat abu itu jatuh menimpa pavement. Rautnya kini tampak tidak begitu menyenangkan, mungkin dia mengingat betapa dia telah lama dibanding-bandingkan dengan salah seorang sepupu seumuran, yang kini telah bekerja pada salah satu perusahaan multinasional.
“Ya udah, deh. Fokus grand opening dulu,” ujar Ares lemah, mencoba mengalihkan pikiran dengan desahan nafas kasar pada akhir ucapan.
Pada Sabtu ke tiga bulan Juli –tepat dua minggu setelah cuti lebaran idul fitri, Gammares VisualCraft mengadakan Grand Opening. Acara dimulai sore hari. Bukan acara mewah dan besar, hanya acara sederhana yang dihadiri oleh teman-teman kampus, orang-orang dari kost seperti Bu Dewi, Pak Yahya, Gina, rekan kerja, Pak Adimas dan rekan-rekan studio photo lainnya. Ibu dan Marwa datang sejak pagi, saat aku masih tidur mereka mengetuk pintu dengan membawa satu koper, tampaknya mereka akan menginap.
“Kamu gak siap-siapin studio? Jam segini kok masih nyantai?” tanya Ibu yang duduk di sofa.
“Ini masih pagi, masih jam tujuh, Bu. Nanti jam sembilan atau jam sepuluh ke studio,” jawabku duduk bersisian dengan ibu.
“Aku sengaja berangkat pagi, Kak. Takutnya macet kalau siangan dikit,” ucap Marwa berjalan dari dapur sambil membawa segelas air untuk ibu, “kak, kami nginep, yah?” lanjut Marwa. Aku mengangguk, ini sudah yang kedua kalinya mereka menginap. Yang pertama saat aku semester dua atau tiga, aku lupa.
Aku mengatakan pada ibu bahwa aku dan Ares sudah memesan beberapa kue dan kudapan kepada Bu Dewi untuk acara nanti, bermacam-macam pilihan, tidak lupa tumpeng yang selalu hadir saat acara pembukaan. Wajah ibu tampak berseri-seri saat mendengarkan aku bercerita mengenai studio. Aku senang melihat antusiasme itu pada ibu. Terlebih saat Ibu bertanya mengenai teknis studio, misalnya jam operasional studio, hari apa aja beroperasi, pembagian jam kerja bersama Ares. Ibu menyarankan agar Marwa boleh dilibatkan jika ingin bertanya-tanya mengenai masalah keuangan mengingat Marwa adalah mahasiswi jurusan ekonomi. Marwa yang tengah duduk pada kursi kerjaku mengangguk, “Gak masalah, aku seneng malah,” ujarnya. Lalu ibu bertanya kembali masalah ujian untuk tugas akhir, aku memastikan kepada ibu bahwa akan menyelesaikan urusan kuliah akhir semester ini.
“Kak? Mental Health Nursing? Keperawatan jiwa? Buku apa, nih?” tanya Marwa sambil membolak balikkan halaman buku itu. Itu adalah buku Aruna yang tertinggal.
“Oohh, itu buku teks anak keperawatan,” aku mengatupkan bibir setelahnya, menahan agar tidak tersenyum. Sejak ibu mengatakan akan ke Jakarta, aku memang ingin memperkenalkan Aruna, tapi bukan begini caranya. “Maksudnya?” tanya ibu menatapku dengan raut lucu. Alisnya bertaut, matanya menyipit. Aku kikuk.
“Kak?!” Marwa mengagetkanku. Aku menggaruk kepala, “duh, gimana ya? Gini deh, itu punya Aruna. Aruna itu mahasiswi keperawatan, kamar 301, tetangga dep—”
“Sekaligus pacar.” Sambung Marwa cepat, dia sepertinya sudah membaca situasi sejak aku mulai terlihat kikuk.
“Bener, Nak? Udah berapa lama? Kok gak pernah cerita?” sambung ibu lagi.
Aku diam. Awalnya aku merasa percaya diri mengakui bahwa aku sudah punya pacar namun tiba-tiba karena Marwa mencegat perkataanku dan pertanyaan ibu terdengar menekan, membuat rasa bersalah muncul. Entah apa yang ibu pikirkan tentang ini. Apa ibu berpikir aku di sini main-main, atau lebih jauh lagi aku khawatir ibu berpikir bahwa aku tidak cukup berduka saat kepergian bapak karena kehadiran seorang perempuan. Entahlah. Aku bergantian melihat ibu dan Marwa, mencari-cari pada mata mereka tentang apa yang mereka pikirkan mengenai aku yang sudah punya pacar.
“Nak? Kamu kenapa? Kok kalut gitu?” tanya ibu tiba-tiba yang membuyarkan segala macam pikiran burukku.
“Ah? Engga, Bu.”
Ibu tersenyum tulus.
Marwa cengar-cengir.
“Ibu pengen kenal, nih!” kata ibu dengan nada bicara riang yang akhirnya membuatku tersadar bahwa hanya aku yang memiliki pikiran yang tidak menyenangkan.
“Iya, nih kak. Kenalin, dong!” Marwa menimpali.
Aku terkekeh malu, “Iya. Aku juga niat ngenalin Aruna. Ntar dia ikut kita berangkat bareng ke studio, ya.”
Ibu mengangguk sambil tersenyum jahil padaku. Marwa sibuk dengan kalimat usilnya, cie cie. Setelahnya ibu kembali bertanya apa yang tidak aku jawab sebelumnya, aku menceritakan secara singkat pertemuanku dengan Aruna, hanya garis besarnya saja. Sejujurnya aku juga tidak terbiasa bercerita begini kepada ibu dan Marwa, sedari kecil aku selalu diam jika dirasa tidak terlalu perlu angkat bicara. Aku bukan pendiam, aku hanya malas bicara dan tidak terlalu pintar basa-basi. Tapi kali ini berbeda, Aruna perlu dibicarakan kepada mereka. Marwa yang tadinya duduk di kursi kerja, saat aku mulai bercerita dia mendorong kursi itu tepat ke depan sofa. Mendengarkan ceritaku seolah anak kecil yang sedang dibacakan kisah kancil.
“Udah? Gitu aja? Masa sih segitu doang?” Selain ceritaku yang singkat, Marwa juga yakin sekali aku menyembunyikan sesuatu.
“Ah! Apa, sih?” aku berkilah. Marwa menunjukku dengan telunjuknya, matanya menyipit menatapku tajam, rahang bawahnya sedikit maju, seolah semua itu mampu menakutiku hingga akhirnya mengaku.
“Eh, eh udah, itu urusan kakak kamu, lagian ibu yakin kakak kamu gak ngapa-ngapain, ya kan, Gam?” Ibu menatapku, matanya sungguh bermakna sesuatu. Menekan dan menegaskan. Seolah sangat siap menghabisiku jika aku macam-macam,
Ini ultimatum.
“He’eh,” aku mengangguk, ragu.
Kemudian aku segera mengirimkan pesan kepada Aruna, menyampaikan bahwa ibu dan Marwa sudah berada di kamarku dan mereka ingin bertemu. Aruna hanya membalas dengan ‘Iya, Gam.’ Lalu saat aku keluar kamar mandi, tepat pukul delapan, Aruna sudah duduk di lantai bersama Marwa dan ibu di sofa, suasananya terlihat santai, bahkan aku mendapati mereka sedang tertawa bersama, membuatku sedikit kebingungan namun juga senang. Marwa menatapku, memutar kepalanya hampir 180 derajat, membuat wajah nya membelakangi Aruna. Dengan menaikkan kedua alis secara cepat beberapa kali, Marwa tersenyum licik. Aku paham benar maksudnya.
“Kamu udah lama?” tanyaku pada Aruna.
“Gak lama kakak masuk kamar mandi, Kak Aruna datang,” Marwa yang menjawab saat Aruna baru saja membuka mulutnya.
“Ini ibu dan adikku,” aku menghampiri mereka.
“Iya udah tau, kan udah kenalan,” lagi-lagi Marwa yang menjawab dengan cepat. Membuatku sedikit kesal.
“Bu, ini Aruna…,” aku mencoba mengenalkan Aruna sekali lagi kepada ibu, karena momen formalitas yang seharusnya terjadi sudah terlewati.
“Iya kak! Astaga! Udah kenalan tadi.”
Astaga! Marwa! Setidaknya biarkan aku melewati momen formal memperkenalkan Aruna kepada ibu. Aku ingin sekali mengangkat Marwa keluar dan menguncinya. Namun tentu saja itu tidak bisa aku lakukan sehingga aku hanya bisa membesarkan mata kepadanya. Marwa membalas dengan menjulurkan lidahnya padaku dengan cepat sebab sepertinya dia juga takut ketahuan Ibu.
“Marwa! Kamu jangan gitu, gak baik!” tegur ibu.
“Ya, Bu.” Ujar Marwa segera.
Kami bersiap menuju studio. Sebelum menuruni tangga, ibu meminta untuk mengunjungi Bu Dewi sebentar, silaturahmi sekaligus melihat pekerjaannya –membuat kue pesanan kami. Bu Dewi tampak senang ibu datang, mereka terlihat seperti teman yang sudah lama tidak bertemu.
“Gam, adik kamu lucu, gemesin,” Aruna berbisik pelan saat kami menuruni anak tangga, ibu dan Marwa berjalan bersisian di depan beberapa langkah.
“Dia itu usil. Kepo juga sama kamu, kalau dia mulai nanya aneh-aneh kamu diem aja,” sambungku. Aruna tertawa pelan.
“Tapi, Gam? Kamu cerita kalau aku dari … panti?” Aruna tampak ragu-ragu. sekaligus khawatir. Aku mengangguk dan merangkulnya kemudian mengusap kuat pangkal lengannya, memberikan kepastian bahwa apa yang dia pikirkan tidak perlu dikhawatirkan, “gak apa-apa. Aku tahu ibu dan Marwa itu gimana. Hal begitu gak perlu kamu takut,” ujarku pelan.
Sepanjang perjalanan, Marwa dan Aruna yang duduk pada bangku penumpang terus bercerita mengenai banyak hal, mulai dari cerita yang hanya dapat dipahami oleh perempuan hingga masalah politik negara yang aku tahu Marwa bahkan tidak tahu apa-apa. Sedangkan ibu, yang duduk di samping pengemudi, banyak tersenyum saja, sesekali ibu melirikku, tersenyum, bola matanya bergerak menunjuk Aruna. Melihat ibu begitu aku lantas ikut-ikutan tersenyum malu. Suasana di mobil sangat akrab sehingga empat puluh lima menit perjalanan terasa begitu singkat.
Acara pembukaan berjalan lancar, tamu-tamu yang kami undang hampir semuanya datang, kalau aku perhatikan hanya satu atau dua orang yang tidak, itu juga teman di kampus. Setelah acara pembukaan dan perkenalan singkat tentang bisnis ini, tepuk tangan para tamu terdengar bergemuruh, potong pita, tumpengan lalu setelahnya acara kebersamaan. Para undangan bebas menyantap makanan yang telah disediakan. Daripada disebut sebagai acara formal, suasana kali ini lebih kekeluargaan. Pak Yahya yang sengaja datang bersama Bu Dewi karena ingin membantu membawakan kue pesanan, ibu yang sedang bercengkrama dengan orang tua Ares, lalu teman-teman yang berkumpul bersama yang secara bergantian menyalami kami memberikan ucapan selamat. Lalu rekan-rekan kerja dulu yang mulai bertanya dan tertarik dengan bisnis kami ini kembali bertanya mengenai usaha ini, kesempatan ini tidak kami sia-siakan, bahkan saat acara pembukaan, aku dan Ares sibuk memberikan profil perusahaan dan kembali berulang-ulang menjelaskan dengan semangat yang sama setiap kali ada yang bertanya.
Acara berakhir sekitar pukul enam, tepat saat rombongan teman-teman kampus pulang dan Ares tengah melakukan video call dengan neneknya di Malang, tidak bisa datang karena masalah kesehatan. Aku meminta Marwa membawa ibu kembali ke kost sebab ibu sudah mulai tampak lelah.
“Kak Aruna gimana?” tanya Marwa pada Aruna.
Aruna melihatku sebentar, “Aku di sini dulu bantuin beres-beres. Gak apa-apa?” tanya Aruna lembut. Marwa mengangguk sambil melihat sekeliling, “iya sih, berantakan banget ini,” ujarnya lagi. Aku menyalami ibu sambil berujar mengucapkan berkali-kali ujaran terima kasih karena telah mendukung. Ibu memeluk sambil mengucapkan selamat sekali lagi dan mengatakan hal yang membuatku terharu, “Bapak pasti bangga sama kamu.” Aku menelan ludah mendengarnya, menahan haru yang menjalar cepat ke dada, “iya.” ujarku pelan.
Aku dan Ares mengantarkan ibu hingga ke mobil. “Nanti aku langsung balik kalau ini udah beres, Bu,” ujarku sambil membantu memasang sabuk pengaman.
“Marwa, hati-hati nyetirnya, kabarin kakak kalau udah sampai,” Kata Ares yang berada di balik jendela sisi Marwa. Aku melotot melihatnya.
“Apaan? Orang adik gua,” dengus Ares. Marwa tersenyum singkat dan menggeleng-gelengkan kepala.
Setelah semua pulang, kami berempat lagi. Aku, Ares, Aruna dan Trisna membereskan studio yang kini berantakan. Sekitar jam sembilan malam setelah makan, kami memutuskan pulang. Studio sudah bersih dan siap buka besok hari. Kali ini Trisna diantar pulang oleh Ares setelah terdengar sekilas melalui percakapan telepon bahwa pacarnya tidak bisa menjemput karena sedang bertugas di instalasi gawat darurat.
“Yah, gitu lah. Gua seneng tapi sedih juga.” Ares terlihat pasrah pada hubungan tanpa kejelasan status dan terkesan tarik ulur dari Trisna.
“Kombinasi yang menyulitkan,” jawabku santai.
Ares mengangkat bahu dengan lemah. Aku menepuk pundaknya sebelum kami berpisah untuk pulang.
-oOo-
Memasuki gerbang kost, Pak Yahya masih di sana, mengutip sampah-sampah plastik di parkiran. Pak Yahya mengucapkan selamat sekali lagi sambil berseloroh, “Sekali-kali potoin saya gitu, lho, Mas,” ujarnya sambil tertawa.
“Datang aja, Pak. Bawa anak-anak sekalian,” ujarku.
“Boleh, toh?” mata Pak Yahya membesar lalu senyum lebar.
“Boleh banget, Pak!” jawabku.
Pak Yahya mengangguk, lalu tiba-tiba dia menepuk dahi, “Mbak Aruna, saya hampir lupa. Mbok e udah di atas,barusan datang, nungguin mbak pulang!” Pak Yahya setengah berseru dan setengah lagi memperlihatkan raut bersalah karena lupa.
“Bu Sarah!?” tanya Aruna tak kalah terkejut.
“Nah iya! Tadi mbok e bilang jenenge Sarah,” ujar Pak Yahya lagi.
“Terus bapak bilang apa?” tanya Aruna panik.
“Yaa saya bilang, pergi ke studio Mas Gamma dari pagi.”
Pak Yahya yang tidak tahu apa-apa terlihat semakin bersalah sebab Aruna tampak gelisah.
Aku kebingungan sendiri.
“Runa? Yuk, ke atas kalau gitu,” ujarku dengan ragu, entah kenapa aku juga ikut-ikutan merasa bersalah. Bahkan aku ragu dia akan setuju untuk bersama-sama naik ke atas.
“Gak bisa barengan, Gam. Harus salah satu. Aku atau kamu dulu yang naik?” ujar Aruna dengan sorot mata yang entah bagaimana aku bisa mengatakannya. Takut?
Aku yang sedang bingung menghadapi situasi menjawab seadanya, “Kamu. Kamu aja yang duluan.”
Lalu tanpa basa-basi lagi, Aruna segera berlari. Baru beberapa langkah dia justru kembali, tergesa-gesa melepaskan jaket jeans, memberikannya padaku, lalu berlari lagi kali ini lebih cepat. Aku dan Pak Yahya hanya termenung dan mematung melihat perubahan sikapnya yang cepat hanya karena mengetahui Bu Sarah datang.
“Saya salah, ya, Mas?” tanya Pak Yahya plengah-plengoh.
“Saya juga gak tahu, Pak.”
Lalu aku menyadari satu hal bahwa setiap kehadiran Bu Sarah, Aruna menjadi gelisah. Padahal menurut ceritanya Bu Sarah bukanlah seorang antagonis dalam hidupnya, justru mendukung Aruna sepenuhnya. Apakah ada bagian yang Aruna lupa ceritakan? Atau memang sengaja untuk tidak diceritakan? Entahlah. Aku terus menaiki anak tangga dengan memikirkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang itu-itu saja.
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden



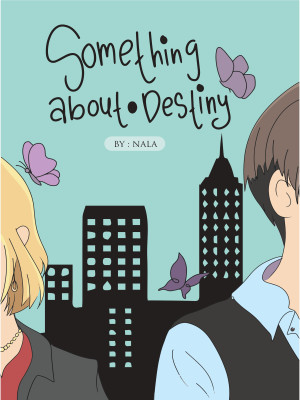









Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)