Pukul 20.15 WIB, aku akhirnya tiba di rumah di Bogor setelah menempuh perjalanan yang kali ini terasa panjang selama hampir satu setengah jam. Jalanan yang semakin ramai, bahkan terjebak macet, membuat gusar semakin bergejolak. Saat aku memasuki halaman rumah, terlihat sudah banyak tetangga dan kerabat yang berkumpul. Banyak dari mereka mengenakan pakaian berwarna hitam, sebagian lagi berwarna putih, melambangkan kedukaan dan kesucian. Benar-benar warna yang sarat kontras.
Aku segera memarkirkan motor dan tanpa ragu berlari masuk ke dalam rumah walau terdengar suara orang-orang di sekeliling memanggil namaku atau bahkan berbisik-bisik melihat kehadiranku. Aku tidak memberikan perhatian pada apapun itu. Fokus utamaku hanya pada bapak yang terbaring diam dan kaku di tengah ruang keluarga. Semakin mendekati tubuhnya, semakin hancur perasaanku rasanya.
“Pak …,”
Aku bisa mendengar suara sendiri dirambati getir. Serak. Nafasku tercekat melihat beliau sudah dipakaikan pakaian terakhirnya, kafan. Keheningan terasa pekat di tengah ruangan yang ramai ini. Cahaya lampu seolah hanya menyoroti wajah bapak yang tenang. Mataku beralih kepada ibu dan Marwa yang duduk di samping tubuh bapak. Isakan mereka menghujam-hujami perasaanku. Ibu dan Marwa bersama-sama menguatkan diri dengan saling menggenggam tangan, berusaha keras menerima kenyataan yang menghentak ini. Aku memeluk tubuh bapak lalu membisikkan kalimat-kalimat do'a. Ibu melihat, kemudian tidak mampu menahan pilu, air matanya yang tadi hanya merembes, kini jatuh luruh. Aku segera menuju ibu dengan berjalan setengah berdiri menggerakkan lutut maju. Aku tidak mau dan juga tidak mampu berdiri tegak di samping tubuh bapak yang terbaring. Aku peluk ibu dengan erat, sedang satu tanganku juga meraih bahu Marwa, menariknya kedalam bahuku. Getaran kesedihan Ibu dan Marwa begitu kuat, begitu nyata, hingga terasa bagai gelombang yang menghantam jantungku. Membuatku ikut ternggelam dalam lautan duka yang dalam. Tubuhku yang terjepit di antara mereka seolah menjadi satu dengan kepedihan yang menguasai kami semua. Kami bersama dalam satu pelukan yang tidak terlupakan. Dalam detik itu, rasanya seolah dunia hancur berkeping-keping di sekitarku. Air mataku perlahan merembes, mengalir dan menghangatkan pipi dan berusaha menyembunyikan kesedihan dengan menenggelamkan wajah di antara bahu Ibu dan bahu Marwa. Kesedihan yang kami salurkan melalui tangisan justru membuat para pelayat ikut menyumbangkan isakan, membuat suasana di dalam rumah menjadi lebih pilu. Aroma harum dari bunga-bunga campuran yang dibawa mereka pun mulai menyelimuti ruangan, menciptakan atmosfer kontras akan kepedihan dan keindahan yang menghormati kepergian bapak.
Sedikit demi sedikit, ketika tangisan ibu mulai bisa dikendalikan, ibu memulai ceritanya dengan suara gemetar. Tiap kata tersampaikan dengan napas berat. Tidak jarang ibu harus mengambil jeda lumayan panjang untuk melanjutkan. Pagi sebelum meninggalkan rumah, Bapak memberitahu Ibu bahwa ia merasa tidak begitu baik. Pandangannya ia keluhkan sedikit buram, perutnya sedikit tidak nyaman, dan rasa panas pada tubuhnya. Semuanya tidak lebih dari keluhan ringan, mungkin itu adalah sesuatu yang bisa diabaikan, sesuatu yang kita semua bisa lalui tanpa terlalu banyak prasangka. Namun, hal-hal kecil itulah yang akhirnya mengubah segalanya menjadi besar. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Ibu, bahwa pagi itu, di bawah sinar matahari yang lembut, ia memberikan sarapan terakhir kepada bapak, tanpa mengetahui bahwa itu adalah sebuah momen perpisahan. Lalu Ibu menceritakan bagaimana detik-detik terakhir bapak yang ia ketahui justru melalui telepon salah satu rekan kerjanya, dimana kehidupan usai begitu cepat dalam rutinitas kantor yang tidak pernah ada habisnya. Bapak meninggal dalam keadaan yang tidak terduga. Saat tengah mengerjakan tugas terakhirnya sore itu, bapak juga menghembuskan nafas terakhirnya. Rekan kerjanya sempat membawa bapak ke rumah sakit, namun takdir berkata lain, bahkan sebelum masuk mobil, bapak diperkirakan sudah tiada. Ibu dan Marwa datang ke rumah sakit segera. Mendengar berita duka, ibu langsung lemas tidak berdaya, sedangkan Marwa menangis sejadi-jadinya.
“Ibu merasa kaki ini gak ditopang tulang lagi, ibu terduduk di lantai. Ibu linglung dan bingung.” Ibu menunduk, menatap tangannya yang dia kepal kuat di atas paha.
Bapak adalah seorang kepala kantor cabang pada salah satu perusahaan BUMN di Bogor yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik dan beberapa transaksi keuangan. Bapak berdedikasi selama tiga puluh dua tahun, bahkan hingga akhir hayatnya.
Setiap kata yang ibu ucapkan membawa kesedihan yang tidak terkendali. Dadaku sesak. Berkali-kali aku ingatkan diri bahwa ini sudah jalan Tuhan. Di ujung cerita ibu, aku kembali memeluknya, tanganku mengusap punggungnya dengan lembut, berusaha menenangkannya meskipun aku tahu bahwa tindakanku tidak akan bisa meredakan pedih hatinya. Sama sekali tidak bisa. Mengurangipun tidak.
-oOo-
Pagi itu, setelah mengantarkan dan menyaksikan bapak beristirahat untuk selamanya dengan tenang, rumah kami masih dipenuhi dengan kehadiran para pelayat. Bahkan Ares dan Fahmi terlihat hadir walau mereka sedikit terlambat, tidak sempat ikut mengantar ke pemakaman. Suara belasungkawa bergema di ruangan, bersatu dalam satu kalimat duka yang mendalam. Ucapan-ucapan mengalir, namun terasa seperti mantra yang terulang, tidak lagi memiliki makna yang mendalam.
Pandanganku samar sedangkan pikiranku terfokus pada masa depan yang terasa begitu hambar. Begitu bercabang dan begitu berubah-ubah. Pertanyaan-pertanyaan yang belum ada jawaban membuat perasaan semakin tidak keruan. Bagaimana aku bisa melangkah menjauh, meninggalkan ibu dan Marwa di sini tanpa seseorang laki-laki yang bisa melindungi mereka? Bagaimana ibu akan mengisi hari-harinya tanpa kehadiran bapak yang selalu tegar di sisinya? Bagaimana dengan biaya kuliah Marwa, dan kehidupan sehari-hari mereka? Masih banyak bagaimana-bagaimana lainnya yang mengitari kepalaku kini dan sama sekali belum ada jawaban pasti.
Saat sore, hanya Ares yang masih berada di rumah. Fahmi sudah duluan kembali ke Jakarta tidak lama setelah adzan Zuhur. Sepertinya Ares sengaja menunggu semua tamu pulang agar bisa menemaniku. Kami berdua duduk di teras depan. Ibu dan Marwa sedang berada di kamar masing-masing, melepas kesedihan sekali lagi.
“Gua jujur gak tahu ngomong apa kecuali turut berduka,” ujar Ares berusaha membuka percakapan denganku yang sedari tadi hanya diam menatap halaman rumah.
“Santai aja, Nyet. Gak apa-apa. Thanks udah nyusulin juga,” ujarku datar. Ares mengangguk kemudian membakar rokok.
Tanganku meraih bungkus Lucky Strike itu.
“Eh! Bocah monyet! Apaan lu? Makan juga belum!” seru Ares segera sambil menyambar bungkus rokok. “Lagian rokok gua juga.”
“Satu doang. Sini dah …,” aku berusaaha meraih rokok itu kembali. Walau tampak berat Ares tetap memberikannya. Aku memang merokok tapi bukan perokok. Sesekali di saat merasa lelah atau mengalami hari berat aku akan merasa sedikit tenang dengan menghisap gulungan tembakau ini.
“Noh, makan dulu, cemilan. Banyak tuh di bawain orang-orang,” Ares menunjuk satu piring kecil berisi beberapa kue yang diambilnya sebelum kami duduk di sini. Sambil membakar rokok, aku melirik kue itu sebentar. Tidak ada selera makan, malah sebenarnya mual hanya dengan melihat isi di piring itu. Warna-warni yang mencolok dari beberapa kue justru seolah merayakan kesedihan. Aku jengkel sendiri dan menghela napas sambil menoleh ke arah lain, menghembuskan asap putih dari mulutku.
“Lu tau darimana?” tanyaku pada Ares. Aku bahkan tidak sempat melihat handphone sejak kemarin malam.
“Arumi.”
“Arumi siapa?” tanyaku sambil mengingat-ingat apakah kami mempunyai teman bernama Arumi.
“Tetangga baru lu itu,” jawab Ares santai.
“Aruna!” kataku seetengah berseru.
Ares sontak tertawa, “Iya. Tahu. Sengaja gua. Berarti lu masih fokus kalo urusan cewek,” ujarnya berguyon, caranya menghiburku.
“Kita kan janjian ketemu di perpus kampus sama anak-anak lain, mau bahas tipografi karya Erik Spiekermann. Gua telpon lu kagak angkat. Ya udah, gua susulin ke kost. Di sana ketemu Aruna. Terus dia bilang kalo…,” Ares tidak melanjutkan kata-katanya, justru dia melihat ke arahku dengan keengganan, “yaahh, gitu dah…,” ujarnya lagi menutup kalimatnya.
“Ya.”
“Eh, telpon Kak Amy, deh! Gua udah sampein sebelum ke sini, tadi gua mampir bentar. Tapi kan lebih baik lu yang langsung ngomong.” Ares mengingatkanku mengenai pekerjaan pada perusahaan garmen yang tiba-tiba aku tinggalkan. Aku dan Ares bersamaan mematikan api rokok dengan menukil ujungnya ke asbak. Aku baru tersadar akan hal-hal lain yang harus dilakukan. Memang tidak boleh berlama-lama tlarut dalam duka. Di sini masih ada dunia yang harus dijalankan. Tak lama setelah itu, Ares izin padaku untuk pulang ke Jakarta. Aku mengatakan padanya bahwa aku akan di sini sampai setidaknya tiga hari, memastikan keadaan ibu dan Marwa baik-baik saja.
-oOo-
Satu, dua hari tanpa bapak sudah terlewati tapi suasana duka masih menyelimuti rumah kami. Masih terdengar dari balik pintu kamar Marwa jika aku melewatinya. Kepergian bapak memberi benturan keras pada hatinya. Bagaimana tidak, Marwa adalah anak kesayangan. Dari kecil Marwa memang mendapat perhatian lebih dari bapak. Aku sangat memaklumi karena dia adalah seorang anak perempuan, memang sepantasnya disayangi dan dimanjakan. Aku justru sangat bangga terhadap Bapak karena mampu menyayangi Marwa tanpa membuat ku merasa terkesampingkan. Bapak mampu mendidik kami sesuai porsi masing-masing.
Tidak seperti Marwa, ibu lebih menunjukkan ketenangan. Entah sejak kapan aku menyadari bahwa di balik kelembutannya, ibu memiliki kekuatan luar biasa untuk sebuah penerimaan, dulu saat aku SMP dan Marwa masih SD, nenek dari garis ibu meninggal. Di antara paman dan bibi yang menangis bahkan salah satu bibiku meraung, ibu mampu mengendalikan diri dengan tetap tenang dan menerima kedatangan pelayat dengan baik. Kini sikap penerimaan yang tenang itu kembali lagi, bahkan untuk menghadapi kepergian orang yang dicintai.
“Bu?” Malam itu aku mengetuk pintu kamar ibu yang sedikit terbuka.
“Ya? Masuk aja, Nak,” suara ibu pelan di balik pintu. Lalu aku masuk. Ibu duduk di kasur sambil melipat pakaian-pakaian yang akan dimasukkan ke dalam lemari.
“Kenapa?” tanya ibu sambil menoleh ke arahku yang berdiri tepat di belakangnya. Cahaya lampu yang terang di kamar ini semakin memperlihatkan wajah ibu kini sudah bisa aku katakan menua, garis-garis pada wajahnya entah sejak kapan mulai terlihat jelas. Seketika perasaan sedih merayap.
“Aku mau bicara, Bu.”
Mendengar itu, Ibu berhenti melipat pakaian kemudian duduk di tepi kasur.
“Sini,” ujar ibu sambil menepuk lembut sisi kasur di sebelahnya agar aku menyusul duduk. Namun aku memilih duduk di lantai sambil menyilangkan kaki.
“Aku khawatir, ibu sama Marwa di sini berdua aja,” kedua tanganku memegang pergelangan kakiku dengan kuat, berusaha menekan gugup yang datang melanda. Ibu menghela napas lalu mengusap kepalaku.
“Gam, Ibu tahu arah pembicaraan ini. Satu hal yang perlu kamu ingat, Ibu gak ingin kamu mengorbankan kuliahmu, apalagi sekarang wisuda sudah dekat. Mulai dari memilih jurusan, kampus, hingga tempat tinggal di sana, semuanya adalah pilihanmu, kan? Ini adalah cita-cita yang kamu bangun sendiri. Masa hanya karena kamu khawatir tentang Ibu dan adikmu di sini, kamu akan mengorbankan semua itu?” Suara Ibu terdengar lembut, penuh kasih sayang, namun juga tegas. Aku mendongak, menatap kehangatan yang tak tertandingi pada wajahnya.
“Khawatir itu gak pernah jadi hanya. Itu besar, Bu. Sekarang tanggung jawab bapak untuk jagain Ibu dan Marwa, memastikan kalian baik-baik aja udah beralih sepenuhnya ke aku.” Aku menambahkan, mencoba meyakinkan Ibu bahwa hatiku tidak akan tenang jika harus meninggalkan mereka berdua di sini, sendirian di tengah ketidakpastian. “Aku bisa pindah kampus.”
Ibu tersenyum. Senyum dengan kawakan seorang ibu yang bangga. Tapi ada sesuatu pada rautnya menunjukkan kesusahan hati pula, “Gam, menjaga itu tida harus berarti dekat. Ada itu tidak melulu tentang hadir. Kasih itu tidak terus-terusan harus terlihat. Berusaha menjadi lebih baik itu memang bagus, tapi bukan berarti memaksakannya agar jadi baik itu harus. Kamu hanya perlu melakukannya sesuai kemampuan, jika tidak, maka akan banyak menimbulkan sakit perasaan, baik untuk dirimu sendiri atau bahkan orang-orang yang kamu pikir akan senang menerima semua pengorbanan ini.”
Ibu Seruni, kamu memang malaikat yang dihadiahkan Tuhan untuk keluarga ini, ucap batinku yang semakin tersiram oleh kehangatan yang kini masuk menelisik hingga relung-relung tulang. Aku mencium tangannya. Kemudian aku sandarkan kepalaku pada lututnya. Tak ada kata-kata yang mampu kukeluarkan untuk membalas ucapan ibu barusan. Lagipula aku tahu bahwa ibu akan jauh lebih sennag jika aku tidak menyambut perkataan itu dengan menyela.
“Bu, terima kasih,” ucapku pelan masih sambil bersandar pada kakinya.
“Kapan berangkatnya?” Ibu kembali bertanya.
“Besok sore, kalau bisa?” aku memberikan pilihan pada ibu, apakah ia akan memintaku untuk tinggal lebih lama atau tidak. Namun yang kulihat ibu justru mengangguk cepat dan menyetujui ucapanku tanpa menentukan pilihannya sendiri. Sebelum keluar kamar, aku memutuskan untuk membantu ibu melipat pakaian yang tadi sempat tertunda.
-oOo-
Aku sudah siap berangkat kembali ke Jakarta. Ibu dan Marwa mengantarku hingga pintu depan. Aku mencium tangan ibu dan memeluknya. Ibu menepuk lembut punggungku.
“Hati- hati, Gam,” ujarnya pelan.
“Ibu, jaga kesehatan, ya! Baik-baik di rumah,” pesanku.
Ibu mengangguk dengan pasti dan tersenyum ringan. Sedangkan Marwa masih setia menekukkan wajah, menatap kaki nya dengan tatapan hampa.
“Mar, besok mulai kuliah lagi. Jangan libur terlalu lama," ujarku menepuk bahunya pelan.
Marwa saat ini berada di tahun kedua kuliah di salah satu universitas swasta di Bogor, mengambil jurusan Ekonomi dan Bisnis. Usia yang hanya berjarak dua tahun itu membuat kami bisa berbincang serius dengan baik dan juga saling meledek dengan cukup konyol.
“Iya, Kak. Kakak juga baik-baik kuliahnya, jangan keluyuran terus sma Kak Ares,” ujarnya dengan suara parau dan sedikit menekan saat menyebutkan kata keluyuran dan Ares. Aku terkekeh. Marwa tertawa kecil walau masih terlihat kesedihan dalam pandangan matanya. Marwa juga mengatakan bahwa dia sebenarnya berharap agar aku bisa tinggal sedikit lebih lama, namun dia tahu benar bahwa ada tanggung jawab yang harus aku selesaikan di Jakarta. Aku berangkat setelah mencium tangan ibu dan memeluk adikku. Sesaat sebelum belok, aku kembali menoleh kebelakang, melihat Ibu dan adikku yang menungguku hilang dari halaman. Marwa tampak melambaikan tangan.
-oOo-
Sudah dua hari aku di Jakarta. Sore itu aku duduk di depan bersama Pak Yahya yang juga sempat menyampaikan belasungkawa.
“Saya dikabarin Mbak Aruna, Mas.”
Aruna lagi.
“Rabu, dua November 2016,” gumamku. Aku mencatat tanggal bapak meninggal pada sebuah buku bersampul coklat yang aku miliki sejak semester pertama, buku itu bukan diary atau semacamnya, hanya sebuah catatan untuk hal-hal penting, atau semacam cita-cita dan impian yang ingin aku wujudkan. Senja berganti malam. Saat sendirian, terlebih saat ini, aku kembali memikirkan ibu dan Marwa. Memikirkan kebutuhan harian di rumah untuk mencukupi mereka. Aku memang bekerja sebagai freelancer sejak semester tiga untuk mempersiapkan diri sebab Marwa mulai kuliah di tahun itu. Aku dengan kesadaran sendiri memahami bahwa aku juga tidak bisa menunggu dan menampung dari bapak saja. Komisi bekerja freelance cukup untuk menutupi kebutuhan harian selama disini. Memang bapak tidak pernah melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua, bapak masih mengirimkan uang bahkan dengan nominal yang sama. Uang dari bapak masih bisa aku simpan untuk berjaga-jaga.
Aku terus memutar otak mencari cara untuk mendapatkan pekerjaan lain dalam waktu dekat, demi membantu kebutuhan Ibu dan Marwa di rumah. Sesekali, aku membuka aplikasi m-banking untuk memeriksa apakah tabungan cukup untuk dikirimkan sementara kepada Ibu. Pikiran-pikiran itu membuat kepalaku menyempit.Tiba-tiba, suara ketukan pintu dan salam dari seseorang membuyarkan lamunan. Aku segera membuka pintu dan melihat Bu Dewi dan Pak Rully berdiri di sana.
“Pak Rully, Bu Dewi,” sapaku saat melihat pasangan suami istri ini tiba-tiba bertamu.
“Gam, saya dapat kabar dari Aruna, bahwa Pak Damar …,” Bu Dewi diam, dia melirik suaminya yang juga tampak tidak ingin melanjutkan. Mereka seolah adu tahan-tahanan. “Kami turut berduka,” lanjut Bu Dewi memangkas situasi.
Aruna lagi…
“Semoga Pak Damar tenang di alam sana,” tambah Pak Rully lagi.
“Iya Pak, Bu. Terima kasih banyak.”
“Kamu yang tabah, ya. Ibu dan adik kamu bagaimana keadannya?” tanya Bu Dewi.
“Mereka udah lebih tenang, Bu. Tadi sore juga sempat video call, keliatannya udah baik-baik aja.”
“Maaf saya gak bisa susulin ke Bogor, karena gak bisa mendadak cuti,” ujar Pak Rully lagi sambil memperbaiki kacamatanya yang turun-turun. Sejujurnya, selama lebih dari tiga tahun di sini, Pak Rully dan aku hanya berbicara beberapa kali. Pak Rully sudah berangkat bekerja setelah azan Subuh sebab menaiki kereta dari stasiun Cikini untuk sampai pada tempat kerjanya pada toko grosir aksesoris mobil di Jakarta Utara dan akan kembali lagi saat hampir semua penghuni kos sudah bersiap akan tidur.
“Gak apa-apa, Pak. Jangan dipikirkan,” timpalku lagi untuk mengikis rasa tidak enak hati pria canggung ini.
“Naah ini, saya buatkan makanan. Kalau belum mau dimakan, simpan di kulkas, ya. Biar awet,” Bu Dewi memberikan satu kotak makanan kepadaku, yang aku anggap sebagai bentuk dukungan yang mampu ia berikan.
“Makasih banyak, Bu Dewi,” ujarku sambil menerima kotak makanan biru muda itu.
Tak berselang lama, mereka pamit pulang. Setelah pintu tertutup, aku lantas menaruh kotak berisi makanan yang diberikan Bu Dewi di kulkas kecil yang biasanya kuisi dengan minuman kaleng, kopi instan dan beberapa cemilan. Kotak makanan dari Bu Dewi berisi lemper ayam dan kue tradisional lain yang aku tidak tahu namanya. Dalam hatiku terbesit rasa syukur atas kehadiran tetangga yang begitu baik.
Tiba-tiba, saat menyusun kue-kue itu, Aruna terlintas dalam pikiranku. Dia tahu bagaimana cara menyampaikan kabar duka kepada orang yang tepat. Meskipun dia tidak secara terbuka mengumumkan kepada semua penghuni kost, dia dengan hati-hati mendekati mereka yang sepatutnya tahu.Terbukti saat tetangga lain menyapa seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa padaku. Aku suka caranya. Aku suka keputusannya itu. Juga ingin sekali berterima kasih padanya atas apa yang telah dia lakukan, termasuk untuk menenangkanku dan menghapus air mataku saat kesedihan melanda. Namun sayangnya sejak aku kembali, entah mengapa aku tidak pernah melihatnya lagi. Kamarnya sepi. Pernah kucoba mengetuk pintunya sekali, namun tidak ada jawaban.
Suatu malam –sepertinya malam kelima sejak kembali dari Bogor, aku yang sedang memarkirkan motor di tempat biasa melihat Aruna turun dari sebuah mobil sedan hitam Aruna menyandang ransel yang agak besar menunjukkan dia telah menempuh perjalanan jauh. Mobil itu tidak sempat parkir dan hanya berhenti di depan pagar. Aruna turun bersamaan dengan seorang wanita, yang aku duga-duga adalah ibu nya. Ibu berjilbab itu mengantar Aruna hingga pintu masuk gedung. Aku melewati mereka yang sedang berbincang di lorong besar penerimaan tamu. Raut wajah Aruna tampak ceria seperti biasa. Begitu juga dengan ibu yang menjadi lawan bicaranya. Aku sengaja melangkah lebih lambat dari biasanya dengan harapan Aruna bisa menyamai langkahku kemudian, ketika dia sudah selesai dengan ibunya. Sesuai harapan, tidak selang berapa lama, aku mendengar Aruna memanggil.
“Gam,” panggilnya. Aku menoleh kebelakang melihat dia mempercepat langkah. Aku tersenyum dan berhenti menunggunya.
“Aruna,” kataku, “dari mana?” Aku bertanya tepat saat dia sudah berada di sampingku.
“Dari Tangerang. Kamu apa kabar? Di rumah gimana?” tanya nya pelan penuh perhatian.
Kami berjalan bersisian.
“Aku baik. Di rumah juga baik. Hanya ada ibu dan adikku di rumah, adik perempuan,” jelasku pada Aruna. Dia menatapku dengan wajah sendu, seolah mengatakan bahwa dia masih bisa merasakan kesedihanku.
“Udah, jangan gitu. Aku gak apa-apa,” Aku menepis tangan di tengah udara antara wajah kami berdua untuk menyudahi tatapan kesedihan yang dia perlihatkan. Aruna tersadar lalu berkata, “Oh. Maaf …,” ujarnya menunduk dan tersenyum.
“Itu tadi ibu kamu, ya? Tinggal di Tangerang?” Aku mengalihkan pembicaraan. Aruna menggelengkan kepala, senyumannya belum surut, “Ibu Sarah, namanya. Bukan ibu kandungku. Aku tumbuh di panti asuhan di Tangerang, sejak umur tiga, menjelang empat tahun. Ini juga aku sekolah keperawatan atas kemauan Bu Sarah. Aku dibantunya sekolah sejak SD.” Aruna menjelaskan dengan tenang. Tidak tergambarkan pada wajahnya raut kesedihan atau penyesalan. Membuat aku berasumsi mungkin saja Aruna telah banyak melalui kepahitan lain sehingga mampu menjelaskan hal ini dengan baik dan bersih seperti yang baru saja dia lakukan. Bahkan dia mampu menyelipkan sebuah senyuman. Aku terperangah mendengarnya, terdiam dan tidak mampu memberikan respons apa-apa. Kata-kata tertahan di tenggorokan. Lalu aku malu mengingat pertemuan kami sebelum ini, dimana aku menangis di hadapannya. Mungkin rasa sedih itu tidak secuil pun jika dibandingkan dengan kepedihan hidup Aruna, namun saat itu dia mampu menunjukkan perhatian yang lebih besar sehingga membuatku merasa sedikit tenang. Aku kagum padanya. Tanpa sadar aku berhenti melangkah dan membuatku tertinggal beberapa langah darinya. Aku terus memperhatikan punggungnya yang kecil itu dari belakang Aku terpesona olehnya. Mataku terus tertuju padanya yang terus menjauh menaiki anak tangga.
“Gam?" Aruna menoleh kebelakang, tepat ke arahku berdiam.
“Ya?” kataku sedikit terkejut sebab lamunanku terputus.
“Ngapain diem di sana? Naik ayuk!”
“Oh? O Iya!” Aku tertawa malu sambil melangkahi anak tangga, menyusul Aruna yang sudah berjarak sekitar lima anak tangga. “Ayuk!”
Saat akan berpisah masuk ke kamar masing-masing, aku benar-benar ingin menanyakan nompr handphone-nya. Tapi aku ragu, entah dia merasa belum patut karena belum terlalu kenal, atau justru aku khawatir dia merasa takut. Tapi, mungkin sesuatu pada wajahku sungguh kentara hingga dia tersenyum menggoda. Dia tahu aku kelimpungan. Dia tahu aku ingin, tapi tertahan. Tapi dia menunggu. Dan kini aku tahu, aku harus bergerak maju.
Akhirnya, nomor kami bertukar. Sebelum masuk kamar, sambil saling menatap, kami memberikan dukungan dan saling menguatkan atas hal-hal yang sudah terjadi. Di dalam kamar, aku membiarkan diriku bersandar lemas pada pintu, memberikan kesempatan diri untuk mengingat betapa memesonanya tetangga baru ini. Aruna, dia gadis luar biasa, bukan?
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden



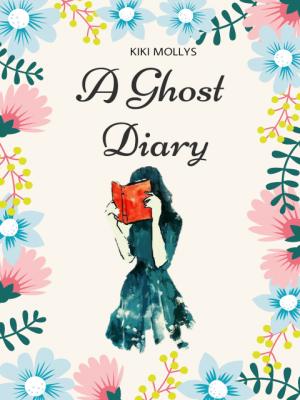









Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)