"Kalau konser ini konser terakhir dunia, siapa yang jadi MC-nya? Tolong jangan Orpheus lagi, jokes dia kering."
Itu kalimat terakhir yang dilontarkan MarJayHop sebelum langit Ethereal retak seperti cermin disambar petir.
Retakan bercahaya merah muda menyapu angkasa seperti sarung mahal yang tersangkut di kawat jemuran. Bukannya angin, yang berdesing justru denting nada minor bercampur petir nge-beat. Langit Ethereal yang biasanya Instagramable ala pastel aesthetic moodboard—kini berubah jadi layar error Windows XP. Dari balik celah, muncul sosok tinggi menjulang.
Dia melangkah seperti orkestra yang kehilangan tempo, mengenakan mantel gelap dan topeng berbentuk not musik yang retak. Suara yang keluar dari mulutnya menggema tiga kali, tanpa efek autotune tapi lebih mengerikan.
"Aku adalah Harmageddon."
MarJayHop mengangkat alis. "Harmageddon? Itu kayak nama boss terakhir game RPG yang kamu save level 99 tapi gak pernah tamat, ya?"
MarViTae ikut menimpali, "Atau nama band metal yang selalu gagal di semi final."
Semua tertawa—kecuali Serana. Ia menggenggam mic ungu di tangannya erat-erat. Cahayanya tidak bersinar cerah, tapi berdetak. Seolah ikut panik.
Harmageddon mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Serana. "Mic ungu telah bangkit. Tapi itu hanya permulaan. Masih ada enam lainnya. Yang paling berbahaya telah kembali ke Aresia. Mic merah."
Sembilan pasang mata langsung memelototi MarHyuk, sang guru yang katanya bijak tapi hari ini lebih banyak diam.
"Kenapa ngeliat aku?! Aku cuma pengamat! Bukan villain!" protes MarHyuk setengah panik.
Lalu, dari celah langit, muncullah seorang wanita tua dengan rambut putih sepanjang lutut. Ia membawa tongkat yang ujungnya seperti garpu tala versi weapon skin.
"Aku Ratu Gema. Penjaga Nada Terakhir. Dan sebelum kalian panik ..., ah, sudahlah, aku sedang malas berbasa-basi!"
Ia memandang Serana lama, dengan tatapan seperti melihat catatan ujian yang hampir sempurna tapi ada satu typo.
"Kau adalah Resonansi. Suaramu bisa menyelamatkan ..., atau juga menghancurkan. Tergantung jalan mana yang kau pilih."
Serana menelan ludah. Mic ungunya tiba-tiba berdetak lebih keras. Tangannya bergetar.
"Aku takut," bisiknya.
"Takut itu perasaan yang normal dialami setiap manusia," ucap MarJuki. "Yang penting jangan takutnya pake alasan klasik kayak 'aku gapunya waktu' atau 'aku sibuk'."
****
Misi Dipecah
Portal merah terbuka di langit seperti lubang dimensi Spotify. Aresia terlihat seperti dunia yang desainnya dibuat oleh arsitek insomniac: langit hitam, kota melayang, dan musik yang terdengar seperti bisikan kemarahan.
"Serana dan MarJuki, kalian berangkat ke Aresia. Tugas kalian adalah mencari mic merah. Namun, kalian harus hati-hati. Suara di sana memekakkan telinga. Nada yang lemah bisa lenyap," perintah MarHyuk dengan nada tenang tetapi tegas.
"Aku ikut!" seru MarJayHop penuh semangat. Bahkan ia telah bersiap untuk berkemas, memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper.
"Tugasmu menjaga portal saja. Karena kamu pernah punya pengalaman menyamar jadi tukang tiket. MarViTae yang akan membantumu, sebab dia intimidating, bisa berguna untuk menghalangi penyusup yang mencoba masuk ke portal. MarYoonGa, kamu ngerti teknologi, just stay here, barangkali saja, nanti ada beberapa alat yang rusak atau terganggu, kamu bisa memperbaiki atau menjelaskan hal-hal yang tak aku pahami. Sementara MarChimmy dan MarJooni kali ini aku tugaskan untuk turun ke dunia manusia. Kalian bisa menyamar sebagai karyawan kantor dan Chimmy pasti cocok jadi HRD."
"Kok kami paling jauh?!" protes MarJooni tak terima. Ia melipat kedua tangan di dada.
"Karena kamu yang paling jago Excel dan Chimmy paling soft spoken, tentunya akan banyak orang senang bergaul dengannya."
****
Masuk ke Aresia
Di depan portal merah berputar, Serana dan MarJuki berdiri. Portal itu berbentuk lingkaran merah dengan not-not musik berputar di pinggirnya. Mirip lubang cacing, tapi penuh dengan berbagai macam playlist.
"Kalau aku berubah... tolong hentikan aku," ucap Serana.
"Kalau kamu berubah, aku juga ikut berubah. Tapi bukan jadi dark mode juga, ya."
Mereka tertawa pelan, lalu melangkah. Telinga Serana mendengar sesuatu. Sebuah lagu yang muncul dari dalam pikirannya sendiri.
Merah menyala, luka terbuka,
Suara cinta, berubah jadi senjata ....
Tangan Serana terasa perih. Entah sejak kapan, muncul luka kecil menyala merah samar di kulitnya. Ia berusaha menutupi luka itu dengan lengan baju panjangnya, agar MarJuki tak merasa khawatir berlebihan. Ketika sampai di ujung terowongan, suara lagu itu kembali terdengar.
"Aku ..., mengapa aku bisa hafal nada lagu ini? Seingatku, aku nggak pernah menyanyikannya."
"Lagu apa? Aku nggak denger apa-apa," tanya MarJuki heran, sebab sepanjang perjalanan ini, telinganya sama sekali tak mendengar melodi apa pun.
Serana menggeleng. "Nggak apa-apa. Mungkin cuma ..., deja vu."
****
Dunia Tanpa Langit
Aresia. Negeri yang menggantung tanpa langit. Tak ada cakrawala, tak ada bintang. Hanya kabut abadi yang melingkupi seluruh penjuru. Kabut itu tidak hanya menyelimuti, tapi juga meredam—meredam cahaya, meredam harapan, dan yang paling penting: meredam suara.
Kota-kota di Aresia tidak berdiri di tanah, melainkan terapung, seperti panggung dalam teater raksasa. Setiap bangunan menjulang seperti menara speaker, dan jalanan diselimuti kabel serta amplifier raksasa. Di kota ini, suara adalah segalanya. Suara bisa menjadi bahasa, bisa menjadi alat pertahanan... bahkan bisa menjadi senjata.
"Ini... kayak konser metal tapi semua penontonnya lagi patah hati," gumam MarJuki sambil mengintip dari balik jendela kapsul udara yang baru mereka tumpangi.
Suara langkah bergema dari kejauhan. Dari balik kabut, muncullah pasukan penjaga kota. Mereka mengenakan seragam perak dengan speaker di bahu, dan helm yang bergetar seperti equalizer digital. Lampu indikator suara di dada mereka berkedip-kedip seperti denyut jantung.
"Siapa kalian?" tanya pemimpin pasukan dengan suara yang disaring autotune kasar, menciptakan gema mengancam.
Serana maju satu langkah. Ia mengangkat mic ungu dari dalam jubahnya, benda langka yang tampak seperti kristal bersinar dari dimensi lain. Mic itu berdengung lembut saat ia mengaktifkannya.
"Kami datang... untuk mendengar."
Beberapa penjaga tertawa. Tertawa mereka bukan sembarangan—tertawa yang memicu getaran suara, yang membuat tanah bergemuruh.
"Tak ada yang mendengar di sini," jawab pemimpin penjaga. "Hanya yang bicara paling keras yang bisa bertahan."
*****
Panggilan Malam
Malam itu, Serana tidak bisa tidur. Suara-suara samar dari masa lalu mengganggu mimpinya. Ketika ia membuka mata, kamar dalam kapsul terasa sunyi, terlalu sunyi. Bahkan detak jantungnya pun seolah kehilangan gema.
Tanpa sadar, langkah kakinya membawanya keluar. Menyusuri lorong-lorong metalik menuju ruang utama stasiun suara, sebuah panggung yang digunakan untuk menguji frekuensi.
Di tengah panggung itu, berdiri satu benda asing: mic merah. Tidak bersinar, tidak berdengung, hanya... ada.
"Kau kembali," suara itu datang entah dari mana. Dalam keheningan, suara itu seperti berbisik langsung ke dalam batinnya.
Serana menggigit bibir. Tangannya gemetar. "Siapa aku sebenarnya?"
Suara itu menjawab, berat dan penuh gema, seperti berasal dari ribuan speaker yang rusak:
"Kau adalah gema dari dirimu yang dulu. Yang menyanyikan lagu ini... saat kau ingin semua orang diam."
Serana menggenggam mic merah. Tiba-tiba, seluruh panggung bergoyang pelan, seolah merespons kehadiran dua mic: ungu dan merah. Cahaya merah samar menjalari lantai.
****
Penyatuan dan Pengkhianatan
Pagi datang tanpa mentari, seperti biasa di Aresia. Tapi suara-suara telah berubah. Ada frekuensi baru, gema yang tak dikenal, seperti ada sesuatu yang bangkit dari tidur panjangnya.
MarJuki menyadari Serana menghilang. Ia berlari menuju panggung utama. Nafasnya berat, langkahnya tak stabil, tapi ia tahu—sesuatu terjadi malam itu.
Dan di sanalah ia melihatnya.
Serana berdiri di tengah panggung dengan mata tertutup. Kedua tangannya memegang mic merah dan ungu. Bibirnya bergerak, menyanyikan lirik yang terdengar seperti mantra.
"Diamlah dunia... diamlah...
Biarku jadi satu-satunya suara."
Mic merah melayang dari tangannya. Udara bergetar. Mic ungu bergabung di udara, dan kedua mic itu pun menyatu. Kilatan cahaya memancar, membentuk gelombang frekuensi yang membelah kabut. Warna yang muncul bukan merah, bukan ungu, tetapi magenta pekat. Warnanya seperti luka yang belum sembuh.
Dari balik cahaya muncul sosok lain. Seorang gadis. Mirip Serana. Serupa tapi tak sama.
Matanya kosong, tak memantulkan cahaya. Rambutnya menjuntai seperti kabel audio yang putus. Gaun merahnya berkilau seperti sirene. Dan senyumnya ..., senyum misterius dan mencekam yang membuat sekujur tubuh MarJuki bergidik.
"Namaku bukan Serana," ucapnya dengan suara yang terdistorsi, seperti tumpang tindih akibat banyak pita suara. "Namaku Arsha. Aku adalah gema dari masa depan yang tak pernah terjadi."
MarJuki menelan ludah. Ia mundur selangkah. "Kau ..., kembaran Serana?" tanyanya dengan suara terbata-bata.
Arsha tersenyum lebih lebar, seolah menyukai ketakutan yang ditunjukkan wajah MarJuki.
"Bukan. Aku adalah bagian yang kalian buang. Suara yang tak pernah didengar. Fragmen dari pilihan yang ditinggalkan. Dan sekarang, aku kembali agar dunia mendengar satu hal, suaraku."
Langit Aresia bergetar. Kabut yang selama ini menutupi dunia mulai retak oleh frekuensi baru. Warna-warna suara menari di udara, membentuk ledakan ultrasonik. Nada tinggi melesat seperti kembang api. Mic merah telah bangkit. Tapi bukan Serana yang memilikinya lagi.
Arsha berdiri di tengah panggung. Warna magenta mengelilinginya seperti aurora. Setiap kata yang ia ucapkan menciptakan tekanan udara. MarJuki berusaha mendekat, tapi udara di sekitarnya terlalu padat, terlalu bising.
"Serana! Lawan dia!" teriak MarJuki. Namun, Serana tak bergerak. Wajahnya kosong. Matanya berkaca-kaca.
Arsha menatapnya. "Serana tak akan bisa melawanku. Aku adalah dirinya yang paling jujur. Yang tidak ingin berbagi panggung."
Ia melangkah maju, dan dengan satu desahan, gelombang suara meluncur seperti badai. Gedung-gedung bergetar. Kabut mencerai-beraikan gema. Mikrofon-mikrofon lain mulai berderak, retak. Tak ada yang bisa menandinginya. Dan ketika semuanya menjadi terlalu sunyi untuk ditanggung, Arsha menutup mata dan mrngucapkan sebuah kalimat yang sanggup membuat semua orang beridik ngeri serta menyadari betapa berbahaya ambisi yang telah menguasai dirinya.
"Ini bukan akhir .... Ini adalah awal dari konserku."


 suciasdhan
suciasdhan




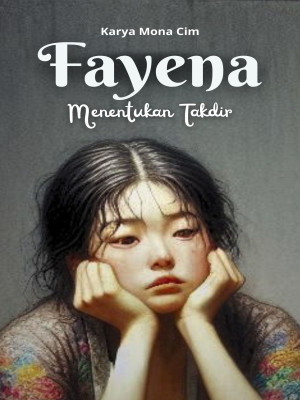





Ini juga bikin ngakak
Comment on chapter Lost