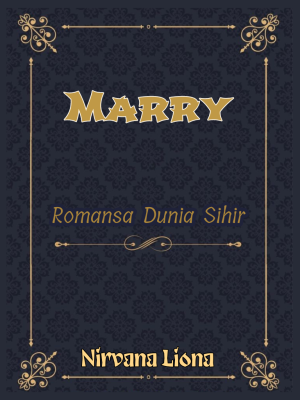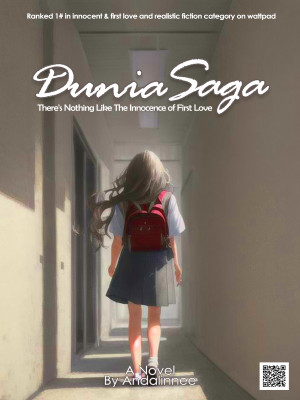Festival berjalan dengan baik. Bulan Oktober yang masih kering membuat ornamen-ornamen di taman tetap tegak sempurna. Para murid terlihat ceria, semangat sekali mencari kotak kayu tersembunyi di taman untuk mendapatkan door prize. Annika merasa bangga untuk pertama kalinya—oh, kerja kerasnya terbayar juga rupanya!
Terlebih saat Danila memberanikan diri untuk bertanya pada Aliyya saat sesi tanya jawab (pertanyaannya titipan Annika). Bu Aliyya Mossfield tersenyum mendengarnya, dan menjawab, “Di akhir ‘Poison and Peony,’ Pamela dan Pristine ‘kan sudah minta maaf dengan Lulu? Tapi rupanya masih kurang, ya?” ucapnya dengan tawa, “Sebenarnya kamu boleh mengimajinasikan sendiri. Kalau imajinasi saya, saya senang kalau mereka berteman lagi. Lulu selalu pemaaf dan si kembar punya seribu cara untuk mencairkan suasana. Tapi bagi mereka pun, prosesnya engga mudah. Mereka harus menyadari kalau mereka salah dengan percaya rumor jahat dan memaklumi kekurangan Lulu yang naif. Di mana-mana proses berteman lagi setelah bertengkar itu butuh hati yang luas dan menerima. Saya sendiri termasuk orang yang kurang percaya bahwa pertengkaran bisa membuat hubungan pertemanan semakin dekat. Iya bisa, kalau mereka sama-sama saling menerima dan memaafkan. Tapi kita semua mungkin pernah lihat atau mengalami pertemanan yang hancur karena pertengkaran, kan? Pada akhirnya, apa pun yang kita perjuangkan insya Allah akan ada hasilnya, kayak Lulu dan si kembar Fletchers.”
Ah, jadi mereka berteman lagi! Annika senang sekali. Pamela dan Pristine dengan permainan mereka yang tak ada habis-habisnya selalu membuat Lulu senang setelah kematian kedua orang tuanya. Ia bisa tidur dengan tenang sekarang. Ia memang selalu berimajinasi kalau mereka pada akhirnya akan berteman lagi, tapi mendengar dari penulisnya langsung seperti mendapatkan verifikasi centang biru!
Festival berakhir pada jam tiga sore. Evaluasi-evaluasi berkepanjangan menahan para anggota prefek dan panitia. Taman dan auditorium dirapikan kembali. Hari sudah gelap ketika mereka selesai. Kak Katya sangat tegas malam ini, melarang anak-anak kembali ke asrama sebelum semuanya selesai. Jatah makan mereka dibungkus dan dikirim oleh para ibu dapur. Tak hanya itu, untuk shalat pun mereka harus shalat berjamaah di mushala sekolah, letaknya memang lebih jauh dibandingkan ke asrama langsung dari auditorium, tapi membuatnya lebih mudah mengontrol para panitia.
Annika berjalan kembali ke asrama dengan gontai. Ia hanya ingin segera membenamkan dirinya dalam selimut dan terlelap sampai hari apa pun ia bangun sendiri. Ia bisa menulis Aqiela Ru’ya Daily besok pagi. Tubuhnya luar biasa pegal dan matanya lelah. Untungnya, Kak Katya menginfokan kalau mereka bisa langsung tidur sampai di asrama, tidak perlu mengikuti belajar malam.
Namun saat ia baru menginjak lantai teras asrama, ia teringat dengan Kiara. Harinya yang padat membuatnya belum menjenguk Kiara sejak kemarin malam. Ia pasti kesepian. Gedung utama selalu sangat sepi saat malam hari. Annika tahu karena juga pernah dirawat semalaman ke sana. Ia menggerakkan kakinya dengan ragu-ragu, lalu berbalik. Ia akan menemani Kiara sebentar, lalu ia akan kembali ke asrama. The perks of being a prefect. Ia bisa kembali ke asrama jam berapa pun tanpa diitanyai oleh Ustazah Medina.
Lampu-lampu taman menemani langkah kaki Annika menuju gedung utama. Suasana jadi cukup terang, kecuali ketika ia melewati pohon akasia tua yang menghalangi cahaya lampu. Annika mempercepat langkahnya. Ia tiba di lobby gedung utama tak lama kemudian, tak sadar bahwa setengah bulan di langit juga menemaninya.
Annika menghentikan langkahnya di depan pintu ruang UKS. Mereka sudah baikan, kan? Benar-benar baikan—berteman lagi seperti sebelumnya? Annika menyingkirkan kekhawatiran bahwa ini hanyalah harapannya sendiri saja, terlebih kemarin kalau diingat-ingat Kiara bicara dengan agak melantur khas orang sakit. Semoga saja ia sadar dengan apa yang ia bicarakan!
Ia membuka pintu perlahan, yang disambut oleh tatapan dari balik kaca mata Ustazah Aisy. “Assalamualaikum, Bu. Saya mau jenguk Kiara, boleh?”
“Malam-malam? Ah, nggak apa-apa. Masuk aja. Anaknya lagi telepon ibunya tapi.”
“Oh, ya udah, deh. Besok aja saya ke—”
“Annie, ya?” tanya Kiara dengan suara serak.
“Iya ini ada temen kamu, Annika C. Amaryllis … ya ampun, namanya susah, ya,” kata Ustazah Aisy seraya membaca badge nama di kerudung Annika dengan susah payah. “Kalau generasi kalian udah jadi ustazah, gimana coba nanti nama muridnya?”
Ustazah Aisy sendiri sebenarnya masih muda. Ia adalah mahasiswi semester lima akademi keperawatan. Namun karena sudah menapaki jenjang yang lebih tinggi dari murid-murid Aqiela Ru’ya, ia jadi merasakan betapa berbedanya zaman dirinya dengan anak-anak sekarang!
“Kiara, kamu udah baikan?” tanya Annika ketika masuk ke dalam tirai Kiara.
“Udah. Huft, tapi engga dibolehin keluar sama Ustazah Aisy,” katanya seraya berusaha duduk. Tapi ditahan oleh Annika, habisnya ia masih pucat dan dari kerutan di dahinya, sebenarnya ia masih pusing.
“Belum pulih soalnya,” kata Ustazah Aisy yang mengantarkan Annika, ia merapikan selimut Kiara. “Kalau udah sembuh total baru boleh pulang, tapi dengan catatan harus laporan makan dan tidur malam ke saya setiap hari. Kiara, kalau ada makanan yang enggak bisa kamu makan, bilang aja ke ibu dapur. Harus makan yang teratur. Tubuh kamu punya hak untuk dipenuhi gizinya.”
“Ya ampun, Us … kayaknya saya malah tambah pusing karena belum sembuh udah dibebankan tugas …” keluh Kiara setengah bercanda.
“Nanti juga terbiasa,” kata Ustazah Aisy dengan tegas. “Saya tinggal dulu, ya, Annika jangan lama-lama, nanti dicariin murabbiyah kamu.”
Kiara tersenyum pada Annika setelah Ustazah Aisy. Senyuman tulus, akhirnya. “Gimana tadi acaranya?”
“Oke,” kata Annika, sejenak membenarkan posisi duduknya di kursi. “Lumayan. Gitu, deh. Ah, aku engga tahu gimana bilangnya …” ucapnya akhirnya. Posisinya sebagai prefek kebudayaan masih amat sensitif bila menyangkut Kiara. Ia tak bisa membuat dirinya berbicara tentang perasaannya sesungguhnya dengan jujur. Apalagi perkataan-perkataan sarkasme Kiara masih menyakitinya kalau diingat.
Sinar mata Kiara makin meredup. Ia menggigit bibir dalamnya, lalu mendorong dirinya untuk berbicara, “Maaf, ya, Nik. Setelah aku berada di sini dan hanya bisa lihat langit-langit sepanjang hari, rasanya perbuatanku kemarin sangat bodoh. Ngga beralasan. Aku kayak orang jahat nggak, sih, Nik?”
“Nggak, kok. Kamu benar—perkataanmu itu … soal aku yang bersikap kayak rubah mungkin benar. Aku yang salah. Aku terlalu menjaga image-ku. Setelah aku pikirkan, rasanya aku … jauh di dalam hatiku, aku selalu ingin dilihat sebagai cewek yang anggun dan santai, tanpa perlu berusaha keras untuk mencapai sesuatu. Berusaha keras itu engga elegan. Bertanya secara langsung itu beresiko mengekspos kelemahanku. Padahal aku cuma aku. Sekarang aku sedikit ngerti, ngga mungkin selalu menyembunyikan kegagalan kita dalam mencapai sesuatu, kalau iya, aku engga akan dapat apa-apa.”
Kiara tertawa pelan sembari memeluk gulingnya lebih erat. “Kamu juga memikirkan banyak hal, ya, rupanya? Aku bahkan sampai engga paham semuanya.”
“Hum. Aku menyembunyikannya dengan baik, ya?”
“Iya. Annika, selama ini aku kira kamu hanya sekedar seru, suka baca novel detektif, dan pintar main musik. Oh, oh, bukan maksudku ‘hanya’ beneran, kamu udah amat keren. Tapi kamu lebih dari itu. Dengan jalan pikiranmu, aku engga curiga kalau kamu sebenarnya keturunan gadis istana.”
“Ssst, jangan keras-keras, Ra. Kalau kabarnya kesebar, tetangga-tetanggaku bakal tahu,” bisik Annika yang tiba-tiba memelankan suaranya. Ia tinggal di sebuah cluster sederhana di Kota Cinada bernama Cluster Middleblue. Rumah-rumah mungil yang berdekatan dengan jumlah tiga ratus unit membuat kabar menyebar dengan cepat. Gosip-gosip liar sering bertebaran di sana dan seringkali membuat Annika geleng-geleng kepala. “Oh iya, tadi kata Ustazah Aisy kamu lagi telepon bunda. Tapi engga, tuh?”
“Bunda lagi … engga tahu. Katanya sebentar lagi telepon lagi. Tadi udah sempat telepon, sih,” kata Kiara seraya mengambil ponsel yang tengah terjerat selimut di punggungnya. Annika memandangi Kiara, dan menangkap ekspresi sedih di wajahnya, seberapa kerasnya gadis itu mencoba menyembunyikannya. Ia mengerjap. Perilaku Kiara yang berubah drastis selama dua bulan mungkin berhubungan dengan keluarganya. Ia tak tahu apakah ia bisa menanyakannya, tapi malam ini bukanlah waktu yang tepat, jadi ia menyimpannya baik-baik. Mata Kiara mencerah ketika mendapat panggilan masuk. “Ah, ini bunda.”
“Kalau kamu mau telepon, aku—”
“Tunggu. Jangan pergi. Bentar aja. Bun, katanya cariin Annie,” ucap Kiara yang disusul dengan layar ponsel yang dihadapkan kepadanya. Bunda Annika terlihat di dalam layar. Kelihatannya habis shalat Isya karena masih mengenakan mukena. Senyumnya mengembang melihat Annika.
“Annika—ya ampun, ternyata kalian baik-baik aja, ya. Ah, kayaknya Kiara lagi masa puber jadi kalau Bunda tanya kamu di mana, dia jadi menggerutu. Ck ck, resiko punya anak gadis. Biasanya kamu selalu sama Kiara kemana-mana. Alhamdulillah, deh. Gimana kabar Mama?”
Annika dan Kiara berpandangan, lalu keduanya mengulum senyum. Semoga saja perang dingin yang baru mereka lalui tidak akan terulang lagi dalam sejarah persahabatan mereka.


 floricialy
floricialy