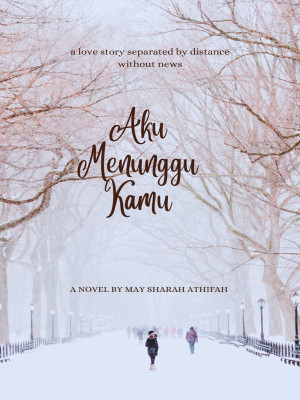Jakarta, 2022
“Seriously, Ana?” tanya rekan kerjaku yang memaksaku untuk bercerita seperti apa malam acara perpisahan yang membuatku senyum-senyum sendiri sepanjang waktu. Surat dari Randa ini memang benar-benar membawaku kembali ke masa itu. “Lo ngga ngarang, ‘kan?”
Aku menggeleng disertai tawa.
“Ya nggalah. Buat apa gue bohong?” jawabku yang sudah ikut mengantri lift yang akan membawaku turun ke lantai dasar. Jika sudah masuk jam pulang seperti ini ramainya bukan main.
“Dan suratnya sampai sekarang masih lo simpen? Semuanya? Ada berapa banyak surat atau udah berapa kali cowok lo bikin lo marah sampai bikin dia harus buat surat?”
Aku mendengkuskan tawa. “Ya ampun. Gue lagi diinterogasi atau gimana sih?”
“Eh sumpah gue tertarik banget sama cowok lo.” Spontan aku melirik tajam. “Eh, maksudnya tertarik banget sama cowok yang kayak cowok lo,” ralatnya kemudian sambil terkekeh.
Aku bersedekap. Mengamati pintu lift yang tak kunjung terbuka.
“Gue ngga pernah hitung udah berapa banyak sih, tapi surat-suratnya emang gue simpen. Soalnya kalau diinget-inget lagi dan dibaca ulang sweet juga,” jelasku tersenyum lagi. “Tapi ya, kalau bisa sih ngga perlu ada surat lagi. Kalau sampai ada surat lagi, itu artinya gue berantem lagi sama dia. Ngga mau jugalah berantem terus. Capek.”
“Iya sih. Terus hadiahnya apa?”
Dahiku mengernyit. “Hadiah apa?”
“Ih, yang di cerita lo tadi. Kalau yang berhasil tebak siapa penulis juga orang yang ada di cerita itu kan katanya dapet hadiah spesial.”
Aku merasa seperti mendapat cubitan yang begitu geli hingga membuatku tertawa.
“Dih, kok malah ketawa?”
Aku masih sibuk menutup mulutku yang nyaris terbuka lebar karena tertawa.
“Sorry, tapi itu hadiah spesial yang paling ngga banget.” Pintu lift akhirnya terbuka. Semuanya secara serentak berduyun-duyun masuk ke dalam. Semoga saja masih ada sisa ruang untuk kami berdua. “Satu kotak amplop merah jambu.”
“What?”
Aku sudah menebak seperti apa reaksinya.
“Sebagai modal kalau mereka mau nyatain perasaan atau semacamnya ke seseorang yang mau mereka tuju,” jelasku masih menggelengkan kepala heran meskipun sudah lewat sekian tahun.
“Terus, jangan bilang amplop dari cowok lo tadi ….”
“Yup. Randa emang ngga modal.”
“Astaga. Hadiah macam apa itu?”
“Gue juga ngga ngerti,” jawabku yang bahkan masih bingung sampai sekarang.
Aku jadi ingat bagaimana puasnya Dinda ketika tahu seperti apa rupa hadiah spesial yang dimaksud Danu. Beruntung dia tidak jadi repot-repot berpikir untuk menebak, sehingga tidak perlu menyesal akan hadiah 'spesial' yang dia terima.
“By the way, gue mau dong kalau masih ada cowok yang kayak gitu,” cetusnya dengan wajah menengadah menatap langit-langit. Mungkin tengah berandai-andai bagaimana rasanya mendapatkan lelaki yang seperti Randa. “Ngga tau kenapa ya, cowok ketus itu emang malah menarik, iya ngga sih? Malah bikin kita penasaran.”
“Sebenernya gue pribadi ngga pernah sama sekali berharap bisa ketemu bahkan pacaran sama cowok ketus yang lo bilang menarik itu,” balasku sambil terus menatap handphone dan mengetik sesuatu. “Tau-tau aja dia muncul di depan gue, ajak ngobrol gue, dan ambil perhatian gue lewat caranya sendiri.”
“Iya deh. Jodoh emang ngga ada yang tau.”
Aku mengangkat wajahku dari layar handphone. “Jadi intinya, sabar aja. Pasti bakal dateng kok, bahkan di waktu dan lokasi yang ngga lo duga,” kataku menepuk-nepuk bahunya. Sok menyemangati.
Kami berdua keluar dari lift usai sampai di lantai dasar. Lanjut berjalan menuju pintu utama gedung dan di sanalah aku dan rekan kerjaku ini berpisah.
“Udah sampai dia?”
“Udah nih. Di depan sana.” Tunjukku dengan gerakan dagu.
“Oke. Salam deh buat Randa. Jangan ketus-ketus dan jangan manis-manis jadi orang. Kasih tau gue juga kalau misalnya dia punya kenalan yang serupa kayak dia.”
Aku mengulum bibir. “Sorry, tapi Randa ngga mau bagi-bagi karena dia ngga mau ada Randa lainnya. Cukup satu aja,” kataku bernada sedih.
“Eh, sial. Ngga cowoknya, ngga ceweknya sama aja ngeselinnya,” gerutunya dimana aku tertawa menyebalkan. Aku akui itu. “Udah ah, gue lanjut pergi ke parkiran. Bye.”
“Bye. hati-hati.”
Detik itu juga layar handphone yang kugenggam berpendar. Lelaki yang satu ini memang tidak sabaran. Aku abaikan dulu saja, toh kami kan masih dalam momen bertengkar. Bukan berarti dia sudah mengirimkanku surat, lantas aku langsung luluh dan memaafkannya. Itu terlalu mudah.
Dan itu dia. Duduk di atas motor sport hitam kesayangannya sejak sekolah dulu. Lebih memilih menungguku di pinggir trotoar yang ada di depan gedung kantor dibanding dengan menungguku langsung di dalam. Alasannya karena di dalam gersang, sehingga dia lebih memilih menunggu di depan, di bawah pohon rindang. Membayangkan dia bicara seperti itu dengan nadanya yang khas, aku sudah lebih dulu memutar mata.
“Hei,” sapaku seraya membenarkan tatanan rambut yang beterbangan tertiup angin.
Randa menoleh. Hatiku seketika mendesah.
Tidak bisa. Aku memang tidak bisa marah padanya. Entah bagaimana cara dia melakukannya, tapi hanya dengan melihat matanya, aku sudah terbius. Terlebih saat ini, segala sesuatu yang ada di dirinya tampak jauh lebih dewasa dibanding dengan seorang Randa enam tahun lalu. Meski kenyataannya dia masih setia dengan rambut plontos andalannya, tapi aku suka. Model rambut itu memang cocok untuknya. Mungkin aku berlebihan, tapi di mataku, Randa memang semenarik itu.
Dia memberikan helm padaku.
“Sekalian makan malam? Yogi bilang dia lagi mampir ke Jakarta, jadi dia ajak aku, Eca, juga Dinda untuk makan malam bareng. Dan yang pasti aku ngga mungkin datang tanpa bawa kamu. Aku ngga mau nafsu makanku hilang karena Dinda yang pastinya bakal ceramahin aku tentang kamu.”
Aku menyipitkan mata. Bukannya menerima, tanganku justru terlipat erat di dada. Ajakan makan malam bersama yang menarik. Kebetulan sudah hampir sebulan ini aku tidak bertemu Dinda.
“Jadi itu alasannya kenapa kamu kasih aku surat? Emangnya kamu yakin dengan munculnya surat itu di atas meja kerjaku, aku langsung maafin kamu? Cara itu udah basi, Randa.”
Randa menarik kembali helmnya. “Basi, tapi tetap bisa buat kamu senyum-senyum sendiri?”
Barulah tanganku keluar dari persembunyian untuk meninju lengannya yang terbalut jaket.
“Ayolah, aku memang suka surat-surat dari kamu, tapi bukan berarti aku suka kita bertengkar terus.”
“Dalam hubungan itu ngga seru kalau flat sepanjang waktu. Lagi pula, pertengkaran kita juga ngga seberapa. Kebanyakan karena masalah ngga penting dan itu juga sumber masalahnya didominasi sama kamu.”
Mataku melebar. “Didominasi aku? Kamu serius bilang begitu?”
Randa mengedikkan bahu. Berpaling menatap jalanan yang mulai padat.
“Okay, aku pulang sendiri aja. Aku harap amplop merah jambumu itu hilang, jadi kamu kebingungan gimana caranya buat dapat maaf aku lagi.”
“Oke,” balasnya dan mataku makin mengembang. Tidak biasanya Randa kalah dengan cepat. Padahal aku tidak bermaksud membuatnya marah, karena faktanya aku memang sudah memaafkannya. Namun, serius untuk kali ini dia marah?
Randa memasang helm di kepalanya dan menyalakan motor. Suaranya menggelegar di sekitarku. Jujur aku bingung apa aku harus menahannya pergi atau tidak. Jadi yang kulakukan aku hanyalah berdiri sambil diam-diam melirik cemas.
Sebelum benar-benar pergi, Randa merogoh sesuatu dari saku bagian dalam jaket. Sigap aku memalingkan wajah sewaktu tahu dia membuka kaca helmnya,
“Ini,” ujarnya menyodorkan sebuah amplop merah jambu padaku. “Modal buat kamu minta maaf.”
Bahuku melorot. “Ish, Randa!” pekikku kesal, tapi bibirku yang sialan ini tidak bisa untuk tidak tersenyum.
Randa menyeringai di balik helmnya. “Udah, cepet naik.”
Dengan memberengut aku mengambil amplop tersebut, memakai helm yang diberikan Randa, kemudian melompat cepat ke dalam boncengannya.
Di atas motornya ini, sambil melingkarkan kedua tanganku begitu erat di tubuhnya, aku tidak berharap sekarang juga akan turun hujan—seperti di kebanyakan sinetron atau film drama romance—karena aku tidak butuh hujan untuk menggambarkan keromantisan momenku bersama Randa. Aku hanya butuh surat.
Surat-surat darinya yang berisikan rangkaian kata-kata sederhana, tapi anehnya mampu menghadirkan sensasi aneh yang membuatku tak henti-hentinya tersenyum. Memang surat-menyurat di antara kami hanya terjadi sesekali. Apalagi dengan adanya surat itu, sekaligus memberi arti kalau hubungan kami sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi aku tidak peduli. Mau seperti apa pun rasa marahku padanya, seperti apa pun rasa kesalku padanya, sebab kalau sudah cinta, aku pribadi tidak bisa berlama-lama untuk mengabaikannya.
Tidak pernah bisa.


 elhrln
elhrln