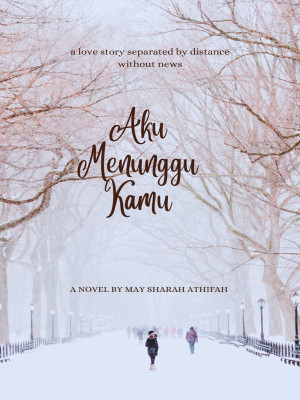“Good luck, babe,” ujar Dinda menepuk-nepuk pelan bahuku begitu dia dan Jeff memutuskan pergi bersama dengan yang lain. Berbondong-bondong masuk ke dalam vila seperti sekumpulan zombie yang tak memiliki semangat hidup lagi.
Sekilas kulihat Yogi juga Eca tersenyum seraya mengacungkan ibu jarinya ke arahku, kemudian keduanya bergabung berjalan bersama Dinda dan Jeff.
Mereka semua serius meninggalkanku di saat seperti ini?
Tapi ini memang masalahmu, Ana. Jangan bawa-bawa orang lain. Segera selesaikan, jangan biarkan menggantung terus, dan pastinya jangan terus merepotkan orang lain.
Aku menghela napas sebelum akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah pertama mendekat pada Randa, yang sialnya justru berdiam diri di dekat api unggun tanpa berniat menghampiriku lebih dulu. Harusnya dia yang mendekatiku, bukan sebaliknya. Namun, Randa adalah Randa. Jalan pikirnya memang berbeda dari yang lain dan aku sudah terbiasa dengan itu.
“Ternyata cocok juga,” cetusnya ketika jarak di antara kami tersisa kurang lebih lima langkah. Benar dengan yang dikatakan Adis sebelumnya: Randa yang sebenarnya telah kembali.
Mengerti apa yang dimaksud olehnya, bola mataku meluncur turun memandangi jaket yang kukenakan.
“Punya Yogi?” tanyaku melipat lengan di dada. Teringat perkataan Yogi yang mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin memilih jaket yang lebih tebal daripada yang kupakai sekarang.
Randa mengedikkan bahu. Kalung rantai yang tersembunyi di balik kaus oblong hitamnya berkilau seperti taburan bintang yang ada di langit. Beruntung cuaca puncak malam hari ini cerah, jadi aku berkesempatan melihat hiasan langit yang indah setelah bosan melihat langit Jakarta yang begitu-begitu saja.
“Aku ngga bawa jaket,” katanya yang cukup menimbulkan tanda tanya di kepalaku. Tubuhku pun meremang usai mendengar kata ‘aku’ yang akhirnya diucapkan oleh Randa setelah sekian lamanya kami saling membisu.
“Kita pergi ke Puncak, tapi kamu justru ngga bawa jaket?” tanyaku sedikit tertawa heran. “Semua orang tau kalau Puncak itu udah pasti dingin, Randa. Mau pagi, siang, sore, ataupun malam.”
“Ya, soalnya aku emang ngga butuh,” akunya dan aku hanya mengangkat alis. “Aku hangat, Ana. Kalau ngga percaya, sini.”
“Heh, ngaco!” semburku meninju dadanya ketika Randa membuka tangannya. Sialnya ucapannya tadi sudah lebih dulu membuatku tersipu. Sampai-sampai wajahku harus berpaling dan merapatkan bibir untuk menyimpan rasa maluku.
Mataku menangkap pergerakan tangan Randa yang terulur ke arahku. Memberikan amplop merah jambu yang berisikan secarik kertas bertuliskan tulisannya yang berhasil buatku luluh—seperti halnya yang dirasakan Adis.
Aku menggigit bibir memandangi amplop itu. Mengambilnya dengan hati-hati.
“Kamu tau kalau kamu ngga perlu repot-repot buat surat kayak gini. Aku cuma butuh kamu bilang langsung,” kataku berganti menatapnya. “Jadi kamu sengaja ngga ajak aku ngomong beberapa hari ini karena kamu udah punya rencana untuk minta maaf lewat surat ini di sini? Kamu sendiri yang buat masalah kita jadi berlarut-larut, Randa. Sementara aku terus-terusan dibuat bingung sama sikap kamu yang terus aja perhatian, padahal status kita sendiri ngga ada kejelasan setelah kita break.”
“Aku cuma mau cari waktu dan cara yang tepat supaya kamu jauh lebih percaya.”
“Percaya kalau perasaan kamu ngga main-main?” sambungku melengkapi. “Lalu setelah aku percaya, apa?”
“Mulai sekarang kita lanjut lagi?”
Ya ampun. Dia memang begitu blak-blakan.
Aku memberikan amplop ini lagi padanya. “Coba kamu sampaikan ke aku lewat tulisan aja. Kelihatannya bakal jauh lebih baik.”
Randa tersenyum tipis dan menggeleng. “Ngga lagi.”
“Oh, ayolah. Kata-kata kamu jauh lebih baik kalau lewat tulisan. Aku suka.”
“Jangan rayu-rayu begitu.”
Aku tertawa, tapi tak lama setelahnya berhenti untuk menarik napas panjang. Akhirnya aku bisa menatapnya lagi, selama yang kumau.
“Makasih, Randa,” tuturku begitu dalam. “Ini surat pertama dan terbaik yang pernah aku terima. Kamu memang selalu punya cara buat aku speechless. Jadi, kira-kira kamu rela lakuin apa lagi buat aku?” Randa melengos seraya mendesah. Pengakuan jika dia rela melakukan apa pun untukku, bak sebuah bumerang yang siap menyerangnya lagi. “Randa?” ledekku dengan mengikuti ke mana arah matanya pergi. “Kenapa juga kamu harus pakai Anastasia Steele sebagai petunjuk buat aku? Kok kamu bisa tau dia?”
Randa terus berusaha menolak bertemu dengan mataku. Beruntung dia lebih tinggi, jadi bukan hal yang sulit untuknya menghalau keberadaanku yang sudah berjinjit-jinjit di depannya.
“Aku ngga punya ide lagi untuk buat petunjuk, oke?”
“Pasti kamu nonton filmnya, iya, ‘kan?” desakku. Semakin tertebak ketika Randa justru tertawa menanggapi pertanyaanku. “Ish, dasar.”
“Hei, ayolah. Aku udah susah payah dapat maaf kamu, terus sekarang kamu jadi marah lagi?” Randa meraih satu lenganku yang masih bersedekap. Ternyata dia memang tidak bercanda. Entah bagaimana bisa, di tengah suasana malam Puncak yang super dingin ini, tangannya masih saja terasa hangat.
Diam-diam aku tengah menyerap seluruh rasa hangatnya ke dalam diriku.
“Ya, ngga lah. Aku ngga bisa atur-atur kamu ngga boleh nonton ini itu.”
Randa menggenggam tanganku semakin erat.
“So, aku benar-benar udah dapat maaf kamu?”
“Apa masih kurang jelas?” tanyaku dimana Randa mengedikkan bahu. “Udah pasti aku bakal menyesal kalau aku ngga maafin kamu. Aku mau kita baikan dan lanjutin hubungan kita. Seperti yang kamu bilang, aku ngga bisa diem-dieman begini sama kamu dan aku juga ngga bisa kalau kita putus. Bayangin kalau setelah lulus ini aku ngga bisa ketemu kamu sesering sekarang aja, aku ngga bisa.”
“Tapi faktanya kita masih akan satu kampus.”
Aku mendengkuskan tawa. “Yah, satu kampus tapi kita putus, buat apa?”
Kedua tangan Randa terjulur. Mengaitkan beberapa helai rambut di belakang telingaku. Dia memang suka begitu. Bahkan dia bisa menghabiskan waktu sekian lama hanya untuk memandangiku dan berakhir mengaitkan rambutku.
“Oke. Jangan bahas-bahas soal putus lagi,” cetusnya menggertakkan gigi.
Mataku memicing. “Kamu kedinginan, ‘kan?”
“Gimana ngga jadi dingin, kalau semua panasnya kamu ambil.”
Kali ini aku meninju lengannya. Sayangnya terlalu padat. “Resek!”
Randa melingkarkan lengannya di bahuku. Membuatku berada di dalam rangkulannya dan aku makin terasa hangat. Sungguh aku tidak bisa tidak menyukai aroma parfum yang menguar di sekelilingnya.
"Kamu masih cemburu kalau aku ngobrol berdua sama Jeff?" tanyaku hati-hati.
"Menurut kamu?"
"Okay, aku tau jawabannnya," cetusku menyudahi sendiri topik pembicaraan yang aku mulai. “Kenapa kamu ngga pernah kasih tau aku alasan kamu lebih pilih antar aku ke rumah Adis daripada antar aku langsung ke rumah?” tanyaku begitu kami berdua mulai berjalan menuju orang-orang yang sudah menghangatkan diri di dalam vila. Kulihat Eca, Yogi, Sonya, dan Dino—yang bukannya beristirahat untuk persiapan pulang esok hari—malah sedang sibuk menyiapkan barbeque grill.
Randa masih diam.
“Juga alasan kamu ada di barisan paling depan waktu upacara. Kamu tau kalau munculnya kamu di situ bisa buat aku blank sama tugas aku?”
Aku menoleh dan Randa menggaruk pelipisnya.
“Sebenarnya aku memang ngga pernah berencana buat kasih tau ke siapa pun. Surat ini benar-benar di luar rencana.”
“Apa pun tentang kamu memang di luar dugaan,” kataku mendesah pelan.
“Tapi justru itu yang buat kamu tertarik, ‘kan?”
“Dan blak-blakan, resek, judes, ketus, dingin—”
“Yakin aku dingin? Malahan aku pikir kamu udah terlalu nyaman sekarang.”
“Shut up, Randa,” kataku tak bisa untuk tidak merona.


 elhrln
elhrln