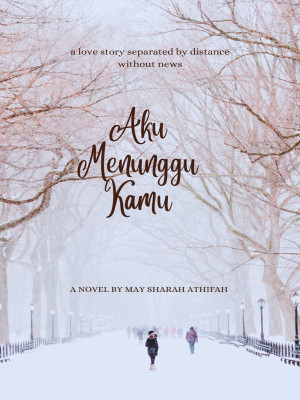Baru kali ini aku tahu jika aku bisa juga ceroboh. Seharusnya sekarang aku sudah naik angkutan umum, menikmati perjalanan pulang, dan kelabakan sendiri ketika sadar dompet tidak ada di dalam tas. Tidak ada pula sepeser pun uang di saku seragam ataupun kantung-kantung yang ada di tas. Beruntung aku menyadari bahwa dompetku tidak ada saat masih menunggu di halte.
Jadi saat ini aku sedang dalam perjalanan berlari lagi ke dalam ruang Paskibra yang sebelumnya kusinggahi.
“Shit,” umpatku pelan.
Ternyata ruangan sudah kosong. Terkunci pula. Walau begitu, melalui pintu kaca yang transparan kulihat tidak ada dompet yang tergeletak di lantai ruangan. Hingga instingku mengatakan, mungkin saja tertinggal di dalam kelas. Kalau ternyata di sana masih tidak ada juga, jelas akan jadi masalah besar untukku.
Dan hasilnya, nihil. Tidak kutemukan sama sekali dimana pun. Sampai ke sudut kelas sudah kucari, tapi tetap tidak ada. Bagaimana ini? Di dalamnya tidak hanya ada uang, melainkan juga kartu-kartu penting. Aku benar-benar menyesal.
Kakiku melangkah lemas ditambah dengan perasaan yang tidak enak. Memikirkan bagaimana caranya aku pulang, juga memikirkan bagaimana nasib dompetku yang berharga. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan hanya duduk pasrah di salah satu anak tangga sembari menyumpah pada diri sendiri mengenai betapa cerobohnya aku.
Tidak.
Tidak boleh menyerah. Mungkin cara ini bisa bekerja.
Kelasku memiliki grup Whatsapp. Kemungkinan terbesar yang terjadi adalah bisa saja salah satu temanku telah lebih dulu menemukan dan saat ini sedang dibawa bersamanya. Jadi, aku bertanya di sana dan respons pertama yang muncul, seperti biasa yaitu dari Danu. Sayangnya dia mengatakan tidak melihat apa pun. Kemudian tiga balasan lainnya dengan jawaban yang serupa. Bahkan Jonathan sempat menawarkan hal yang tidak penting apabila aku tidak bisa pulang, yaitu mengajakku agar menginap di apartemennya saja yang tidak jauh dari sekolah.
“Ha ha, lucu,” celetukku.
Eca juga sempat-sempatnya membuatku jengkel. Dia begitu semangat menawarkan diri untuk membantu mencari, tapi masalahnya dia sudah terlanjur sampai di rumah, jadi bagaimana?
“Ke laut aja,” rutukku.
Hingga akhirnya Adis membalas bahwa dialah yang menemukan dompetku.
“Thanks, God,” kataku menghela napas lega.
Rasanya itu sungguh seperti sebuah tanaman sekarat yang akhirnya dihujani berliter-liter air. Adis pikir aku sudah pulang, dia juga tidak kepikiran untuk mencariku ke ruang Paskibra. Ditambah ponselnya mati total dan Eric juga sedang tidak masuk sekolah karena sakit. Alhasil, Adis putuskan untuk membawa pulang saja dan saat sampai di rumah nanti baru dia akan memberitahuku.
Astaga, aku sungguh bersyukur. Tidak segan aku langsung memberikan emotikon cium, peluk, juga malaikat, karena Adis memang sudah seperti malaikat penolongku.
Akan tetapi, tetap saja. Bagaimana caranya aku bisa pulang? Menyewa ojek online? Masalahnya di rumah tidak ada orang dan aku juga tidak ada simpanan uang di rumah. Lantas aku membayar pakai apa? Masih adakah orang yang bisa membantuku di sini? Anak-anak ekskul basket atau futsal yang sedang latihan di lapangan, mungkin?
“Ana!”
Seseorang memanggil dari arah belakang. Yogi. Dari arahnya jalannya, kurasa dia baru saja dari toilet.
“Kok masih di sini? Tadi kayaknya gue liat lo udah mau pulang.”
Dari sekian banyak orang di sekolah yang berlalu-lalang saat jam pulang, dia masih sempat melihatku? Agak berlebihan, tapi senangnya merasa diperhatikan.
Aku menceritakan alasan mengapa aku masih di sekolah. Ternyata Yogi tidak membuka ponselnya sama sekali sejak tadi, jadi dia tidak tahu kabar terkini di Whatsapp mengenai dompetku yang hilang.
“Kalau gitu lo gue antar pulang aja.”
“Emangnya ngga ngerepotin?” tanyaku basa-basi, padahal kenyataannya sangatlah senang dan merasa sangat tertolong.
“Ya ngga lah,” jawabnya setengah tertawa. “Malahan gue senang bisa antar lo pulang. Cuma masalahnya, lo mau tunggu di sini dulu ngga? Gue mau bantu beli beberapa barang persediaan UKS yang habis. Cuma sebentar kok, kalau ngga macet.”
Kepalaku refleks mengangguk cepat. “Iya. Ngga masalah.”
“Oke, kalau gitu gue pergi dulu. Tunggu ya.”
Yogi pun langsung berlari pergi menuju parkiran dengan ekspresi riang.
Aneh. Padahal dia sudah kelas XII, tapi masih saja bersedia mengurus ekskulnya yang sebenarnya sudah diurus oleh anak kelas XI. Serupa sebenarnya dengan ekskulku dan berbeda sekali dengan ekskul olahraga. Kapan saja bisa bermain basket, futsal, ataupun lainnya, tanpa peduli sudah tingkat berapa dia. Bahkan sekarang yang terlihat sedang bermain basket di lapangan, kebanyakan adalah anak kelas XII.
Sudah tiga puluh menit berlalu. Apa Yogi serius jika tiga puluh menit itu termasuk dalam kategori sebentar? Kenapa dia belum juga datang? Apakah jalanan macet seperti yang dikatakannya? Atau mungkin terjadi sesuatu? Sebelumnya aku begitu panik dengan dompetku yang hilang dan sekarang kembali panik karena Yogi. Dia membuatku khawatir.
“Wohoo!” seru seseorang yang tak sengaja kutabrak akibat kepanikanku. “Kenapa lo hobi banget nabrak dan ketabrak orang sih?” tanya Randa membenarkan posisi tali tasnya yang melorot, juga mengambil seragamnya yang jatuh akibat tertabrak olehku. Bukannya sok tahu, tapi Randa memang suka terlihat bermain basket tanpa seragam. Dan sebagai penggantinya, dia selalu memakai kaus oblong hitam yang dihiasi dengan sebuah kalung rantai polos bergantung di lehernya.
“Maaf, Randa, gue—”
“Dompet lo bukannya udah ketemu?” sergahnya.
Aku bergeming. “Oh, ternyata lo tau,” kataku dengan suara meredup.
Randa pun ikut heran melihat tanggapanku yang terkesan heran. Setahuku Randa adalah salah satu anggota yang tidak terlalu aktif di grup. Mendapati kalau ternyata dia tahu info tentang dompetku, jadi sebenarnya selama ini dia hanya berperan sebagai silent reader.
“Terus kenapa masih di sini?”
Sedikit ragu untuk menjelaskan, tapi Randa masih menunggu untuk mendengarkan.
“Itu dia masalah barunya. Gue ngga punya uang buat pulang.”
“Ternyata hidup lo miris juga ya.”
Mendengar itu aku mendesis pelan. Randa tetaplah Randa. Terkadang ucapannya itu memang nyelekit.
“Sebenarnya tadi Yogi udah nawarin mau antar gue pulang, cuma—”
“Terus?”
Aku mendengkus. “Bisa ngga, jangan potong omongan orang kalau orang itu belum selesai ngomong?”
Randa mengedikkan bahu dan melengkungkan bibirnya ke bawah. Menyebalkan.
“Cuma udah tiga puluh menit dia ngga balik-balik dari beli barang persediaan UKS. Gue khawatir ada apa-apa sama dia.”
Randa diam sejenak. Menjadikan waktuku terbuang hanya untuk menatapnya.
“Ngga usah khawatir begitu. Tunggu aja sebentar lagi,” ucapnya dan dengan cepat aku berpaling sambil menghela napas. “Atau lo mau gue jadi pengganti Yogi?"
Jelas itu adalah tawaran yang menguntungkan! Namun, tidak tahu kenapa aku justru mematung. Memikirkan sesuatu yang sebenarnya kosong.
“Kayaknya jawabannya ngga. Oke gue pergi duluan,” cetus Randa.
“Eh, gue mau!” seruku menghentikan langkahnya.
“Susah banget kayaknya milih antara gue atau Yogi.”
“Bukan gitu. Kan gue juga ngerasa ngga enak sama dia. Lagi pula, masih khawatir juga,” jawabku sungguh-sungguh. Padahal Yogi sudah berbaik hati menawarkan, tapi aku justru meninggalkannya. Aku hanya tidak ingin di cap buruk olehnya.
“Santai. Nanti gue yang kasih tau Yogi. Dia juga bakal ngerti. Tapi gue ngga langsung bawa lo ke rumah lo ya. Gue bakal bawa lo ke rumah Adis buat ambil dompet lo,” jelasnya. Randa berkata padaku seolah dia sedang memperingatkan sesuatu kepada anak kecil.
Aku berpikir. "Emangnya rumah Adis di mana?”
“Udahlah, pokoknya gue tau. Sekarang gue mau ambil buku dulu di ruang basket, jadi lo tunggu di sini,” perintahnya. Entah kenapa perkataan itu membuatku panik.
“Jangan!” seruku saat Randa baru ingin melangkah pergi.
Lelaki ini melihatku dengan penuh tanda tanya. “Kenapa?”
Aku tidak yakin akan mengatakan ini. Randa pasti akan menertawakanku. Membuat diriku sendiri tampak bodoh di depannya.
“Soalnya tadi Yogi juga bilang begitu dan nyatanya dia ngga ke sini lagi,” jawabku menunduk rikuh. Mencoba tidak ingin melakukan kontak mata dengannya.
Walau begitu, bukan berarti telingaku tidak menangkap suara tawanya.
“Astaga ruang basket cuma di lantai dua, Ana. Lucu deh,” sembur Randa masih geleng-geleng tertawa. “Lo hitung aja sampai sepuluh, gue pasti udah di sini lagi,” lanjutnya berbalik pergi diiringi dengan tawa yang menggema di sekitar lorong tangga tengah.
Dan, aku benar menghitung dengan posisi membelakangi tangga. Tidak bermaksud bercanda, aku benar-benar menghitung. Jeda tiap hitungannya mengikuti detak jantungku. Sewaktu sudah mencapai detik ke sepuluh, kutunggu munculnya Randa. Hingga lewat detik ke sebelas, dua belas, dan di detik ke tiga belas belum juga dia muncul. Mencoba berpikir positif bahwa mungkin saja dia kesulitan mencari bukunya. Berlanjut detik ke empat belas dan ke lima belas, spontan tubuhku berbalik dan menemukannya sedang berdiri santai menyender pada tembok.
“Sampai segitunya takut gue ngga balik.”
Aku belum merespons, sementara Randa perlahan melangkah mendekat.
“Nih pakai helm. Kita ke rumah Adis,” katanya dimana aku segera mengejar langkahnya ke arah parkiran.
Setelah Randa siap, aku pun naik dalam boncengannya.
“Rumah gue di daerah Kelapa Gading, sama rumah Adis jauhan mana?” tanyaku memastikan, sebab kupikir Randa sengaja memilih membawaku ke rumah Adis lebih dulu dikarenakan jaraknya yang lebih dekat dari kawasan Salemba.
“Adis … daerah Bekasi. Ngga masalah, ‘kan?”
Dasar. Itu kan lebih jauh.


 elhrln
elhrln