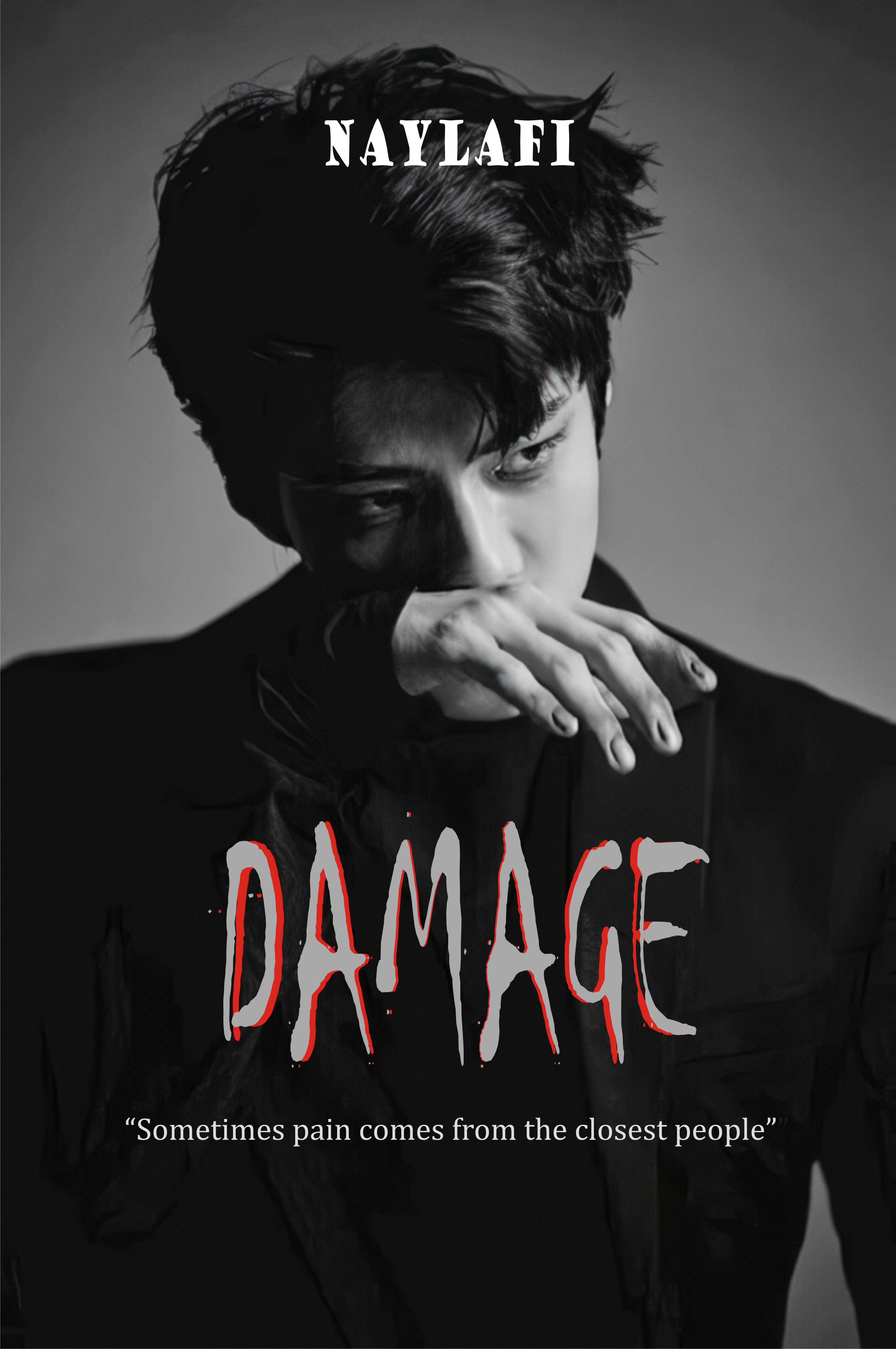Di hari kesembilan kebersamaan mereka, Tisha jadi membantu Sawala mengurus pojok baca. Saat jam istirahat mereka berbagi tugas dan Tisha kebagian mengurus yang ada di angkatannya. Awalnya dia sempat ragu bercampur takut karena harus berpapasan dengan siswa lain yang terasa memberinya pandangan aneh. Namun, Tisha berusaha mengabaikan hal itu.
Sampai saat Tisha menyusun buku di pojok kelas IPS terakhir, seorang cowok bertubuh gempal menghampirinya. “Kamu murid baru?”
Tisha sempat tertegun. Namun, dia cepat mengendalikan diri. “Bukan.”
“Kamu kelas apa?” tanya cowok itu lagi sambil memperbaiki frame kacamata kotaknya.
Tisha tak berniat membalas lagi. Dia memilih beranjak. Namun, saat memutar badan, dia melihat Sawala berdiri tak jauh darinya.
“Beres, Dek Tisha?” tanya Sawala dengan keceriaan seperti biasa.
Tisha mengangguk. Siap memangkas jarak dengan Sawala. Namun, langkahnya terhenti karena cowok tadi kembali bersuara.
“Kamu Tisha? Tisha Andira?”
Tisha menoleh. Menemukan mata cowok itu berbinar.
“Aku Fathan. Fathan Naufal. Teman SD-mu.”
Seketika Tisha berlari. Mengabaikan semuanya, termasuk Sawala yang hanya bisa melongo.
***
Kenapa dia seperti tadi? Sejak kapan dia sekolah di sini? Kenapa Tisha tidak menyadarinya selama ini?
Tisha sama sekali tidak bisa fokus mengikuti mata pelajaran terakhir. Kepalanya terlalu berisik dengan keheranan karena sosok yang baru ditemui. Fathan, orang yang paling tidak ingin Tisha temui sejak kematian orang tuanya.
Sedikit banyak Tisha menganggap Fathan sebagai penyebab dukanya. Andai dulu Fathan tidak meminta tolong padanya, mungkin hidup Tisha masih lengkap. Namun, Tisha lebih banyak menyalahkan dirinya sendiri yang mau-mau saja menolong cowok yang dulu dia anggap sahabat.
Tisha kecil memang akrab dengan siapa saja, termasuk dengan laki-laki. Fathan adalah salah satu sahabat dekatnya karena dulu mereka sama-sama suka menggambar dan membuat tulisan indah, kaligrafi. Setiap hari mereka selalu saling menempel, ke mana-mana bersama. Sampai kejadian nahas itu menghancurkan semuanya.
Tisha menolak kehadiran Fathan. Bahkan saat Fathan dan orang tuanya melayat pun Tisha bersembunyi di kamar. Sampai akhirnya Tisha berhasil membujuk Riana membawanya pindah ke kota tempat sang kakak kuliah, dan benar-benar menutup kesempatan berhubungan dengan Fathan.
Tisha baru menyetujui ajakan Riana untuk kembali tinggal di rumah lama mereka setahun lalu, setelah tanpa sengaja melihat postingan salah satu teman SD-nya yang menunjukkan Fathan menggunakan seragam SMP kota lain. Tisha pikir Fathan tidak lagi tinggal di lingkungan lamanya dan akan terus melanjutkan sekolah di kota itu, jadi dia mau kembali karena yakin tidak akan bertemu lagi.
Namun, pertemuan mereka hari ini membuyarkan segala ketenangan Tisha. Luka dan kemarahannya kembali mencuat. Tisha harus bisa memutus akses dengan Fathan lagi.
“Sialan!”
“Apa, Tisha?”
Sialnya umpatan Tisha tersuarakan cukup keras dan terdengar oleh sang guru yang hobi menjelaskan sambil berkeliling ruangan, dan kini guru itu tepat di sisi bangku Tisha yang ada di paling belakang. Tisha hanya bisa meminta maaf sambil menundukkan kepala.
“Tuliskan ayat ini di papan tulis!” Guru itu menyodorkan buku agama yang tebal.
Tisha menerimanya dengan lemas. Namun, dia cukup bersyukur. Untung dia hanya disuruh menyalin tulisan, bukan menjawab soal. Sebab, pemahamannya di mata pelajaran ini cukup parah. Nilai rapornya saja mepet KKM bahkan pas UAS pun dia sering remedial dengan membeli buku Juz Amma.
“Tolong lebih serius, ya, kalau pelajaran Ibu.” Guru itu kembali bicara sambil mendampingi Tisha di bagian depan kelas. “Ini tuh ilmu penuntun sepanjang hidup. Insyaallah kita akan mendapat ketenangan dan keselamatan jika memahami agama secara baik dan benar.”
Tisha menghentikan gerakan spidol. Benarkah? Dia juga akan tenang jika belajar agama?
***
“Maaf aku enggak bawa roti. Nanti kita makan mi ayam, yuk!” Sawala memecah keheningan yang terasa mencekam. Sejak kemarin meninggalkan Sawala di pojok baca, sampai selesai Salat Asar di hari Rabu ini, Tisha setia terdiam. Diam yang tidak seperti biasanya, tatapannya tampak sendu. Membuat Sawala khawatir.
Tisha mengerjap, lantas menggeleng. Seharian ini kepalanya memang berisik. Pertanyaan tentang cara menghindari Fathan dan penasaran akan pernyataan guru agama bergantian menggentayangi.
“Eh, kenapa? Enggak enak mi-nya? Atau enggak suka suasana pinggir jalannya?”
“Rasanya enak, kok. Tapi ....” Tisha mengeluarkan dua kotak dari tas. “Aku bawa ini.”
Sawala mengernyit. “Apa?”
“Nugget tahu.” Suara Tisha mencicit. “Kakak enggak alergi tahu, kan?”
“Enggak,” balas Sawala cepat. Merasa familiar dengan ucapan Tisha karena itu pernah diucapkannya di awal pertemuan mereka.
“Tapi kalau Kakak lebih mau mi ayam, kita makan itu aja.” Tisha akan memasukkan kotaknya lagi.
Namun, Sawala menahannya. “Aku mau itu. Mari kita makan.”
Tisha tersenyum. Senang keberaniannya membawa makanan untuk dibagi mendapat sambutan baik, padahal dia sempat takut Sawala akan menolak tingkah anehnya itu.
“Tapi jangan di sini, deh.” Sawala melihat sekitar mereka yang banyak hilir mudik orang yang sudah atau akan salat. “Kita ke kantin aja, yuk”
“Emang boleh makan yang bukan makanan dari sana?” Tisha tidak terlalu tahu bagaimana kebiasaan di sana. Dia hanya pernah ke kantin beberapa kali, saat masa pengenalan lingkungan sekolah.
“Bo ... leh.” Suara Sawala memelan. Dia menyadari kegalauan Tisha, yang mungkin tidak suka dengan ide tersebut. Sekejap kemudian dia tersenyum karena terlintas ide lain. “Kita ke tempat favoritmu aja, yuk. Belakang kelas itu. Enak kayaknya di sana.”
“Tapi mukenanya?” Tisha melirik dalam musala.
“Kuurus nanti.” Sawala bangkit dan menarik Tisha.
Semilir angin menyambut dua gadis itu. Mereka duduk bersisian di bawah pohon nan rindang, beralaskan rerumputan.
“Adem banget, ya. Pantes kamu betah di sini.” Sawala menjeda kunyahannya, melirik Tisha yang hanya menanggapinya dengan anggukan. “Terima kasih untuk makanannya. Buatanmu, kan?”
“Iya .... Hasil ngikutin resep dari buku yang Kakak kasih kemarin.” Tisha menggigit bibir. Dia tidak tahu apakah idenya ini baik atau tidak. Sebab, baru kali ini dia masak dengan mengikuti resep di buku.
Sawala berbinar. “Oh, ya? Yang makanan fungsional? Bahannya apa aja? Enak banget ini.”
“Tahu, sayuran, sosis, dicampur sama tepung,” Tisha menekan-nekan jempol tangan, berusaha mengingat, “terus ... dipanggang.”
“Eh, dipanggang? Kukira digoreng, lho, ada kriuknya gini.”
“Makanan fungsional kan buat kesehatan, menghindari minyak.” Sambil terus menjelaskan manfaat yang dia ketahui dari buku kemarin, Tisha menelan ludah. Merasa aneh dengan diri sendiri yang sepertinya sudah berbicara terlalu banyak, tetapi dia tidak kelelahan. Makin banyak Sawala bertanya, makin tertarik juga Tisha untuk bicara. Ah, kenapa Tisha jadi seperti ini?
Merasa agak serak, Tisha mengeluarkan dua botol dari tas. “Kakak mau jus?” Itu juga dia buat dengan mengikuti resep di buku.
“Eh? Terima kasih.” Dengan wajah yang linglung Sawala menerimanya. Bukannya dia tidak suka dengan sikap Tisha. Dia hanya tidak mengira jika Tisha punya sisi berbeda selain menjadi pasif.
Tisha hanya mengulas senyum tipis. Lagi-lagi kehangatan menyelusup hatinya. Ternyata seperti ini sensasi menyenangkan dari berbagi, bisa membuat lupa dari kegelisahan. Mungkinkah itu juga yang selalu Sawala rasakan?
Setelah makan mereka menuju musala. Suasananya sepi, orang-orang sudah meninggalkan sekolah.
“Uhm ....”
Gumaman Tisha membuat gerakan Sawala membuka sepatu terjeda. “Kenapa, Dek?”
“Apa ... aku boleh ikut masuk musala?”
“Boleh. Mau ngadem, ya?”
Tisha menggeleng. “Kalau boleh aku mau ikut beresin mukena.”
Sawala berkedip lambat beberapa kali. “Yang benar, Dek?”
“Benar,” balas Tisha serius.
Sawala berdeham. “Oh, boleh. Mari ke dalam!”
Di tengah kesibukan memilah-milah dan melipat kain itu Tisha memberanikan diri untuk menyuarakan penasaran yang sudah lama mengganggunya. “Beresin mukena ini kewajiban Kakak?”
Sawala yang sedang menata di lemari menghentikan gerakan sejenak, membalas tatapan Tisha, kemudian menggeleng. “Wajib itu kalau enggak dilaksanakan akan dapat hukuman, kan? Sedangkan aku kalau enggak beresin mukena enggak dapat hukuman, jadi bukan kewajiban, sih. Lebih ke sunah.”
Tisha mengernyit. “Sunah?”
Sawala mengangguk mantap. “Iya, kalau dikerjakan insyaallah akan dapat ganjaran baik, kalau ditinggalkan enggak apa-apa.”
“Terus yang wajib beresin ini siapa? Penjaga sekolah?”
“Kayaknya enggak ada yang secara khusus diwajibkan urus ini, deh. Eh, Rohis ada rutinan beresin tiap Jum’at, setelah beres kajian, tapi pekan lalu aku izin enggak ikut jadi kamu enggak lihat. Terus dua bulan sekali anggota rohis bagi-bagi bawa pulang beberapa pasang mukena buat dicuci.”
“Terus kenapa Kakak mau beresin setiap hari?”
“Karena ... aku ingin menjalankan sunah.”
Tisha tak sanggup berkata lagi.


 salwariamah
salwariamah