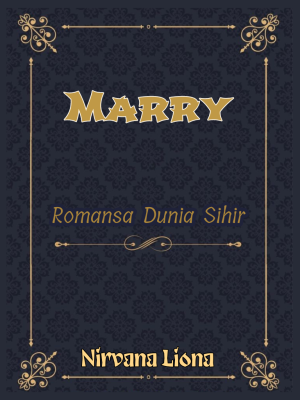“Micin habis, Sha?” Riana bertanya di tengah suapan menikmati makan malam buatan sang adik. Rasa olahan tahu yang dicecapnya kali ini berbeda dengan masakan Tisha biasanya yang senantiasa gurih.
“Hah?” Tisha mengangkat sebelah alis. “Enggak. Kita kan baru belanja bulanan kemarin.”
“Terus kenapa ini masakannya pada hambar. Enggak kamu bumbuin?”
“Aku bumbuin, kok, tapi takarannya dikurangi, sesuai petunjuk di buku Resep Makanan Fungsional. Itu tuh makanan buat kesehatan, jadi enggak boleh kebanyakan micin.”
“Heh, kesambet apa kamu? Tumben banget kamu baca buku.”
“Kemarin di perpus Kak Sawala ngasih aku buku resep. Ya udah aku coba ikuti. Tadi aku juga kasih hasilnya ke dia dan dia bilang enak.”
Riana bersiul. “Cie, udah tahu caranya makan depan dia?”
Tisha mendengkus.
Riana tertawa. “Kayaknya kalian makin akrab, ya? Waktu itu juga di perpus Teteh lihat kalian ngobrolnya akrab banget.”
Tisha mengedikkan bahu. “Biasa aja. Aku hanya mencoba menikmati hari-hari kebersamaan kami. Setelah tiga hadiahku di tangan, kami selesai.”
“Oh, iya, udah kepikiran mau minta apa aja?”
Tisha mengangguk mantap.
“Spill, dong. Biar Teteh bisa persiapan kalau-kalau memakan dana.”
Tisha diam sejenak. Keinginan utamanya adalah tentang ketenangan tanpa diusik Riana, tetapi dia sedang malas mendengar ceramah jika mengatakannya. Kemudian, dia ingat hasil perenungannya setelah mendapat pertemuan tak menyenangkan kemarin. “Aku mau minta pindah sekolah.”
“Hah?” Bola mata Riana melebar. “Kenapa? Kamu benar-benar enggak mau ketemu lagi sama Sawala? Semengganggu itu dia?”
Tisha berdecak. “Bukan karena Kak Sawala.”
“Terus kenapa?”
“Fathan. Tadi aku ketemu dia di sekolah. Jadi, aku mau pindah ke mana pun yang enggak ada dia.”
“Fathan?” Riana diam sejenak, menggali ingatan tentang nama itu. “Oh, teman SD kamu itu, ya?”
“Iya.” Tisha menyahut cepat seraya bangkit, bersiap membereskan peralatan makan. “Dia yang menjadi alasan aku membuat Bunda dan Ayah pergi.”
“Astaghfirullah, Tisha!” Riana mencekal pergelangan tangan Tisha, menyuruh kembali duduk. “Dengarkan Teteh. Enggak ada yang salah atas kepergian Bunda dan Ayah. Semua yang menimpa keluarga kita adalah takdir Allah. Bunda dan Ayah pergi karena Allah yang memanggil mereka. Enggak ada yang bisa mempercepat ataupun menghalangi takdir-Nya.”
Riana merengkuh Tisha. “Semua takdir Allah itu baik, Sha. Cuma kadang kita enggak mengetahuinya. Bisa jadi apa yang kita anggap buruk justru itu yang terbaik buat kita. Kayak kepergian Bunda dan Ayah, menurut kamu itu sesuatu yang buruk. Namun, mungkin itu cara Allah menyayangi Bunda dan Ayah. Allah ingin melindungi Bunda dan Ayah dari kefanaan dunia.”
Tisha tergugu. Tanpa sadar bulir-bulir bening meluncur dari matanya. “Tapi ... kenapa Allah enggak sekalian manggil kita? Allah enggak sayang kita?”
Riana mengusap pipi Tisha. “Allah juga pasti sayang kita. Namun, mungkin Allah punya rencana lain agar kita membantu Bunda dan Ayah.”
Tisha menghentikan isakan, tetapi tidak memberikan tanggapan. Dia masih berusaha mencerna kata-kata sang kakak. Ini memang pertama kali mereka membicarakan kepergian orang tua secara terbuka. Sebelumnya Tisha tidak pernah memiliki cukup kekuatan untuk mengusik luka yang ingin dia lupakan.
“Katanya ada tiga amal yang tidak akan putus meski seseorang sudah meninggal, yaitu sedekah jariah; ilmu yang bermanfaat; dan doa anak yang saleh. Kita enggak bisa mengutak-atik dua yang awal karena itu usaha Bunda dan Ayah selama hidup, tapi kita sangat bisa untuk memaksimalkan yang terakhir. Kita bisa berusaha sekeras mungkin untuk menjadi anak saleh dan terus mendoakan Bunda dan Ayah. Mengusahakan agar alam kubur mereka lebih terang.”
Riana beralih menggenggam tangan Tisha. “Jadi, mari bersama-sama menambah amalan untuk Bunda dan Ayah, ya.”
Tisha menyusut hidung. “Apa Teteh enggak pernah sedih karena kepergian Bunda dan Ayah? Dulu juga Teteh enggak nangis saat mereka baru meninggal.”
Riana menghela napas. “Sedihlah, Sha. Teteh juga manusia biasa. Dulu Teteh nangis, cuma enggak di depan kamu. Jujur, Teteh sempat kesal sama kamu, terutama saat tahu kronologinya gimana. Niat pulang buat liburan malah harus urus penguburan. Itu bukan pengalaman menyenangkan.”
Tisha tertegun. Dia memang tahu Riana tidak terlalu menyukainya saat orang tua mereka masih ada. Namun, dia tidak pernah mengira jika Riana menyimpan kesal padanya karena kematian itu. “Tapi kenapa Teteh enggak pernah menunjukkannya? Kenapa Teteh malah urus aku?”
“Karena Allah melembutkan hati Teteh, Sha. Saat di jalan dan dapat kabar itu hati Teteh panas, Teteh berniat nyemprot kamu. Tapi saat sampai dan lihat kamu tergugu di sisi jenazah Bunda dan Ayah, tiba-tiba hati Teteh dingin. Teteh sendiri enggak paham ke mana perginya kemarahan itu. Yang Teteh ingin saat itu hanya merengkuh kamu. Dari sana Teteh jalan setengah sadar, mengikuti bisikan, entah dari mana, untuk mengurus kamu.”
“Sampai sekarang masih enggak sadar?”
“Penginnya gitu, tapi sayangnya Teteh udah sadar.” Riana menjauh dan menyandarkan tubuh. “Tepat 40 hari dari kepergian Bunda dan Ayah, Teteh ngobrol sama mentor di komunitas keagamaan kampus. Beliau banyak ngasih insight, termasuk tentang penerimaan akan takdir dan kewajiban akan mengurus kamu. Allah, Bunda, dan Ayah mengamanahkan kamu ke Teteh sebagai ladang ibadah. Jadi, Teteh akan terus berusaha untuk menjalankan amanah itu sampai ada yang menggantikannya.”
Tisha mengernyit. “Siapa?” Tiba-tiba dia waswas. Jangan-jangan Riana berniat membuatnya diadopsi.
“Suami kamu.” Riana terkekeh renyah. Aura sendu menguap dari sekitar mereka.
Tisha memelotot. “Teteh dulu sana, buruan cari suami. Udah mau kepala tiga juga, masih aja betah jadi solo.”
Riana berdeham. “Emang kamu enggak apa-apa kalau Teteh nikah?”
“Kenapa aku harus apa-apa? Aku malah akan senang kalau Teteh nikah, karena nanti Teteh jadi punya orang lain buat diperhatikan, berarti aku bisa lebih bebas. Bakal lebih bagus kalau suami Teteh ngajak Teteh merantau, aku bisa hidup sendirian.”
Riana memukul paha Tisha. “Enggak ada, ya. Kamu sepaket sama Teteh, ke mana pun Teteh pergi kamu akan diangkut. Tapi insyaallah Teteh pastikan kita akan tetap tinggal di daerah sini setelah Teteh menikah.”
“Emang yakin calon Teteh bakal setuju?”
“Dia udah setuju.”
“Hah?”
“Coming soon.” Riana bangkit dan meninggalkan Tisha.
“Apa maksud Teteh?!”
***
Pukul tiga pagi. Lagi-lagi Tisha terbangun dari tidur yang tidak terlalu nyenyak. Tadi malam, setelah puas menangis, Tisha tidur dengan gelisah. Dia memikirkan kata-kata Riana. Sebagian hatinya ingin mengamini ucapan Riana. Namun, sisi lainnya masih merasa berat. Dia merasa masih belum siap untuk menerima semuanya.
Denting bunyi barang terjatuh membuat Tisha mengerjap. Dengan gontai dia bangkit dari ranjang dan keluar kamar. Tiba di dapur dilihatnya Riana sedang menunduk dekat lemari.
“Sahur lagi?”
Riana menoleh sambil menyengir. “Iya. Mau masakin lagi, Chef?”
Tisha berdecak, tetapi tak urung mendekati kulkas, lalu berkutat dengan bahan masakan. “Kayaknya Ramadan kemarin Teteh enggak banyak bolongnya. Udah dibayar juga kan pas Syawal? Kok masih puasa terus, sih?”
“Teteh lagi belajar puasa sunah.”
“Hah?”
“Ada yang namanya puasa Senin dan Kamis, mengikuti kebiasaan Rasulullah.”
“Manfaatnya?”
“Ya, dapat pahala.” Suara Riana menahan gemas. “Tapi bisa sambil melatih ketenangan, sih. Lagi puasa kan dilarang ambekan.”
Tisha tertegun. Kembali, dia mendengar tentang kaitan agama dan ketenangan. Apa aku juga bisa tenang jika mencoba jalan itu? Menenangkan diri dengan puasa?
“Sha, awas itu pisau kena tangan!”


 salwariamah
salwariamah