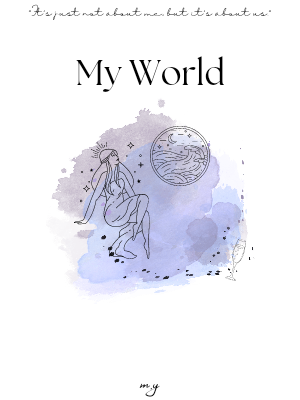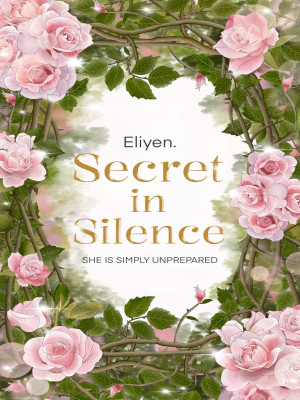“Jadi kita sudah lihat iklannya di Line dan Instagram. Terus kita mau apa?”
Ditanya begitu, aku malah memandang ke luar jendela sambil berpikir. Jantungku berdebar-debar. Akan diselenggarakan sebuah welcoming party untuk para mahasiswa pertukaran di kampusku, dan panitianya berhasil mengundang sebuah band visual kei di antara bintang tamu penyanyi internasional. Ternyata salah seorang mahasiswa pertukaran yang orang Jepang adalah anggota band visual kei, meski hanya kecil-kecilan. Tapi, wow! Sepertinya keren sekali kalau bisa menonton visual kei secara langsung.
“Kita harus dateng,” aku berbisik.
“Tapi, tiketnya mahal banget,” Dian memprotes sambil mengerutkan dahi.
“Heh? Berapa memangnya?”
Dian menyebutkan sejumlah angka.
“Hmm, padahal acaranya untuk internal aja, ‘kan?” Aku tidak menyangkal bahwa harga tiketnya tidak murah.
“Yah ... kecuali kamu punya relasi ... orang dalam, tahu maksudku? Kita nggak akan punya kesempatan.”
Dian adalah teman sekelasku dan syukurlah dia juga penyuka manga—komik Jepang—dan banyak hal berbau jejepangan. Bagaimana lagi kami bisa dekat dalam dua bulan pertama kuliah ini? Dia asli Kota Pelajar dan tiap hari pulang ke rumah, tak sepertiku yang tidak setiap hari bisa bertemu orang tua—tapi, hei, itu tak masalah. Setidaknya aku punya banyak kesempatan untuk pulang, tak seperti beberapa teman asrama yang rumahnya betul-betul jauh dan terkendala biaya sehingga hanya bisa pulang setahun sekali—atau pada beberapa kasus, malah sampai mereka tamat kuliah.
Bukannya aku dan Dian mencuri obrolan di tengah jam kuliah; ini karena dosen kami sakit mendadak dan absennya beliau menciptakan jeda yang cukup panjang antara jam kuliah pagi dan siang. Bagiku mending tetap di kampus daripada bersepeda pulang-pergi saat matahari sedang terik-teriknya!
“Dian, ini mungkin kesempatan sekali dalam seumur hidup,” aku bersikeras, tapi tetap mempertahankan nada membujuk. “Kapan lagi, sih, kita bisa nonton langsung orang Jepang manggung?”
Kulihat Dian mulai goyah, jemarinya memainkan ujung kain kerudung merah jambunya yang panjang. Matanya melirik ke kiri-kanan seraya memertimbangkan usulku.
“Masih dua bulan lagi. Kita bisa nabung mulai hari ini. Lagipula, kamu, ‘kan, nggak ngekos.”
Aku menahan diriku untuk melontarkan senjata terakhir, aku menimbang-nimbangnya lagi. Agak sensitif kalau membicarakan penghasilan keluarga. Aku tahu biaya kuliah Dian ditanggung oleh pemerintah lewat beasiswa, jadi mestinya uang sakunya bisa ditabung. Tapi lalu pikiranku meloncat: kalau Dian dapat beasiswa dari pemerintah, artinya mungkin keluarganya kurang mampu secara finansial? Kalau begitu, apakah aku salah dengan membujukinya seperti ini? Tapi aku merasa bersemangat tentang ini dan ingin Dian ikut denganku, sampai hampir tak bisa menahan diri.
Dian masih membisu sambil memandang kosong ke arah layar proyektor yang standby menunjukkan merk perangkat itu. Aku menunggu, mengantisipasi beberapa skenario dalam pikiran terhadap apa pun yang kemungkinan jadi reaksinya yang berikut. Kemudian dia menatapku dan berujar sungguh-sungguh,
“Kamu aja, deh, Ra. Aku nggak ikut. Orang tuaku bisa marah kalau tahu aku buang-buang uang. Oke, mungkin buang-buang uang bukan istilah yang tepat. Intinya aku harus setia sama kepercayaan mereka, ‘kan? Mereka kasih aku uang saku untuk mendukung kuliahku. Jadi ... kalau buat nonton visual kei?” Dia mengangkat bahu, suaranya agak bergetar di akhir kalimat.
“Ow, sori. Ya udah. Maaf ya, Dian.”
Kurutuki diriku karena kurang bijak berpikir. Dian satu-satunya temanku di kelas, dan kalau dia marah padaku, aku mau masalahnya segera dibereskan. Kalau orang tuaku tahu aku memakai uang saku untuk nonton konser, apa yang akan mereka bilang? Meskipun sebetulnya kami berkecukupan? Yah, tidak terlalu cukup, untuk membeli sebuah sepeda motor lagi untukku. Tapi toh aku puas dengan sepeda kesayanganku yang kupakai sejak masih SMP.
“Nggak, nggak apa-apa. Santai aja,” balas Dian dengan nada ringan, mengeluarkan buku catatan dari tasnya. “Lupakan dulu deh soal visual kei. Kamu mau ngajarin aku nggambar reaksi redoks? Kamu, ‘kan, jago Kimia Organik.”
Aku tersenyum kecil, merasa persahabatanku terselamatkan sekaligus harga diriku melambung. Minggu lalu saat kuis Kimia Organik, aku mendapatkan nilai tertinggi di kelas, dan dengan itu dihadiahi sebuah pin berbentuk kincir angin dari Belanda berhubung dosen yang bersangkutan baru saja diundang dalam pertemuan ilmiah di sana.
Ujian tengah semester sudah mendekat dan kami harus belajar keras. Ternyata aku sudah jadi mahasiswa selama setengah semester.
“Oh iya, kamu sudah punya master lengkapnya Kimia Dasar?” Dian bertanya. “Aku baru dapat sampai praktikum kelima, dan itu artinya cuma sampai minggu depan.”
“Punya dong,” jawabku tanpa mem-filter nada bangga yang memang susah dibendung. “Minggu lalu waktu wawancara BEM, aku sekalian minta ke kakak tingkat.” Badan Eksekutif Mahasiswa fakultasku memang termasuk organisasi kampus yang paling awal membuka rekrutmen.
Sepasang mata Dian berbinar. “Aku mau fotokopi, dong.”
Aku mengangguk. “Boleh. Besok aku bawain. Nanti malam ingetin aku, ya.”
“Trims, Ra. Kamu memang penyelamatku.” Dian mengembuskan napas lega. Sepertinya dia sangat kesulitan menyusun laporan praktikum yang harus ditulis tangan itu. Yang kami maksud master adalah laporan praktikum buatan kakak tingkat dan sudah dinilai serta dikoreksi. Gaman adiluhung di medan perang kuliah-praktikum yang bertubi-tubi.
“Eits, jangan serta-merta disalin, lho. Master cuma panduan, bukan buat jiplakan.”
Dian hanya tersenyum kecut. “Yah, pelan-pelan, deh. Ayo, reaksi redoksnya dulu.”
Aku memutar bola mata dan meraih kertas. “Oke. Contohnya mana nih?”
Kadang aku gemas dengan orang-orang seperti Dian. Di satu sisi, mereka begitu mengagungkan amanah dan kepercayaan orang tua; tapi di sisi lain, mereka membenarkan hal sontek-menyontek seperti dalam kasus laporan praktikum yang kami bicarakan barusan. Perkaranya bukan pada berat-ringannya tugas yang disalin. Membuat laporan praktikum memang menyusahkan, padahal praktikumnya sendiri sudah susah, apalagi laporannya harus ditulis tangan dan disertai kajian pustaka. Jadi selain menulis apa yang dilakukan saat praktikum, kami juga harus membaca dasar-dasar teorinya dulu untuk bisa menganalisis data. Memang logikanya demikian, bukan? Mana bisa orang menyusun kesimpulan kalau tidak ada hipotesis, dan bagaimana bisa ada hipotesis kalau tidak terlebih dahulu membaca teori yang ada?
Dengan jadwal kuliah dan praktikum yang padat, kami harus lembur sampai malam kalau mau semuanya selesai dengan memuaskan. Dan itu yang terjadi padaku hampir tiap malam. Untungnya aku belum pernah ‘didatangi’ tengah malam seperti Kak Vira.
“Nggak persis disalin, kok. Cuma, kalimatnya diubah sedikit. Apa itu namanya, parafrase?” Dian pernah bilang begitu waktu aku tahu teman-teman juga melakukannya.
Melihat kenyataan bahwa semudah itu bagi orang lain membuat laporan praktikum sementara aku sendiri berjuang sambil terkantuk-kantuk, hatiku jadi sakit. Seolah karena mayoritas orang melakukannya, maka hal itu menjadi benar.
Yang berbeda sendiri malah jadi kelihatan salah. Kadang dunia ini begitu lucu.
*
Kristin sedang di ruang makan—yang beralih fungsi jadi ruang belajar di luar jam makan—ketika aku pulang ke asrama.
“Halo, Tin,” sapaku. “Kamu lagi ngapain?” Aku memandangi laptop yang terpajang di depannya. Jemari Kristin sibuk menari di atas tuts.
“Lagi nyelesaiin makalah,” dia menjawab, memindahkan pandangannya yang serius dari layar laptop kepadaku untuk sedetik saja. “Sori Ra, Udah kepepet deadline nih aku ...,” dia berkomat-kamit sebentar, melirik ke sebelah kanan bawah dari layarnya, “... oh, no. Aku kehabisan waktu. Habis ini aku harus langsung ke kampus.”
“Oke. Sori kalau ganggu. Semangat buat makalahnya! Aku ke kamar, ya.”
“Oh, nggak apa-apa, kok. Makasih, ya. Dan, aku pikir kamu pasti mau banget ketemu buddy-ku. Dia orang Jepang dan umurnya sebaya kita.”
“Hah?”
Aku nyaris melompat kegirangan, tapi itu sangat bukan Ashira sekali. Kristin adalah anggota Buddy Club kampus yang mendampingi para mahasiswa pertukaran itu dan aku tahu setiap anggota ditugaskan bagi satu mahasiswa asing, tapi Kristin belum pernah bilang siapa mahasiswa yang menjadi buddy atau temannya. Aku bahkan lupa kalau itu artinya Kristin bisa dibilang termasuk ‘orang dalam’ yang Dian bicarakan tadi, soal welcoming party yang akan datang.
“Wow! Beneran? Dia yang anggota band visual kei itu? Aku bisa ketemu dia?”
“Nanti aku ceritain, deh,” Kristin melambaikan tangan untuk mengusirku sambil nyengir. “Deadline, deadline.”
“Oke. Nanti malem aku ke kamarmu, ya!” ujarku sambil menggerak-gerakkan jari dengan mengancam, tapi juga sambil menyeringai, karena kalau Kristin sampai terlalu larut pulang ke asrama, aku akan menggelitiki tengkuknya—dan dia sangat tak tahan kegelian kalau dibegitukan.
Aku sudah akan melangkah ke kamarku ketika aku melihat sekelebat bayangan di pojok ruangan. Seorang wanita ... wanita bersayap, sayapnya transparan tapi lebar seperti kupu-kupu raksasa dan dia memegang segumpal bulu hitam di tangannya. Kuraih tangan Kristin yang sedang mengetik dengan jantung serasa melompat.
“Hei, Tin ... kamu lihat orang itu? Perempuan itu, yang di sebelah sana?” Aku membungkuk, mendekatkan mulutku ke telinga Kristin. Kurendahkan suara sambil tetap menatap ke pojok, takut apa yang kulihat bakal lenyap kalau aku tidak mengawasinya.
Kristin ikut menatap ke pojok dan, yang mengagetkan, dia mengangguk.
“Apa itu hantu? Kenapa bisa muncul di siang hari?” tanyaku.
“Itu bukan hantu.”
Nada suara Kristin yang tenang membuatku menoleh sambil mengerutkan dahi; aku bahkan tak sadar suaranya mengindikasikan bahwa dia lebih tahu dariku, sesuatu yang biasanya tak kusukai.
“Hah?” Aku terlalu terperangah untuk merasa sebal. Kulihat lagi wanita di pojok ruangan itu, yang tersenyum sekilas, lalu lenyap saat aku berkedip.
Kristin meneruskan, “Itu bukan hantu, Ra. Itu Fidelia.”
*
Aku berjalan cepat-cepat, mengekor di belakang Kristin yang mendahuluiku karena dia bilang sedang dikejar oleh waktu, padahal waktu tidak punya kaki. Tubuh Kristin agak lebih berisi dibandingkan aku, tapi jelas dia pelari yang lebih baik—katanya dia pernah jadi atlet maraton waktu sekolah.
Kami sedang di kampus, tepatnya di Jurusan Hubungan Internasional—kampusnya Kristin, dan dia sedang menuju kantor dosennya untuk mengumpulkan makalahnya yang selesai nyaris di garismati.
Kulirik jam tanganku; jam empat sore kurang tiga menit. Kristin sudah sampai di depan kantor dosennya. Sementara dia mengetuk pintu, aku mencari-cari kursi dan menemukan sebuah, terbuat dari stainless di dekat pilar. Kristin sudah masuk dan aku sedang ancang-ancang untuk duduk, ketika aku melihat seorang pria bertubuh pendek yang memakai kilt—pakaian tradisional Skotlandia yang pernah kutonton di film-film—sedang melintas di koridor seberang. Pria itu membawa sebuah terompet besar berbentuk melingkar—aku cukup yakin namanya horn, dari anime-anime musik—dan gerak-geriknya saat berjalan lucu sekali karena dia tampak keberatan muatan. Tapi dari raut mukanya tampak bahwa ia seperti sedang menggerutu dan aku mengurungkan niat untuk coba menyapanya atau bahkan menolongnya membawa instrumen itu. Lagipula bahasa Inggrisku untuk dialek Skotlandia tak begitu bagus.
Barangkali pria itu juga salah satu mahasiswa pertukaran yang juga ikut serta dalam chamber orchestra. Aku jadi bertanya-tanya dalam hati, sesungguhnya ada berapa, sih, mahasiswa pertukaran?
Pertanyaan yang untuk sementara tak terjawab itu tergantikan dengan keingintahuanku membacai majalah dinding di depan kursiku. Dibuka kursus bahasa Prancis di Lembaga Bahasa Kampus—aku pernah belajar sedikit saat SMA. Bahasa yang satu itu punya lafal yang berbeda jauh dari cara penulisannya, yang menurutku sendiri kedengarannya seperti orang sedang pilek, tapi orang-orang sedunia menganggap bahasa Prancis adalah bahasa yang romantis. Kemudian ada beberapa pengumuman beasiswa pertukaran ke Eropa. Kubacai sekilas persyaratan yang ada dan menemukan bahwa tak ada yang spesifik untuk bidang studiku. Ada yang menerima mahasiswa semua program studi, ada juga yang mensyaratkan jurusan ilmu budaya atau seperti penyelenggara mading yang dimaksud, hubungan internasional.
Aku sendiri punya impian untuk pergi ke London, Britania Raya, dalam rangka kuliah. Jadi kalau aku mencari program-program seperti itu, otomatis aku memasang syarat sendiri: harus tentang penelitian di bidang farmasi. Yang membuatku sangat sulit untuk mendapatkan yang kumau. Tapi, dengar-dengar, di fakultasku sendiri ada program exchange bagi mahasiswa tingkat tiga atau empat. Tinggal menunggu waktu saja.
Ngomong-ngomong soal menunggu waktu, menurutku Kristin agak terlalu lama di dalam kantor dosennya. Aku jadi khawatir, jangan-jangan makalahnya dikumpulkan terlambat dan dia sedang kena teguran. Tapi, waktu akhirnya dia keluar, Kristin tampak sangat puas.
Aku berdiri mendekatinya. “Gimana??”
“Dosenku suka sama tulisanku,” ujar Kristin, menggiringku ke arah teras yang sepi. “Beliau mau aku masuk timnya untuk penelitian yang berikut. Katanya analisisku sangat komprehensif.”
“Wow, keren!” ujarku sambil tersenyum tulus. “Kamu memang rajin, sih, Tin.”
“Tapi bakalan susah, sih. Soalnya aku belum pernah terlibat di penelitian ilmiah,” Kristin mengusap-usap belakang kepalanya sambil merendah.
“Kamu pasti bisa, Tin,” sahutku memberi semangat. Sebagai tambahan, kutepuk bahunya. Dipercaya dosen dalam jurusan yang tadinya tidak terlalu diminatinya pasti sangat membanggakan untuk Kristin.
“Makasih ya, Ra. Oiya, ngomong-ngomong, aku sudah janji.”
Aku memandanginya. “Ya ... kamu mau cerita di sini? Nggak di asrama aja?”
“Nggak. Lebih baik cerita di sini.”
Aku tak paham apa maksudnya dengan ‘lebih baik cerita di sini’, tapi kami memang sedang berada di bagian yang tampaknya paling sepi dari kampus jurusan Hubungan Internasional. Dari tadi tak ada orang lain lewat di situ.
Kristin memulai dengan serius, “Aku tadi bilang, itu bukan hantu. Perempuan itu. Dia bukan hantu.”
“Ya.” Aku menatap Kristin balik. “Kalau bukan hantu, terus apa?”
Kristin tampak berpikir sejenak. “Aku juga nggak bisa mendefinisikannya.”
“Tapi kamu juga sempat lihat dia, terus perempuan itu menghilang, iya, ‘kan?”
Anggukan sebagai jawaban. “Tapi bukan hantu. Dia hanya ... ada.”
Aku mulai agak tak sabar. “Tadi kamu bilang namanya ... ‘Fidelity’? Bahasa Inggrisnya ‘kesetiaan’?”
“Fidelia,” Kristin mengoreksiku. “Dan ini rahasia di antara kita berdua saja, ya, Ra.”
Aku mengernyit tapi mengangguk, menunggu kelanjutan penjelasan Kristin.
“Kapan pun seseorang mencoba nyuri sesuatu, Fidelia akan muncul.”
Mataku melebar dalam keterkejutan, tapi Kristin tidak berhenti di situ.
“Dan aku lega sekarang, akhirnya aku bisa cerita pada seseorang.”


 roux_marlet
roux_marlet