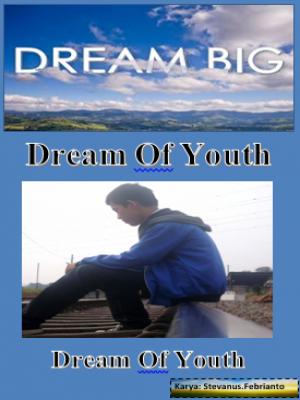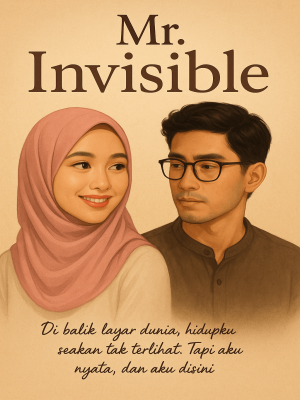Resah dan tak nyaman akhir – akhir ini sering menyambangi hati. Perasaan tak tenang yang entah dari mana datang dan penyebabnya tersebut, terus terang membuat jam tidurku kembali berantakan. Jika dipikirkan lebih cermat, hal ini terjadi semenjak Fida menanyakan pendapatku mengenai sosok ketua umum penerus Farzan.
Perasaan tak enak tersebut semakin membuat pening ketika serbuan lanjut dua periode berdatangan tanpa henti. Seolah tak lelah memborbardir via online, kedatangan Nadila ke kost membuatku menelan ludah gusar. Nadila memang orang yang enak diajak berdiskusi tentang semangat dan gejolak hati, namun jika sudah membahas dua periode, terus terang ini tidak menyenangkan. Track record Nadila sebagai wakil ketua divisi kaderisasi dan posisi litbang saat ini pastilah membuat dirinya mendapat amanah untuk mendekati kader dan membujuk untuk lanjut.
"Masa, kamu nggak lanjut, sih, Rin?"
Aku tersenyum tipis menghadapi raut berharap Nadila.
"Bukan gitu, Mbak. Jujur, aku masih nggak tahu, masih bimbang," ungkapku.
Wajah Nadila berubah pias mendengar jawabanku. Sangat jelas bahwa jawaban yang Nadila harap didapatkan adalah kemantapan keputusan lanjutku. Akan tetapi, terus terang, niat melanjutkan dua periode telah menurun drastis setelah mengetahui fakta bahwa Narendra mencukupkan diri di periode ini. Sejujurnya, aku tidak cukup percaya penerus ketua umum selain Narendra dan hal tersebutlah yang membuatku kembali berpikir ulang.
"Adek, tolong jangan kaya Kakak Besar yang lanjut tiga periode cuma karena seseorang," tegur Nadila yang tampaknya curiga bahwa kebimbanganku ada sangkut pautnya dengan Narendra.
Selama mengikuti organisasi sejak sekolah menengah, satu hal paling membekas di benakku adalah untuk tidak sekalipun memilih suatu organisasi karena seseorang. Semua alasan haruslah murni dari diri sendiri. Suatu pernyataan yang kuyakini dengan penuh selama bertahun – tahun dan tidak sedikitpun goyah bahkan terbantah. Suatu prinsip yang tentu masih kuyakini dan menjadi pedoman kala memutuskan organisasi mahasiswa mana yang kupilih di kuliah.
Akan tetapi, prinsip selama bertahun – tahun tersebut ternyata goyah ketika aku berada di rohis kampus. Dengan orang – orang rohis yang memang lembut dan kelewat toleransi sabarnya, prinsipku digerus dengan begitu lembut. Begitu tersadar, ternyata keyakinanku telah berubah.
"Kakak Besar," panggilku lembut, "menurutku, ya, nggak masalah lanjut nggaknya seseorang karena seseorang juga. Nantinya pun, aku bakal gerak bareng orang – orang itu, kan? Lha, kalau aku aja nggak percaya, nggak yakin, gimana aku mau membersamai temen – temenku?"
"Gimana rohis nanti, Dek?"
"Mbakku, menghadapi anak – anak yang sekarang dengan permasalahan yang ternyata sekompleks itu, ada campur tangan vmj juga, jujur rasanya sakit. Emang egois, tapi jika pun nanti aku mutusin lanjut, ya, itu nggak lebih buat ADK," tuturku masih dengan nada lembut seperti sebelumnya.
Namun, sorot tak rela di mata Nadila sungguh tidak dapat disembunyikan. Rasanya perih, namun terkadang aku juga ingin memikirkan diriku lebih dahulu sebelum mendahulukan organisasi seperti yang selama ini selalu kulakukan.
"Kakak Besar," panggilku membuat Nadila kembali mendongak, "lanjutku itu, ya … buat Airra, sayap kananku. Juga buat ADK sama tujuan – tujuan yang cuma bisa aku raih kalau sayap kiriku turut serta."
.
.
.
Mengesampingkan dua periode dan laporan pertanggungjawaban kegiatan MR yang bahkan belum tuntas, proker selanjutnya sudah masuk lebih dari setengah persiapan. Sebagai program kerja terbesar rohis, Campus Islamic Week ternyata juga menyita banyak daya dan waktu. Memang tidak sebanyak MR, namun di proker ini keotoriteran Farzan yang semakin menjadi membuat kian pening. Perpecahan internal rohis pun sebagai bukti seberapa parah dampak dari kekeraskepalaan Farzan yang bentrok dengan Fatih selaku Ketua Divisi Syiar dan Galih yang merupakan ketuplaknya, tidak terhindarkan.
"Persis kayak yang aku bilang, CIW kita laksanain di Ruang Serba Guna," kata Farzan tegas.
Atmosfer syura' seketika berubah tak nyaman. Bukan hanya suasana, raut wajah tak ramah pun juga sudah menyambangi seluruh panitia yang hadir. Tak ada kata tersampaikan, namun setidaknya kurang lebih ada satu suara yang sama – sama tersimpan dalam benak. Dari seluruhnya, udara di sekitar Galih dan anak – anak syiar adalah yang paling tidak bisa berbohong.
"Tapi, RSG tuh pojok banget, nggak, sih? Orang bakal susah nemuinnya, apalagi malem."
Kalimat keberatan dari Luna setidaknya cukup mewakili keresahan dalam hati. Sebab dipikirkan dengan baik, posisi RSG sangat jauh dari gerbang utama di direktorat. Sangat berbanding terbalik dengan masjid kampus yang tepat di sisi jalan raya, sehingga mudah ditemukan. Pelaksanaan kegiatan di malam hari sementara esoknya merupakan Hari Senin, juga turut menurunkan peluang kehadiran peserta.
"Tapi, dengan pembicara sekelas beliau, menurutku tetep bakal banyak yang datang, sih," ujar Fatih.
Di luar dugaan karena tak ada yang menduga bahwa kali ini Fatih justru langsung setuju dengan pendapat Farzan. Raut pias tak dapat disembunyikan kala melihat ekspresi sama tegasnya di wajah pemuda itu. Pikiran bahwa Fatih akan turut menyuarakan tempat pelaksanaan di masjid, nyatanya terpatahkan di depan muka. Dan raut tak habis pikir Luna serta Azizah sungguh tidak tertahankan.
.
.
.
"Rin, birokrasi RSG beda sama Masjid Daarul Muhtadin, ya?"
Pertanyaan tiba – tiba Galih terus terang membuat heran. Sebenarnya, pertanyaan tersebut lumrah mengingat bahwa kedua tempat tersebut termasuk calon tempat dilaksanakannya CIW, namun mendapati Galih bertanya di jam selarut ini rasanya agak ganjil. Pun selama hampir setahun berada di organisasi yang sama, tidak sekalipun Galih menanyakan hal seperti ini padaku.
"Sebenarnya, alur birokrasi semua tempat di kampus, tuh, kurang lebih sama. Bedanya cuma di helper aja, Lih. Emang kenapa?"
Tak ada jawaban berarti dari pemuda tersebut, namun intuisi justru berbisik sebaliknya. Kecurigaan yang membuat hati tak tenang hingga pikiran tak henti menduga. Pada nyatanya, waktu adalah jawaban terbaik. Waktu menyatakan semuanya secara terus terang tanpa menyembunyikan apapun. Kabar angin yang tak tahu bertiup dari mana telah tiba hingga ke rungu.
Keteguhan Galih untuk tidak melepas tempat pelaksanaan pertama rupanya satu linier dengan egoku. Mungkin, kesal dan kecewa atas sikap Farzan semenjak kegiatan terakhir masih tersisa dalam diri. Bahkan, kusadari dengan penuh bahwa emosi negatif tersebut kini telah berkembang. Ingatan akan raut Narendra yang tidak mendapat otoritas penuh dan terluka, secara tak langsung membuat diri memutuskan untuk berada di pihak Galih.
Tidak lagi ada sosok ketua yang kubiarkan memenuhi egoisme ketua yang lain. Karena pada akhirnya, egoisme ini hanya akan saling bertumbuk dan membuat diri semakin berantakan. Apakah salah jikalau aku berharap rohis tempatku sekarang tetap utuh dan baik – baik saja? Setidaknya, tempatku bertemu sosok sayap dan pembelajaran terbaik ini, akan harmonis hingga waktuku habis.
"Jadi, gitu plus – minus antara running dulu atau mediasi dulu. Tapi," aku sengaja memberi jeda sedikit lebih lama sebelum melanjutkan, "yang manapun keputusanmu, aku tetap bakal di pihakmu buat tetap ngusahain masjid."
Tidak banyak hal yang bisa diberikan sebagai bantuan selain dukungan seperti ini menurutku. Jika melihat kondisi ADK sekarang pun, dapat disimpulkan bahwa seluruhnya telah berada di pihak Galih. Mayoritas suara panitia juga demikian, sehingga hanya Fatih yang paling jelas tetap berada di pihak Farzan. Suatu hal yang mengerikan karena perbedaan keputusan ini sungguh membuat internal rohis yang sudah berantakan semenjak MR menjadi makin buruk.
Akan tetapi, seolah tidak cukup dengan ketidakakuran ini, pesan yang datang dari Galih membuat jantungku berdebar tidak karuan. Pesan yang telah terbaca dari bar notifikasi, tak berani kubuka. Pikiran burukku justru menduga Galih adalah si pengirim mengingat pertanyaan bombardirku mengenai jadwal kegiatannya jikalau bertumbuk dengan CIW hingga beberapa saat lalu.
"Kalau aku bilang nggak, ya, enggak."
Rasa sesak dalam dada menyentakku mendapati pesan di bar notifikasi. Perasaan tak nyaman beserta pikiran buruk telah menyingggung perasaan Galih membuat diri refleks menggigit bibir bagian dalam. Apakah kali ini aku melukai perasaan kader lagi seperti yang pernah kulakukan dulu kala masih di rohis sekolah? Suatu ketidaksengajaan dan kesalahpahaman hingga mengakibatkan seseorang tersebut mengundurkan diri.
"Dahlah, ketuamu udah bilang gitu, Rin."
Ternyata pesan sebelumnya merupakan pesan diteruskan dari Farzan. Pada momen itulah, kedua mata terasa sangat panas dan air mataku nyaris meleleh. Tidak mengira bahwa Farzan akan secara terus terang menyatakan keengganannya dengan kalimat sekasar itu. Tidak tahu bagaimana perasaan Galih sekarang, namun tentu rasa sakit pasti mengusiknya.
.
.
.
"Ra, bisa – bisanya Mas Farzan bilang gini ke Galih!" seruku kesal.
Airra menggulir riwayat chatting – ku dengan Galih hingga ketika tiba di pesan yang kumaksud, wajahnya berubah keruh. Ketika Airra mendongak, matanya telah menyorot tajam dengan alis saling mendekat. Helaan napas kasar ketika menyerahkan ponsel padaku telah menunjukkan apa yang memenuhi dadanya sekarang.
"Heh, semena – mena banget jadi orang! Kayak gini siapa yang mau ada di pihaknya? Nggak cukup kemarin MR berantakan, sekarang mau bikin CIW kayak gitu juga?! Otoriter banget astaga!" cerocos Airra hingga wajahnya memerah.
Keresahan yang sama, amarah yang menggebu, dan kecewa yang membeludak tanpa sadar justru membuat air mataku tiba – tiba mengalir. Kekesalan tak tertahankan ini sungguh membuat hasrat berteriak membuncah. Namun, ketika bersitatap dengan Airra yang keluar justru tawa. Bukan tawa menyenangkan, justru tawa menyakitkan karena air mata turut mengucur membersamai tawa.
Seperti dua orang gila yang sedang berbagi resah. Seolah ruangan ini adalah teritori terlarang bagi orang luar, menjajah tanpa bersedia mengalah menjadi saksi bisu untuk dua orang perempuan yang semangat dan harapannya telah dikacaukan oleh orang yang dilihat sebagai kakak sendiri. Mungkin, terlalu banyak hati dan atensi yang diberikan, oleh karena itu ketika tempat yang menjadi segalanya berubah berantakan tak sesuai di awal, baik aku maupun Airra jadi seperti ini.
.
.
.
Sungguh, aku menyadari bahwa saat ini diriku sedang tidak baik – baik saja. Berada di keramaian memang membuat daya baterai sosialku terkuras lebih cepat. Ditambah ketidakhadiran Airra di sisiku membuat bingung bagaimana berbagi emosi dan pikiran, sehingga pikiran lebih sering melalang buana alih – alih fokus pada syura' CIW yang seharusnya mendapatkan atensi penuh. Di tengah rasa penuh itu, ekspresi lesu Narendra justru mengundang.
Kamu sakit?
Jawaban yang kuperoleh berupa chat tidak membuat lega. Sebaliknya, justru membuat kian tak tenang sebab dilihat dari sudut manapun Narendra sungguh tidak baik – baik saja. Menengadah dari layar ponsel berlanjut sekilas pandang membuatku menemukannya.
"Cuma agak nggak enak badan, Rin."
Sudah kuduga. Memangnya siapa yang akan percaya dengan jawaban baik – baik saja jikalau sorot mata beserta ekspresi menunjukkan sebaliknya?
"Rin, kenapa ketua National Campus Social Project nggak kamu atau Airra aja?"
Di tengah perasaan tidak nyaman tersebut, suara Aisya yang tiba – tiba berbisik di luar topik justru membuat jengkel. Aku menyampaikan sumpah serapah dalam hati, kemudian menghela napas kasar. Bibirku tersenyum masam di balik masker, namun berusaha menjaga nada bicara setenang mungkin.
"Nggaklah, Mbak. Mending yang lain dulu. Galih juga udah oke, kok, jadi ketua," jawabku tak kalah lirih.
"Tapi, kamu sama Airra udah ada pengalaman NCSP kemarin," ucap Aisya seolah tidak setuju dengan keputusan Tim NCSP saat ini.
Sungguh, Aisya dan Farzan memang memiliki sisi egois beserta ditaktor yang sama. Pikirku dan Airra adalah memberikan kesempatan posisi ketua pada orang yang paling potensial dan memungkinkan. Menilai bagaimana Galih mengonsep CIW sejauh ini dan inisiatif mengusulkan diri, rasanya cukup masuk akal jika seluruh tim menyetujui hal tersebut. Lagipula, walaupun Aisya menjadi ketua tim lolos pendanaan tahun kemarin, dia tidak berhak menginterupsi otoritas tim karena situasi saat ini dirinya bukan bagian tim pengusul.
"Rin," aku yang baru saja kembali dari masjid usai syura' berakhir, berhenti dan berbalik, mendapati Galih duduk bersama Narendra di tangga masjid, "Narendra mau ngomongin social project."
Mataku yang semula menatap Galih karena dia yang memanggilku, beralih pada Narendra. Momen ketika bersitatap rasanya menjadi aneh. Aku merasa canggung.
"Eh, nggak, Rin, enggak. Galih yang mau ngomong," kilah Narendra membuatku mengernyit.
Galih menunjukkan gestur berkilah, "nggak, Rin. Narendra yang sebenarnya dari tadi mau ngomong."
"Ha, apa, sih? Nggak paham aku, kalian nggak jelas, beneran," pungkasku langsung meninggalkan mereka.
Sesaat sebelum berbalik, mendapati ekspresi geli di wajah Galih justru membuatku gemas. Rasanya menyebalkan karena aku sungguh tidak suka dengan orang yang saling lempar untuk mengatakan sesuatu, kemudian berakhir tidak jadi. Menggantung dan menyebalkan. Seperti sedang dipermainkan.
Baru saja mencapai posko, sosok Farzan sudah menjulang di depan pintu tengah berbincang berdua dengan Devi. Saat ini pasti sorot mataku sudah tidak enak dipandang.
"Rin, mau ngomong bentar," titah Farzan.
"Lho, kok, mendadak banget, Mas. Kebiasaan buruk, asli," sergahku.
Bagaimana mungkin rasa kesal tidak mendidih di dada. Tersisa D – 1 sebelum pelaksanaan CIW dan Farzan menyatakan untuk tidak menyediakan konsumsi dikarenakan dana yang sedikit, sehingga kemungkinan tidak mencukupi. Memikirkan bagaimana rasa kecewa peserta mengingat bagian benefit di pamflet telah mencantumkan konsumsi.
"Aku dari awal nggak acc konsumsi box," ujar Farzan.
"Mana ada Mas Farzan bilang gitu. Itu masih nutup, Mas, kalau nggak bisa box tinggal ganti isinya. Kita udah jajanan pasar, lho, Mas," jelasku penuh penekanan.
Devi yang menatap sendu membuatku menghela napas sebal. Bisa kutangkap di sini bahwa sebelumnya Devi pasti sudah berdebat panjang dengan Farzan, ah, lebih tepatnya dicerca. Ekspresi lesu bercampur bingung di wajah perempuan muda itu menunjukkan bahwa pasti tidak satupun penjelasannya bisa mengubah pikiran Farzan.
"Mas Farzan jangan aneh – aneh, deh. Sungguh, ya, masa juga cuma dikasih air mineral gelasan aja?" tanyaku tak habis pikir.
"Lha, ya, makannya aku nggak acc, kan, tapi bisa – bisanya udah pesen."
Haruskah aku berteriak tepat di depan wajah menyebalkan itu? Pasalnya semua hal terkait pemesanan konsumsi sudah secara nyata ada riwayat pembahasannya di chat group dan berwujud notulensi. Bukankah keteledorannya jika dia tidak tahu karena sering tiba – tiba menghilang dari rohis dan muncul mendadak bersama segala ucapan yang harus dituruti?
"Oke, yang kemarin kesalahan. Ya, udah. Sekarang, gini aja, gimana, Mas? Konsumsi buat peserta tercepat soalnya terbatas, kan? Atau kita kurangin porsinya yang penting semua bisa dapet."
"Iya, aku setuju sama Rinka," tutur Devi tiba – tiba, "daripada kita cancel, Mas, lebih baik kalau kita kurangin porsinya. Tapi, dikurangin isinya pun masih layak, kok, menurutku buat ukuran konsum kajian akbar islami gini."
Keberatan tergambar di raut wajah Farzan. Jelas sekali bahwa dia akan mengeluarkan segala jenis pembelaan untuk mempertahankan pendapatnya. Sungguh tidak bijaksana jikalau boleh jujur dan hal tersebut membuatku semakin kecewa. Namun, sesungguhnya aku juga cukup keras kepala dan ucapanku sebelumnya yang penuh penekanan tanpa menyembunyikan rasa kesal mungkin membuat dia mau tidak mau setuju pada akhirnya.


 rhea_adeya
rhea_adeya