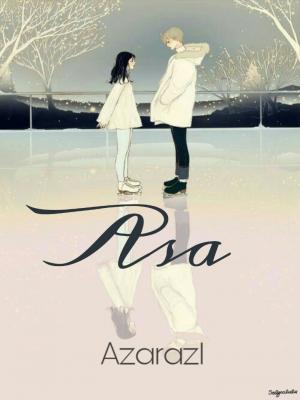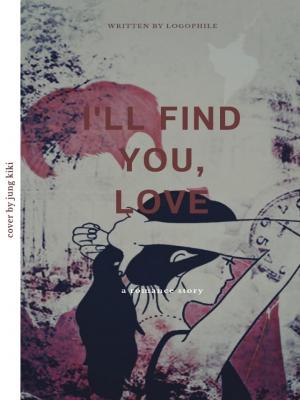"Karka, Karkata."
Aku tersentak karena panggilan suara yang membuyarkan lamunanku. Aku melirik ke arah sumber suara yang memanggil: seorang wanita dengan rambut panjang yang menyentuh pundak. Tubuhnya terbentuk sempurna di balik pakaian ketat yang dipakai, bola matanya berwarna-warni atau lebih tepatnya aku tidak tahu itu warna apa; hijau atau biru gelap. Yang aku tahu dia tengah melotot dan melambaikan tangannya tepat di depan wajahku. Aku mendengus, kembali aku isap batang rokok yang terselip di kedua jari. Mata aku kerjapkan beberapa saat sebelum kesadaran mulai kembali menghampiri. Sesaat aku sempat berjalan-jalan ke masa lalu, mengingat bagaimana aku dengan polosnya berharap akan dapat gorden emas setelah hidup dengan benar. Dan bagaimana aku berharap roda akan naik ke permukaan, ya benar, roda yang aku tumpangi memang mulai naik meski setelahnya aku dilempar ke dinding bata yang tidak rata. Kalau aku tahu efeknya akan seperti ini aku tidak akan pernah berdoa sepanjang malam agar rodanya bergerak. Bajingan memang, hidup tidak tahu ke mana arahnya, tapi terlalu takut untuk mati, terlalu banyak dosa. Jangankan mati, ingat api Neraka dan pembalasan Tuhan saja sudah meremang semua bulu yang ada di tubuh.
"Mikirin apa? Jauh banget pandangannya," ulangnya perlahan. Kening kawanku berkerut, menunjukkan air muka tidak paham atas jawabanku barusan. Aku masih buang muka, masih bungkam seperti Sapi yang habis makan rumput.
"Enggak ada, cuma ingat masa lalu. Sempat mikir, mungkin kalau aku balik lagi ke masa lalu kayaknya enggak bakal kayak ini kehidupanku. Ada enggak mesin kayak gitu? Kalau ada aku mau beli," jawabku iseng setengah serius. Jujur saja aku memang ingin kembali ke masa lalu, aku ingin bertemu dengan Kala lagi dan beritahu dia kalau hidupnya singkat. Tidak seperti yang dia pikirkan selama ini, Kala selalu percaya kalau dia akan hidup panjang lalu menikah dengan wanita luar biasa yang akan mengurusnya hingga tua. Kala juga sudah sering membayangkan bagaimana dia akan hidup dengan anak-anaknya, bagaimana dia akan membangun hubungan panjang merepotkan yang biasa disebut rumah tangga. Seperti Kala yang senang berkhayal, Ibu juga sudah membayangkan kalau akan punya cucu dari Kala dan Istrinya. Meski sedikit, aku juga berharap begitu. Kala itu manusia baik, dia salah satu manusia baik yang aku temui sepanjang kehidupanku. Dia peduli, dia sayang keluarga dan giat bekerja. Kala suka mengeluh, tapi tidak menyerah. Kala suka sebal dengan lingkungan tapi tidak pernah lupa Tuhan. Kala selalu ingat Tuhan seperti aku yang selalu ingat makan.
"Haha. Mimpi, ya? Kalau ada mesin seperti itu dijual, kamu juga enggak akan sanggup beli Karka. Pasti mahal banget, 'kan? Dan lagi, itu menyalahi aturan dunia. Belum ada manusia yang bisa menang lawan waktu, waktu itu bagian dari semesta. Dan semesta itu punya Tuhan, punya niat bangun mesin waktu sama saja dengan menentang Tuhan. Kamu enggak mikir begitu? Tapi lucu ya Ka, kita ngomongin Tuhan di tempat kayak gini." Gadis cantik yang sudah jadi kenalanku sejak belasan tahun lalu ini terkikik. Lucu katanya. Aku diam saja dan menatap setiap gerak bibir merahnya yang tidak alami, anak ini tipikal perempuan yang menyenangi perias wajah. Segala macam perias ia punya, mulai dari pemerah bibir hingga perona pipi. Aku menyebutnya serangkaian benda pengubah nasib. Bukan apa-apa dan bukan omong kosong. Manusia memang seperti itu, selalu menilai secara objektif, saat objek yang dipandang itu indah dan menarik mata maka akan diperlakukan dengan syahdu diiringi suara merdu. Coba bandingkan dengan objek buruk rupa dan tidak sedap dipandang mata. Pandangan sinis dan pikiran negatif akan melekat pada mereka, hanya berdiri dan melihat akan disangka maling, hanya menatap tanpa berkedip disangka penjahat. Tidak ada perlakuan syahdu apa lagi suara merdu, yang ada hanya ujaran buruk dan melukai hati.
Namun, uniknya. Jadi cantik di sini juga tidak bagus melulu, wanita-wanita cantik di kota juga punya kesengsaraan masing-masing. Mulai dari dibilang genit sampai dituduh perebut pasangan orang lain. Dunia dan manusia itu lucu, mereka enggan melihat diri, maunya melihat orang lain dan apa-apa yang tidak mereka punya. Kalau iri tidak mau mengakui, yang ada malah mencaci maki. Ada saja alasan tidak masuk akal yang dipakai. Setengah lucu, setengah menjijikkan. Iya, aku juga sama. Beruntungnya, aku tidak pernah iri dengan Kala. Aku iri dengan manusia-manusia yang tidak peduli pada Tuhan dan kematian, aku iri pada keberanian sekaligus rasa tidak peduli mereka pada akhirat nantinya.
"Iya betul. Mana ada yang jual, mana ada manusia yang mampu mengalahkan waktu dan melawan Tuhan. Manusia asalnya dari tanah, sudah diberitahu sejak dulu. Malaikat yang asalnya dari cahaya saja tunduk pada Tuhan, kenapa yang dari tanah malah berani. Lucu. Enggak apa-apa, kita enggak perlu ke Masjid kalau cuma mau ngomongin Tuhan. Pernah dengar enggak? Tuhan ada di mana-mana. Ada di hati kita, ada di kepala kita, beneran ada di mana-mana. Jadi, Tuhan enggak bakal keberatan kalau kita omongin di sini. Malah Tuhan bakal sedih kalau umatnya enggak pernah ingat dia." Omonganku mulai ngelantur, entah karena asap rokok yang mulai memenuhi otak atau karena aku ingat Kala.
Kala.
Kakak laki-lakiku yang aku rindukan, Kakak laki-lakiku yang sudah diambil Tuhan. Tuhan, apa Engkau merindukan Kala di sisi-Mu? Apa Engkau menginginkan Kala ada di dekat-Mu? Jadi Kala harus pergi lebih dulu seperti Bapak.
Tuhan.
Aku tidak marah, aku sungguh tidak menyalahkan dunia atas kepergian Kala dan Bapak. Boleh saja ambil mereka, Kala dan Bapak adalah kepunyaan-Mu, tapi Tuhan kalau aku sedih, boleh ya? Aku, salah satu umat-Mu yang tidak betul-betul setia, salah satu umat-Mu yang ingat pada dosa tapi tetap mendekatinya.
"Capek ya? Pulang yuk. Sudah malam juga, mau di sini sampai kapan? Liburnya juga mau habis. Lusa sudah mulai kerja, 'kan?"
Aku mengangguk sebagai jawaban. Tara benar, mau sampai kapan di sini? Aku mengedarkan pandangan; langit gelap dengan cahaya bulan dan kelip bintang, deretan lampu jalan yang terkadang mati sendiri, penjual makanan dan orang lalu-lalang. Kulirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan; pukul satu pagi. Kami di sini dari pukul sembilan malam, empat jam duduk dan buang waktu memang menyenangkan. Apa lagi tidak perlu memikirkan pekerjaan esok hari, tidak perlu juga memikirkan besok makan apa. Uang sisa gaji masih tersisa, meski tidak akan cukup untuk beli emas apa lagi beli rumah. Hal-hal yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya. Ada banyak celoteh yang tidak mau pergi dari otak, tentang pendewasaan diri dan cara hidup benar. Hidup dengan benar itu memangnya bagaimana? Pelit terhadap diri sendiri atau terlalu mementingkan masa depan? Hidup seperti itu tidak salah, seisi dunia tahu kalau masa depan adalah hal yang penting. Namun, pernahkah terlintas dalam pikiranmu; bagaimana kalau mati esok? Dan kau belum mencoba apa-apa, dan kau belum pernah memberikan apa-apa, dan kau belum pernah berbagi apa-apa. Menyesal selalu belakangan, tetapi kalau sudah hilang nyawa tidak akan bisa lagi menyesal. Tinggal menunggu orang-orang membawamu ke tanah lapang dan membiarkan tubuh dimakan cacing.
"Aku ke rumahmu ya? Malas balik ke kost."
"Oke. Tunggu di sini, aku pesan taksi dulu, soalnya Galaksi enggak bisa jemput. Kerjaannya masih numpuk katanya." Aku melirik ke arah Tara yang membicarakan Galaksi, salah satu kawan dari lingkaran pertemanan yang berakhir menjalin hubungan dengan Tara. Di antara kami bertiga, aku yang paling muda, Tara dan Gala satu tahun di atasku. Usia mereka dua puluh empat, tahun ini, sementara aku masih dua puluh tiga. Aku kenal dengan Tara lebih dulu dibanding Gala, karena kami satu sekolah. Tara tergolong siswi yang pintar, dia sering juara kelas dan aktif dalam kegiatan belajar-mengajar. Dia juga anggota kesiswaan yang banyak dipuja guru-guru. Dan aku ikut anggota kesiswaan agar bisa bolos kelas dengan alasan konkret.
"Oh, ya sudah. Naik taksi panggilan juga bagus, selama Tara enggak sendirian, aman-aman saja harusnya. Kalau Tara sendirian, baru enggak boleh. Males urusan sama Galaksi. Dia kalau ngomel, panjang kayak kereta api baru lepas landas." Bibirku mengerucut, mengingat bagaimana tipikal Galaksi yang suka mengoceh kalau kami pulang larut malam. Di luar dari Tara yang memang tergolong gadis cantik dan selalu digoda kutu jalanan. Kumatikan api rokok yang masih menyisa sembari menatap ke arah Tara yang sudah sibuk dengan ponsel genggamnya. Perlahan, aku menarik napas melupakan banyak hal yang sudah aku lewatkan dengan sia-sia. Salah satunya bagaimana aku menolak Galaksi sebelum Tara berkata jika ia menyukai Galaksi.


 reztelliot
reztelliot