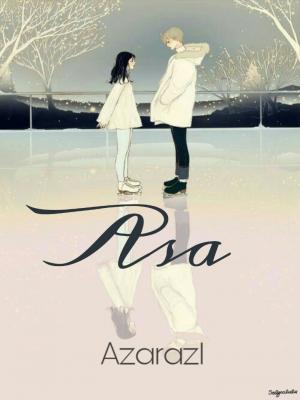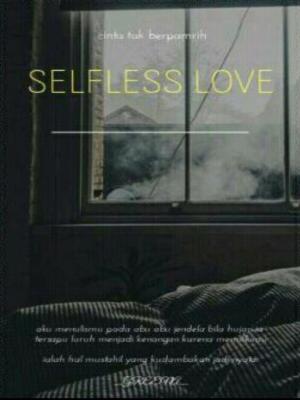Tunggu, umurku sudah tujuh belas tahun Januari kemarin, apa sekarang aku sudah boleh iri dengan Karis yang berangkat dan pulang sekolah mengendarai motor? Meski kami sama-sama belum punya SIM, orang tua Karis jauh lebih memilih memberikan anak mereka kendaraan untuk pergi ke sekolah, alasannya cukup simpel, naik motor kan selalu lebih efisien daripada naik kendaraan umum, dan juga lebih irit dari segi ongkos.
Kemarin dengan tidak tahu dirinya, aku meminta Ibuk untuk membelikan motor, kalau tidak bisa beli yang baru, yang second-pun tidak masalah, asalkan aku tidak harus menunggu Pak Jaja menjemputku setiap pulang sekolah. Kalau nggak sering terlambat sih aku gak harus pusing-pusing meminta motor ke Ibuk, ini aku sudah dua puluh menit loh berdiri di depan gerbang.
“Emang kamu udah bisa naik motor?” Tanya Ibuk padaku.
“Ya gimana mau bisa naik motor, orang motornya aja nggak punya.”
“Terus, buat apa Ibuk beliin motor kalau kamu nggak bisa naiknya, ibuk juga nggak bisa naik motor, jadi Ibuk rasa saat ini Pak Jaja aja sudah cukup buat kita.”
“Ya, gimana Serayu mau bisa naik motor kalau motornya saja nggak ada,” rengekku, dan perdebatan dengan ibuk tidak akan pernah selesai kalau aku belum menangis.
Pak Jaja ini sudah kami anggap saudara, sejak kepergian bapak, Pak Jaja persis merangkap menjadi sosok ayah bagi ibuk dan aku. Membenahi genteng bocor, memasang gas kalau ibuk tidak ada di rumah, menjadi supir, mengantar kami we’re ever we fly, tukang kebun, membetuli ledeng, menguras kolam ikan, apa saja dia kerjakan.
Umurnya lebih tua dari mendiang ayah sepuluh tahun, sebab itu dia tidak pernah mau jika ditawari pekerjaan lain, dan lebih nyaman mengabdi di rumah kami. Beliau tidak punya istri, sanak saudaranya di kampung juga tidak bisa diharapkan keberadaannya.
“Pak Jaja sudah tua, Sera. Sabar dulu.” Itu adalah jawaban ibuk setiap aku mengeluh kalau Pak Jaja telat datang.
“Apa coba minta tolong ke Leo, ya?”
Aku berpikir, kemudian memutuskan untuk memberitahu Leo bahwa sahabatnya ini sedang terlantar di depan sekolah, sudah seperti ikan teri.
Jika bisa, aku mau minta diberikan pangeran sekarang, bukan yang berkuda putih juga boleh, pangeran dalam bentuk tukang ojek, tukang angkot, miniarta, atau apa saja yang bisa mengantarku pulang, datanglah! Datanglah!
Namun, belum sempat pesan itu terkirim, Dia datang.
“Hai.”
Ketika aku memejamkan mata dan berdoa sungguh-sungguh, aku tidak percaya Tuhan mengabulkannya secepat ini. Ah, doa orang yang terdzalimi memang kata ibuk itu mujarab. Iya kan? Aku sudah lapar, kepanasan, kebelet juga. Jadi, mari kita lihat, siapa pangeranku kali ini.
“Sera? Ngapain merem?”
“Hah? Bani? Ngapain lo di sini?”
“Kebiasaan, kalau ditanya jawabannya pertanyaan juga.” Lantas dia mematikan mesin motornya, membuka helm, memperlihatkan jajaran giginya yang putih. Melanjutkan pertanyaannya “Kok belom balik?”
“Biasa, nunggu Pak Jaja, kayaknya ketiduran lagi.”
Dia, Bani. Benar, dia adalah mantan anggota mading sekolah, dia Bani. Bani yang kusebut anak kelas sebelah yang aku taksir selama kami berorganisasi bersama-sama. Masih Bani yang sama yang membuatku kadang nggak tahu harus bersikap seperti apa, Bani yang sama yang membuat perasaanku...
“Oh, mau bareng?”
Berbunga-bunga.
Pertama-tama, terima kasih kepada Pak Jaja sebab keterlambatannya membuatku memiliki kesempatan ini, kedua aku juga berterima kasih kepada Tuhan yang mengabulkan doaku lebih dari apa yang kuminta.
“Eh, nggak usah, Ban. Gue tunggu aja, atau nggak bisa pesen ojek juga, kan. Lagian rumah kita nggak searah.”
“Santai aja, gue mau ke arah rumah lo juga soalnya. Ibu gue titip kue bolu dan toko langganannya di ruko deket rumah lo.”
Bagaimana? Kita sudah cukup dekat kan untuk tahu alamat rumah masing-masing? Yang jelas bukan karena PDKT, tapi karena waktu OSIS dulu kan, setiap orang diminta ngumpulin biodata masing-masing. Bani jauh lebih tinggi dariku yang hanya 156 cm ini. Sekita dua jengkal kurang sedikit, deh. Rambutnya sedikit bergelombang, tapi bukan ikal atau keriting, tapi tidak bisa dibilang lurus juga. Kulitnya sawo matang tapi cerah, orang-orang menyebut telinganya caplang karena lebar, alisnya biasa saja, tidak tebal, tapi bulu matanya lentik sekali, aku pernah mengira dia tanam bulu mata, tapi kata Karis itu tidak mungkin.
“Ayo, lo mau di sini sampe sore?”
Baiklah, mari anggap ini sebagai sebuah hadiah tahun terakhir berada di SMA, biar aku juga punya cerita, aku pernah dibonceng pulang oleh seseorang yang aku sukai, kelak jika tidak ada Bani di masa depanku, aku bisa menceritakannya sebagai sebuah cerita yang indah. Eh, kok jadi ngomongin gini sih? Cita-cita dulu, baru cinta-cinta.
“Oke, sorry ngerepotin ya, Ban.”
“Nggak masalah. Ayo naik.” Huh, untung saja motor Bani bukan seperti motor-motor anak SMA di novel-novel. Motor matic biasa yang tidak perlu effort lebay untuk menaikinya. Aman. Andaikan hubunganku dengan Bani lebih dari sekadar kenalan di organisasi, apa aku bisa meminta Bani mengajariku naik motor. Hush, Sera, pikiranmu kacau lagi.
“Gimana rasanya naik motor?”
“Huh? Emang kenapa?”
“Kan Pak Jaja biasanya bawa mobil.”
“Ya nggak ada masalah sih, naik motor lebih enak, lebih cepat, bisa kena angin, bisa nyalip.” Mendengar jawabanku, Bani tertawa renyah sekali, aku bisa melihatnya sedikit dari balik kaca spion yang memantulkannya. Wah, hari ini akan kucatat dalam sejarah.
“Gue kira lo nggak suka naik motor, karena nggak pernah liat lo naik motor.” Bani tidak tahu saja, betapa inginnya dia bisa punya dan naik motor. Sayangnya, ibuk tidak pernah berpikiran hal yang sama, kata Karis, aku harus maklum karena aku anak semata wayang, tapi apa salahnya anak satu-satunya naik motor?
Khawatir? Ya kalau nggak begitu bukan ibuk, sih namanya.
“Nyokap nggak pernah ngasih izin gue naik motor, kalo boleh mungkin cita-cita gue jadi pembalap, bukan jadi gamers,” kataku sedikit berteriak.
“Gue percaya, lo bisa jadi gamers profesional, Ser.”
“Huh?” aku berteriak sedikit, kumohon semoga Bani tidak sakit telinga. Aku minta dia untuk mengulangi ucapannya yang barusan, tapi dia malah menggeleng dan tersenyum, “pengangan, ayo kita ngebut, whuuuuuuuusss.”


 lynxamanda
lynxamanda