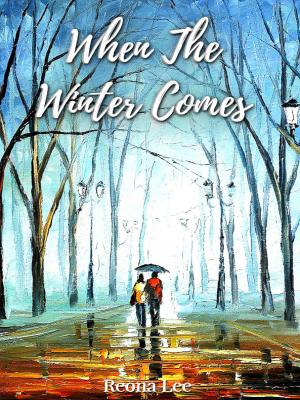Kami kembali berdamai. Dan sejak hari itu pula, kami menjaga perasaan masing-masing. Seperti menerima keberadaan Ari di sekelilingku, dan Ari yang bersikap biasa-biasa saja ketika aku mulai membahas soal Fajar. Aku menduga dia telah menerima bahwa perasaannya padaku tak bisa kubalas.
Hari di mana babak ketiga dimulai. Kami berlima sempat video call dengan Fajar melalui ponselku. Anak laki-laki itu memberi kami semangat meski dia terlihat terbaring di atas tempat tidur. Menurut Tante Rani, kondisi Fajar selalu drop saat malam hari seperti merasakan rasa sakit di kepala yang luar biasa.
Dan Fajar selalu berkata melalui telepon, “Aku nggak apa-apa, Wa. Cuma pusing dikit. Kamu fokus latihan aja biar Team Phoenix masuk final.”
Aku tahu Fajar berbohong, karena Tante Rani selalu melaporkan kabar terbaru Fajar kepada Ari yang kemudian diteruskan padaku dan teman-teman yang lain.
Dengan tubuh yang gugup, aku duduk di bangku venue. Babak ketiga di hari itu bisa dikatakan hari yang membuat andrenalinku diuji mati-matian. Terdapat empat game dalam babak ketiga, siapa yang memenangkan empat poin lebih awal, dialah yang menang. Team Phoenix kalah dua kali di game pertama dan kedua. Aku sempat down di panggung seolah tak ada harapan lagi untuk menang.
Namun, saat istirahat sebelum babak ketiga dimulai, Guntur sebagai moodbooster tim memberikan semangat kepada kami berempat agar tak mudah menyerah begitu saja.
“Inget, ya, kalian. Takdir itu bisa dirubah kalau kita punya tekad!” Papar Guntur dengan semangat.
Tanganku gemetar saat memegang botol air mineral.
“Kalau kita kalah, masih ada lower bracket.” Kemudian Guntur tertawa.
“Nggak ada lower bracket buat kita!” gilirna Ari yang berseru. “Kalau upper bisa, kenapa nggak?”
Dua laki-laki itu berperan besar dalam membangkitkan semangat rekan satu timnya. Game ketiga pun dimulai. Aku berusaha untuk fokus saat kembali ke venue. Kami menghadapi fase draft pick dengan lancar, tidak ada cekcok antara Ari dan Rian yang berbeda pendapat seperti biasanya. Dan di game ketiga ini, Team Phoenix memenangkan pertandingan. Dan kami berhasil menerobos pertahanan tim lawan dengan memenangkan game keempat.
Kedua tim berhasil seri, 2-2. Team Phoenix kembali berunding saat sesi istirahat sebelum game kelima dimulai. Walau kami semua lelah secara mental, tetapi kami harus profesional untuk memasuki final.
Game kelima dimulai. Hasilnya, Team Phoenix kalah, 2-3. Game keenam adalah penentuan tim musuh, tetapi Team Phoenix berhasil memenangkan game tersebut. Hasil kembali seri, 3-3. Game ketujuh adalah penentu segalanya, siapa yang berhak maju ke babak final.
Aku merapalkan doa-doaku. Aku melakukan ini untuk temanku yang sedang berbaring lemah di ranjangnya. Kami memiliki inspirasi untuk tak takut pada semua yang menghantui kami bahkan untuk game sekalipun.
Deg!
Sorak pengunjung mall terdengar ramai saat mereka menyaksikan game terakhir dari kedua tim di babak ketiga ini. Mereka berseru-seru menyebut nama tim kebanggan yang baru saja memenangkan game ketujuh di babak ketiga ini.
“TEAM PHOENIX! TEAM PHOENIX!”
Aku menangis dengan gemetar. Saat itu, aku separuh sadar saat Ari memelukku—lebih tepatnya kami berlima saling berpelukan di atas venue. Harapan kami di hari itu terjawabkan oleh tekad dan keberanian kami melawat rasa takut.
Kemudian Yaya pingsan di tempat—Guntur sempat menolongnya agar tubuh gadis itu tak membentur ke lantai. Kemudian panitia penyelenggara memanggil tim medis untuk menangani Yaya secepatnya.
***
Yaya siuman dari pingsannya setengah jam yang lalu. Saat bangun, dia tertawa penuh haru. Aku merasa lega karena boleh jadi Yaya terlalu syok dengan game ketujuh yang begitu menguras mental.
Setengah jam kemudian, Ari menyetir mobil yang kami tumpangi. Kami berencana pulang secepatnya agar bisa beristirahat setelah melalui ‘peperangan’ yang panjang.
“Finalnya kapan tadi, Yan?” tanya Ari pada Rian yang ada di bangku mobil ketiga.
“Sebulan lagi. Tadi baru aja aku dikasih tahu kalau lawan kita dari SMAN 1.” Jawab Rian dengan tubuh yang bersandar lemas di bangku mobil.
“Masih lama, sih… tapi kita bisa latihan.”
“Iya. Aku juga punya kenalan yang ikut turnamen ini. Aku tahu betul dia sukanya main hero apa.”
Guntur ber-oh pelan. “Kalau gitu, kita bisa analisis mereka.”
Rian mengangguk. “Nanti aja aku kirimin nama-nama akunnya.”
“Siap, Kapten!”
Perjalanan dari Surabaya ke Sidoarjo berlanjut sampai teman-teman kami tertidur, kecuali aku dan Ari yang tetap terjaga. Ari fokus mengemudi denga permen kopi yang menjadi andalannya agar tak mengantuk. Sementara aku sibuk menatap jalanan luar melalui jendela kaca mobil.
“Nggak tidur, Wa?”
Aku mengerjap pelan saat Ari tiba-tiba bertanya. “Nggak ngantuk.”
“Oh,” Ari menjawab singkat sembari tersenyum simpul—aku bisa melihatnya dari kaca spion.
“Setelah lulus kamu kerja apa kuliah, Wa?”
Aku tahu, Ari selalu bisa mencari topik agar bisa mengobrol denganku. “Bapak nyuruh kuliah, aku juga minat kuliah.”
“Oh, nanti yang ikut jalur akademik itu, ya? Eh… apa namanya… S… SNMPTN!”
Aku mengangguk. “Rencananya sih gitu. Doain aja keterima.”
“Aamiin. Mau ambil jurusan apa?”
“Bahasa Indonesia.”
“Kenapa nggak Bahasa Jepang? Kamu, kan, suka anime.”
Aku menggeleng. “Takutnya berhenti di tengah jalan. Kasian Bapak soalnya yang biayain.”
“Menyerah sebelum berperang itu namanya.”
Aku tertawa kecil. “Iya, sih…” lalu aku menyamankan posisi duduk. “Kalau kamu, Rik?”
Awalnya Eric menggeleng pelan. “Aku nggak minat kalau nerusin satu di antara pekerjaan Mama sama Papa. Kayaknya aku bakalan merantau ke Jakarta buat daftar masuk ke tim E-sport.”
Mataku melebar. “Kamu serius, Rik? Mau jadi pro-player?”
“Namanya juga impian, Wa.” Kekeh Ari yang kemudian membuka bungkusan permen kopi dengan satu tangan dan gigi, lantas mememakannya.
Aku mengangguk-angguk. “Kalau punya tekad dan berusaha, pasti berhasil.”
“Aamiin. Makasih buat doanya, Wa.”
Aku mengangkat kedua alis. “Santai.”
Kemudian Ari tak lagi berbicara, mungkin agar aku tidur di mobil seperti yang lain. Namun, sampai di rumah, aku tidak bisa tidur karena tak sabar ingin memberitahu Fajar bahwa timnya telah memasuki babak final.
“Dadah, Wawa. Nanti mau mabar, nggak?” ucap Ari saat aku baru saja turun dari mobil putih itu. Yaya, Guntur, dan Rian sudah diantar oleh Ari terlebih dahulu, karena jarak rumahku dan Ari berdekatan.
Aku menggeleng pelan sebagai jawabannya. “Nggak dulu, deh. Jenuh karena habis tanding tujuh game.”
Ari tertawa terbahak-bahak. “Ya udah, aku pulang dulu, ya, Wa.”
Aku mengangguk, lalu mobil yang dikendarai Ari melaju dengan mulus ke jalan pemukiman desa.
Kemudian aku memasuki rumah yang sepi. Bapak sedang bekerja, Ibu dan adikku ada di pasar belanja bahan pangan. Ah, aku sendirian di sore ini. Karena rumahku kotor, aku pun menyapunya. Setelah menyapu lantai, giliran menyapu halamannya yang penuh sampah daun pohon jambu yang menguning.
Baru saat rumahku bersih, aku pergi membersihkan diri sendiri. Setelah berpakaian rapi, aku duduk santai di sofa dan mulai membuka aplikasi berwarna hijau untuk memberitahu Fajar. Kulihat terakhir dia online sekitar lima menit yang lalu.
Me : Hai, Jar. Gimana kabar kamu? Semoga baik-baik aja.
Me : Oh, iya, Jar. Team Phoenix maju ke babak final.
Tak perlu menunggu waktu lama, pesanku terbaca oleh Fajar, kemudian dia mengetik sesuatu. Aku menunggunya lama sekali. Apa dia ingin bercerita?
Fajar X ML : Wa, boleh video call sama kamu, nggak?
Aku sempat tercengang membaca teksnya. Tanganku gemetar, aku tidak pernah video call dengan satu lawan bicaraku karena diriku selalu terlihat gugup—tetapi aku tidak ada masalah dengan panggilan suara.
Boleh jadi wajahku memerah karena tersipu saat itu.
Me : Boleh.
Fajar X ML : Kamu duluan, ya, Wa. Nanti aku angkat.
Aku tidak bisa menahan senyumanku yang lebar. Saat mulai menekan tombol video call, aku langsung mengubah mimik wajahku agar tidak terlihat mencurigakan di hadapan Fajar.
Kemudian Fajar mengangkat panggilan video itu. Kulihat dia sepertinya duduk di atas ranjang. Bahkan Mbak Tina dan dua perawat yang bekerja di rumah Fajar—berdiri di samping anak laki-laki itu dan melambaikan tangan menyapaku.
“Haloo, Najwa! Widih, Team Phoenix masuk final, nih!” suara Mbak Tina terdengar menggelegar.
Aku tertawa. Pasti Fajar yang memberitahu Mbak Tina. “Finalnya satu bulan lagi, Mbak Tina. Masih ada waktu buat kita latihan.”
Pernyataanku baru saja membuat Fajar tercengang—aku bisa melihatnya dengan jelas. “Serius satu bulan lagi?”
Aku mengangguk-angguk. “Iya, Jar.”
“Finalnya di mana, Wa?”
“Finalnya nanti di Royal Plaza Surabaya, bakalan ada kursi penontonnya kayak di panggung APL.” Ujarku penuh semangat.
“Team Phoenix lawan tim apa, Wa?”
“Team dari SMAN 1.” Jawabku.
Fajar mengangguk-angguk. “Oh, iya, Wa. Besok setelah pulang sekolah kamu ada acara, nggak?”
“Ehm, nggak ada, sih.”
“Besok bisa ke rumahku, nggak? Ngajak Mas Ari juga nggak apa-apa.”
Aku terkekeh--sama sekali tidak keberatan. “Oke, Jar.”
“Kalau gitu udahan dulu, ya, Wa. Kamu yang tutup teleponnya.”
Aku mengangguk-angguk. “See you, Jar.” Kemudian menekan tombol merah untuk mengakhiri panggilan video tersebut.
Meski Fajar tidak memintaku untuk datang ke rumahnya, aku akan tetap berangkat. Perasaanku sedang berbunga-bunga dengan wajahku yang senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Hari itu aku menyadari sesuatu.
Apa aku jatuh cinta dengan Fajar?
***
Di sekolah, aku sangat kaget melihat Ari yang terlambat datang selama setengah jam dan saat mata pelajaran matematika dimulai pula. Alhasil dia dihukum mengerjakan soal di papan oleh Bu Nia—guru matematika kelas 12. Dia sempat menengok buku tulis temannya, dan dengan akal-akalannya, dia berhasil mengerjakan soal yang rumit itu.
“Salah. Tapi nggak apa-apa. Ada usaha dikit.” Ujar Bu Nia.
Kami semua tertawa.
“Dah, boleh duduk kamu, Ari. Lain kali jangan terlambat di jam pelajaran saya!” ketus Bu Nia.
Ari mengangguk, dia berjalan lantas duduk di bangkunya yang ada di sebelah bangkuku.
“Rik,” bisikku saat kelas terasa lengang karena kami sedang diberi tugas harian oleh Bu Nia.
Ari menoleh padaku, lalu dia mengangkat dagunya—isyarat, apa?
“Kok telat?” bisikku pelan.
Ari mengembuskan napasnya. “Ban motorku bocor di tengah jalan.” Balas Ari dengan bisikan pula.
Aku ber-oh pelan. “Terus kamu berangkat sama siapa?”
“Jalan kaki, sama ngopi sebentar.” lelaki itu menyeringai di akhir kalimat.
Sejenak aku tercengang. “Emangnya bocor waktu sampai di mana?”
“Deket MPP.”
Aku menghea napas pelan. Pantas saja Ari terlambat. Jika diukur dari peta, tempat Mall Pelayanan Publik atau MPP memiliki jarak sekitar 2,9 kilometer. Secara Ari selalu berangkat pagi.
“Kenapa nggak telepon? Aku bisa jemput kamu tadi.”
“Hp-ku mati, Wa. Kabelnya nggak kecolok pas ngecas kemarin. Mau ngecas di warung tapi nggak ada colokan kabel, terus keburu telat juga.”
Aku menggeleng heran.
Kemudian kami kembali fokus pada mata pelajaran matematika. Walau sejujurnya ini adalah mata pelajaran yang sangat aku benci, aku tetap mengerjakannya dengan rumus yang ada. Apalagi Ari yang selalu asal-asalan mengerjakan matematika dan berakhir dapat nilai rendah.
Jam istirahat berdering dari pusat pemberitahuan sekolah. Saat Bu Nia keluar dari kelas, Ari langsung mengambil charger, lalu mencolokkannya di stopkontak yang ada di sebelah meja guru. Laki-laki itu duduk di sebelah kursi guru sembari men-charge ponselnya.
Aku pun menghampiri laki-laki itu—tidak menghiraukan para siswi yang sinis menatapku, juga para siswa yang berceloteh cie cie terutama Rian. Aku sudah lelah menasehati mereka bahwa kami tidak ada hubungan apapun selain persahabatan.
“Rik,” panggilku.
“Hm?” Ari masih fokus dengan layar ponselnya.
Aku berjongkok di depannya. “Nanti pulang sekolah ke rumahnya Fajar, yuk.”
“Eh?” Ari langsung menatapku, mematikan layar ponselnya. “Nanti?”
“He-em. Fajar yang minta. Aku sama kamu. Bisa?”
Ari ber-oh pelan. “Tapi aku udah ada janji sama Papa. “Biasalah. Urusan bisnis Papa di Surabaya. Aku disuruh ikut.”
“Yah…” wajahku terlipat kecewa.
Ari tersenyum. “Maaf banget, Wawa Cantik. Soalnya bakalan ada rapat pemegang saham terbesar setelah Papa. Aku salah satu kandidatnya.”
“Bukannya kamu nggak minat sama pekerjaan papamu?” mataku memicing.
“Kalau masalah duit sih minat aja, Wa.” Kekeh Ari.
Aku tersenyum seraya menggeleng heran. “Arik Arik…”
“Besok aja, Wa, kita ke rumah Fajar pas pulang sekolah. Tapi kamu nggak usah bawa motor. Aku jemput aja kayak dulu itu.” Papar Ari seraya kembali menatap layar ponsel.
Aku tersenyum simpul. “Okay, Rik.” Kemudian aku bangkit berdiri, lantas berjalan keluar kelas untuk membeli makanan di kantin.
***
Dan benar saja, saat pulang sekolah, Ari dijemput oleh papanya—aku memanggilnya Om Erico. Beliau menyapaku dengan riang saat baru saja turun dari mobilnya. Sementara Ari sudah lebih dulu masuk ke mobil.
“Tadi Arik telat masuknya, ya, Mbak Wa?” tanya Om Erico.
Aku mengangguk.
“Owalah, nanti sekalian ngambil di bengkel aja, deh.”
Aku tersenyum seraya mengangguk lagi.
“Buruan, Pa!” Ari berseru pelan setelah membuka kaca jendela mobil papanya.
Om Erico terkekeh. “Ya udah, Mbak Wa. Kita pulang dulu, ya. Hati-hati di jalan.”
“Iya, Om. Hati-hati juga.”
Om Erico memasuki bangku kemudi, lantas mobil putih itu berjalan mulus di jalanan. Dan Ari sempat melambaikan tangannya padaku melalui kaca mobil.
Kemudian aku melangkah ke parkiran untuk mengambil motor. Seperti biasa, sebelum ke rumah Fajar, aku membeli beberapa roti dan buah-buahan di minimarket terdekat. Buah yang mereka jual selalu segar dan selalu baru setiap harinya.
Motorku berhenti dengan mulus di tepi gerbang rumah Fajar—sengaja kuletakkan di sana agar tidak mengganggu jalan. Kemudian aku menekan bel di sebelah gerbangnya, tak lama setelah itu, seseorang datang membukakan gerbang.
“Ehh, Najwa! Kirain siapa…”
“Met sore, Mbak Tina.” Sapaku riang.
“Iya iya. Ayo masuk, udah ditungguin Fajar, tuh.” Kemudian Mbak Tina membuka sedikit gerbang. Setelah aku masuk, Mbak Tina kembali menutup gerbang tersebut.
“Biasanya kalau pagi Fajar suka di kamar game-nya. Terus kalau sore-sore gini dia ada di belakang rumah.”
Aku mengangguk-angguk mendengar penjelasan Mbak Tina. Dan ada satu hal yang perlu aku tanyakan. “Adiknya Fajar di mana, ya, Mbak? Kok jarang lihat?”
“Ina pulang ke rumah neneknya—ibunya Nyonya Ninda. Soalnya Pak Dani nggak mau Ina lihat kakanya sakit-sakitan begini. Dia jadi nggak mau sekolah karena terlalu peduli sama kakaknya.” Ujar Mbak Tina dengan helaan napas di akhir kalimat.
Aku tersenyum. “Dia masih kecil, lho, Mbak. Tapi udah punya rasa peduli, ya.”
Sementara kami sudah menapakkan kaki di lantai marmer rumah mewah ini. Kemudian memasuki pintu rumah setinggi tiga meter.
“Iya, Wa. Keluarga ini emang harmonis. Tapi ada aja ujiannya.”
Aku tersenyum simpul, tahu maksud ucapan Mbak Tina. “Eh, Tante Ninda di mana sekarang, Mbak?” tanyaku.
“Lagi belanja di pasar sama Pak Dani. Bentar lagi juga pulang.”
Aku mengangguk pelan. Lalu kuserahkan kresek merah berisi roti dan buah-buahan yang aku bawa pada Mbak Tina. “Ini, Mbak, masih seger buahnya.”
“Repot banget, sih, Wa.” Ujar Mbak Tina seraya menerima kresek merah itu. “Makasih, lho, ya.”
Aku menyeringai lebar.
“Fajar lagi di belakang rumah, Wa. Kamu samperin aja, ya. Mbak mau ke dapur dulu.”
Aku mengangguk sementara Mbak Tina berjalan menuju ke dapur yang jaraknya tidak jauh dari ruang tamu. Dan aku pergi ke belakang rumah mewah ini melalui pintu yang jaraknya sekitar dua puluh meter dari posisiku.
Kubuka pintunya, lalu aku mendapati Fajar yang duduk di kursi roda di bawah pohon yang teduh sembari membaca sebuah buku.
“Fajar!” sapaku riang. Kemudian aku berjalan menghampirinya.
Lelaki itu memekik pelan, wajahnya pun terlihat bahagia akan kedatanganku.
“Maaf, ya, Arik nggak bisa datang, soalnya diajak papanya ke Surabaya.” Jelasku.
Fajar mengangguk, memaklumi. “Kamu aja yang datang udah cukup, Wa. Aku kesepian di rumah.”
“Padahal ada Mbak Tina dan perawat lain yang nemenin kamu, lho.” ujarku.
“Tapi aku tetep kesepian.”
Aku menyeringai lebar. Kemudian kudapati sebuah kursi yang tergeletak di dekat batang pohon. Lantas aku mengambil dan menduduki kursi plastik itu di sebelah Fajar.
“Masa kesepian, sih? Apa karena Ina nggak ada di rumah ini?”
Sejenak Fajar tercengang. “Eh…” lalu dia menundukkan pandangan, tersenyum tipis. “Ya, gitu, deh.”
Aku baru saja tahu buku apa yang sedang dibaca oleh Fajar saat dia menutup buku itu di pangkuannya. “Buku yang pernah aku kasih, ya?”
“Oh, ini?” Fajar tersenyum, menatap buku itu sejenak. “Aku suka bukunya, Wa. Makasih banget.”
Ah, aku merasa bahagia jika melihat temanku bahagia. Buku itu terasa hambar untuk diriku yang lebih menyukai buku-buku fiksi. Namun, boleh jadi buku itu menjadi sebuah penghargaan bagi orang-orang terpilih yang membacanya.
“Aku punya buku fiksi di perpustakaan pribadi, Wa. Kamu boleh ambil kalau mau.” Ucap Fajar.
“Eh?” aku mengerjap-erjap, terkejut akan pengakuannya. “Kamu punya perpustakaan pribadi?”
“Iya. Waktu masih di Jawa Barat, aku suka ngoleksi buku-buku. Ngumpulinnya mulai dari kelas empat SD.”
“Waw… jarang aku nemu cowok yang hobi baca.”
Fajar menyeringai. “Aku orangnya introvert, takut banget bersosialisasi, ya gitu deh. Terus almarhumah Ibu beliin aku buku-buku waktu itu, kekumpul sampe ratusan. Pas aku pindah ke Jawa Timur, Bunda yang bantu aku mindahin buku-bukunya terus bikin perpustakaan pribadi di rumah ini.”
Aku mengangguk-angguk mendengar penjelasan Fajar. “Perpustakaannya di mana kalau boleh tahu?” Aku bertanya karena saat melihat suasana kamar utama Fajar, tidak ada rak buku seperti perpustakaan di sana.
“Ayo, aku tunjukin ke kamu.”
***
Aku mendorong kursi roda Fajar saat ia mengajakku untuk menunjukkan di mana letak perpustakaannya. Ternyata tempat itu ada di pojok lantai satu dekat dengan kamar mandi. Saat kubuka pintunya, suasana ruangan itu benar-benar seperti perpustakaan.
Buku-buku yang tersusun rapi di rak dinding dengan tinggi sekitar dua setengah meter. Di setiap raknya, terdapat tag kategori seperti novel Indonesia, novel terjemahan, self-development, komik, biografi, sampai buku panduan memasak. Aku seperti berada di dunia fantasi ketika memasuki perpustakaan tersebut.
“Wah, ini berapa duit yang dibutuhin, ya…” gumamku pelan.
Fajar tertawa kecil mendengar gumamanku. “Setiap tahunnya aku bisa beli sampe lima puluh buku, Wa. Tiap hari baca.”
Aku mengangguk-angguk. Lalu kutemukan sebuah buku fiksi terjemahan yang terkenal. Bahkan aku sudah menonton movie-nya.
“Kamu punya Harry Potter, Jar?” aku menunjuk buku yang berjajar dengan rapi di depanku.
Fajar mengangguk. “The Deadly Hallows yang paling seru, Wa. Aku yakin banget kalau kamu udah nonton filmnya.”
Aku balas mengangguk dengan antusias. “Tapi aku belum pernah baca novelnya. Eh, dulu waktu di perpustakaan SMP, aku nemu novel Harry Potter, tapi tebelnya minta ampun. Aku kayak nggak sanggup buat baca. Ya udah nggak jadi pinjam.”
Fajar tertawa mendengarku bercerita. “Emang tebel, Wa. Tapi seru, tahu. Kamu bisa ambil, kok. Lagian udah nggak guna lagi…”
Senyumanku perlahan memudar akan kalimat terakhir yang dilontarkan Fajar kepadaku. Laki-laki itu menundukkan pandangan, lalu mengusap ujung matanya.
Aku menggeleng pelan, lantas berjongkok di depan kursi roda laki-laki itu. “Kamu kenapa bilang kayak gitu, Jar?”
“Hmm… Enggak apa-apa.”
Aku mengulum bibirku yang kering.
Kemudian Fajar mengenggam jemariku di atas pahanya. “Stadium akhir.” Lantas dia menggeleng pelan. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, “Aku nggak punya keyakinan lagi buat hidup, Wa.”
Aku terkejut dengan pengakuannya, tetapi aku menggeleng pelan, balas menagkup kedua tangannya. “Dokter Rani—”
“Sebenarnya dokter itu nggak nyembuhin kita, Wa. Dokter hanya bisa ngasih waktu lebih lama untuk kita hidup. Hanya Tuhan yang menentukan usia kita sejauh mana.”
Air mataku jatuh saat itu juga. Karena baru kali ini aku melihat ekspresi Fajar yang sedih—berbeda saat aku baru saja tahu dia memiliki penyakit kanker otak yang sudah berada di stadium tiga.
“Wa, kalau misalnya aku udah nggak ada di bumi, kamu mau, kan, simpan buku-buku ini?”
Tenggorokanku tercekat, dalam situasi ini, aku tidak tahu harus memberi jawaban yang tepat seperti apa. Karena sebelumnya tak pernah kudapati seorang teman yang diuji oleh penyakit seperti Fajar.
Dia bahkan tidak memiliki harapan untuk hidup lagi.
“Jangan bahas soal itu lagi, ya, Jar. Aku kurang suka.” Ujarku dengan air mata yang menetes.
Fajar tertawa kecil, lantas mengusap hidungnya yang basah. “Maaf. Tapi kamu mau, kan, simpan buku-buku ini nanti?”
Aku menggeleng pelan. “Buku ini berharga buat kamu. Orang asing nggak boleh sembarangan pegang, kayak aku.”
“Kamu bukan orang asing, Wa.”
Aku mengusap kedua pipiku. “Eh?”
Lelaki itu mengulas senyum, lantas menundukkan pandangan. “Enggak jadi.”
Tentu aku bisa membaca maksud Fajar melalui raut wajahnya. Dia ingin mengatakan sesuatu padaku, tetapi dia seperti ragu untuk mengeluarkan kalimatnya.
Aku pun melepaskan genggaman tanganku dengan Fajar.
“Besok aku berangkat ke Singapura, Wa. Berobat di sana.”
Aku bergeming untuk sesaat. “Berapa lama kamu ke Singapura?”
“Hmm… mungkin sebulanan. Terus balik ke sini kalau Team Phoenix menang.”
Aku terkekeh pelan. Akhirnya keadaan hatiku sedikit membaik. “Team Phoenix pasti juara! Kita latihan terus dan berusaha supaya menang. Kalau menang, nanti trofinya buat kamu.”
Fajar tercengang. "Beneran?"
Aku terkekeh menyaksikannya. “Iya, Jar. Kita semua udah sepakat. Kamu simpan trofinya di perpustakaan ini. Kamu juga anggota Team Phoenix, lho.”
“Tapi… aku nggak ikut main…”
“Hei, kita ini tim.” Sahutku.
Fajar menarik ujung bibirnya, tersenyum penuh haru padaku. Aku bisa merasakan perasaannya di hari itu, bahwa dia tak lagi memikirkan soal kematian.
***
Aku tidak berlama-lama saat berkunjung di rumahnya Fajar. Begitu Tante Ninda dan Om Dani kembali dari pasar, aku langsung pamit pulang. Bunda dan papanya Fajar terlihat senang akan kedatanganku kemari, sebab mereka melihat senyuman Fajar saat duduk di kursi roda di ruang tamu.
Sampai di rumah, dan seperti biasa, aku membersihkan diri, menyiapkan buku pelajaran untuk besok, dan juga menyapu lantai rumah karena Ibu sibuk memasak untuk makan malam nanti.
Dan pada malam setelah makan malam, Ari menelepon saat aku baru saja memasuki kamar.
“Iya, Rik?” ucapku seraya duduk di tepi kasur.
“Gimana Fajar tadi?” suara Ari terdengar dari seberang sana.
Aku menghela napas. “Udah stadium akhir.”
“Astaga…”
“Katanya besok dia berangkat ke Singapura buat berobat.”
“Hah? Kok Mama nggak bilang ke aku, sih?” Ari terdengar berseru tertahan.
“I-iya… nggak tahu kalau itu…”
“Terus gimana?”
“Apanya?” aku balik bertanya.
“Mental Fajar nggak down, kan?”
Aku menggigit bibir, menahan air mata yang membendung di kelopak mata. Aku kesulitan menjawab pertanyaan Ari. Namun, aku juga ingin menceritakan semuanya kepada sahabat yang aku percaya agar pundakku terasa ringan.
“Wa?” Ari bersuara.
“Bisa ketemuan aja, nggak, Rik?” Lalu air mataku jatuh tanpa disuruh.
***
Dulu, saat aku dan Ari masih kecil, kami biasa bermain di tepi sawah. Dan itu sangat dekat dengan letak rumah Ari sekarang. Tempat itu terletak di sebuah perumahan dengan pohon besar yang teduh.
Dengan hoodie dan celana panjang yang aku kenakan, aku bertemu Ari yang duduk bertongkat lutut di atas bebatuan dengan kaos putih dan celana selututnya. Dia langsung beranjak bangkit saat menyadari keberadaanku.
“Mau beli es tebu, nggak?” tanya Ari—karena di dekat daerah ini, ada penjual es tebu yang lumayan laris setiap harinya.
Aku mengangguk.
Setelah membeli es tebu yang dibungkus es plastik dengan sedotan—seperti es cekek—kami duduk di bebatuan. Begitu hening untuk sesaat karena aku masih menikmati manisnya es tebu di malam hari ini.
“Iya, Rik.” Aku mulai membuka suara. “Tadi Fajar sempet down, dia bahas soal… ajal ke aku.”
Ari mendengarkan dengan menatap lawan bicaranya.
“Awalnya dia nunjukin perpustakaan pribadinya ke aku. Terus… terus dia nyuruh aku buat simpan buku-buku ini nanti kalau dia udah nggak ada di bumi… Sama aja dia bahas itu, kan, Rik?”
Ari mengangguk pelan.
“Aku nggak bisa ngasih dia jawaban yang bener.” Helaku seraya mengerjap-erjap agar air mataku tak jatuh. “Tapi untungnya aku bisa bikin dia tersenyum tulus. Nanti setelah pulang dari Singapura dan Tim Phoenix juara satu, trofinya buat Fajar.”
Ari mengangguk lagi. “Iya. Kita berlima udah sepakat soal itu.”
Aku mengusap wajah dengan telapak tangan—sementara telapak kiriku memegang plastik dengan es tebu yang tinggal separuh. “Aku boleh bilang sesuatu ke kamu nggak, Rik?”
“Soal?”
Aku menarik napas, lantas membuangnya pelan. Dan dengan penuh keberanian, aku menatap wajahnya, lantas berkata, “Kalau aku suka orang lain, kamu nggak apa-apa, kan?”
Ari terlihat tercengang, lalu kulihat jakunnya bergerak naik-turun. “Maksud kamu…”
Aku mengangguk pelan. “Kamu pasti tahu, kan? Siapa yang aku maksud?”
Ari menggeleng pelan. “Nggak mungkin, Wa.”
“Apanya yang nggak mungkin, Rik?” air mataku terlanjur menetes. “Nggak ada yang tahu soal perasaan. Aku cuma mau minta maaf ke kamu, kalau aku nggak bisa balas perasaan ka—”
“Bukan itu yang aku maksud.” Sahut Ari.
Rahangku rasanya berkedut melihat sahabatku itu memelotot.
Kemudian Ari memegang kedua pundakku. “Aku nggak masalah kamu suka orang lain, atau nggak bisa balas perasaan aku. Tapi kamu beneran suka sama dia? Kamu… kamu mau nyakitin diri kamu sendiri?”
Aku menggeleng sebagai jawabannya. “Perasaan itu muncul tanpa alasan, Rik. Aku suka dia bukan berarti aku mau menyakiti diriku sendiri. Justru keberadaan dia bikin perasaanku senang. Aku tahu kamu peduli sama aku, tapi kamu nggak bisa ngelarang aku buat suka sama seseorang.”
“Iya iya aku tahu.” Ucap Ari, lalu dia memegang keningnya yang boleh jadi terasa pening. “Wa, kamu yakin Fajar akan bertahan hidup?”
“Ya harus yakin, dong!” Aku beranjak berdiri. Saat ini emosiku membludak dengan diiringi oleh air mata. “Besok Fajar akan ke Singapura. Kamu tahu sendiri tenaga medis di sana lebih canggih.”
Ari menatapku dengan pandangan sendu, seolah prihatin dengan keadaanku saat ini.
Aku kembali duduk di bebatuan, lantas menyeruput es tebu dari sedotan, sejenak perasaanku kembali lebih lega setelah membuang semua yang menjadi beban berat di pundakku.
Kemudian Ari menepuk bahuku. Dia tersenyum saat aku baru saja menoleh. “Aku akan mendukung pilihan kamu. Aku sahabatmu, bukan?”
Aku tersenyum, lalu menyeka pipi. “Makasih, dan maaf, Rik.”
“Nggak apa-apa.”
“Kamu cemburu sama Fajar?”
Ari menghela napas, tersenyum kecil. “Kalau dibilang cemburu, sih, iya. Karena dia orang yang bikin kamu jatuh cinta. Aku aja gagal.”
“So sorry…” gumamku pelan.
“Tapi itu perasaan kamu. Aku nggak berhak nentang, aku terima keputusan kamu.” Imbuh Ari dengan tersenyum teduhnya.
Perasaanku di malam itu terasa lebih lega setelah berbagi keluh kesah dengan sahabatku. Saat itu aku benar-benar masih seorang gadis yang naif, yang tidak bisa merasakan bahwa Ari boleh jadi merasa sakit hati karena tahu aku menyukai orang lain.
Namun, demi diriku, malam itu dia tidak mengamuk seperti sebelumnya. Dia mencoba membuatku nyaman, karena cintanya telah tertolak. Dan Ari memilih untuk menjadi seorang sahabat daripada harus memusuhiku.
Aku sadar, saat itu aku benar-benar egois.
***


 hawaeve
hawaeve