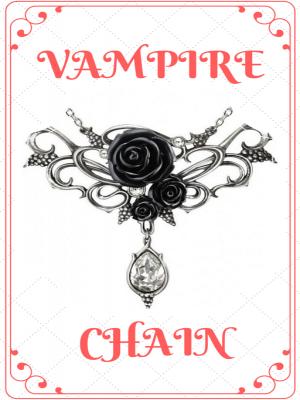Fajar X ML : Bisa, dong. Aku seneng kalau kalian sering datang ke rumah.
Aku membaca balasan Fajar saat setelah mandi sore. Kulihat status WhatsApp-nya masih online, maka aku juga membalasnya lagi,
Me : Kamu kok bisa jatuh dari tempat tidur kemarin, Jar?
Tak perlu menunggu waktu lama, Fajar membalas chat-ku,
Fajar X ML : Ceritanya aku mau ngambil hp, Bunda naruhnya di dalam nakas. Tanganku nggak nyampe, terus jatuh, deh.
Fajar X ML : Tapi aku baik-baik aja, kok😊
Aku tersenyum melihat jawabannya.
Fajar X ML : Tapi aku nggak dibolehin Bunda main AL lagi, Wa. Takutnya aku stress terus kepikiran.
Me : Nggak apa-apa, kok. Yang penting kesehatan kamu No. 1. Dari dulu AL game yang bikin stress, sih😃
Fajar X ML : 😅😅😂
Aku pun tak membalas chat-nya ketika kulihat status WhatsApp Fajar sudah tidak online lagi. Aku membiarkannya istirahat saja. Semua ini demi kebaikannya sendiri walau aku masih ingin mengobrol dengannya lebih lama.
Namun, di sisi lain, aku merasa hampa jika Ari tidak meneleponku sore ini. Biasanya dia selalu merecokiku dengan panggilan dan pertanyaan anehnya. Sudah makan, nggak? Atau, Ke warung ice cream yuk, aku traktir. Padahal aku benar-benar malas keluar rumah.
Tiba-tiba ponselku berdering. Kusangka Ari yang menelepon, rupanya Yaya. Kami saling menyimpan nomor WhatsApp sejak keputusan menjenguk Fajar di rumah sakit tempo hari.
“Halo, Yaya.” Sapaku.
“Halo, Mbak Najwa. Nggak gangguin kan?” di seberang sana, suara Yaya terdengar.
“Eh, enggak, sih…”
“Besok kita jemput Fajar, yuk, Mbak. Katanya dia habis jatuh dari tempat tidur, ya?”
Aku mengangguk pelan. Pasti Rian yang memberitahu. “Aku juga ada niatan mau jenguk dia besok. Tadi Fajar bilang boleh di WA.”
“Oalah, dia udah online WA, Mbak?”
“Iya. Kamu chat dia, nanti dibalas kok.”
“Ehmm, nggak deh, Mbak. Takutnya ganggu. Tapi fiks kita jenguk Fajar bareng-bareng besok, ya, Mbak?”
Aku terkekeh. “Iya, Yaya.”
“Oke, Mbak. Besok kita kumpul di depan ruang guru. Basecamp OSIS lagi dipake rapat soalnya.”
“Iya, nggak apa-apa, Ya. Eh, tapi kamu nggak ikut rapat OSIS, dong?”
Kudengar Yaya yang sedang terkekeh pelan. “Udah diberi izin mau jenguk Fajar sama ketuanya.”
Aku mengangguk-angguk. “Oh, yaudah kalau gitu.”
“Iya, Mbak Najwa. Aku tutup teleponnya dulu, ya.”
Tut. Sambungan diputuskan oleh Yaya. Lalu kuletakkan ponsel itu di atas kasur.
Benar. Kehidupanku sehari-hari selalu seperti ini. Terulang beberapa kali hingga aku bosan harus melakukan apa.
Buku yang aku beli kemarin, membuatku hambar. Agar buku itu tidak tergeletak di kamarku, aku pun berniat untuk memberikannya pada Fajar besok.
Dan pada keesokan harinya, sesuatu telah datang menungguku.
***
Hari itu, benar-benar hari teraneh yang pernah aku alami. Di mana orang yang selalu merecokiku, hanya diam di tempat duduknya dengan ponsel vertikal—tanda tidak bermain game. Saat kusapa, dia tidak membalasnya. Aku tidak sakit hati, tapi… kenapa dia tiba-tiba bersikap seperti itu?
Tidak hanya sapaanku saja, sapaan Rian pun sama sekali tidak ia hiraukan. Ari memasang wajah datar, dengan mata yang seolah tak sanggup menatap semua orang.
Sikap Ari membuatku dan Rian bertanya-tanya sebagai teman dekatnya. Bukankah dia orang yang paling ceria di kelas? Kenapa mendadak sikapnya murung begitu?
Atau… apakah ada masalah dengan keluarganya?
Dan ketika jam pembelajaran telah selesai, aku tidak melihat keberadaannya. Kami sudah berjanji untuk menjenguk Fajar. Aku, Rian, Yaya, dan Guntur berkumpul di depan pos satpam untuk menunggu Ari.
“Jangan-jangan dia pulang?” tanya Yaya cemas.
“Nggak mungkin. Pasti lagi disuruh Pak Setio download software buat ujian harian minggu depan.” Jawab Rian.
“Tapi Mas Arik udah tahu kalau kita ada rencana jenguk Fajar, kan?” tanya Guntur yang ditujukan untukku dan Rian.
Rian mengangguk. “Udah, kok. Dia cuma bilang iya doang.”
Kami manggut-manggut. Tak menunggu waktu lama, kami langsung melihat sosok Ari yang berjalan turun dari tangga.
“Arik, kita jenguk Fajar ke...”
Suaraku mendadak terputus. Wajah ceriaku berangsur lenyap saat Ari bersikap tak acuh kepadaku dan yang lain. Dia justru terus melangkah maju—seolah menganggap aku tak ada.
“Rik?” panggilku, tetapi dia terus berjalan hingga wujudnya keluar dari gerbang.
“ARIK!” kali ini aku benar-benar berteriak. Kesabaranku diuji. Dan karena seruanku itu, Ari menghentikan langkah kakinya.
Di belakangku, Yaya, Guntur, dan Rian saling bertukar pandang.
Aku langsung berjalan cepat menghampiri Ari. Suasana sekolah sudah sepi, sehingga membuat keberanianku untuk berbicara kepada Ari semakin besar tanpa khawatir dicemooh oleh siswa perempuan.
“Maksud kamu apa, sih, Rik?” tanyaku saat sudah menghadap padanya.
Ari mengernyit menatap wajahku. “Kamu nanya? Apa aku harus jelasin ke kamu?”
“Ya harus dijelasin, dong!” balasku dengan tegas. “Sikap kamu ini kayak anak kecil tahu, nggak! Apa-apa maunya dipahami terus!”
“Iya! Aku emang pengennya dipahami terus!” Ari berteriak lantang.
“Tapi kamu nggak mau memahami!” aku langsung menyahut. Entah seperti apa ekspresi wajahku. Saat itu aku benar-benar kesal.
Boleh jadi ketiga temanku di pos satpam menatap getir kami berdua yang sedang berdebat.
“Aku kecewa sama kamu, Wa! Kamu nggak pernah balas perasaan aku!” Balas Ari dengan suara yang lantang.
Aku menggeleng pelan. Saat berdebat dengan seseorang, mataku terasa panas. Dan baru saja perkataan Ari membuat air mataku menetes tanpa disuruh.
“Rupanya kamu bohong, Rik! Kamu bilang, kamu nggak berharap sama aku. Tapi nyatanya kamu ngarep lebih ke aku!” aku berteriak dengan tenggorokan yang rasanya tercekat. "Aku cuma mau kita jenguk Fajar—"
“Selalu aja Fajar yang kamu bahas! Waktu aku ngobrol sama kamu, kamu malah anggap aku benalu! Iya, kan, Wa?!”
“Itu kenyataannya!” aku balas berseru di hadapan wajahnya. “Aku lagi khawatir sama keadaan Fajar, tapi kamu—”
“Kamu lebih khawatir sama dia yang baru kamu kenal, dan kamu sama sekali nggak khawatir sama orang yang udah kenal kamu dari kecil?” sahut Ari dengan mata yang melotot.
Aku menggeleng pelan. “Itu salah kamu sendiri, Rik!” aku sudah menangis, pipiku basah karena air mata. “Aku nggak nyuruh kamu buat suka ke aku, kan? Ekspetasi kamu aja yang ketinggian!”
Ari menatap mataku dengan rahang yang berkedut. Dia tak membalas ucapanku barusan.
Lengang. Aku menarik napas, mengusap kedua pipiku yang basah. Kemudian aku bergerak selangkah mundur. “Kamu cemburu sama Fajar, Rik?” tanyaku dengan suara pelan dan kedua alis yang nyaris bertautan.
“Iya! Aku cemburu! PUAS KAMU?!”
Setelah melontarkan kalimat itu, Ari langsung pergi ke parkiran motor dengan menyenggol pundakku. Aku masih bergeming di tempat. Yaya dari pos satpam datang menghampiri, lantas merangkul pundakku.
Aku tidak pernah berdebat dengan Ari sampai air mataku menetes seperti ini sebelumnya. Pernyataannya itu membuat hatiku sakit. Dan aku pun menyadari kesalahanku sebelumnya.
Ari ingin mendapatkan perhatianku. Dia ingin jawaban atas perasaannya dariku.
“Udah, Mbak. Jangan nangis.” Yaya meletakkan kepalaku di rangkulannya.
Saat menangis, tubuhku terasa lemas. Sehingga hari itu, kami tidak jadi menjenguk Fajar. Rian, Guntur, dan Yaya bersama-sama mengantarku ke rumah. Ibu melihat kedatanganku dengan wajah yang sembab. Kemudian Rian yang menjelaskan kepada Ibu bahwa aku dan Ari baru saja berdebat.
Setelah itu, Yaya, Guntur, dan Rian pergi dari rumah. Rian berkata agar jangan memikirkan ucapan Ari lagi. Besok-besok dia pasti akan menyesal karena telah bersikap seperti ini dengan sahabatnya sendiri.
Namun, aku selalu merenung jika baru saja berdebat dengan seseorang. Bisa dikatakan aku adalah pemilik hati yang sensitif.
Aku duduk di kasur kamar—aku masih belum mengganti seragam karena memikirkan ucapan Ari. Aku mengerjap saat ibuku datang ke kamar dengan membawa potongan buah timun mas kesukaanku.
“Ayo mandi. Kakinya bau tuh.” Ucap ibuku dengan pelan seraya meletakkan piring timun mas di atas meja belajarku.
Aku sempat tersenyum kecil.
“Dulu, rumah kita sama rumah Tante Rani deketan, apalagi kita punya anak yang seumuran. Kalian teman dekat sejak kecil. Ke tempat les barengan, bahkan selalu main barengan sampe maghrib. Cuma waktu SMK ini aja kalian satu sekolah. Waktu kamu kelas empat SD, Tante Rani sama Om Erico pindah ke RT sebelah, soalnya rumahnya yang disini buat tempat tinggal kakaknya Om Erico. Ya, jarak rumah mereka sama rumah kita sekitar dua ratus meter aja, sih.” Ibu mulai bercerita.
Aku senantiasa mendengarkan kalimat Ibu.
“Sejak kecil, kamu sama Ari bertengkar terus. Ari suka godain kamu sampe nangis, dan kamu suka banget bikin emosi Ari meledak. Dulu waktu kecil, pertengkaran kalian lucu deh. Tapi sekarang kayaknya udah beda lagi.” Imbuh Ibu seraya tersenyum.
Kemudian Ibu memegang pundakku. “Kamu boleh cerita ke Ibu, kok, Wa. Tentang masalah apa aja, jangan takut. Kita sesama perempuan, jadi kita bisa saling memahami.”
Kepalaku tertunduk. “Ari suka sama aku, Buk.”
“Ehhh…” ibuku tercengang. “Terus terus?”
“Tapi aku nggak ada perasaan kayak gitu ke dia. Aku cuma anggap dia sebatas sahabat.”
Ibu menghela pelan.
“Dan aku juga punya kenalan lain, dari adik kelas yang namanya Fajar. Kita kenal dari game, bahkan dia juga ikut turnamen karena ajakan Ari. Tapi sekarang dia punya penyakit, jadi nggak bisa ikut turnamen dan main game lagi. Ibu, tadi itu Ari bilang ke aku kalau dia cemburu sama Fajar.” Aku menghadap pada Ibu dengan air mata yang mengalis deras. “Dan dia ngarep ke aku, Buk. Padahal sebelumnya dia bilang nggak masalah kalau aku nggak bisa balas perasaannya.”
Ibu mengusap punggungku. “Kalian sudah dewasa, sebaiknya bisa menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Apalagi ini soal hati yang nggak bisa dipaksakan.”
Aku mengangguk pelan. “Aku juga salah, Buk. Aku kayak nggak adil di matanya. Aku kurang ngasih perhatian ke dia yang… apanya yang perlu diperhatiin, sih?”
Ibu tersenyum. “Nak, orang yang udah jatuh cinta, susah buat nggak cemburu ke orang lain. Ibu nggak belain salah satu di antara kalian berdua. Ibu cuma mau kalian segera damai aja, deh. Cinta itu urusan belakangan.”
Aku mengulum bibir yang kering. “Iya, Ibuk.”
“Berarti ini tadi nggak jadi jenguk Fajar itu, ya?”
Aku mengangguk pelan.
“Ya udah. Besok-besok, kan, bisa jenguk Fajar.”
Aku mengangguk-angguk.
“Udah. Tuh, dimakan buahnya. Ibu tadi beli di pasar, ada diskon. Terus kamu mandi, jangan pake seragam sekolah sambil tidur di kasur. Banyak kumannya.” Tutur Ibu dengan sedikit tawa.
Aku mengangguk-angguk lagi.
***
Lelaki itu mengeluarkan segala sesuatu yang bisa dimakan dari kulkas. Erico sempat heran melihat aksi putra tunggalnya itu.
“Hei hei, jangan banyak-banyak. Nanti Papa nggak kebagian.” Ujar pria dengan kaos dan celana selutut itu. Dia duduk santai di sofa sembari menonton televisi.
“Beli lagi aja.” Jawab Ari dengan ketus, lalu dia membawa beberapa macam camilan, susu kotak, dan buah-buahan segar ke dalam kamarnya.
BRAK! Ari menutup pintu kamar kuat-kuat. Erico di kursi sofa dan Rani yang baru saja kembali dari dapur terkejut melihat reaksi putra tunggalnya itu.
“Ari kenapa, Pa?” Tanya Rani seraya meletakkan dua cangkir teh di meja, lantas duduk di sofa.
Erico mengangkat kedua bahunya. “Barusan ngambil semua makanan di kulkas.”
“Waduh, dia ngambek tuh, Pa.”
“Kenapa ngambek, ya? Apa karena jaringan Wi-Fi, ya, Ma?”
Rani terkekeh.
“Kita samperin yuk, Ma.” Ajak Erico setelah menyeruput sedikit teh dari cangkirnya.
“Jangan. Ntar dia tambah ngambek. Tunggu amarahnya mereda aja.” Pungkas Rani.
Jika diluar Ari terlihat badass, berandalan, dan sebagainya, maka di rumah Ari benar-benar dimanja oleh orangtuanya. Rani maupun Erico bisa menghadapi sikap Ari yang ngambek dengan membiarkannya selama beberapa jam sampai Ari sendiri yang mau bercerita.
Di dalam kamarnya yang penuh dengan poster-poster anime Jepang dan girlgroup asal Korea itu, Ari menyalakan komputernya. Dia akan begadang malam ini dengan bermain game FPS sepuasnya. Di meja belajarnya, terdapat banyak camilan serta kotak susu untuk berjaga-jaga.
Dia masih kesal setelah berdebat dengan Najwa saat di sekolah. Namun, ada sedikit rasa bersalah di benaknya karena telah berkata lantang kepada gadis yang amat ia cintai itu.
Saat komputernya baru saja menyala, Ari meminum susu dari kotaknya, lalu lanjut memakan keripik kentang.
Tiba-tiba ponselnya berdering—beruntungnya Ari belum memulai game-nya. Sehingga dia mengambil ponsel, lantas melihat nama yang tertera di layar itu.
Ari mendengus kasar, lantas menggeser tombol hijau. “Apa?”
“Eh, santai, Bro!” di seberang sana, suara Rian terdengar. “Bentar, Guntur mau ikut.”
“Buruan.”
“Nyalain speaker-nya, Bro!” ucap Rian.
Ari menelan tombol speaker, lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Kemudian Ari bisa mendengar suara Guntur dari telepon itu. Sambungan tiga orang sekaligus.
“Selamat malam, Kakak-kakak,” Suara Guntur terdengar dengan tawa dari seberang sana. “Kita akan membahas perihal insiden yang terjadi tadi siang setengah sore.”
Ari berpangku tangan. Siap mendengarkan.
“Menurut kita, sih, Rik. Kamu harus minta maaf sama Najwa. Kita tahu kalau perasaanmu itu nggak terbalaskan. Tapi yang namanya perasaan, nggak bisa dipaksain, Rik.” Tutur Rian.
“Bener, tuh. Kasih Mbak Najwa waktu buat memutuskan. Kalau hatinya bukan buat Mas Arik, terima aja sih.” Hela Guntur.
“Nggak adil!” seru Ari tertahan.
“Kamu pasti paham, kan, gimana tipikal Najwa? Dari ceritamu aja dia nggak pernah pacaran. Pas aku tanya, sih, dia emang nggak minat sama pacaran.”
“Tapi aku kesel aja… Dia bahasa cowok lain di depanku.” Balas Ari.
“Heh, Rik, bukannya Najwa cuma anggap lu sekedar sahabat, ya? Yang namanya sahabat itu membagi cerita suka-duka.” –Rian
Ari mengusap wajahnya yang terasa dingin, lalu dia meraih remot, mematikan AC di kamarnya.
“Betul kata Mas Iyan, tuh.” Guntur lagi-lagi nimbrung. “Pokoknya bikin Mbak Najwa nyaman. Perilaku Mas Arik tadi sore itu salah banget. Cemburu itu boleh—orang rasa suka, kok. Tapi nggak berhak buat marahin anak orang. Iya, kan?”
“Ya ya ya.” Kata Ari. “Terus aku harus apa?”
“Pake nanya. Ya minta maaf, lah!” –Guntur.
“Najwa itu orangnya peduli, Rik. Jadi nggak perlu kamu cemburu sama Fajar. Apalagi Fajar lagi sakit kanker otak, udah stadium tiga lagi. Najwa sebagai temannya juga peduli, dong.” –Rian.
“Gitu, ya?”
“Logikanya gitu, Rik. Jadi kamu salah banget marahin Najwa tadi.” –Rian.
Lelaki itu mengempaskan punggungnya ke sandaran kursi. Lalu dia memejamkan kedua matanya seraya mengingat kejadian sore tadi.
Di sisi lain, Rani dan Erico diam-diam menguping pembicaraan Ari dengan teman-temannya itu melalui pintu kamar. Mereka pun bisa memahami alasan Ari yang merajuk hari ini.
“Ternyata Arik suka sama Wawa, Ma!” bisik Erico.
Rani mengangguk. “Kirain aja cuma temen. Nggak tahunya lebih.” Lalu dia tertawa pelan.
“Papa! Mama! Aku tahu, ya, kalian di sana!” teriak Ari dari dalam kamarnya. Telinganya itu tajam, seolah bisa mendengar suara napas orangtuanya dari kejauhan.
Rani dan Erico tertawa pelan, lalu mereka pergi dari pintu kamar Ari—membiarkan anak laki-laki mereka menyendiri agar pikirannya tenang.
***
Di sekolah, aku datang dengan rasa yang percaya diri. Aku bertemu dengan Ari di kelas, tetapi aku tidak menyapanya—sengaja tidak menghiraukan keberadaannya. Aku masih merasa sakit hati, pun juga merasa bersalah karena menganggapnya benalu. Padahal selama ini kurasakan dia selalu menghiburku dengan kalimat-kalimat anehnya.
Hari berjalan dengan rasa yang berbeda. Walau aku dan Ari satu kelompok dalam tugas membuat video pendek, kami sama sekali tidak berinteraksi. Aku pun mendengar bisikan-bisikan siswi yang sedang membicarakan kami seperti,
“Eh, Najwa sama Arik kok nggak kayak biasanya, sih?”
“Bertengkar kali.”
“Baru kali ini aku lihat mereka kayak orang asing.”
“Iya, tuh. Biasanya kentel banget.”
Dan lain sebagainya.
Bel pulang pun berbunyi. Tak sengaja aku bertemu dengan Yaya dan Guntur di dekat pos satpam. Aku balas menyapanya, lalu pamit pergi karena aku ingin ke suatu tempat.
Ya. Aku berencana menjenguk Fajar sendirian. Terdengar egois memang—tetapi aku dan Ari masih saling diam—akan sangat tidak enak jika aku tidak mengajak Ari secara aku mengajak Rian, Yaya, dan Guntur.
Aku sempat berhenti di sebuah minimarket, lantas membeli roti, buah-buahan dari uang saku tambahan pemberian Ibu. Ibu bilang aku harus meminta maaf kepada Fajar karena tidak menepati janji.
Karena Fajar tidak online WhatsApp kemarin malam. Kulihat status terkahir dilihat pada 13.21. Jadi aku belum sempat minta maaf, akan lebih baik disampaikan secara langsung saja.
Sekitar lima menit dari minimarket dengan kendaraan motor, aku sampai di rumah Fajar. Kupencet tombol bel di sebelah pagar rumah mewah itu. Kemudian seseorang datang membuka gerbang.
“Eh, Wawa!”
“Met sore, Mbak Tina.” Sapaku riang.
“Ayo masuk, aduh, Nyonya Ninda lagi di luar. Aku sama temenku lagi jagain Fajar main game di kamarnya.” Mbak Tina bercerita.
Sembari memasuki halaman rerumputan yang hijau, aku mengangguk-angguk. “Emang udah dibolehin main game, Mbak?”
“Asalkan bukan game yang bikin stress aja, sih.”
Aku terkekeh pelan.
“Dik Fajar! Lihat siapa yang datang, nih!” seru Mbak Tina saat baru saja ada di kamar Fajar yang khusus untuk main game.
Aku menengok sedikit, lantas tersenyum saat Fajar memutar kursi rodanya ke ke belakang lantas tercengang melihat kedatanganku. Kulihat di komputernya, sepertinya dia bermain game santai berjenis open world RPG atau role-player RPG seperti Genshin.
“Najwa?”
Di dalam ruangan itu, juga ada dua perawat yang lain. Mbak Tina memperkenalkan diriku pada kedua rekan kerjanya.
“Najwa bisa temani Fajar, kok. Kita keluar aja biar nggak ganggu.” Ucap Mbak Tina.
Aku menggeleng. “Nggak apa-apa, kok, Mbak Tina.”
“Udahlah, Wa.” Mbak Tina mengedipkan satu matanya. Kemudian Mbak Tina bersama kedua rekannya keluar dari kamar itu. “Kalau butuh apa-apa, kita di ruang tamu.”
Aku mengangguk, lantas memasuki kamar Fajar. Kemudian aku meletakkan bungkusan kresek putih di atas meja kecil. “Ini dari aku, dari Ibu aku juga.”
“Makasih, Wa.” Ucap Fajar.
Aku mengangguk, lantas duduk di kursi. Ah, keadaan tiba-tiba menjadi canggung begini.
“Eh, gimana keadaan kamu?” tanyaku, membuat topik.
“Agak enakan dikit, sih.Tapi kayaknya aku udah nggak dibolehin sekolah lagi.” Jawab Fajar dengan pandangan yang tertuju pada wajahku.
Aku manggut-manggut.
“Kenapa kemarin nggak datang, Wa?” tanya Fajar dengan tawa ringannya.
“Sebelumnya maaf banget, Jar. Ada masalah dikit. Kemarin kita nggak jadi jenguk kamu.” Ujarku dengan pandangan yang tertunduk.
Fajar ber-oh pelan. Dia tertarik mengobrol denganku dan tidak menghiraukan game-nya. “Masalah apa, Wa? Kamu boleh cerita, kok.”
Pandanganku terangkat, lantas tersenyum simpul. “Sama Arik.”
Fajar memasang tawa pahit, lantas mengangguk-angguk.
“Jadi aku datang ke sini sendirian karena nggak enak hati sama Ari kalau aku ngajak yang lain.”
Fajar mengangguk-angguk walau dia tidak tahu masalah di antara kami berdua. Dan aku tidak mau membuat Fajar memikirkan masalah sepele ini dengan menjelaskan apa yang terjadi. Aku hanya ingin kesehatan Fajar terjaga.
"Oh, iya, Jar." aku mengeluarkan sesuatu dari tas ransel. "Aku sempat beli ini, tapi nggak kebaca. Soalnya nggak terbiasa baca buku non-fiksi. Jadi... buat kamu aja."
Fajar terkekeh. "Yakin buat aku, nih?"
Aku mengangguk-angguk.
Fajar pun menerima buku tersebut dariku. "Aku pinjem, ya, Wa."
"Nggak, buat kamu aja. Percuma kalau aku yang punya."
"Tapi ini bagus lho. Termasuk kategori self-improvement."
Aku tersenyum seraya menggeleng. "Nggak apa-apa, kok. Buat kamu, ambil aja."
Fajar tersenyum tipis. "Makasih, Wa." lalu dia meletakkan buku itu di atas keyboard komputer. "Nanti malam aku baca."
Kemudian suara ketukan pintu terdengar. Aku dan Fajar kompak menoleh. Ada dua reaksi yang berbeda: Fajar tersenyum ceria, sementara aku melotot karena terkejut akan kehadirannya.
“Eh, Mas Arik?”
“Wawa gitu dari dulu. Ke mana-mana nggak ajak-ajak.” Ujar Ari seraya memasuki kamar. Lalu dia meletakkan bingkisan pemberiannya di atas meja—dekat dengan barang bawaanku.
“Makasih udah datang.” Ucap Fajar pada Ari.
Wajahku berpaling dari Ari—aku tidak kuasa menatapnya.
Kulihat dari ujung mata, Ari mengambil kursi lantas duduk di antara aku dan Fajar. Seolah memisahkan jarakku pada juniorku itu.
“Widih, main Genshin, Jar?” ucap Ari dengan pandangan yang tertuju pada layar komputer.
“Newbie.”
“Ooohh. Aku juga main game ini. Tapi di PC, sih.”
"Iya. Kalau di hp kurang jernih aja rasanya."
Dua laki-laki itu tertawa.
Sejenak kudapati Ari dan Fajar menjadi akrab hanya dengan membahas soal game sampai merek device yang muat untuk berbagai macam game. Sejenak aku seolah menjadi nyamuk di sini. Namun, aku senang melihat interaksi mereka. Setidaknya Ari tidak memusuhi Fajar karena cemburu denganku.
“Eh, kalian ada masalah apa?”
Tiba-tiba pertanyaan Fajar membuatku dan Ari bergeming di tempat.
Kemudian Fajar mengubah posisi kursi rodanya dengan kedua tangan—dia pindah tempat di antara aku dan Ari. Lalu Fajar meraih tanganku dan Ari, lantas menyatukan kami seperti orang yang berjabat tangan.
Aku dan Ari saling bertukar pandang.
“Nggak baik sahabat dari kecil suka bertengkar.” Fajar tersenyum lebar. “Dokter Rani pernah bilang kalau waktu kecil kalian sering bertengkar, tapi kalau udah dewasa, mending jangan deh. Soalnya udah beda. Nggak lucu lagi kayak waktu kecil.”
Aku menundukkan pandangan, masih memegang tangan Ari.
“Aku nggak tahu kalian ada masalah apa. Tapi kalian harus damai, nggak ada diem-dieman lagi. OK?” imbuh Fajar.
Aku pun tersenyum simpul—padahal air mataku ingin menetes saat ini juga. Fajar benar-benar orang yang tulus. Dia memang tidak tahu masalah yang kami hadapi, tetapi dia mau membantu kami kembali berdamai.
“Maafin aku, Wa.” Ucap Ari. “Maaf karena udah marahin kamu.”
Aku tersenyum tipis. “Iya. Aku juga minta maaf.”
“Enggak. Aku yang salah di sini. Kamu nggak salah, kok, Wa.” Sahut Ari.
“Tetep aja aku salah karena bikin kamu marah-marah.” Balasku.
“Nggak-nggak. Aku aja yang nggak bisa nahan emosi.”
Kemudian kami berdua sama-sama tertawa. Fajar di tengah-tengah kami menghela napas lega melihatku dan Ari yang sudah bisa berdamai lagi.
“Nah, gitu dong. Aku suka, lho, lihat kalian berdua ketawa.” Ucap Fajar seraya merangkul pundak kami berdua.
Kulepas tanganku dari Ari, kemudian kami saling bersitatap sembari tersenyum. Aku pun menyadari satu hal, bahwa kunci perdamaian dalam suatu hubungan adalah dengan saling berebut kesalahan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirinya paling benar.
Apakah Ari juga berpikir seperti itu?
***


 hawaeve
hawaeve