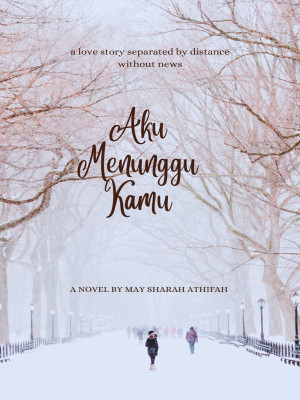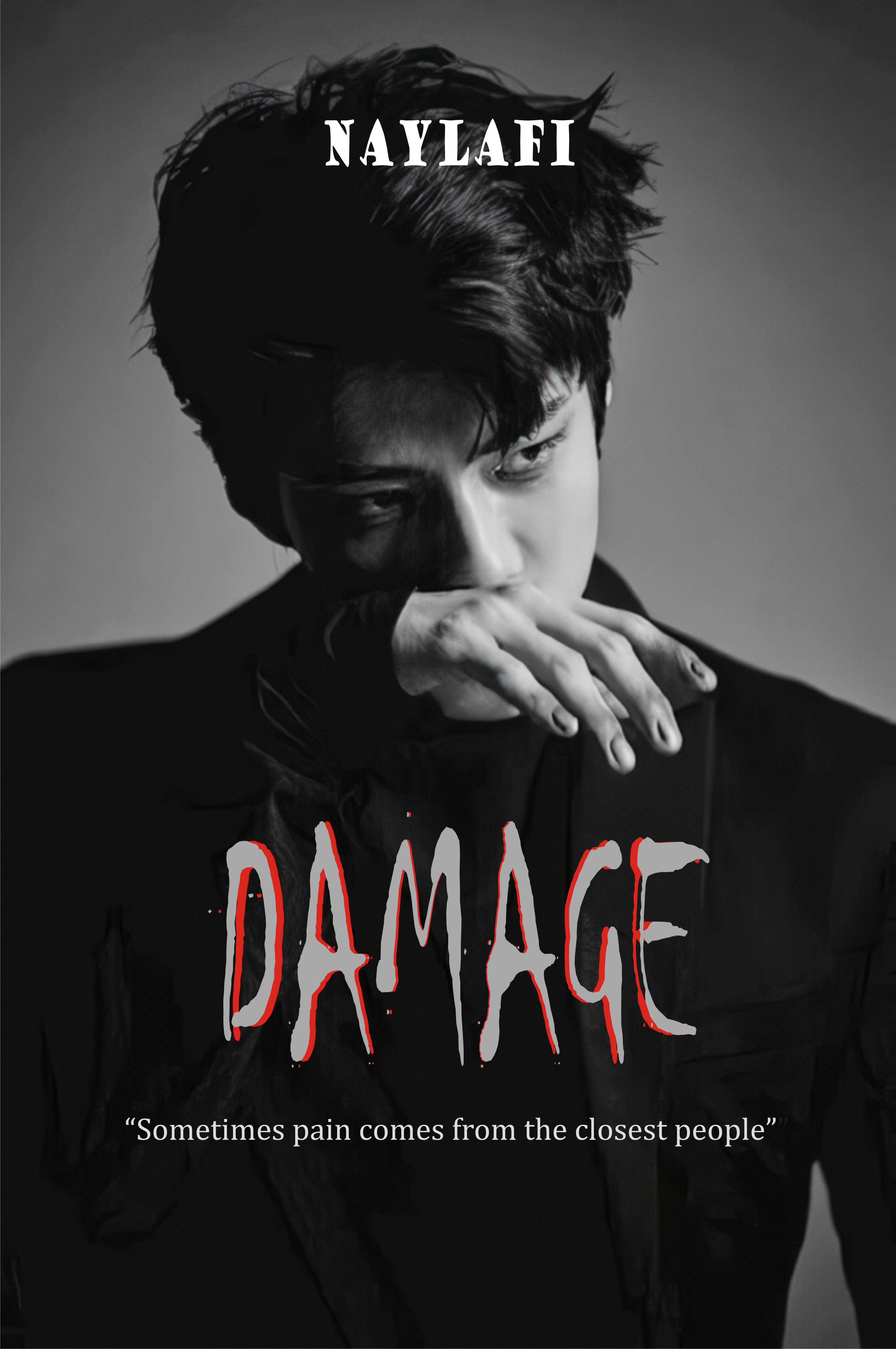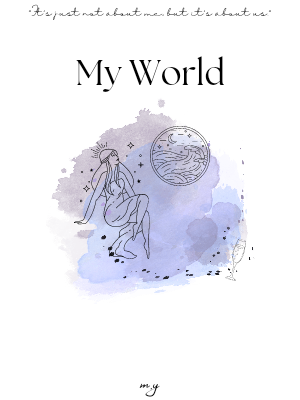(Mimpi)
"Lihat teman-temanmu itu! Mereka tak pernah membangkang. Tidak sepertimu!"
"Itu karena orang tua mereka mendidik dengan benar!" Aku balas berteriak, tidak peduli menjadi anak yang durhaka.
"Mereka selalu menunjukkan sopan santun! Bukan sepertimu, dasar batu! Enyah dari hadapanku!" bentak wanita di depanku ini, tak lain ibu kandungku sendiri. Bahkan aku masih bertanya-tanya apa benar wanita berwatak keras ini memang sungguh ibu kandungku.
"Seharusnya kau bersyukur mempunyai anak cerdas sepertiku!" usapku sinis. Jangan salahkan aku yang hanya mencontoh sikap wanita itu.
"Teman-temanmu itu suka berbagi, tidak pelit sepertimu." Ia menekan kalimat itu, membuat rahangnya tampak keras.
"Mereka berbagi karena tidak ada hal penting yang harus dibeli. Sedangkan aku? Aku harus membeli banyak buku untuk persiapan Olimpiade Sains nanti. Tidakkah kau mengerti perasaanku ini? Terlalu banyak pikiran yang bersarang di otakku. Ditambah lagi kau memarahiku di saat aku harus belajar karena besok simulasi," ucapku dengan penuh penekanan, kurasakan otot leherku menegang.
Sikap menurut pada orang tua? Itu bukan sifatku. Aku pembangkang. Ingat itu. Bukankah sifat anak tergantung orang tua? Terkadang aku ingin mempunyai orang tua seperti guru Bimbingan Konseling di sekolahku yang memahami bagaimana menghadapi anak.
"Sedari kecil kau sakit-sakitan. Kau tidak tahu uang yang kuhabiskan untukmu berobat! Jangan sombong hanya karena terpilih Olimpiade!"
"Kalau Ibu tidak ikhlas mengobatiku, kenapa dulu membawaku berobat? Bukankah Ibu senang bila aku tidak ada di dunia ini?"
Ibu akan memukul kepalaku dengan tongkat sapu yang sedari tadi dipegangnya. Sebelum tongkat itu mendarat, aku sudah terlebih dahulu membuka mata dengan jantung berdentum.
"Viva, Minum dulu." Suara lemah lembut menyadarkanku dari mimpi, lebih tepatnya kilas balik diriku waktu bertengkar hebat dengan Ibu.
Aku meneguk segelas bambu air bening. Sejenak pandanganku berkunang. Nyupena (mimpi) itu sama persis dengan kejadian empat tahun yang lalu. Sedikit menyesal telah membangkang pada orang tua, tapi tetap saja menyakitkan bila aku dibanding-bandingkan dengan orang lain.
Mungkin aku bisa terlempar ke masa ini karena anugerah bisa terbebas dari kemarahan Ibu. Atau malah kutukan karena menjadi anak durhaka? Entahlah, yang penting aku sekarang betah tinggal di masa ini.
"Boleh Emak tahu kau melindur apa sampai menangis begini?" tanyanya menyadarkanku yang tengah berderai air mata.
Aku memeluk Emak dengan erat, mencoba mengenyahkan ingatan tentang masa lalu kelam yang selalu saja menghantuiku.
"Emak sayang padaku, kan?" tanyaku.
"Tentu saja. Apa pun yang terjadi, Emak sangat-sangat menyayangimu lebih dari siapa pun," jawabnya sambil tersenyum.
Aku bersyukur dipertemukan dengan Mak Lastri di masa ini. Kuharap, selamanya aku tetap di sini bersama orang-orang yang menyayangiku.
🌼
Aku yang tadinya berniat menemui Arya di sawah, urung karena Dadari yang bertamu ke rumahku. Ia menenteng mainan tradisional dakon dari kayu dan batu untuk kami mainkan bersama. Aku hanya menang satu kali di empat permainan. Tentu saja! Aku kan sudah lupa bagaimana cara memainkan permainan ini. Terakhir kali adalah waktu Sekolah Dasar karena setelah itu aku tidak mempunyai teman yang bisa diajak bermain permainan tradisional.
Setelah lelah bermain bak masa kecil kurang bahagia, kami duduk bersantai di bangku pelataran, menikmati hilir mudik orang yang melintas membawa sekeranjang rumput maupun padi.
Rumah Mak Lastri berada di pinggir jalan, begitu pula rumah Dadari. Jarak rumah satu sama lain lumayan jauh, sekitar tiga puluh meter. Tempat tinggal kami lumayan jauh dari keramaian pasar. Setiap harinya hanya terdengar aktivitas orang di hutan dan juga kicau burung serta gonggongan anjing yang tidak sebising suara knalpot motor. Di samping itu, lain lagi saat malam hari yang terlampau sunyi sampai suara ranting jatuh dan semak bergoyang pun terdengar sangat jelas.
"Siapa lelaki tampan waktu itu?" celetuk Dadari. Aku yakin siapa yang dimaksudnya.
"Arya, dia sahabatku." Berat mengakui kalau dirinya hanya sahabatku, tapi bagaimana lagi memang itu kenyataannya. Aku tidak memiliki hubungan khusus dengan Arya. Hubungan tanpa status katanya selalu jaya.
"Bisakah kau mengenalkanku padanya?" tanya Dadari dengan berseri-seri.
Aku memaksakan sudut mulut untuk tertarik ke atas, yang berujung senyumanku itu berkedut. Aku mengangguk sembari memalingkan muka tak nyaman. Aku khawatir kalau mereka kenalan, Arya bakal naksir padanya. Secara, paras Dadari enak dipandang dengan mata bulat yang selalu menyipit tiap kali tertawa, bulu matanya lentik alami, hidung mungil di tengah wajah tirusnya, dan bibir yang juga mungil semerah delima. Tak ayal tubuhnya montok juga. Lelaki mana yang akan menolaknya?
Aku menunduk, memastikan dada Nayaviva tak kalah dari Dadari. Aku melipat bibir, kecewa menemukan dada yang tampak kecil menggunung. Sementara itu, aku belum tahu bagaimana wajah seorang Nayaviva. Lain waktu aku bakal minta Emak memberikanku sebuah cermin.


 orenertaja
orenertaja