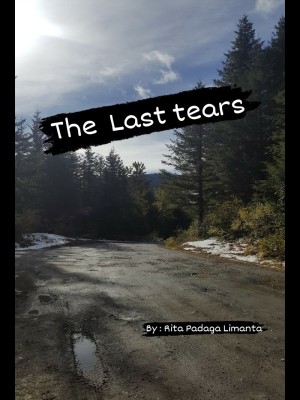Jumat, 6 September 2013
Secangkir kopi susu menemani pagiku. Katanya kafein yang terkandung di dalamnya mampu mengendurkan syaraf yang tegang. Membuat pembuluh darah melebar sehingga melancarkan peredaran darah.
“Bagaimana, enak kan kopi buatanku?” ucap Felix yang berjalan dari arah dapur.
“Sluurp … aah,” aku menyeruput kopi buatan Felix, “Sedap. Persis kopi yang dijual di Kafe-kafe.”
“Ah bisa saja kau, Fyan.”
“Aku serius.”
Felix berjalan mendekatiku. Ia berbisik di sebelahku.
“’Aini mau menikah?”
Seketika aku mematung.
“Dari mana Felix tahu?” batinku.
“Aku mendengar perbincanganmu dengan ’Aini tadi malam.”
“Mungkin kau salah dengar.”
“Ah tidak …,” ucap Felix, lalu duduk dikursi belajarnya, “aku sempat mendengar sedikit percakapanmu semalam dengan ’Aini.”
“Aneh. Aku baru tahu kalau ada orang tidur yang bisa menguping pembicaraan orang lain.”
“Bukan begitu. Aku sempat terbangun sebentar. Lalu melanjutkan lagi mimpiku. Sayang kalau mimpi indah itu tidak dilanjutkan.”
“Kau kira mimpi itu seperti series film di TV?” Aku tertawa kecil.
“Siapa tahu saja aku sedang beruntung. Ya kan?” sahut Felix sambil meniup-niup kopi panas di cangkir berukuran sedang berwarna orange.
“Ada-ada saja kau, Fel.”
“Kalau kuperhatikan, kau tak pernah melakukan video call dengan Emak dan ‘Aini ya, Fyan?”
“Pernah, kok. Kau ingat saat kita wisuda kan?”
Felix mengangguk.
“Hanya saja kalau aku sedang di apartemen ‘Aini memang hampir tidak pernah melakukan video call.”
“Kenapa?”
“Dia tahu ada lelaki lain yang bukan mahramnya di sini.”
“Apa hubungannya?”
“Adikku malas karena mesti pakai jilbab. Khawatir terlihat auratnya kepada yang bukan mahramnya.”
“O ….” Felix mengangguk “Jadi ….”
“Tok … tok … tok ….”
Felix tidak melanjutkan ucapannya saat mendengar bunyi ketukan pintu apartemen kami. Felix berjalan menuju pintu.
“Siapa, Fel?” tanyaku pada Felix saat ia mengintip keadaan di luar dari lubang kecil di pintu.
“Fritz.”
Felix membuka pintu. Fritz langsung masuk dan menghampiriku. Tanpa basa basi ia langsung menyeruput kopi yang ada di mejaku.
“Tumben kau pagi-pagi ke sini?”
Fritz merebahkan badannya di kasurku.
“Pasti ada yang ingin ditanyakan,” ucap Felix.
“Semalam aku baru saja membaca artikel di internet.”
Aku memalingkan wajahku ke arah Fritz. Sementara Felix berjalan mendekat, lalu duduk di tepi kasurku.
“Sebuah tuduhan yang diarahkan untuk Nabi kita,” lanjut Fritz.
Aku menyimak ucapan Fritz. Felix pun tak kalah serunya ikut menyimak.
“Memangnya artikel apa yang kau baca, Fritz?” tanyaku
Fritz menceritakan tentang artikel yang dibacanya. Sebuah artikel yang ditulis oleh pihak yang tidak suka dengan Islam. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pedofilia lantaran menikah dengan seorang bocah.
“Benar begitu, Fyan, Nabi menikahi ‘Aisyah di usia enam tahun?”
“Wah masih kecil sekali,” sahut Felix, “Jadi benar Nabi kalian itu Pedofilia?”
“Hei, kau jangan kurang ajar, Fel,” ucap Fritz kesal sambil mengusung kepalnya, “Jangan kau tuduh Nabi kami dengan tuduhan keji seperti itu.”
Tuduhan Nabi sebagai pedofilia, seorang yang orientasi seksualnya tertarik kepada anak-anak, memang sudah menjadi fitnah keji para orientalis. Kali ini aku mendengarnya langsung dari mulut room mate-ku sendiri, Felix.
“Benar. Beliau memang menikahi ‘Aisyah Radhiallahu ‘Anha saat masih berusia enam tahun. Namun, baru menjalani rumah tangga berumah tagga dengan Nabi saat usianya sembilan tahun,” ucapku sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.
Fritz melenggong. Mulutnya terbuka lebar.
“Jadi benar?” ucap Fritz meyakinkan.
“Pada riwayat lain ada juga yang menyebutkan bahwa usia ‘Aisyah Radhiallahu ‘Anha saat menikah dengan Nabi adalah tujuh tahun,” ucapku melanjutkan, “namun perbedaan enam atau tujuh tahun itu sama sekali tidak masalah. Seperti halnya kita saat menyebutkan usia. Kadang kita menyebutkannya selisih satu tahun. Seperti halnya tahun ini usiaku sudah masuk usia dua puluh empat tahun, walau menurut bulannya aku belum genap dua puluh empat tahun. Kadang aku menyebutnya dua puluh tiga tahun jalan dua puluh empat tahun atau dua puluh empat tahun jalan.”
“Enam tahun atau tujuh tahun? Tetap saja itu masih usia anak-anak, Fyan,” tegas Felix, “kasihan sekali nasib si anak.”
***
“Apa mungkin riwayatnya tidak valid?” tanya Fritz meragukan.
“Tentang usia Aisyah saat dinikahi Nabi itu diriwayatkan oleh dua imam hadits yang karya mereka telah diakui sebagai kitab paling shahih setelah Al-Qur’an. Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya,” jawabku meluruskan, “Tidak pantas kita menuduh mereka sebagai pendusta apalagi penyebab fitnah karena telah meriwayatkan kisah pernikahan Nabi dengan Aisyah.”
Lalu, aku menceritakan secara singkat kisahnya. Sebuah kisah yang diriwayatkah oleh Imam Bukhari dalam haditsnya menyebutkan bahwa selama tiga malam berturut-turut Rasulullah memimpikan hal yang sama. Sesosok malaikat mendatangi Sang Nabi dengan membawa gambar ’Aisyah yang dibungkus dengan kain sutera. Malaikat mengatakan pada Sang Nabi bahwa sosok wanita yang ada pada gambar yang dibawanya adalah istrinya.
“Bukan begitu maksudku,” ucap Fritz.
“Apa kau pikir hadits tentang ‘Aisyah Radhiallahu ‘Anha menikah di usia enam tahun itu dhaif atau bahkan palsu? Lantas apakah yang tidak suka dengan islam akan berhenti memfitnah?”
“Ya, tapi aku rasa itu sangat tidak rasional, Fyan.”
“Apakah rasio manusia yang menjadi tolak ukur keautentikan sebuah hadits, Fritz? Apakah hanya hadits yang cocok dengan akal baru dianggap shahih? Jika tidak cocok maka menjadi tidak shahih?”
Fritz menegakkan badan, lalu manyandarkannya di dinding.
“Apa kau pernah tahu kisah tentang butanya mata malaikat maut karena dicolok oleh Nabi Musa ‘Alaihissalam pada saat Nabi Musa hendak dicabut nyawanya?”
Fritz menggelang.
“Atau kau pernah mendengar kisah tentang perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa ‘Alaihissalam tentang sebab Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Nabi Muhammad melihat Nabi Musa sedang shalat di dalam kuburnya? Ibu yang membunuh bayinya maka si ibu dan bayinya masuk ke neraka?”
Sekali lagi Fritz pun menggelang.
“Lantas apakah serta merta kita mendhaifkan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim lantaran kisah itu tidak rasional menurut akal manusia?”
Fritz terdiam. Kerutan di dahinya seolah menautkan kedua alisnya.
“Jangan hanya karena takut akan fitnahan dari orang yang tidak suka dengan Islam lantas kita langsung ber-apologetic bahwa segala hadits yang dituduhkan itu berstatus lemah. Justru sebaliknya, kita harus memberikan pembelaan. Dengan cara yang benar. Bukan malah meragukan keabsahan hadits shahih. ”
***
“Kita bisa mengatakan seseorang itu pedofilia jika orientasi seksualnya hanya kepada anak-anak. Sementara Nabi Muhammad sangat jauh dari orientasi seperti itu. Kalau memang Beliau seorang pedofilia tentulah semua istrinya, atau sebagian besarnya, adalah wanita berusia anak-anak. Pada kenyataannya mayoritas istri Nabi adalah janda, wanita dewasa bahkan ada yang sudah tua. Hanya ‘Aisyah Radhiallahu ‘Anha yang dinikahi Nabi pada usia sangat belia.
“Rasanya tidak masuk akal saja ada orang yang sudah tua menikahi seorang bocah,” ucap Felix.
“Perlu kau ketahui Fel, bahwa hal pertama yang harus diimani oleh umat islam adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukanlah berdasarkan dari hawa nafsu. Bukan atas dasar keinginan manusiawi semata. Namun, dilakukan atas perintah dari Allah,” ucapku menjelaskan, lalu mengutip terjemahan Al-Qur’an Surah an-Najm ayat ketiga sampai dengan ayat kelima, “… dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.”
“Termasuk pernikahan Sang Nabi dengan Aisyah, puteri dari sahabat terdekatnya, Abu Bakar Shiddiq?” tanya Fritz.
“Tentu saja,” jawabku meyakinkan, “Bagi kita mungkin tidak masuk akal kerana kita membandingkannya pada masa sekarang.”
“Maksudmu itu hal yang wajar di masa Nabi, Fyan?” tanya Fritz.
“Salah satu contohnya adalah Abdullah bin Amr bin Al ‘Ash yang hanya berbeda 11 tahun dari Amr bin Al ‘Ash, ayahnya,” ucapku memberikan contoh, “itu artinya kita bisa mengetahui bahwa Amr bin Al Ash menikah pada usia yang masih sangat belia.”
“Tetap saja menurutku itu sebuah keanehan,” ucap Felix, “Aneh saja saat melihat seorang menikah di usia sekitar 10 hingga 13 tahun.”
“Aneh?” tanyaku.
“Jangan kau bilang kalau pernikahan di usia dini ini juga ada dalam agamaku?”
Aku menarik napas. Seperti biasa Felix memandang skeptis padaku. Aku yakin pasti dia tidak mudah percaya begitu saja dengan penjelasanku tentang kitab sucinya.
“Itu tidak mungkin.” Felix mengelak.
“Bagaimana jika aku bisa membuktikannya?”
***


 hadismevlana
hadismevlana