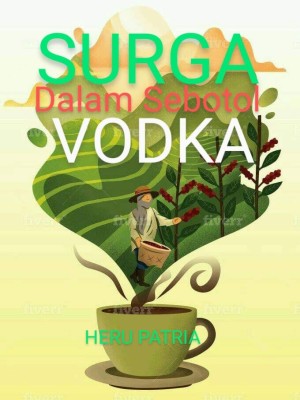Hingga tengah malam mataku sulit terpejam. Rasanya hari ini begitu banyak persoalan hidup. Detak jarum jam terdengar begitu jelas. Sementara Felix sudah terlelap sejak beberapa jam lalu. Segala aktivitas sudah kulakukan. Mulai dari salat sunnah hingga menuntaskan bacaaan satu juz Al-Qur’an. Satu buku pun sudah selesai kubaca. Namun, yang kudapati hanya kedua mata yang lelah. Ketika kurebahkan badan dan kupejamkan mata rasanya sulit sekali untuk melelapkannya. Seolah aku lupa bagaimana cara sederhana untuk tidur seperti sebelum-sebelumnya.
Hatiku gundah. Harusnya ucapan Om Thimoty di pesta tadi membuatku bahagia. Sebab dia telah memberikan restunya kepadaku untuk menjadikan putrinya belahan jiwa. Namun, pada kenyataannya kini hatiku dalam dilema. Mendadak, restu dari Om Thimoty seolah menjadi momok yang menakutkan. Bagaimana aku bisa lega? Sementara hingga detik ini aku belum berhasil mendapat restu dari Emak.
Tengah malam tiba-tiba handphone-ku berdering. Aku meraihnya dengan meraba-raba meja belajar. Mataku sudah cukup berat tapi tak kunjung terpejam juga. Badanku sudah cukup lelah meski untuk bangun sejenak. Jika menelepon di jam segini siapa lagi kalau bukan dari Teluk Kuantan?
Jarak dan waktu kadang menjadi hambatan. Kadang ‘Aini lupa jika meneleponku saat siang di Teluk Kuantan, maka di Saskaton sudah tengah malam.
“Sudah mau tidur ya, Bang?” Terdengar suara ‘Aini dari seberang sana.
“Hmmm …,”jawabku singkat.
“Baru saja Pak Ramli datang melamar ‘Aini.”
Seketika mataku segar. Aku langsung mendudukkan tubuhku dan bersandar. Tak lama terdengar suara sesegukkan dari ‘Aini. Aku berdiri berjalan menuju jendela, lalu mengintip gelap malam di luar sana. Aku mencoba menenangkan ’Aini. Agak lama, akhirnya ’Aini pun membuka suaranya.
“Lepas pulang sekolah ’Aini heran melihat ada sejumlah uang dari mulut ampop coklat yang terbuka. Ada Pak Ramli juga di sana.”
“Mau apa Pak Ramli datang lagi ke rumah? Uang buat apa? Emak sakit lagi?”
“Nggak, Bang.”
“Lalu buat apa Pak Ramli bawa uang ke rumah?”
“Pak Ramli mau melamar ’Aini, Bang.”
Lalu ‘Aini menceritakan kejadian beberapa lalu yang baru saja membuat shock dirinya.
***
POV: ‘Aini
“Ada apa ini, Mak?”
Emak hanya terdiam. Aku melihat ke arah Pak Ramli. Kulihat, ia tersenyum genit ke arahku sambil memainkan janggut tips di dagunya.
“Begini,” ucap Pak Ramli sambil menegakkan duduknya, “maksud kedatangan saya hari ini adalah untu melamar Dik ’Aini.”
Aku sangat kaget dengan ucapan yang baru saja kelauar dari mulut Pak Ramli.
“Maksud Bapak?” ucapku sambil mengerutkan dahi.
“Tenang, tidak usah kaget seperti itu. Nggak terburu-buru kok. Saya akan menunggu ’Aini sampai lulus sekolah.”
Darahku bergejolak panas. Napasku memburu mendengar ucapan Pak Ramli yang seperti tanpa dosa itu.
“Maaf, Pak. Jangan samakan saya dengan perempuan lain yang mudah tergiur dengan uang apalagi sampai dinilai jelek karena disebut sebagai perempuan perebut suami orang.”
“O tidak ... kamu tidak merebut suami orang. Saya akan menceraikan Rini.”
“Tidak. Bapak tidak perlu menceraikan Mbak Rini. Bapak juga tidak perlu repot harus menunggu saya lulus sekolah. Lebih baik Bapak fokus dengan Mbak Rini dan istri pertama Bapak, juga kepada anak-anak bapak. Bapak punya tanggung jawab besar membahagiakan mereka.”
“Insyaallah mereka sudah terjamin. Saya adil menafkahi mereka.”
“Maaf, Pak tapi saya ....”
Belum selesai aku berucap, Pak Ramli pun memotongnya.
“Loh apa salahnya berpoligami? Selama saya bisa adil dan mencukupi nafkah anak istri saya. Lagi pula poligami tidak haram kan? Sunnah Nabi pula?”
Dengan santainya Pak Ramli berucap seperti itu. Sementara aku tidak terima dengan sikapnya yang seolah menggampangkan urusan agama.
“Poligami memang tidak haram tapi juga bukan menjadi suatu kewajiban kan? Jika Pak Ramli berdalil bahwa poligami itu sebagai sunnah nabi, masih banyak kok sunnah-sunnah nabi lainnya seperti sedekah, dhuha, tahajud, menyantuni janda-janda dan yatim yang tidak mampu. Sebelum jauh mengamalkan poligami mungkin bapak bisa lebih fokus ke sunnah yang lain. Atau bahkan menunaikan kewajiban seorang laki-laki muslim seperti salat berjamaan tepat waktu di masjid misalnya?”
Aku masuk ke kamar. Pak Ramli terlihat kecewa dan malu dengan responku. Sementara Emak hanya terdiam dan juga merasa tidak enak. Tak berapa lama, aku kembali keluar dari kamar dengan membawa sejumlah uang dan kwitansi rumah sakit.
“Alhamdulillah kami ada sedikit rezeki untuk mengganti uang bapak tempo hari,” ucapku sambil menyerahkan uang itu dengan meletakkannya di atas meja.
Pak Ramli makin merasa malu dan salah tingkah.
“Hutang kami sudah lunas ya Pak. Terima kasih sudah membantu keluarga kami. Kami akan selalu ingat dengan kebaikan Bapak. Tapi bukan berarti bapak bisa membeli kami dengan harta Bapak,” ucapku dengan suara menahan amarah sambil meletakkan uang di atas meja, “agar tidak terjadi fitnah dan kejadian Mba Rini melabrak saya terulang lagi, saya mohon bapak tidak perlu datang ke tempat kami. Bukan kami bermaksud memutus silaturahmi tapi saya hanya berusaha untuk tidak terjadi mudharat yang lebih besar menimpa keluarga kami.
“Kalau begitu saya pamit dulu Mak, ’Aini.”
Pak Ramli berdiri, lalu berjalan keluar.
“Pak Ramli?” panggilku.
Pak Ramli berhenti sejenak sambil menengok ke arahku.
“Uang bapak,” ucapku sambil menyerahkan uang yang tadi tergeletak di atas meja.
Pak Ramli mengambil uangnya, lalu keluar sambil tertunduk malu. Aku menghampiri Emak.
“Emak sudah coba menolak Pak Ramli, tapi dia terus memaksa.”
“Ya Mak, ’Aini ngerti kok. ’Aini yakin Mak nggak akan tega kalau ’Aini harus menikah dengan Pak Ramli kan? Emak kan pernah bilang: biar kita hidup serba kekurangan tapi kita harus tetap punya harga diri.”
Emak mengangguk pelan, lalu memeluk sambil mengusap kepalaku pelan.
“Kalau masih ada Abah atau ada Bang Sofyan di sini mungkin kita tidak direndahkan seperti ini ya Mak,” ucap ’Aini lirih di pelukan Emak.
***
Hampir setengah jam ‘Aini menceritakan keluh kesahnya atas lamaran Pak Ramli. Akhirnya ‘Aini lega setelah mengungkapkan semua isi hatinya. Beruntung aku segera mengirimkan uang untuk mengganti biaya operasi untuk Emak tempo hari. Kalau tidak, mungkin ceritanya akan berbeda. Banyak orang yang memanfaatkan situasi. Seolah baik. Padahal ada maksud tertentu di balik semuanya. Aku paling tidak suka dengan orang yang memanfaatkan kelemahan orang. Pamrih. Menagih balas budi atas kebaikan yang sudah diperbuatnya.
“Tapi ngomong-ngomong, Pak Ramli tuh cakep juga loh, orang kaya lagi,” ucapku menggoda, “Kenapa ’Aini nggak mau?”
“Itu semua nggak ngejamin akan hidup bahagia ke depannya, Bang. Kan Abang pernah bilang, cari pasangan hidup itu nggak cukup hanya modal rupa dan harta, tapi juga kesolehannya!”
“Memangnya Pak Ramli itu kurang sholeh?”
“Iya.”
“Tahu dari mana?”
“Paling gampang itu kita perhatikan aja salatnya. Seberapa baik dia menjaga salatnya.”
“Memangnya ‘Aini memantau terus aktivitas ibadahnya?”
“Nggak sih Bang. Cuma pernah sih tempo hari saat Pak Ramli datang ke rumah. Saat sudah terdengar azan isya dia malah asyik ngobrol sama Emak.”
“Mungkin dia akan salat di rumah?”
“Ya mungkin, tapi bukankah Abang pernah bilang, kalau salah satu ciri lelaki muslim baik itu nggak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Terutama salat isya dan shubuh.”
Percakapan di telepon usai. Tapi ada satu urusanku yang masih menggantung. Restu dari Emak. Rasanya masih ingin berlama-lama. Namun, waktu terus merangkak meminta untuk memberikan tubuhku untuk beristirahat. Apalagi percakapan terakhirku dengan ’Aini tadi tentang salat isya dan shubuh berjamaah. Jangan sampai hanya karena tidur larut malam aku kehilangan keutamaan sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam muslim dalam haditsnya:
“Barang siapa yang melaksanakan shalat Isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan shalat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan shalat Shubuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan shalat semalaman penuh.”
Jangan sampai kejadiaan tempo hari terulang kembali. Sesalnya sungguh tak tergantikan. Rugi rasanya meski masih bisa melakukan salat secara mandiri. Sebab Allah memiliki keutamaan bagi mereka yang menjalankannya. Tentunya yang paling penting aku tak ingin dicap sebagai orang munafik sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam haditsnya:
“Tidak ada shalat yang paling berat bagi orang munafik daripada shalat Shubuh dan Isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak.”
Kupasang alarm berlapis sebagai ikhtiar agar tidak telat salat berjamaah. Lalu kucoba pejamkan mata seraya lirih mengucap doa.
“Bismika allahumma ahya wa bismika amut.”
***


 hadismevlana
hadismevlana