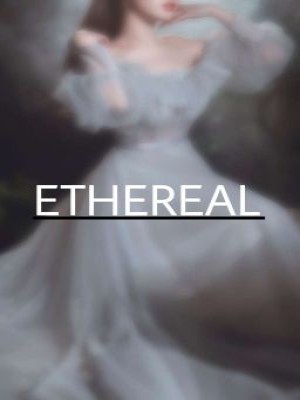Usai aku membacakan puisi di acara pesta tadi, Om Thimoty mengambil microphone. Aku dan Felix belum sempat beranjak dari posisi semula. Tiba-tiba Om Thimoty menceritakan kejadian beberapa hari lalu saat aku hendak melamar putrinya. Setelah tempo hari aku mendapati seolah Om Thimoty menolak lamaran hari ini terjadi hal sebaliknya. Bahkan Om Thimoty mengumumkannya di hadapan para tamu undangan.
Seketika jantungku seolah berhenti berdetak saat sebuah ucapan yang seharusnya membuatku bahagia meluncur dari bibirnya. Restu seorang ayah kepada lelaki yang hendak meminang putrinya. Aku seperti berada di suatu dimensi di mana waktu mati dan semua benda yang bergerak tiba-tiba berhenti. Harusnya aku menjadi salah seorang lelaki paling bahagia. Lelaki paling beruntung sebab akhirnya mendapatkan restu dari ayah seorang gadis berhati mulia dan berwajah jelita. Sungguh seharusnya aku adalah lelaki paling mujur di antara pria-pria yang menaruh hati padanya.
“Bagaimana Sofyan?” tanya Om Thimoty sambil tersenyum.
Ucapan Om Thimoty membuat seolah nyawaku terlepas dari raga. Sungguh ini di luar rencana. Aku bingung harus menjawab apa. Semua mata tertuju padaku seolah memintaku untuk segera menjawabnya. Jika memang benar Om Thimoty merestui hubunganku dengan Kiara, lalu apa maksud reaksinya tempo hari saat aku datang ke apartemen Kiara untuk melamar putrinya? Apa maksud Om Thimoty tempo hari yang langsung pergi meninggalkanku tanpa merespon lamaranku sepatah kata pun?
“Ya Allah, aku harus menjawab apa?” batinku.
Permintaan Om Thymoty begitu sulit terlaksana sekejap mata. Sebuah permintaan yang menurutku sangat berat. Dalam waktu sesingkat ini aku harus memutuskan perkara besar dalam hidupku. Sebuah pernikahan.
“Ini sudah di depan matamu, Fyan. Cukup mendengar kesedianmu dan kau akan hidup bahagia dengan seorang wanita yang selama ini kau cinta.” Seolah ada bisikan itu di telingaku.
Pasalnya beberapa waktu lalu saat perjalanan menuju Delta Hotels by Marriott Bessborough aku belum juga berhasil menelepon Emak. Akankah Emak merestui pilihanku? Jika tidak aku tidak hanya akan membuat hati Kiara terluka, tetapi juga keluarga besarnya. Jika saja Emak benar-benar tidak setuju dengan wanita pilihanku, entah apa yang harus kukatakan pada Om Thimoty nanti. Tentu aku akan merasa orang paling bersalah. Mungkin ia akan menuduhku sebagai seorang lelaki tak punya hati. Hanya bisa mempermainkan perasaan wanita. Padahal tidak ada maksudku untuk melakukan yang demikian.
***
Aku memandang Kiara yang duduk di sebelah Tante Anna, ibunya. Dia terlihat sangat cemas saat aku harus menjawab pertanyaan ayahnya. Bukannya aku tak berani mengambil sikap dengan segera menjawabnya. Hanya saja aku masih memiliki Emak. Selain restu dari Om Thimoty, aku pun butuh restu dari Emak. Benar menikah itu ibadah. Namun, tanpa restu dari Emak, aku merasa ada yang mengganjal di lubuk hatiku terdalam. Ini menikah, ibadah, bukan main-main.
Jauh hari sebelum aku datang ke apartemen Kiara untuk menemui ayahnya, aku pernah mengatakan tentang sebuah syarat padanya. Sebuah syarat yang menurutku sangat sederhana. Namun, sangat berarti untukku melangkah ke depan dalam mengarungi biduk rumah tangga. Sebuah restu. Sebelumnya, aku sudah mengatakan pada Kiara bahwa aku harus meminta restu kepada Emak. Hanya dengan restu Emak sajalah aku akan memutuskan untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Menikah.
“Jawab saja, Fyan. Restu dari Emak bisa menyusul belakangan. Lagi pula kau kan laki-laki. Bisa menikah meski tanpa wali.” Lagi-lagi ada bisikan itu terdengar di telingaku.
Hatiku bergejolak. Restu dari Emak akan menjadi penentunya. Aku akan turut apa yang emak katakan selama itu tidak dalam rangka kemaksiatan. Bahkan aku pun akan menuruti jika emak ternyata menolak pilihanku meski tanpa alasan. Aku tak ingin menjadi anak durhaka dengan menyakiti perasaan orang tua karena membantah ucapannya. Meski sebenarnya tak ada kewajiban bagi seorang lelaki untuk meminta restu kepada orang tuanya sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan.
Aku punya keyakinan bahwa apa pun yang orang tua pilihkan maka itu adalah demi kebaikan anak-anaknya. Termasuk dalam hal jodoh, aku percaya dengan hal itu. Bukan berarti aku termasuk orang yang suka dijodoh-jodohkan. Hanya saja aku memiliki prinsip bahwa dalam memilih jodoh haruslah atas ridho dari orang tua. Sekalipun sebagai laki-laki aku tak memerlukan wali dalam pernikahan namun aku tak mau memandangnya sesederhana itu.
Sedemikian cintanya pun aku pada seorang kekasih hati jika Emak tidak meridhoi maka sebuah pernikahan tak akan pernah terjadi. Bukan berarti aku bermaksud menambah syarat dan rukun pernikahan. Bukan pula bermaksud mengubah syariat Dia yang Maha Sempurna.
“Insyaallah,” jawabku memberanikan diri.
Entah, apakah jawaban yang baru saja terucap itu tepat atau tidak. Betapa saat ini hatiku seperti terombang-ambing di tengah lautan luas. Hanya mengikuti takdir angin yang berembus tak tentu arah. Apakah berlayar hingga ke tempat tujuan? Ataukah karam sebelum tiba di pulau bahagia? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang jelas aku akan mencoba menghubungi Emak sekali lagi. Meminta restunya atas seorang wanita yang kupilih untuk kelak menjadi pendamping hidupku.
Om Thimoty telihat lega saat aku menjawab pertanyaannya. Senyumnya melengkung di wajah. Kulihat, Kiara pun tampak bahagia. Senyumnya membuat wajahnya makin jelita. Gemuruh tepuk tangan pun memenuhi ruangan pesta.
***
Terlanjur cinta terurai indah
Dalam alunan rindu asmara
Merajut kata indah
Terangkum dalam kitab cinta
Waktu seolah berjalan begitu lambat. Perjalanan pulang dari pesta ke apartemen terasa begitu berat. Kata-kata Om Thimoty yang terucap setelah aku membacakan puisi, masih melekat. Memintaku untuk segera menghalalkan putrinya. Seolah ada segunung batu di atas pundak. Kupejamkan mata, lalu kuambil napas dalam-dalam.
“Gila … aku nggak salah dengar kan? Om Thymoty memintamu menikah dengan Kiara. Ah … I ... I ... ini anugerah Sofyan,” ucap Felix kegirangan, “Apalagi yang menghalangimu? Kau sudah lulus S2, aqidah kalian pun sudah sama, apalagi Fyan?”
“Kau pernah bilang,” ucap Fritz menggebu, “menikah itu ibadah, lalu apalagi yang mesti kau khawatirkan?”
“Tapi kau tampak seperti orang yang tak bahagia?” heran Felix, “bukankah kau yang menginginkan saat-saat seperti ini, Fyan?”
Aku mengangguk. Aku menjawab pertanyaan dua sahabatku itu dengan mengangkat kedua bahuku.
“Lantas mengapa kau tampak tidak bahagia?” tanya Fritz.
***


 hadismevlana
hadismevlana