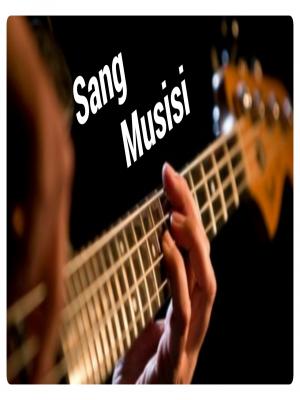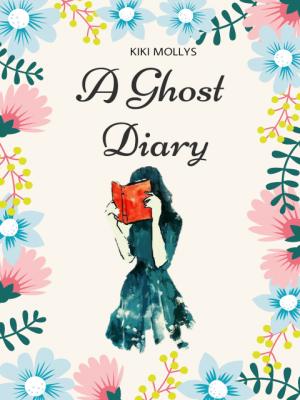Tepat pada malam di hari yang sama segera digelar Tasyakur Binni’mat atas kehamilan Ratri dengan mengundang hampir semua tetangga di lingkungan rumahnya. Tahmid, Tasbih dan Takbir bergema memuji kebesaran Allah Sang Pemberi Nikmat Sejati. Namun, semua justru membuat hati Yudis semakin tersakiti. Betapa tidak, dia dipaksa bahagia dengan kehamilan istri yang bukan dari darah dagingnya. Yudis mesti bersandiwara di hadapan para tetangga seolah dirinya baik-baik saja. Padahal, remuk hatinya dan segala amarah tengah berkecamuk dalam dada. Ucapan selamat dari tetangga kepadanya hanya dijawab dengan senyum ala kadarnya. Senyum yang dia usahakan dengan segenap jiwa melengkung di bibirnya dengan kondisi hati yang lara. Betapa sulit bagi Yudis untuk berpura-pura bahagia malam itu. Hatinya yang gundah membuat acara tasyakuran terasa begitu lama baginya.
Selama acara syukuran, Yudis hanya menunduk menyembunyikan raut kekecewaannya. Air matanya berlinang. Ingin sekali dia berteriak untuk meluapkan emosinya. Berkali-kali matanya melirik jam di dinding yang seolah bergerak begitu lambat. Ingin rasanya dia pergi, tapi dia bimbang. Apa nanti kata orang? Bagaimana nanti dia menjawab pertanyaan sang ibu jika tidak ada di acara?
“Bukan! Itu bukan anakku!” teriak Yudis dalam hati.
Namun, semua amarah dan kecewa hanya mampu dia pendam dalam dada. Laksana terserang asma, sesak merambati dadanya. Air mata yang menetes pun kian deras. Sialnya, semua orang malah menyangka bahwa Yudis terharu. Bisik-bisik tetangga yang hinggap di telinganya, mengira air mata yang keluar itu adalah air mata bahagia.
"Masyaallah, calon ayah baru begitu bahagia sampai terharu," celetuk salah satu tetangga yang duduk tak jauh dari Yudis. Beberpa celetukan serupa pun dia dengar dari yang lainnya. Mereka mengira Yudis begitu bahagia hingga meluap menjadi air mata. Sementara, Yudis tak merespon mereka. Ucapan para tetangga itu justru malah makin membuat hatinya terluka.
Usai syukuran, rumah kembali sunyi. Ratri, Bu Farida, Umi Siti dan Ustad Suhada duduk-duduk di ruang tengah. Tampak sekali kebahagian memancar dari wajah mereka. Perbincangan ringan pun mengalir hingga tak terasa hari sudah mendekati tengah malam. Bu Farida menawarkan besannya itu untuk menginap. Awalnya, Umi Siti menolak karena khawatir merepotkan. Namun, Ratri membujuknya agar bisa bermalam di rumahnya. Akhirnya, malam itu Umi Siti dan Ustad Suhada, menginap di rumah anak menantu mereka.
Sementara, Yudis sejak usai acara tasyakuran, memilih untuk duduk sendirian di balkon. Seperti biasa dia duduk pada tempat khusus di area yang biasa dia gunakan untuk melukis. Kuas pun sudah siap menyapu cat warna-warni untuk ditorehkan pada kanvas putih di hadapannya. Sudah lebih dari satu jam, Yudis hanya mampu menatap kanvas putih di hadapannya. Tangannya kaku. Imajinasinya beku. Entah ke mana perginya jiwa seni dalam batinnya. Terjadi kekacauan dalam otaknya. Sehingga ketika angin berembus cukup kencang ia seperti tak merasakan apa-apa. Dadanya terlampau panas dengan apa yang sedang dialaminya.
“O Allah, apa ini karma karena aku telah menyakiti Dewanti?” desahnya ketika tiba-tiba seraut wajah perempuan bermata coklat berwajah indo bermain-main dalam ingatannya. “Maafkan aku, Dewanti.” desahnya lagi.
Satu garis dari kuasan cat warna cokelat terlukis di sana. Seterusnya goresan-goresan lain pun turut menyerbu kanvas hingga membentuk pola. Semua mengalir apa adanya. Lahir dari hatinya. Yudis mencurahkan semua perasaannya pada sebuah kanvas sambil menikmati bulan yang perlahan tertutup awan hitam. Seperti hatinya yang kini diliputi kabut kesedihan dan kemarahan yang tak terluahkan.
Tangan yang terus bergerak meliuk-liuk di atas kanvas diiringi air matanya mengalir kian deras meleleh di pipi, bermuara pada bibir. Asin air mata dikecapnya sepenuh hati yang perih. Dia merasa bahwa semua ini adalah balasan dari Allah karena telah menyia-nyiakan cinta tulus seorang wanita bernama Dewanti kepadanya.
***
Terbayang kembali olehnya saat terakhir bertemu dengan Dewanti. Sosok wanita yang sudah hampir empat tahun jadi tambatan hatinya. Pengindah tatapan mata, penyejuk kalbu. Namun, Yudis terpaksa harus meninggalkannya karena rasa cinta kepada ibu yang melebihi kecintaannya kepada apapun yang dicintainya.
Ketika itu, senja tak menampakan kecantikannya. Langit gelap. Gerimis turun membasahi aspal sejak setengah jam lalu. Yudis duduk di sudut sebuah kafe di kawasan Kemang Jakarta Pusat. Matanya menangkapi rintik hujan dengan tatapan dari kaca jendela yang mulai berembun. Dia menuliskan sebuah nama ‘Dewanti’ pada kaca berembun itu. Kemudian menghela napas dalam.
Di luar, seorang wanita menyeberang jalan setengah berlari menuju kafe tempat di mana Yudis duduk termangu. Dia menutupi kepalanya dengan sebuah map berwarna biru muda. Bajunya sedikit basah. Yudis segera berdiri menyambutnya di pintu kafe dengan senyum dan tatapan penuh cinta.
“Sudah lama? Maaf ya tadi aku sibuk membersihkan dulu wajah dari semut,” ucap perempuan bermata coklat itu manja sambil merapatkan kedua tangan di depan dada.
“Kenapa dengan wajahmu?” Yudis meneliti wajah sang kekasih.
“Aku kan manis ....” Dewanti mengedip-ngedipkan mata genit seperti boneka. Lucu sekali tingkahnya.
Yudis tersenyum geli sekaligus gemas. Selalu suka mendengar setiap kata yang keluar dari bibir tipis Dewanti. Yudis menggandeng tangan kekasihnya itu menuju tempat duduknya tadi. Beberapa orang pengunjung tersenyum melihat kemesraan mereka. Yudis menggeser kursi, Dewanti tersenyum menatapnya. Mereka duduk berhadapan, bertatapan.
Di luar hujan mulai reda. Seperti biasa, sisa hujan membuat genangan air di beberapa titik. Langit masih gelap. Seperti sudah membuat janji sebelumnya, lampu-lampu mulai menyala hampir bersamaan menggantikan posisi matahari menerangi bumi. Namun, sebanyak apa lampu-lampu itu, tetap tidak akan pernah bisa menandingi terangnya matahari. Seperti tak pernah tergantikannya Dewanti dalam hati Yudis selama ini. Begitu juga dengan yang dirasakan Dewanti.
Dewanti yang saat itu sedang menyisir rambut dengan jarinya tiba-tiba terdiam. Dia heran melihat Yudis yang menatapnya kali ini. Tatapan Yudis kali terasa begitu berbeda. Ada sesuatu yang entah, tersirat di matanya. Dewanti membalas menatap Yudis dengan mata sedikit disipitkan. Agak ragu Dewanti untuk bertanya kepada kekasinya itu. Namun, sirat mata yang tak biasa dan tatapan yang penuh tanda tanya membuat Dewanti memberanikan diri untuk membuka suaranya. Senyumnya yang indah mengawali sebelum akhirnya terlontar katapkata.
“Kenapa, sayang?” tanya Dewanti sungguh-sungguh.
***


 hadismevlana
hadismevlana