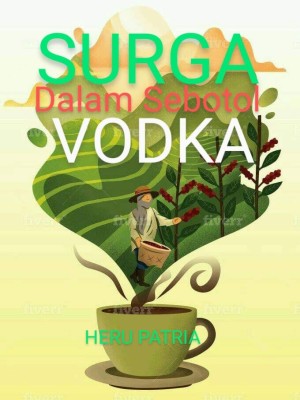Blok 10-Benita
Semesta Benita
Kediaman Keluarga Rorimpandey berhantu. Para tetangga, rekan bisnis, dan kolega enggan bertandang ke sana. Kabarnya, hantu di rumah mewah itu sangat menakutkan. Ia kerap menampakkan diri dalam wujud pria berpakaian serbaputih dan berwajah amat pucat. Semakin hari, semakin tak sedap isu yang berembus. Rumor yang terdengar belakangan ini adalah sebab dari datangnya penunggu di Kediaman Rorimpandey tak lain karena anak semata wayangnya yang punya mata batin.
Hunian yang digosipkan tetangga itu adalah rumahku. Kalian mungkin sudah tahu siapa sosok hantu yang dimaksud. Dia tak lain bayangan putih yang memperlihatkan diri di cermin sepulang aku dari rumah sakit beberapa waktu lalu.
Bagiku dia bukan hantu biasa. Sebenarnya, aku tak mau menyebutnya hantu karena dia belum meninggal. Namun, aku tak punya perbendaharaan kata lain untuk menyebut eksistensinya saat ini. Terkadang dia hanya kelihatan seperti asap atau bayangan putih. Akhir-akhir ini wujudnya tampak semakin solid. Bahkan terkadang aku dapat merasakan helaan napas dan detak jantungnya. Hantu mana yang masih bisa bernapas dan memiliki denyut jantung?
“Kakak, jangan liat!” larangku saat akan berganti pakaian.
Sosok pria berwajah pucat itu mengukir senyum. Dia memalingkan wajah. Tangan putihnya menutupi kedua mata. Merasa aman, aku melepas gaunku. Aku tak perlu repot ke kamar mandi tiap kali berganti baju. Secepat kilat aku mengganti gaun putihku dengan piyama bermotif mawar. Hatiku berangsur lega.
“Kamu pikir kamu bisa lega secepat itu?” tanya figur pucat itu tajam.
Aku tertohok. Zakaria, tak pernah berubah. Ia seperti cenayang. Nalurinya setajam pisau cukur yang sering dipakai Papa.
“Benita!” Ia sedikit meninggikan suaranya karena aku hanya diam.
Aku menoleh malas. “Kenapa, Kak?”
“Harusnya aku yang tanya itu ke kamu. Kenapa kamu sembunyikan itu?” Zakaria menunjuk dadaku.
Dalam heningnya malam, di tengah pekatnya gerimis yang menyetubuhi tanah, aku terpekur. Apakah tadi dia tidak benar-benar menutup matanya?
“Lebam. Luka di tubuh. Memar biru. Itu semua kenapa, Benita?” cecar Zakaria khawatir. Belum pernah kulihat dia sekhawatir ini. Bahkan ketika depresi postpartum Sabila memburuk dan ia harus diasingkan ke rumah pemulihan jiwa, ia tak setakut ini.
Otakku berputar cepat, mencoba menyusun alibi. Belum sempat aku membuka mulut untuk melontarkan kebohongan, ia menukas.
“Jangan coba-coba bohong. Cerita sama aku, Benita.”
Ups, lagi-lagi dia tahu aku akan mengarang cerita. Kuhela napas panjang. Membuat kesepakatan dengan kelenjar air mata untuk tidak berproduksi. Kutatap nanar dinding kamarku yang berlapis wallpaper Flower Story. Tuhan, aku tak sanggup menatap matanya.
“Tanganku sendiri yang melakukannya,” desahku.
Aku tak siap ketika ia menubrukku. Pelukannya begitu erat seolah ingin mencekikku. Mataku melebar tak percaya melihat likuid bening membasahi netra Zakaria. Dia menangis? Menangis untukku.
“Kamu, ibu perinya Magenta, tempat curhat banyak orang ... melakukan itu?” Zakaria berkata sendu. Aku benci melihat kekecewaan menyakitkan di paras tampannya.
Aku menggeleng kuat. Tolong jangan bawa Magenta. Mereka tak perlu tahu.
“Boleh aku tahu apa alasannya?” selidik Zakaria setelah ia menguasai diri.
Hatiku berteriak menyebut namanya. Ya, kekecewaan cinta amat parah yang membuatku menyayat tubuhku sendiri. Luka-luka fisik ini terlahir dari luka batin yang menyiksa.
“Apa karena aku? Apa kamu sering melakukan ini setelah aku menikahi Sabila?”
Kami bagai melakukan komunikasi satu arah. Aku tertunduk diam dan dia merespon isi hatiku yang terkunci tanpa suara. Zakaria mengepalkan tangan. Sejurus kemudian dia bergerak ke meja belajar. Diraihnya cutter dan disayatkannya benda itu ke kulitnya. Sesaat aku menahan napas, mengira ia akan terluka. Nyatanya, benda tajam itu tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Aku senang karena jejak jiwa Zakaria tak bisa melukai dirinya sendiri.
“Tolong berhenti lakukan itu, Benita. Jangan membuatku makin bersalah.” Zakaria memohon putus asa seraya melempar cutter ke tempat semula.
Aku membisu. Kulangkahkan kaki menuju ranjang dan aku duduk di atasnya. Dia menyusul di sampingku. Apa Zakaria akan menceraikan Sabila bila aku berhenti melukai diri? Tepat ketika tanda tanya itu melintas di kepalaku, Zakaria memelukku lagi. Ia bernyanyi lembut di telingaku.
Sebenarnya aku ingin dekatmu
Namun ku sadari ku tak bisa
Tak boleh ku disini
Bahaya ku makin cinta
Ah, nyaman sekali berada dalam dekapannya. Rengkuhan Zakaria adalah pelukan terhangat setelah pelukan Mama. Merdu suaraku membalas nyanyiannya.
Ku tak ingin jauh
Tak ingin berpisah
Mengapa semua selalu indah
Saat denganmu?
Sayang untuk di akhiri
Tatapan kami bertemu. Kulihat pancaran luka di mata teduh Zakaria. Tuhan, apakah luka ini karenaku? Atau karena rumah tangganya dengan Sabila yang telah hancur? Dalam pilu yang memagut, kami bernyanyi bersama.
Andai kau bisa mengerti
Betapa beratnya aku
Harus aku tetap tersenyum
Padahal hatiku terluka
Adakah arti cinta ini?
Bila ku tak jadi denganmu
Jika memang ku harus pergi
Yakinlah hatiku kamu
Malam ini tak ada bintang. Kusapukan pandang ke langit yang tersiram hujan. Ingin ku mengadu pada bintang. Tapi ia bersembunyi di balik gumpalan awan tebal. Aku ingin bertanya mengapa semesta harus mempertemukanku kembali dengan Zakaria.
Mengapa cinta pertemukan?
Bila akhirnya di pisahkan
Dan mengapa ku jatuh cinta?
Pada cinta yang tak jatuh padaku (Tiara Andini ft Arsy Widianto-Bahaya).
**
Hari ini aku terbangun dengan mata merah. Semalam aku kurang tidur. Aku maraton mengerjakan tugas: mata kuliah Pancasila and Religion, Naratif Lisan, dan Filologi. Pak Aan meminta kami membuat video kampanye toleransi berdurasi maksimal lima menit. Dosen Filologi memberi setumpuk naskah kuno untuk diterjemahkan. Pusing kepalaku mengerjakannya. Huruf Arab gundul dan Pegon tak kukuasai sebesar pemahamanku dengan notasi musik. Tugas Naratif Lisan lebih ringan. Dosen hanya menyuruh kami membedah fungsi utama dan sekuen dalam teks cerita rakyat yang diberikannya. Semua tugas itu baru tuntas menjelang subuh.
Remuk badanku. Aku bahkan terlalu lelah untuk berlalu ke dapur dan membuat sarapan. Pelan-pelan aku bangkit dari ranjang. Saat akan mengambil ponsel di atas nakas, tersentuh oleh tanganku sebuah baki. Wangi tinutuan atau bubur Manado membelai hidungku. Siapa yang membuat makanan asal leluhurku? Jelas bukan Mama-Papa, karena mereka sudah pergi ke mall jam segini. ART kami sedang cuti.
“Aku.”
Suara bariton Zakaria membuatku terlonjak kaget. Pria berparas pucat itu turun dari meja belajar dan menghampiriku.
“Sejak kapan hantu bisa masak?” tanyaku kikuk seraya meraih baki berisi semangkuk bubur Manado dan segelas susu coklat hangat.
“Memangnya cuma perempuan atau manusia hidup yang bisa masak? Hantu juga bisa. Mungkin suatu saat nanti harus ada emansipasi hantu.”
Hampir saja aku tersedak. Pada suapan pertama aku langsung jatuh cinta. Masakannya enak sekali. Kupikir wajar karena sama-sama mengalir darah Manado Borgo dalam tubuh kami.
“Aku juga bisa masak yang lain. Kamu mau apa? Sphagetti, steak, pizza, coto Makassar, nasi goreng, tinggal request.” Dia berkata meyakinkan.
“Bisa masak resotto?” tantangku.
Ia tak sempat menjawab karena hp-ku keburu berdering. Itu notifikasi pengingat. Siang ini aku janjian sama Mama dan Papa untuk lunch di mall. Segera kuselesaikan sarapan dan aku meluncur ke kamar mandi.
Empat puluh lima menit berselang, aku telah duduk manis di mobilku. Mengemudikan benda mewah keluaran Nissan itu menyusuri ruas tol dalam kota. Aku tak ingin terlambat. Berulang kali konsentrasiku pecah karena sisa-sisa kantuk masih mendera.
Gerbang tol masih jauh. Kantuk makin tak tertahankan. Mobilku oleng ke kanan. Pembatas jalan menganga di depanku, siap menelan mobilku dalam kecelakaan tunggal. Mataku sesekali terpejam menahan kantuk. Pembatas jalan bersiap melahap mobilku dan ....
Plush!
Sesuatu memberati punggungku. Tanganku yang memegang kemudi bergerak di luar kendaliku. Tetiba aku tak lagi mengantuk. Namun, aku merasa melihat jalanan bebas hambatan dengan mata orang lain. Sensasi aneh apa ini?
Terus dan terus tanganku bergerak di luar kendaliku. Aku menghindar dari pembatas jalan dan melaju kencang hingga ke gerbang tol. Sesampai di luar tol, kurasakan beban berat di punggungku terangkat.
“Astaghfirullah,” gumamku sambil terengah.
Sesaat aku menepikan mobil di pinggir jalan. Kuatur napasku, kutenangkan pikiranku. Peristiwa tadi membuatku shock.
“Tenang ... semuanya baik-baik saja.” Seseorang berbisik di sampingku.
Aku menolehkan kepala. Zakaria duduk di bangku penumpang, persis di sampingku.
“Udah lama nggak bawa mobil.”
Aku tergamam. Rupanya dia merasukiku dan memegang kendali mobil. Dua kali sudah dia menolongku hari ini: membuatkan sarapan dan menghindarkanku dari kemungkinan masuk rumah sakit.
“Terima kasih,” lirihku.
“Justru aku yang berterima kasih. Kamu orang pertama yang bisa kurasuki. Aku sudah mencoba memasuki tubuh orang lain, tapi tak pernah bisa. Momma, Papa, bahkan Sabila. Hanya kamu yang bisa kurasuki.”
Perkataan Zakaria terus menghantuiku hingga aku mendaratkan kaki di mall. Suasana jelang bulan suci kentara sekali di mall milik keluargaku ini. Dekorasi pohon kurma, beduk mini, dan lagu-lagu religi yang diputarkan. Mama dan Papa memelukku hangat begitu aku tiba di food court. Kian dekat bulan suci, kian banyak orang memadati food court. Mungkin mereka ingin makan siang di hari-hari terakhir sebelum berpuasa seharian.
“Sayang, Mama dan Papa sudah sepakat untuk memanggilkan paranormal ke rumah.” Papa mengumumkan saat kami mulai makan siang.
Aku terbatuk. Di sampingku, Zakaria bergerak resah. Mama pun menunjukkan chat tetangga kami di WAG RT. Katanya, ia mendengar kelontang-kelonteng panci di dapur saat lewat depan rumah kami tadi pagi.
“Jangan, jangan panggil paranormal,” tolakku.
“Kenapa? Kamu berteman sama hantu penghuni rumah kita?”
Aku diselamatkan oleh dering notifikasi. Pesan di grup Magenta membuat jantungku hampir copot.
Aini Trunajaya:
Yuke kabur. Gue nggak tau dia kemana. Kalo ada yang ketemu dia, tolong kasih tau gue.


 maurinta
maurinta