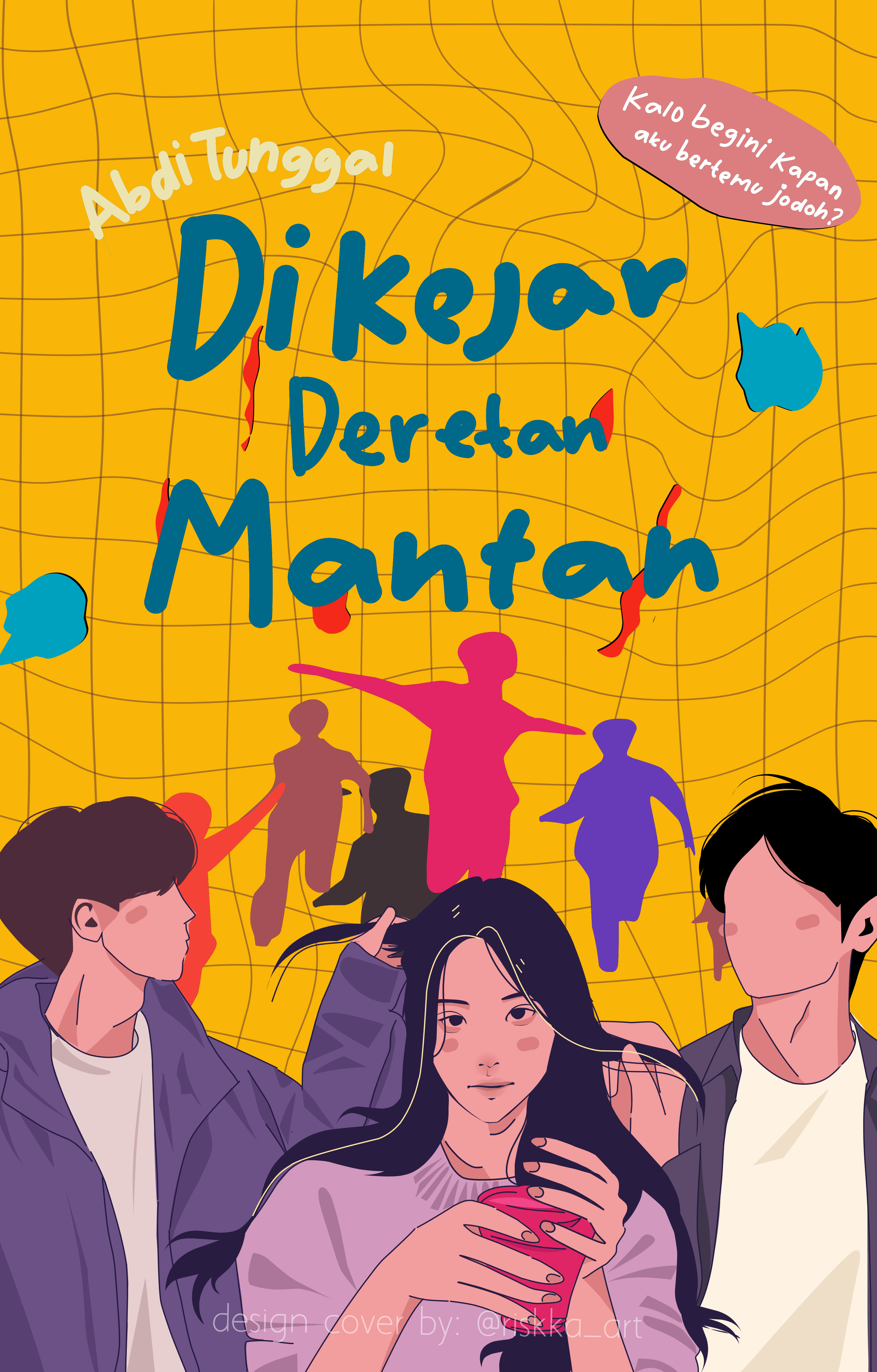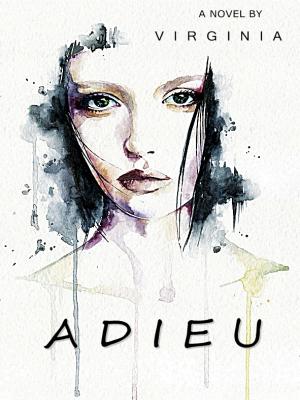Blok 3-Aini
Semesta Aini
Dear, Writer Academy
Sebagai warga keturunan Tionghoa, dari kecil aku diperkenalkan sebuah pepatah klasik yang kira-kira artinya begini dalam Bahasa Indonesia: kasih ibu seperti air yang mengalir, dan kasih anak hanyalah sepanjang hembusan angin yang berlalu. Awalnya aku tak percaya. Tapi setelah aku dewasa dan mengalami rentetan peristiwa pahit dalam hidupku, mataku terbuka untuk membenarkannya.
Kulalui masa kecil dengan bahagia. Aku hidup berkecukupan. Papa punya kios di Pasar Hong Kong, Singkawang. Sedangkan Mama buka warung makan di rumah. Aku sulung dari empat bersaudara. Tiga adikku terpaut cukup jauh usianya denganku.
Mama sosok ibu pekerja keras. Dia bangun tiap pukul empat pagi, memasak menu buat warung makan, dan membuka warungnya pukul enam. Pelanggan Mama kebanyakan sopir dan buruh proyek. Mama menjual bubur ayam, nasi kuning, lontong sayur, dan bermacam menu sarapan di warungnya. Kalau beruntung, dagangan akan habis pada pukul sembilan. Waktu istirahat untuk Mama dimulai sejak dagangan habis sampai menjelang sore.
Awalnya kukira hidupku akan selalu baik-baik saja. Prediksiku meleset. Memasuki masa SMP, badai itu datang.
Papa terjerat hutang karena judi. Sebuah kejutan di keluargaku karena kami baru tahu Papa ternyata penjudi ulung. Pantas saja sering kali dia membawa banyak uang di luar laba jualannya. Sepandai-pandainya penjudi, kelak akan jatuh juga. Begitu pun nasib papaku. Papa kalah telak di meja judi. Hartanya amblas sebagai kompensasi.
Ketika utang kian menumpuk, dengan terpaksa kios di pasar harus terjual. Beberapa peralatan warung milik Mama ludes kali berikutnya. Lintah darat makin berulah. Hampir saja rumah kami disita.
Baik Mama dan Papa sama-sama stress. Papa sama sekali tak berguna. Bukannya mencari jalan tengah untuk menyelesaikan yang diakibatkan hobi buruknya, ia malah melarikan diri dengan mabuk-mabukan. Aku yang masih SMP perlahan mulai meraba keadaan. Ekonomi keluargaku morat-marit. Menginjak semester pertama di kelas dua SMP, kuputuskan berhenti sekolah. Mama sempat melarang. Katanya dia masih sanggup membiayaiku. Oh Mama, justru aku yang tak sanggup melihat sorot lelah di mata Mama.
Kulepas seragam putih biruku. Hari-hariku diisi dengan kerja keras di toko sepatu. Aku menjaga toko mulai pukul sembilan pagi hingga sembilan malam. Dari sinilah aku mengenal tentang laki-laki. Dalam waktu singkat, teman lelakiku bertambah banyak. Aku lebih suka berteman dengan pria ketimbang wanita karena menurutku pria tidak banyak drama, selalu ada, dan lebih mengutamakan logika ketimbang perasaan.
Tak sedikit teman pria yang menyatakan cinta padaku. Aku tolak semua cinta mereka karena aku hanya ingin berteman. Terlebih kondisi rumah masih kacau-balau. Mana mungkin aku malah asyik pacaran sementara ketiga adikku terlantar, punya Papa peminum, dan Mama yang terpaksa jadi pekerja migran di Taiwan? Ya, Mama terpaksa berangkat ke negeri orang untuk menjadi penjaga lansia. Cita-cita Mama ingin melunasi semua hutang Papa, membangun rumah besar untuk kami, dan memulai kembali usaha warung makannya.
Masa lajangku berakhir di umur tujuh belas tahun. Aku menikahi pria yang lebih tua 27 tahun dariku. Mulanya keluarga sempat ragu akan niatku. Namun, kulakukan itu demi mereka. Calon suamiku berjanji membiayai hidup kami sekaligus menutup hutang Papa. Bukankah itu tawaran yang sangat menggiurkan? Rencana pernikahanku membuat patah hati teman-teman lelakiku.
Aku pun menikah dan dikaruniai empat anak. Ketika anak keempatku lahir, Mama pulang dari Taiwan dengan tangan kosong. Ia dideportasi karena ketahuan menjadi pendatang ilegal. Gaji Mama juga tak dibayarkan selama tiga tahun oleh majikannya. Sejak saat itulah Mama tinggal bersamaku.
Mama memperlakukan keempat cucunya dengan penuh kasih sayang. Apa pun yang mereka inginkan selalu Mama penuhi. Suamiku juga senang dengan kehadiran Mama. Janjinya untuk membiayai hidup kami sekeluarga dan membayar lunas hutang Papa dipenuhinya dengan sangat baik. Aku beruntung memilikinya.
Kebahagiaan kami tak berlangsung lama. Aku dan suamiku ditangkap polisi dengan tuduhan mengedarkan narkotika. Jujur, aku sama sekali tak tahu-menahu tentang ini. Yang kutahu suamiku berbisnis minuman kekinian seperti boba, Thai Tea, es kepal milo, dan Chatime. Seperti itulah pengakuannya padaku. Ternyata, dus-dus besar yang kuduga bahan baku pembuatan minuman ringan itu berisi narkoba.
Aku yang tak tahu apa-apa tetap dijatuhi vonis hukuman. Kini aku dan suamiku mendekam di penjara. Saat inilah kami sadar kalau hanya Mama yang tetap mencintai kami. Mama tak pernah absen menjenguk kami tiap minggu. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mama berjualan kue. Sisa kekecewaan pada suamiku terus membekas. Aku merasa tertipu. Dia menyalahgunakan kepercayaanku dengan ....
Sampai di sini, gue berhenti membaca. Tiap huruf yang diguratkan Cintya Chen di suratnya meneriakkan derita. Penderitaan panjang yang dia tanggung sejak remaja hingga menjadi ibu beranak empat.
“Semua cowok sama aja!” seru gue keras. Separuh pengunjung cafe menoleh ke arah gue. Bodo amat.
Ini surat keenam belas yang gue baca. Udah empat jam gue nongki di Smart Cafe. Surat-surat para perempuan narapidana sengaja gue bawa ke sini. Mendingan gue baca di sini dari pada di rumah. Yang ada gue suntuk kalo di rumah mulu. Cuma papasan sama Papa, liat mukanya aja udah enek.
Smart Cafe berlokasi dekat rumah tahanan tempat perempuan terpidana kasus narkoba. Cafe ini tidak hanya menyediakan makanan ringan dan minuman enak, tetapi juga koleksi buku hingga WiFi gratis. Koran cetak edisi terbaru juga ada di rak atas. Heran ya, zaman digital gini masih ada yang langganan koran fisik.
Ini tempat langganan gue kalo lagi nulis atau baca karya orang lain. Gue juga suka ajakin anak Magenta ke sini. Jaraknya nggak jauh-jauh amat dari Villa Istana, tempat tinggal gue sama bokap, atau dari Narcissa Regency tempat anak-anak Magenta tinggal. Menu favorit gue di sini tart karamel dan cappucino. Gue bisa betah nongkrong seharian di sini.
Dari bangku yang menghadap ke tirai air, gue bisa liat langit senja di luar perlahan menggelap. Malam membungkus kota. Potongan tart karamel entah keberapa yang gue pesan makin mengecil. Balok-balok es di dasar gelas minuman gue perlahan mencair. Merahnya senja berganti kelamnya malam.
Meski begitu, gue enggan beranjak dari sini. Gue masih baca surat-surat karya perempuan narapidana kasus narkotika. Kalian kira gue lakuin ini Cuma-Cuma? Nggaklah, ogah lagi gue terima proyek gratisan.
Sejak lulus SMA tahun lalu, gue memulai debut di dunia kepenulisan. Perlahan tapi pasti nama gue mulai meroket. Spesialisasi gue script film sebenarnya. Tapi gue oke-oke ja kalo disuruh bikin tulisan lain. Gue sering didapuk banyak sutradara besar buat garap skenario film mereka. Pernah juga gue nulis buat Viu dan Netflix. Proyek terbaru yang selesai gue tangani itu film dokumenter tentang ibu kota baru, kolaborasi sama pemerintah pusat. Kadang gue diundang jadi pembicara di webinar kepenulisan. Beberapa hari lalu, sebuah komunitas menulis rekrut gue sebagai editor dan penyeleksi naskah dalam proyek mereka. Proyek itu bertajuk Surat Project: Suara Hati Narapidana Perempuan dari Lembah Narkotika. Eits, gue nggak asal aja terima tawaran itu. Gue harus pastiin dulu berapa bayaran yang gue terima. Kalo fee-nya kecil, ya jelas gue nggak mau. Untungnya komunitas itu kelebihan duit. Buat kerjaan ginian aja gue dibayar enam juta.
Anak Magenta yang paling tau gimana komersilnya gue. Gue paling anti terima proyek nulis gratisan. Dalam pikiran gue, sebuah tulisan itu buah pikir penulisnya. Butuh perjuangan dan proses untuk menghasilkan tulisan. Masa udah capek-capek nulis trus nggak dibayar? Buang tenaga, rugi waktu pula.
Otak komersial gue merambat ke hal lain. Kadang gue mikir-mikir dulu kalo mau bantu orang. Apa untungnya buat gue? Apa gue bakal rugi kalo bantu dia? Anak Magenta sendiri sampai heran sama sifat buruk gue yang satu ini.
Ya, gue akui itu buruk. Beberapa orang udah menilai sikap komersial gue kelewatan. Gue udah belajar menebalkan telinga dan jadi muka tembok.
Alasan gue jadi komersial gini bukan karena gue tergolong sobat misqueen. Coba kalian pikir aja sendiri. Gue anak bungsu, nyokap pramugari plus pemilik Irene Homestay. Bokap pemilik Istana Villa yang cabangnya ada di semua tempat wisata. Kurang kaya apa gue? Kedua kakak gue udah berkeluarga. Sekarang ini tanggung jawab bonyok ya tinggal gue seorang.
Bukan, mylove. Gue lakuin ini bukan karena uang. Gue cuma pengen hargai diri gue sendiri. Kalo diri sendiri aja nggak bisa menghargai, gimana orang lain?
Gue menyesap ice cappucino untuk terakhir kali. Tepat ketika makanan dan minuman di hadapan gue tandas, selesai sudah semua surat yang harus dibaca. Gue baru mau berdiri buat bayar ke meja kasir pas hp gue bunyi.
From: Irene
Nduk, pulang ya. Dicariin Papa. Jangan lupa makan, ya.
Gue mendengus. Tanpa membalas pesannya, gue tutup aplikasi Whatsapp. Fyi, Irene itu nama nyokap gue. Ya, gue namai dia pakai nama di kontak alih-alih pakai sebutan Mama, Momma, atau sejenis itulah. Dia bukan bagian penting di hidup gue.
Kepercayaan gue ke nyokap luntur perlahan pas skandal perselingkuhannya dengan seorang pilot terbongkar. Bokap marah banget waktu itu. Hampir aja mereka cerai. Tapi akhirnya mereka batalin niat itu. Buat gue nggak ada bedanya cerai atau enggak. Toh dua-duanya super sibuk dan hampir nggak pernah saling bicara kecuali kalau ada perlunya aja.
Tahun lalu, nyokap memang banyak di rumah dan ngurus villa. Mau terbang gimana? Banyak negara tutup pintu. Tapi sejak era kenormalan baru dan banyak maskapai menggeliat, nyokap sibuk lagi jadi kacung pesawat. Maaf ya, gue terlalu kasar. Anggap aja itu ekspresi kekesalan seorang anak.
Gue banting pintu mobil. Honda Jazz silver kesayangan gue lajukan menembus jalan beraspal. Badan gue udah kangen kasur empuk, AC kamar, dan bantal kudanil kesukaan. Alunan musik instrumentalia menemani perjalanan.
Mobil berdecit di lampu merah. Beberapa pengamen menyemut, mengharap uluran tangan pengemudi mobil. Gue nggak mau buka kaca. Karena gue lagi bad mood, gue ogah mau kasih ke mereka. WA dari nyokap selalu bikin mood gue hancur.
Gue membelokkan mobil ke kawasan Flower. Sebenarnya ini cuma nama karangan gue. Soalnya di sini nama-nama jalannya kayak nama bunga. Di sini juga ada salah satu cabang dari Istana Villa, villa yang gue tinggali bareng bokap. Kawasan Flower lumayan sepi. Beberapa batang lampu merkuri menerangi ruas jalan yang basah. Apakah habis hujan? Atau ini sisa air dari petugas pemelihara taman?
Di tengah kawasan ini, berdiri empat bangunan yang udah familiar banget sama gue. Bangunan di ujung kanan adalah masjid besar. Menara kokohnya menjulang anggun. Hijau warnanya, warna kebanggaan Islam. Sebuah katedral besar berdampingan dengan masjid. Kedua rumah ibadah ini mesra, saling mendampingi dan memeluk. Nggak jarang umat dari kedua rumah ibadah berbagi tempat parkir. Toleransi terjaga sekali di sini. Berseberangan dengan kedua rumah ibadah, Istana Villa berdiri angkuh dengan pagar putih dan halaman luasnya. Gerbang Narcissa Regency berada tepat di sisi kanan villa. Cuma gue yang nggak satu kompleks sama anak Magenta yang lain. Ah, gampang kok kalo mau kumpul geng. Tinggal jalan dikit aja.
Nggak sabar rasanya pengen berjumpa bantal dan guling. Sambil nyetir, pikiran gue berkelana. Mulai dari kamar gue yang nyaman, pesan dari nyokap, sampai surat yang gue baca. Hmmm, surat-surat para napi itu bisa dibilang punya napas feminisme.
Sampai sekarang gue sendiri bingung kenapa orang mutusin jadi feminis. Apa karena patah hati? Banyak yang salah sangka sama feminisme. Sebuah ideologi yang menginginkan kesetaraan perempuan di bidang politik, ekonomi, ruang publik, dan ruang pribadi. Banyak yang mengira para feminis benci pernikahan, benci laki-laki, pengen ngalahin laki-laki, dan segepok prasangka lainnya.
“Ngaku feminis, tapi kok nggak bisa angkat galon sendiri? Kalo mau jadi feminis, harus siap kehilangan haknya, dong. Hak ditraktir, hak diantar-jemput, hak dibantuin angkat barang berat, dan hak tempat duduk di transportasi publik. ‘Kan katanya mau ngalahin cowok.” Pernah gue dengar Yune, temen sekelas gue di kampus, bilang gitu ke Rahmania. Rahmania itu mantan temen gue dan mantan sahabatnya Marina. Nggak usah tanya kenapa karena gue males cerita.
Gue rasa feminis nggak segitunya. Sekeras-kerasnya gue, gue nggak pernah secara eksplisit menyatakan diri kalo gue bukan feminis. Gue cuma berteman dengan banyak feminis.
Keasyikan melamun, tanpa terasa gue hampir sampai. Wait, wait. Kayaknya ada hal mencurigakan di depan gereja. Ada sepasang pria dan wanita berbaju gamis naik sepeda motor. Tas hitam besar tersandang di pundak si lelaki. Mereka mau ngapain, ya?
Gue melempar pandang ke arah gereja. Terlihat jemaat yang baru selesai Misa berjalan melintasi halaman. Oh ya, gue lupa. Hari ini Kamis Putih. Pantesan gereja agak lebih ramai dari biasanya. Trus pasangan gamis itu mau ngapain, ya? Kayaknya nggak mungkin mereka umat gereja.
Sepasang pemuda berjalan menyusul jemaat lainnya. Pada saat bersamaan, pria-wanita bergamis turun dari sepeda motor. Tas hitam di pundak si pria terbuka. Terlihat sebuah kabel ditarik dan ....
Dor! Dor!
Jantung gue mau copot. Buru-buru gue keluar dari mobil. Gereja megah nan indah itu luluh lantak. Teriakan histeris terdengar. Nama Tuhan dilangitkan. Tubuh-tubuh bergelimpangan. Kaca jendela pecah, memuntahkan serpihan ke pelataran. Tiang kayu di dekat pagar gereja roboh.
Dari balik debu tebal dan kekacauan itu, gue lihat pasangan bergamis udah jadi mayat. Dada gue terasa tertusuk pisau. Ya, Allah, gue baru sadar apa yang baru saja terjadi.
Bom. Fix, ini serangan teroris. Dan pasangan bergamis yang tadi naik motor itulah pelakunya.
Gue merosot ke aspal. Bego, bego, bego. Aini bego. Harusnya dari tadi gue ngeh kalo mereka teroris. Harusnya gue bisa cegah atau minimal melapor. Semuanya terlambat, terlambat.
Sirine meraung. Polisi berdatangan. Rombongan wartawan berlompatan dari mobil-mobil berlogo perusahaan media dengan kamera di tangan.
Aini, lo harus kuat. Perlahan gue menguasai diri. Gue bangkit berdiri. Sumpah, lutut gue lemes banget. Pada saat itulah gue dengar erang kesakitan di samping kanan. Gue sontak menoleh.
Laki-laki itu ...
Laki-laki yang gue liat keluar paling akhir.
Laki-laki itu adalah ... Yuke.
Bagai tertarik magnet, gue berjongkok di sampingnya. Tangannya sedingin es waktu gue pegang. Ya, Allah, apa dia ... mati?
Enggak. Gue geleng-geleng kepala sendiri. Dia masih hidup.
Tanpa buang tempo, gue lambaikan tangan ke arah polisi berseragam hijau yang paling dekat posisinya sama gue. Gue minta tolong buat angkat Yuke ke mobil. God, gue sendiri nggak tau kenapa pengen bawa dia sendiri ke rumah sakit. Bisa aja, ‘kan gue biarin polisi aja yang bawa?
Gue jalan ke mobil bareng si polisi. Beberapa meter di depan mobil gue, salah seorang warga sekitar situ berbaik hati buat nyetirin mobil gue ke RS. Ah, Alhamdulillah, pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu. Jadilah gue meluncur ke rumah sakit disopirin sama warga sekitar. Gue duduk di belakang, memangku kepala Yuke.
“Pak, tolong cepetan. Saya takut nggak keburu,” suruh gue. Oke, silakan bilang gue nggak tau diuntung. Udah ditolongin, masih nyuruh-nyuruh lagi.
“Iya, Mbak.”
Mobil meluncur sederas pelanduk menuju rumah sakit. Gue tatap lekat-lekat pemuda di pangkuan gue. Cuma cewek abnormal yang bilang dia jelek. Mukanya ganteng banget. Kulitnya putih. Dan matanya itu ... mata sipit yang teduh. Gue berani bilang kalo Yuke tampan dan cantik di saat bersamaan.
**
Gue mondar-mandir di lorong rumah sakit. Tingkah gue udah kayak calon bapak nungguin lahiran anak pertamanya. Resah dan gelisah, gue layangkan pandang ke UGD. Dokter lama amat sih nanganin si Yuke. Duh, kok gue nggak bisa berhenti mikirin dia, ya? Semoga lukanya nggak parah.
Klek
Pintu putih di depan gue membuka. Dokter berjalan keluar diikuti suster. Masker medis menutup rapat wajah mereka.
“Keluarga pasien atas nama Yuke Ernesto Tandiono?” Suara sang dokter mengudara.
Gue mengangguk dan berjalan mendekat. Terpaksa gue bohong. Biar gue cepat tau keadaan dia.
“Syukurlah lukanya tidak terlalu parah. Dia hanya perlu memakai kursi roda selama beberapa hari sampai luka di telapak kakinya sembuh.”
Penjelasan nakes itu bikin hati gue lega. Kenapa gue sepeduli itu sih sama Yuke? Tapi ucapan dokter selanjutnya buat kelegaan gue sirna.
“Saya belum tahu persis apa yang dia alami. Tapi sepertinya, peristiwa itu memperparah kondisi mentalnya.”
Otak gue lola. Memangnya Yuke punya kondisi mental kayak gimana? Setahu gue, dia baik-baik aja.
“Yuke kenapa ya, Dok?” tanya gue ketakutan.
“Rekam medisnya menunjukkan kalau Yuke punya riwayat komplikasi depresi dan PTSD.”
Bagai tersambar petir gue mendengarnya. Yuke, pemuda populer dan berprestasi, anak istimewa tapi semangatnya tinggi, pernah depresi dan ada komplikasi PTSD? Gue tau kalau PTSD atau post traumatic stress disorder terjadi setelah seseorang melihat, mendengar, atau mengalami pengalaman traumatis/kejadian yang tidak menyenangkan. Kategorrinya seperti perang, perundungan, penyakit yang mengancam jiwa, dan kelainan seksual. Gue tahu kalau Yuke pernah dihujani perundungan sewaktu ‘dibuang’ tantenya ke panti. Ternyata serangan terorisme di gereja itu membuat kondisi psikisnya amat jatuh.
Di dalam, gue lihat Yuke duduk bersandar. Tumpukan bantal membuat punggungnya nyaman. Gue hampiri tempat tidur. Kok gue ragu ya, dia masih mengenali gue? Apa gue coba kenalan lagi?
“Hai ... Yuke,” sapa gue kaku.
Dia nggak ngejawab. Bikin gue tengsin aja. Sedetik kemudian, gue sadar kalau tatapan matanya kosong. Irisnya memang memancarkan keteduhan. Namun, sorot matanya hampaaa banget. Dari bibirnya terlontar senandung.
Cicak cicak di dinding
Diam-diam merayap
Datang seekor nyamuk
Hap!
Lalu ditangkap
Sekali lagi gue terperangah. Tatapan mata, raut wajah, dan suaranya, entah kenapa bikin hati gue terasa sakit. Bukan, bukan sakit hati karena dia nyuekin gue. Ini jenis rasa sakit yang beda. Semacam ... rasa nggak tega. Belum pernah gue merasakan hal kayak gini. Gue nggak rela teman sekelas gue, kesayangannya anak sekelas, jadi drop kayak gini.
Setelah menyelesaikan senandung lirihnya, Yuke baru ngeh ada gue. Manik matanya menatap ke tempat gue berdiri. Dia seolah tau gue ada dimana, padahal dia buta. Gue jadi agak salah tingkah. Asli, salting diliatin cowok seganteng itu.
Dua orang perawat berjalan masuk. Mereka bersiap mendorong brankar Yuke ke ruang rawat biasa. Yuke terlihat tidak nyaman dengan kehadiran dua suster itu. Terdorong tindakan impulsif, gue pegang tangannya. Gue berbisik,
“Nggak apa-apa. Mereka ini baik kok. Yuk, aku temenin pindah.”
Raut wajah Yuke berangsur tenang. Polos banget, ya Allah. Gue nggak kuat liatnya lama-lama.
Yuke dipindahkan ke ruang rawat biasa. Dua jam berikutnya gue temenin dia. Gue jagain dia sampai tertidur. Pesan-pesan nyokap dan puluhan miss call bokap gue anggurin. Hampir tengah malam ketika gue ninggalin rumah sakit. Gue mencatat dalam hati untuk datang lagi ke rumah sakit besok pagi.
Kelap-kelip lampu Istana Villa menyambut kedatangan gue. Tubuh tinggi kekar milik bokap menghalangi langkah gue di teras. Mukanya cemas banget. Pertanyaannya gue hiraukan. Capek gue kalo harus jelasin gue dari mana.
Gue menyusuri ruang tamu yang dipenuhi sofa putih dan lampu gantung. Anak tangga putih gue naiki. Kamar gue ada di lantai atas, dua pintu sebelah kanan dari tangga.
Wuuush
Semburan pendingin udara menyerbu lengan dan tungkai gue yang pegal. Cepat-cepat gue ambil handuk dan baju bersih. Sebelum tidur gue pengen mandi. Di kamar mandi, gue putar keran air hangat dan duduk di bawah shower. Rasanya kayak ada tangan-tangan tak kasat mata yang memijit badan gue. Ah, rileks.
Dari rantai air yang menari riang, dapat gue lihat bayangan wajah Yuke. Sungguh gue nggak bisa lupain dia. Kenapa otak gue jadi penuh sama sosoknya, ya? Gue memukul-mukul pelan kepala gue, berharap bayangan Yuke bisa hilang tersapu air. Nyatanya enggak. Sosok itu justru semakin mendominasi benak gue.
Ada dorongan di hati untuk selalu dekat dengannya. Dan ... ini pertama kalinya gue buang waktu sekian jam buat nolong temen sekelas. Gue bahkan nggak sempat mikir untung-ruginya. Yang gue pikirin waktu itu hanyalah keselamatan cowok tampan di pangkuan gue.
Aini, mikir apa sih lo? Yuke, ‘kan bukan siapa-siapa lo. Gue merutuki diri sendiri sambil membalurkan sampo. Beberapa jam lalu, gue sendiri yang bilang kalo semua cowok sama aja.
Tapi ....
Yuke ini beda. Beda banget dibandingkan fakboy yang sering gue temui. Dia edisi terbatas. Gue sendiri juga nggak tau kenapa bisa bilang begitu. Padahal dulunya gue nggak gitu kenal sama dia. Gue cuma tau Yuke itu cowok pintar, populer, kehilangan penglihatan karena Ulkus Kornea, dan udah jadi anak yatim. Udah, ah. Yuke terus. Setelah membilas diri, gue matiin shower. Gue keringin badan pakai handuk trus berpakaian. Time to rest.
**
Pemuda tampan berkulit putih itu sekilas terlihat normal. Ia terduduk di kursi roda. Seorang gadis berambut pendek dan berkulit sawo matang mendorong kursi rodanya di seputaran halaman rumah sakit. Gadis bercelana jins biru dan berkardigan hitam itu gue.
Dari tadi Yuke diliatin sama anak-anak berpiyama rumah sakit. Tatapan mata Yuke masih sama kayak pas pertama kali gue ketemu dia beberapa hari yang lalu. Mukanya juga pucat. Dia sama sekali nggak menggubris sapaan sesama pasien rumah sakit atau ocehan gue. Yune dan Tante Laras-ibu kandungnya-pun nggak dia kenal. Keadaan Yuke benar-benar parah sejak tragedi itu. Ironisnya, Yune malah salah paham di saat seperti ini. Dia kira kembarannya sengaja benci atau lupain dia. Jadilah Yune belum datang lagi sampai sekarang dan ninggalin Yuke sama gue.
Nanti siang Yuke udah boleh pulang. Gue pulangin dia kemana, ya? Ke rumahnya, ke Istana Villa, atau ke RPJ (Rumah Pemulihan Jiwa) Menur Kasih? Tapi kok gue nggak yakin ya, kalo di rumahnya dia bakal dirawat dengan baik?
Tiba-tiba lewat di depan kami sebuah keluarga kecil: ayah, ibu, dan satu anak balita. Mata Yuke melebar saat memandang ke titik tempat mereka berada. Tanpa diduga, Yuke berteriak-teriak.
“Yuke mau Hyung! Yuke mau Hyung! Mau Hyung!”
Gue sama sekali nggak siap dengan perubahan drastis ini. Yuke teriak-teriak sambil memukuli pegangan kursi roda. Gue berhenti mendorong dan ganti berlutut di depannya. Lembut gue pegang tangannya.
“Y-Yuke kenapa?” Gue terbata, sedih bercampur takut.
Teriakan Yuke belum berhenti juga. Seisi halaman menatap kami berdua.
“Yuke mau Hyung! Yuke mau Hyuuung!”
Jeritannya berubah menjadi isakan. Oh God, gue nggak tahan. Gue pegang kedua bahunya. Kristal-kristal bening berjatuhan dari matanya yang teduh.
“Apa yang dimaksud Hyung itu Yune? Mau Aini panggilin Yune ke sini? Cerita sama Aini,” pinta gue.
Tak ada jawaban. Memang percuma nanyain hal ini ke orang berpenyakit jiwa.
Makin banyak yang menatap kami dengan pandangan aneh. Gue jadi nggak enak. Tanpa pikir panjang, gue dorong kursi roda Yuke kembali ke dalam bangunan rumah sakit.
Sesuatu menarik perhatian kami di lobi rumah sakit. Hal itu tak lain adalah sebuah piano hitam. Bagus banget di rumah sakit ada piano. Mungkin gue lagi kerasukan Musai, dewi perlambang seni anak Zeus dan Mnemosine. Gue ajak Yuke ke dekat piano itu.
“Yuke mau aku nyanyiin nggak?” tawar gue. Sengaja gue pakai aku-kamu biar nggak terkesan kasar. Biar bagaimana pun, Yuke orang berkebutuhan khusus. Dia harus diperlakukan dengan lembut.
Dia mendongak. Percik antusias terpancar di matanya.
Jari-jari gue menari pelan di atas tuts piano. Gue memang nggak sejago Benita atau Marina. Tapi okelah kalo cuma mainin lagu. Asal jangan disuruh aransemen aja.
Sambil mainin intro, gue kebayang anak Magenta. Gue kangen mereka. Sibuk ngurus Yuke, gue jadi belum bisa ketemu mereka. Komunikasi kami tetap lancar meski nggak ketemuan. Terakhir gue baca di obrolan grup Magenta kalo Marina curhat. Katanya dia takut naksir sama ayahnya sendiri. Ah, ada-ada aja tuh anak.
Intro selesai. Perlahan gue bernyanyi.
Cinta adalah misteri dalam hidupku
Yang tak pernah ku tahu akhirnya
Namun tak seperti cintaku pada dirimu
Yang harus tergenapi dalam kisah hidupku
Ku ingin slamanya mencintai dirimu
Sampai saat ku akan menutup mata dan hidupku
Ku ingin slamanya ada di sampingmu
Menyayangi dirimu sampai waktu kan memanggilku (Ungu-Kuingin Selamanya).
Yuke bertepuk tangan. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, gue liat senyumnya. Senyum merekah di wajah pucat Yuke. Seulas senyum yang dia berikan buat gue.
“Bagus.” Yuke memuji, lirih.
Gue tarik napas dalam-dalam. Aini, tahan. Jangan nangis. Lo harus kuat kayak biasa. Masa sama cowok aja lo mewek?
Sepotong janji terbit di hati gue. Janji untuk membuat Yuke tetap tersenyum. Gue bakal pastiin senyum itu nggak akan hilang dari wajahnya.
**
“Yuke, aku urus administrasi dulu, ya,” pamit gue. Dia mengangguk. Gue dudukkan dia di kursi dekat loket administrasi. Abis itu gue jalan menuju loket.
Nggak butuh waktu lama sampai administrasi dan printilannya kelar. Baru aja gue mau balik ke tempat Yuke nunggu, gue liat seorang gadis yang sangat gue kenal. Rambut cokelatnya, gaya bajunya yang anggun, dan langkahnya yang panjang-panjang gue familiar banget. Dia salah satu member Magenta. Ngapain, ya, dia di sini?
“Erika,” panggil gue ragu.


 maurinta
maurinta