Jika ada hari sial, Dara percaya pagi ini adalah hari sialnya. Siapa sangka bocah tengil yang mengejar-ngejarnya setahun belakangan ini adalah anak Pak Mahdi? Kalau tidak harus bersembunyi, Dara pasti langsung keluar dari rumah itu tadi. Sayang sekali, dia masih membutuhkan bantuan Pak Mahdi, setidaknya hingga sebulan ke depan.
Sehabis sarapan bersama, Naga bersikeras mengantarnya ke tempat kerja. Bocah keras kepala itu tidak menerima alasan apa pun, padahal tempat kerja Dara hanya berjarak 200 meteran saja dari rusun. Jalan kaki pun paling lama hanya sepuluh menit. Lagi pula, Naga akan mengantarnya dengan apa? Jalan kaki juga kan, ujungnya?
“Lo nggak punya kerjaan lain selain ngintilin gue?” Dara nyaris tidak bisa mengontrol volume suaranya ketika menegur Naga yang berjalan lambat di belakangnya. Heran, sudah dua kali ditolak, bagaimana bisa pemuda itu masih memiliki kepercayaan diri setinggi langit begitu?
“Gue mau ke halte depan, kok. Pede amat ngira gue ikutin.” Naga terkikik.
“Kalau mau bohong tuh kreatif dikit, dong. Semua orang juga tahu kalau halte ada di sebelah sana.” Dara berbalik dan menunjuk arah yang berlawanan dengan tujuannya.
“Ya emang gue nggak boleh beli sesuatu dulu di minimarket?”
“Nggak boleh. Nama lo udah gue masukin blacklist.”
Dara dapat melihat seringai di bibir pemuda itu. “Oh, kerjaan lu ganti sekarang? Udah bukan kasir lagi? Naik pangkat jadi manajer?”
Gadis itu menghela napas. Percuma memang. Dia hanya akan menghabiskan tenaga karena berdebat dengan Naga. Sudah sejak lama dia sadar tidak akan bisa menandingi kemampuan debat pemuda yang tersenyum-senyum di belakangnya itu. Sebagai seorang lelaki, Naga memiliki kemampuan bicara yang luar biasa. Emak-Emak PMS aja kalah. Mulut kecilnya sangat bertolak belakang dengan jumlah kata yang keluar dari sana setiap harinya.
Begitu sampai di tempat kerja, Dara memilih menyapa beberapa rekan kerjanya dan mengabaikan Naga yang mulai berkeliling di dalam minimarket. Tuhan, bahkan beberapa bagian dari rak display masih berantakan dan tampak sedang diatur oleh salah seorang pegawai. Naga bertingkah seolah dia seorang supervisor yang tengah mengawasi anak buahnya. Dara kembali menghela napas. Sabar, perintahnya pada diri sendiri, mari bertahan sebentar lagi.
Dara bersyukur Naga tidak nekat menungguinya hingga jam istirahat siang. Jadi dia bisa leluasa menyelinap ke kafe seberang tanpa diikuti seperti tahanan rumah. Dia harus bertemu seseorang. Karena waktu istirahatnya tidak banyak dan harus bergantian dengan rekannya, Dara memilih bertemu di daerah dekat tempat kerjanya.
“Aku nggak bisa lama,” ujar gadis itu sambil terengah. Orang yang ingin dia temui rupanya sudah menunggu. Bagus, berarti dia tak perlu membuang waktu lebih lama. Dara setengah berlari tadi demi memangkas waktu.
Lelaki di hadapannya terlihat tenang. Dia menyodorkan sebotol air mineral dingin ke hadapan Dara. Tak ada waktu untuk menolak, Dara segera meminum air itu hingga nyaris tandas. Lelaki di hadapannya terkekeh.
“Nggak usah ketawa. Apa aku kelihatan kayak pelawak?” sergah Dara sinis. Sebelum gadis itu mengusap mulutnya dengan punggung tangan, lelaki tadi sudah menempelkan selembar tisu dengan sigap ke mulut Dara. “Makasih.”
“Kenapa nggak mau dijemput, sih?”
“Aku nggak mau ngerepotin.” Dara lantas mengeluarkan sebuah kartu dari dompetnya, kemudian meletakkan kartu itu di meja dan menyorongkannya ke arah lelaki di hadapannya. “Kamu tahu aku nggak butuh itu kan, Dim?”
Lelaki itu, Dimas, berdecak ketika melihat kartu yang disodorkan Dara. “Kapan kamu mau pulang?”
“Kapan kamu mau tutup mulut soal keberadaanku?” Dara justru membalikkan pertanyaan Dimas.
“Aku nggak pernah ngasih tahu soal kamu ke siapa pun. Kalau akhirnya kamu ketahuan, itu bukan salahku. Kamu tahu orang tuamu punya banyak mata.”
“Karena itulah aku nggak jauh-jauh dari kamu. Kamu mata mereka. Kalau aku ketahuan, artinya apa?”
Dimas tertawa. “Aku nggak tahu apa lagi yang kamu cari, Ra. Aku udah pernah bilang bakal selalu dukung kamu meski impian kamu bukan Palette.”
“Palette itu punya Papa....”
“Kamu tahu banget alasan papamu bikin Palette. Jangan menyangkal,” sergah Dimas saat melihat Dara membuka mulut. “Aku nggak pernah maksa kamu buat menikah secepatnya. Tapi kamu keterlaluan akhir-akhir ini. Nggak ada mimpi yang mudah, Ra. Aku tahu. Karena itu kubiarkan kamu mencarinya sendiri.”
Dara menunduk, memainkan gantungan bulu di dompetnya. Gadis itu sudah kehilangan selera makannya bahkan ketika melihat seporsi pasta diletakkan di hadapannya. Dimas selalu benar, Dara tahu itu. Lelaki itu sudah terlalu sabar menghadapinya. Seharusnya dia tidak menyia-nyiakannya seperti yang selalu dikatakan Mama. Apalagi jika melihat Naga, seharusnya Dara bersyukur sudah memiliki Dimas.
Hanya saja, pikiran tentang pernikahan masih sangat jauh dari kepalanya. Dara sudah terlalu banyak melihat perempuan yang kehilangan mimpinya setelah menikah. Sebut saja Mama. Wanita itu sangat ingin menjadi seorang desainer pakaian, tetapi begitu menikah, Mama harus meletakkan mimpinya dan mengurus Papa serta Dara.
Dara tidak ingin seperti itu. Dia tidak akan menyerahkan mimpinya pada pernikahan. Meski sampai sekarang dia tidak benar-benar tahu apa mimpinya, apa yang sebenarnya sangat ingin dia lakukan, toh Dara tetap menikmati kebebasannya setahun belakangan. Selama 29 tahun hidupnya, Dara belum pernah memutuskan sendiri apa yang akan dimakannya hari ini, baju apa yang harus dia pakai, bahkan dia tidak pernah tahu rasanya berpanas-panasan di dalam bus.
“Makan, nanti kuantar balik.” Dimas menginterupsi lamunan Dara. “Kamu yakin mau tinggal sama Pak Mahdi? Nggak mau nempatin apartemenku aja?”
Dara mengangguk sambil menyuapkan satu gulungan besar pasta. “Sebulan,” ucapnya setelah menelan makanannya, “Aku nggak akan minta tambahan waktu lagi setelah itu.”
Dimas menghela napas. “Terakhir kali kamu bilang sebulan, berubah jadi enam bulan. Apa kali ini juga bakal kayak gitu lagi?”
Gadis di hadapannya tersedak, lalu terkekeh pelan. Sebelum menjawab, Dara meneguk air di botolnya. “Kali ini nggak akan molor. Janji.”
“Jangan pindah tanpa ngasih tahu aku. Langsung telepon kalau ada apa-apa, hm?”
Dara hanya mengangguk, lalu menghabiskan makanannya pelan-pelan.
“Oiya, aku lupa bilang. Besok aku harus ke Bandung, tiga hari. Nggak apa-apa kalau Milky ikut kamu?”
“Eh? Aduh, aku belum bilang ke Pak Mahdi kalau mau bawa Milky. Gimana, dong?”
“Yah, aku udah bawa sekalian kandangnya tadi.”
Dara menggaruk kepalanya. “Ya udah deh, kayaknya nggak apa-apa kalau dikandangin.”
Pembicaraan mereka berakhir bersamaan dengan jam istirahat Dara yang sudah selesai. Begitu saja memang. Berbicara dengan Dimas selalu menyenangkan. Meski berdebat, mereka selalu bisa mengakhiri perdebatan itu tanpa saling marah atau merasa kecewa. Dimas, entah bagaimana, selalu menemukan solusi bagi kegelisahan yang Dara rasakan. Gadis itu juga menemukan kenyamanan ketika bersama Dimas. Tentu tidak selalu, karena ada kalanya Dara merasa Dimas terlalu membosankan.
Dimas mengantar Dara dengan mobil hingga tiba di depan minimarket, sementara lelaki itu akan menemui Pak Mahdi untuk menitipkan Milky. Dara bilang, mungkin Pak Mahdi dan istrinya masih di warung mereka. Jadi Dimas berencana akan langsung ke terminal begitu menurunkan Dara.
“Yah, mainnya sama yang bermobil. Pantesan nggak tertarik sama pengangguran.”
Dara menoleh ke arah suara. Naga, bersama temannya, menyindir Dara tepat setelah mobil Dimas pergi dari sana. Pemuda itu tengah merokok sambil menikmati kopi cup yang diseduh di dalam minimarket.
“Ya kalau udah tahu pengangguran, kerja dong makanya,” balas Dara. “Belum kerja aja sok-sokan ngajakin cewek pacaran. Emangnya cewek mana yang mau diajakin nongkrong ngopi di teras minimarket?”
Tak perlu menoleh untuk tahu ekspresi Naga. Dara hanya cukup mengabaikan dan melanjutkan pekerjaannya. Sesekali, anak manja macam Naga memang perlu ‘dipukul’ agar melihat kenyataan.
Dari counter kasir, Dara dapat melihat Naga menyundut sisa rokoknya di asbak, kemudian beranjak dan mengajak temannya pergi. Gadis itu tersenyum lebar. Dia kini tahu apa yang harus dilakukan selama sisa waktu yang dijanjikannya pada Dimas tadi. Meski ini bukan menyangkut mimpinya, setidaknya dia harus membalas kebaikan Pak Mahdi selama ini.


 idhafebriana90
idhafebriana90
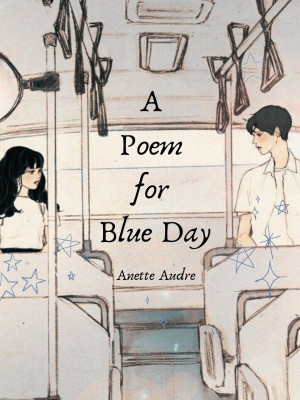




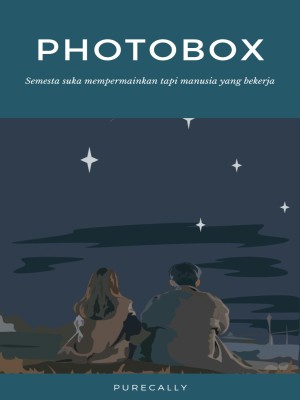




Nggak ada notifnya
Comment on chapter TWICE