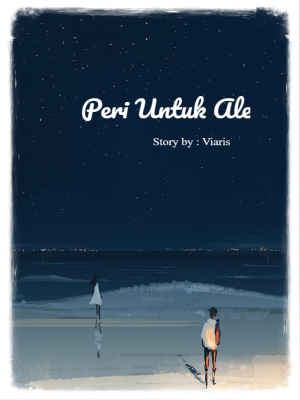“Celana kakak bagus sekali, banyak sakunya.” Ucap Yui dengan polos.
“Panggi aku ‘abang’. Abang Nadif.” Sambil melebarkan tangan dan kuajak dia tos.
“Celananya bagus, Bang.” Ulangnya sambil meringis.
“Kamu mau?”
“Hihi, aku masih kecil, Bang. Kedodoran nanti.”
Aku ikut tertawa, “Ini celana khusus untuk terjun di lapangan kalau sedang penelitian, dibuat dari bahan khusus supaya kalau kena ruput gatal, kayu runcing atau benda sejenisnya, kulit kita tetap terlindungi. Semisal Yui mau, brarti kalau nanti sudah besar harus jadi peneliti juga…”
Yua yang sudah sampai lebih dulu berteriak memanggil kami, “…sudah sampai!”
Tak kusangka ada bukit dengan lebar setengah lapangan bola di sini. Dan ternyata tidak hanya ada aku saja, beberapa pemuda yang sedang bermain ponsel pun tengah duduk di sudut maupun di tengah tanah luas ini.
Bukit ini bernama Bukit Njahe. Dinamakan begitu karena dahulu warga Sarang Panjang kerap kali membuat api unggun dan kumpul-kumpul di bukit ini dengan membawa segelas minuman jahe hangat dari rumah masing-masing.
“Maaf, Pak Bah, baru dapat sinyal.” Suaraku dari ujung telfon.
Yua dan Yui segera menyatu dengan anak-anak lain yang ada di sana.
“Ah, tak apa, aku paham betul keadaanmu.” Suara Pak Bah sedikit putus-putus dari ujung telfon sana, tapi ini lebih baik, aku bisa mendengar dan sedikit mengartikan ucapannya, “Begini, Nak. Mr. Arief nampaknya masih sibuk dengan urusannya sendiri saat ini, jadi biarkan aku yang menyampaikannya. Kemarin secara tiba-tiba Mr. Arief kembali dihubungi oleh seseorang bernama Pram yang selama bertahun-tahun ini kita cari.”
Telingaku berdiri dan jantungku berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya karena mendengar ini.
“Namun karena Mr. Arief terlalu sibuk, ia tak sempat membalas pesan dari Pram itu secara langsung dan ketika di telfon balik, nomornya sudah tidak aktif.”
Ahh, gumamku, kecewa. Dulu hal seperti ini juga pernah terjadi, dan tidak ada hasilnya juga.
“Aku tahu, tentu, aku tahu, ini bukan kabar melegakan yang ingin kau dengar, Dif. Hanya saja aku rasa ini bisa jadi pertanda jika benar Pram itu benar ada, masih hidup dan ia adalah Ayahmu, maka pencarian kita selama ini tidak akan sia-sia karena tanda-tanda keberadaannya kembali muncul. Aku rasa Tuhan pasti akan memberikan sedikit belas kasihannya pada kita semua untuk perkara ini, tidak mungkin hal yang terus kita tekuni dan cari selama bertahun-tahun, tidak membuahkan hasil untuk ikhtiar dan doa yang telah kita lakukan, setidaknya akan ada jawaban yang akan kita terima nanti, tapi persiapkan dirimu untuk mengahadapi apapun nanti jawaban itu. Ingat, meskipun jawaban itu mungkin kelak tidak kau sukai, tapi setidaknya pertanyaanmu terjawab, karena pertanyaan yang baik bukan pertanyaan yang jawabannya ‘iya’ atau ‘tidak’, tapi adalah pertanyaan yang terjawab. Setidaknya itu cukup.”
Aku paham betul dengan maksud Pak Bah kali ini, ia ingin menyampaikan sesuatu namun tidak ingin membuatku terlalu berharap juga tidak mau aku kecewa. Ia menjagaku dengan kata-katanya dari dua kenyataan yang mungkin selama ini sudah terjadi padaku tanpa ia ketahui, kecewa dan terlalu berharap.
“Tapi tenang, Nak. Kabar baiknya aku dan Leo akan coba mencari informasi yang mungkin bisa kami usahakan, Mr. Arief masih saja terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, cukup ia menjadi perantara saja. Kau tenang saja, Nak. Kerjakan tugasmu di situ dengan baik, aku tak mau kau kena masalah karena pekerjaanmu yang tidak becus.”
Aku tertawa dibuat-buat, “Urusan pekerjaan, bisa ditanyakan pada bos-bosku saja yang sebelumnya, dan Pak Bah adalah salah satunya.”
“Oke. Jika perhitunganku benar, maka di situ sekarang sudah lebih dari jam tujuh, maka ini sudah waktunya kau berangkat.”
Percakapan kali ini ditutup dengan salam dari masing-masing sumber suara. Dan dari sana terdengar suara Pak Bah yang samar-samar “Aih, susah sekali pakai hp besar ini.”
Aku bersama Yui dan Yua segera turun dari bukit Njahe, mereka harus sekolah dan aku harus bekerja ke lapangan. Progres kami lumayan baik karena banyak warga yang membantu mengangkati batu dari tempat ekskavasi. Namun misteri asal dan siapa yang menyebabkan hal ini belum terpecahkan.
“Nanti malam Abang mau ikut kami mencari tikus hutan atau tidak?” Yui menawariku.
“Tikus hutan? Untuk apa?” Aku hampir saja terperosok ke pinggiran jalan saat turun menuruni bukit.
“Iya, betul tikus.” Yui ikut menyahut.
“Untuk dimakan, Bang.” Yua menambahi.
“Hah? Sungguhan?” Tanyaku dengan nada tidak percaya “Kalian makan tikus?”
“Kami tidak, yang makan biasanya orang-orang tua dan anak-anak yang sudah besar. Tapi aku pernah mencobanya.” Yua sudah sedikit lebih besar dari Yui, namun karena ia perempuan, ia tidak ikut ke kebun, ia bagian bantu-bantu masaknya saja. Kalau Yui, sedari ia berumur tiga tahun, kadang digendong Ayahnya untuk masuk hutan. Namun itu hanya pernah Yui rasakan satu kali.
Aku sebenarnya agak geli dan mual mendengar tikus dikonsumsi, tapi dari yang Yua dan Yui jelaskan padaku, daging tikus hutan itu berbeda dengan tikus rumahan pada umumnya, karena tikus hutan makanannya adalah buah dan dedaunan hutan jadi dagingnya kurang lebih mirip dengan marmut atau kelinci.
Tapi secara penampilan, tikus hutan sama seperti tikus rumah, bulunya kecoklatan dan ekornya panjang.
“Kadang, di musim tertentu, Kakung juga mencari belalang di kebun kalau malam. Untuk di makan juga. Tapi ibu dan Kakung tidak memakan tikus, hanya belalang saja, cuma memang kadang ibu disuruh memasak oleh para pemburu tikus karena masakan ibu yang terbaik, jadi ibu hanya bantu masak saja.” Yua menjelaskan.


 littlemagic
littlemagic