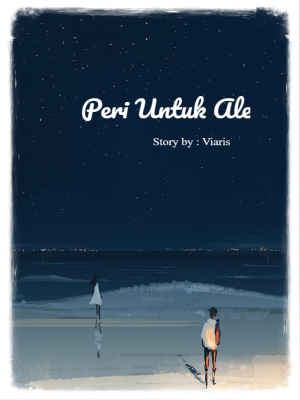Di perjalanan aku terus mengingat apa yang dikatakan Pak Bah padaku seminggu yang lalu. Bahwa mereka yang istimewa adalah mereka yang tidak pernah pergi. Memang kiranya begitu, seketika orang datang, seketika juga orang pergi, dan mereka yang tetap tinggal tidak mungkin tidak ada artinya sama sekali.
“Aku akan mengusahakanmu!” ucapku pada pada setumpuk kertas berharga yang berisi apa-apa saja yang harus kulakukan di lapangan nanti. Mungkin yang membuat aku berbeda dengan rekan disekitarku adalah, aku selalu membuat catatan di buku kecil tentang kata-kata, daftar barang dan kegiatan yang harus aku selesaikan.
Aku terbangun dengan kepala sedikit tengeng karena salah bantal dan mungkin efek tidur di perjalanan, dari sekian banyak spesies makhluk hidup yang bisa tidur di mana saja, aku adalah salah satunya. Leherku pegal ampun-ampunan karena bantal di bus ini benar-benar tidak lolos uji seleksi postur leher, entah manusia macam apa yang akan nyaman dengan bantal begini, keras dan rata.
Aku dan tim tiba di sebuah desa yang sangat berkabut setelah menempuh jalan yang menanjaaaakkk dengan kemiringan lebih dari empat puluh lima derajat, miringnya itu miring sekali, aku berani bertaruh. Kalau jadi soal fisika, mungkin kita akan disuruh mencari kecepatan roda berputar atau mencari panjang lintasan.
Di kanan dan kiri bus adalah lereng terjal yang cukup membuat lutut gemetar kalau berdiri di ujungnya, takut terjungkal atau tertimpa tebing yang di atas. Tanah-tanah di beberapa tempat juga terlihat menyangga batu besar yang berlumut namun kokoh dan tegak menantang sinar matahari yang berusaha keras menyelinap di celah-celah kabut.
Desa itu benar-benar berkabut, aku belum pernah melihat kabut setebal itu bahkan di Nara yang letaknya masih di pegunungan sekalipun. Udaranya terasa dingin bahkan ketika kami belum sampai di lokasi, sampai-sampai beberapa kawan meminta AC bus dimatikan karena memang tidak dibutuhkan.
Mungkin karena kami tiba saat masih pagi jadi kabut masih betah mengambang di bukit dan lembah-lembah, setelah sedikit siang dan matahari pagi telah mengintip di balik perbukitan, pelan-pelan mereka terangkat dan membentuk jalan-jalan ilahi dari sinar yang terpancar menyerong dari ufuk timur.
Meskipun telah lama tinggal di kota, aku akrab sekali dengan udara sejuk ini. Pagi dingin menusuk tulang, namun segar dan menghilangkan kepenatan. Yang kini terpampang di depanku adalah hijau seluas mata memandang dengan sedikit selaput tipis yang belum meninggalkan lembah dan ladang.
Aku bersama tiga rekanku yaitu Elnusa yang kerap dipanggil El, Sabang dan Guna tinggal di sebuah rumah milik seseorang lelaki yang kami panggil sebagai Mbah Kakung. Aku tak tahu siapa nama aslinya, tapi itu bukan masalah. Seluruh jagat desa memanggilnya begitu. Beliau tinggal bersama satu putri dan dua cucunya.
Rumah Mbah Kakung cukup besar dan sederhana, ada empat kamar, dua kamar mandi, sebuah dapur dengan tungku perapian kuno, sebuah ruang ibadah dan sebuah ruang tamu. Atap rumah ini disangga oleh tiang tinggi yang terbuat dari kayu jati asli dengan pagarnya wangi entah dari kayu apa.
Sempat aku kira ada pengharum ruangan di seluruh rumah ini, namun tidak satu pun kutemukan wujud pengharum itu, hingga El memberi tahuku bahwa yang harum itu adalah dinding tegak yang menyekat rumah, barulah aku mengerti.
Halaman belakang rumah ini menghadap ke timur, dengan tebing berundak yang tidak terlalu tinggi, namun cukup untuk membuat patah tulang jika terjatuh dari sana.
Aku sekamar dengan El, sementara Guna dengan Sabang. Sebenarnya, kamar yang aku tempati ini adalah kamar dari anak sulung Mbah Kakung yang hanya pulang setahun sekali kalau lebaran Idul Fitri dan kamar Guna adalah kepunyaan Yua  cucu Mbah Kakung dan anak pertama dari Ibu Tinah. Jadilah Yua tidur bersama ibu dan adiknya, Yui.
cucu Mbah Kakung dan anak pertama dari Ibu Tinah. Jadilah Yua tidur bersama ibu dan adiknya, Yui.
Mbah Kakung belum genap seribu hari ditinggal kekasihnya, Mbah Putri, yang selalu ia ceritakan pada kami. Tak jarang ia menyebut kebiasaan-kebiasaan Mbah Putri yang masih ia ingat saat kami sedang melakukan hal yang sama.
“Tinggallah di sini seperti di rumah sendiri. Tapi kuharap kalian para anak muda bisa mengerti keadaanku yang rewel ini. Tinah, anakku mulai besok akan tinggal di rumah sebelah karena penghuninya akan pergi jauh dan ia minta kami merawatnya.”
Jadilah rumah ini seperti asrama putra, karena Yua tinggal bersama ibunya di rumah sebelah, sementara Yui ~adik Yua, tidur berpindah-pindah. Yui masih berusia empat tahun, sebagai cucu lelaki satu-satunya, Yui sangat lengket dengan Kakungnya itu.
Penyambutan kami di rumah ini sangat hangat mengalahkan udara dingin yang menguasai sekitar. Kini di rumah ini ada Mbah Kakung, Yua, Yui, aku dan tiga rekanku, Ibu Tinah yang sibuk menyajikan makanan dibantu beberapa rekan perempuan satu projekan yang sedang main kemari. Ada juga satu lelaki parubaya yang esok akan pergi dan rumahnya dititipkan kepada Mbah Kakung dan Bu Tinah.
“Panggil saya Pak Udi.” Sapa lelaki parubaya itu seraya menjabat tangan kami. “Kalian boleh menggunakan rumahku juga untuk kegiatan jika rumah gedong Mbah Kakung ini kurang luas.” Kami tertawa menanggapi ucapannya, rumah Mbah Kakung lebih dari cukup.
“Mungkin perempuan-perempuan yang tinggal di rumah Pak Kadus bisa ikut berkenalan juga. Aneh sekali jika rumahku disambangi oleh orang-orang yang tidak aku kenal.” Minta Mbah Kakung.
Masing-masing dari mereka memperkenalkan diri, ada dua ibu-ibu yaitu Ibu Dhena dan Ibu Nada, keduanya adalah seorang arkeolog senior dari balai budaya.
Kemudian ada perempuan berwajah bulat yang senang sekali berbicara bernama Gembi, satu mahasiswi magang bernama Maharani, dan seorang ahli forensik bernama Eoni. Tiga gadis ini sebaya denganku, tapi mungkin lebih tua aku satu atau dua tahun.
Dalam projek kali ini, satu tim terdiri dari 14 orang dibantu oleh bapak-bapak sekitar untuk penggarapan lapangan. Untuk urusan cangkul-mencangkul aku tentu bisa melakukannya, namun untuk membedah tanah puluhan meter dengan sembilan orang laki-laki yang basiknya peneliti dalam waktu singkat sangatlah tidak masuk akal. Untuk itu kami mengajak petani dan buruh desa untuk ikut serta.
Di hari pertama sampai desa, tidak banyak yang kami lakukan. Setelah sowan dengan kepala desa dan perangkatnya, tim disarankan untuk berberes kamar yang akan kami tinggali karena waktu kami di sini tidaklah sebentar. Malamnya kami hanya berkumpul dengan pemilik rumah, makan-makan enak dan istirahat. Perjalanan dari tempat pemberangkatan awal sampai ke desa ini sungguhlah bukan jarak yang dekat. Setidaknya butuh dua hari untuk benar-benar sampai.


 littlemagic
littlemagic