Tidak ada satu hari pun lewat tanpa aku memikirkan
dirinya. Dan walaupun sudah 9 minggu, satu hari dan 19 jam berlalu sejak aku
menemukan cincin Anna tergeletak di depan pintuku, rasa sakitnya masih begitu
baru seolah hal itu baru terjadi sembilan belas menit yang lalu. Aku tidak tahu
apakah akan ada satu hari di mana aku bangun dan dirinya bukan yang pertama
hadir di benakku. Apakah akan tiba suatu hari di mana aku akan merasakan
baik-baik saja tanpa tercekik kekosongan yang datang dari segala penjuru ini. Aku
membenci diriku karena dilahirkan di Amerika. Aku benci Anna karena dia tidak
dilahirkan di America. Tapi bila kita bukan diri kita yang sekarang, apakah
kita bahkan akan bertemu? Bahkan jika kakek dan nenekku melaut ke Indonesia dan
bukan ke Amerika, apakah aku akan bertemu dengan dirinya? Dan dalam situasi
seperti apa? Dan akhirnya, aku hanya punya semua pertanyaan tak berguna yang
tak ada jawabannya ini. Ada begitu banyak orang dan situasi yang dapat
kusalahkan tapi semuanya tidak akan mengubah fakta bahwa aku telah kehilangan
dirinya.
Aku mendengar ketukan ringan pada pintuku. Ketukan
setengah hati. Mungkin itu si pemilik komplek apartemenku. Bulan lalu dia
meminta diriku untuk membayar sewa lebih cepat karena dia perlu membayar
tagihan kartu kreditnya. Mungkin dia menginginkan hal yang sama lagi bulan ini.
Aku membuka pintu. Bukan, yang ada di depan pintuku bukan si empunya apartemen.
Yang ada di sana adalah Anna. Hatiku melompat dan tiba-tiba ada segumpal kertas
di kerongkonganku. Aku hanya berdiri di sana, memandanginya, mencoba untuk
berendam di ruang yang kami tempati bersama ini, mencoba menghirup pemandangan
di hadapanku.
“Hai, Dayton,” katanya. Suaranya lirih seolah ia harus mengerahkan
seluruh tenaganya hanya untuk mengucapkan namaku.
“Anna,” kataku, merasakan namanya pada bibirku. “Apa
... apa yang kau lakukan di sini?” tanyaku, dan langsung menyesalinya.
Pertanyaan itu terdengar seolah aku tidak ingin dia ada di sini padahal yang
sebaliknyalah yang benar.
“Aku... sejujurnya aku tidak tahu,” katanya.
“Apakah.. kau mau masuk?” tanyaku.
“Mungkin itu bukan ide yang baik,” katanya. Tapi aku
tidak bisa hanya membiarkannya berdiri di sana, bukan? Jadi aku maju dan meraih
tangannya. Aku merasakan kulitnya pada kulitku dan ingat semua waktu dulu di
mana aku masih punya hak untuk menyentuhnya sesering yang kuinginkan. Apakah
aku cukup mensyukuri waktu-waktu itu atau aku menganggapnya biasa saja? Kapan
terakhir kali aku menyentuhnya? Apakah saat itu aku sadar itu akan jadi yang
terakhir kalinya? Tentu tidak. Apa yang akan kulakukan bila aku tahu? Ia
memandang jari kami yang saling bertautan seolah itu sebuah benda angkasa luar
yang tidak dapat dipahaminya. Dengan perlahan, aku menarik Anna ke dalam
apartemenku. Dengan jemari kami masih terus bertautan seolah aku begitu takut
dirinya akan menguap hilang bila aku melepaskannya, aku menutup pintuku.
Setelah itu, aku tidak tahu siapa yang bergerak lebih dulu. Mungkin aku,
mungkin juga dirinya. Ia berada di dalam pelukanku, bibirnya pada bibirku,
tanganku sibuk menariknya, menyentuhnya, meraihnya seolah aku sedang berusaha
menempatkan seluruh tubuhnya di dalam kedua telapak tanganku. Aku mendalamkan ciumanku.
Aku menciumnya untuk memberitahunya bahwa aku tidak akan pernah mencintai orang
lain sebesar aku mencintai dirinya. Aku menciumnya untuk mengatakan bahwa tidak
akan ada suatu hari di mana aku bangun dan menemukan diriku tidak lagi
mencintainya. Aku menciumnya untuk memohon supaya aku tetap boleh berada di
dalam hidupnya. Ia membalas ciumanku. Ia meletakkan kedua lengannya di belakang
leherku seolah ingin memastikan aku tidak pergi ke mana-mana. Yang
sesungguhnya, aku memang tidak akan pergi ke mana-mana. Dia lah yang akan pergi
meninggalkanku.


 arleen315
arleen315

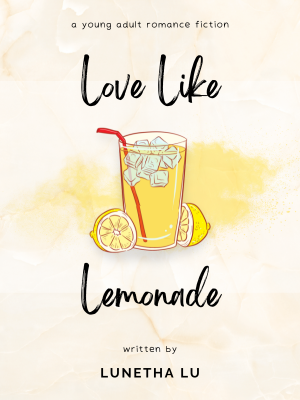
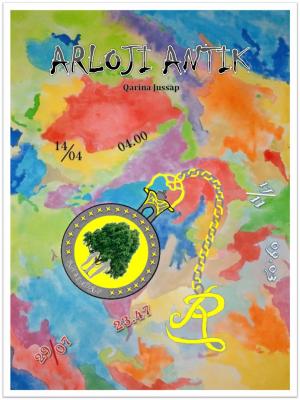







One of my favorite authors / writers
Comment on chapter opening page