Aku mendapat pinjaman motor dari kantor untuk mengantarkan barang ke desa-desa. Motor ini boleh aku bawa pulang, dan aku dapat uang bensin setiap seminggu sekali.
Cukup menyenangkan bekerja menjadi kurir di sini. Aku bisa pergi ke sana kemari, mengunjungi tempat baru dan mengerti jalan-jalan yang belum pernah aku lalui sebelumnya.
Biasanya Mr. Arief hanya sebulan sekali berkunjung ke kantor tempatku bekerja. Sebagai komisaris pusat, ia diperkenankan mengunjungi kantor tiap cabang.
Meskipun gayanya sedikit mengerikan dan aneh tapi ia sungguh orang yang baik.
Yang tidak terlalu menyenangkan bekerja di sini adalah aku yang tak akrab dengan karyawan yang tinggal di kantor.
Raut mereka seperti wajah-wajah yang terpaksa bekerja dan tak dapat tunjangan di akhir bulan.
Sejauh ini hanya ada dua orang yang kukenal dengan baik.
Itu pun karena Mr. Arief yang memintanya untuk membawaku berkeliling kantor dan mengenalkan fasilitas yang ada di sana.
"Tolong nanti kalau kamu lewat Berian Raya, saya mau titip barang, bilang saja dari kantor, di sana ada perumahan namanya Klipang. Plangnya besar, kamu pasti tidak akan kesulitan mencarinya." Mr. Jehian menyodorkan sebuah paket berbalut kertas coklat dengan sebuah alamat tertempel di atasnya. "Ongkirnya nanti gampang ya. Aku kasih lebih. Ini bukan lewat pos, barang ini milik pribadi. Bisa ya?"
"Beres Pak." Kuacungkan jempol ke arah Mr. Jehian.
Setelah motorku sudah cukup panas segera kukemas karung berisi barang milik pelanggan dan kutancap gas dengan semangat penuh, tanpa rem!
Sebenarnya pekerjaan ini melelahkan, hampir 70% hariku adalah di jalanan, tapi aku rasa tidak ada pekerjaan yang menghasilkan tapi tidak melelahkan.
Ada sebuah harga yang harus dibayar, entah itu dengan pikiran, tenaga ataupun dengan perasaan.
Aku beruntung mendapat pekerjaan ini, dari pada tidak punya pekerjaan sama sekali.
Perlahan-lahan aku merasakan nikmatnya perjalanan. Meskipun pergiku hanya di sekitar kota kecamatan tapi aku rasa aku mulai menyukainya.
Mengetuk tiap pintu rumah dengan berkata, "Kak, Paket." kemudian menanyakan nama yang tertulis di barang kiriman, mengucapkan terima kasih lalu pergi lagi ke alamat tujuan berikutnya.
Seperti itu berulang ulang. Dalam sehari aku bisa sampai dua puluh kali mengucap salam dan berteriak, "Kak, paket."
Tak terhitung berapa kali aku berdecak kagum mengamati pemandangan bukit dan gunung yang saling terhubung.
Aku jadi tahu mengapa Zahwa sangat suka tinggal di tempat ini. Katanya, untuk alasan apa pun ia akan selalu lebih menyukai gunung daripada pantai.
Dan aku setuju.
Di daerah desa yang berada di atas bukit, kabut masih bisa ditemukan padahal sudah jam sembilan.
Pohon pinus yang meramaikan lembah-lembah, menjadi lukisan nyata yang diam dan tetap berada di tempatnya, seolah menyaksikan setiap orang yang melintas dengan sangat mafhum, tunduk dalam kekuasaan yang Maha Kuasa sang pemilik seluruh alam.
Keterampilanku dalam mengendarai sepeda motor meningkat tiga kali lipat dari biasanya.
Aku sudah lebih berani menyalip bus atau truk yang kadang lambat berjalan di tanjakan.
Aku bisa menyelip di antara dua kendaraan yang tengah berjalan dari arah yang saling berlawanan pada ukuran jalan yang medium.
Menerjang tikungan-tikungan tajam pun sudah khatam kutaklukan. Aku adalah raja jalanan di daerah pegunungan.
Dering ponselku berbunyi beberapa kali, tapi aku tidak bisa mengangkatnya di tengah jalan.
Jujur saja, aku adalah orang yang jarang mendapatkan pesan singkat ataupun telepon dari seseorang.
Orang-orang di sekitarku bisa langsung menemuiku tanpa harus menghubungi lewat telepon dan aku terbiasa karenanya.
Meskipun kini ponselku baru dengan fasilitas dan kecanggihan yang jauh lebih baik dari ponsel lamaku, tapi tidak mengubah intensitas pesan atau panggilan yang datang.
Sama saja.
"Kak, pakeeet," ucapku pada penghuni rumah berpagar tinggi dengan cat dinding berwarna pastel dan di sebelahnya terdapat lapangan badminton.
Lapangan sedang ramai dengan atlet dan penonton, sepertinya sedang ada turnamen.
Hal ini membuatku sedikit lebih berusaha dalam mengucapkan kata-kata andalanku, "Kak, pakeeet!"
Kuperhatikan, di perumahan Klipang ini memang tempat tinggalnya orang-orang elit.
Semua rumahnya mempunyai halaman yang luas dan desain yang apik-apik, bukan seperti perumahan yang model dan bentuk rumah satu dengan rumah lainnya sama.
Beberapa menit belum mendapatkan jawaban, mataku merayapi dinding pagar mencari tempat yang memungkinkanku untuk menemukan sebuah bell atau lonceng.
"Nah! Di sana ternyata." Sebuah tombol dengan lambang lonceng berwarna merah terpasang di pojok kanan atas pada tembok di samping gerbang.
Namun, sebelum telunjukku menyentuh benda itu, sudah lebih dahulu terdengar suara orang membuka gembok gerbang dari halaman dalam.
Tidak lama kemudian, muncul seorang perempuan menggunakan kerudung berwarna pastel dan baju tidur yang kelihatannya mahal, rasanya pantas dengan rumahnya yang semegah ini.
Untukku yang terbiasa dengan dinding anyaman bambu dan semi kayu, melihat rumah gedong begini, wajar saja berdecak kagum.
"Permisi, apa benar ini kediaman Ibu Mei?" Perempuan itu mengangguk, tak banyak yang aku katakan.
Seperti biasa, setelah paket tersampaikan, aku mengucapkan terima kasih dan pergi ke alamat selanjutnya.
Kejadian di kantor hari ini cukup lucu, Mr. Jehian membeli tiga plastik besar berisi buah naga yang ia beli di pasar kota kabupaten.
Entah dalam rangka apa, tapi kelihatannya perasaannya sedang baik. Aku ikut terkena dampaknya.
Apoy dan Seli membawa buah naganya ke rumah, sementara untuk karyawan yang bujang sepertiku, lebih suka menjadikannya bahan pesta di kantor.
Sepulang dari mengantar barang, aku menyempatkan untuk berkumpul dengan teman-teman.
Entah apa yang membuat mereka jadi gila sekali dengan buah naga, terus terang aku sebenarnya biasa saja dengan buah satu ini.
Malah aku merasa aneh dengan warna merah mudanya yang amat mencolok, belum lagi ketika selesai makan bibir kita jadi mirip dengan anak-anak SMA yang gemar sekali memakai lipstick shade 59.
Mungkin karena terbawa suasana, aku jadi bisa menghabiskan satu setengah buah naga untuk perut sendiri.
Awalnya setengah buah naga aku makan menggunakan sendok, yang setengahnya diambil oleh Ipan.
Merasa belum cukup, Apoy memberiku setengah lagi buah naga, dan aku terima dengan senang hati.
Aku memakannya dengan menggunakan sendok yang sama. Hari itu bibirku benar-benar seperti gadis SMA yang menggunakan lipstick shade 59.
Kemudian malamnya, beberapa karyawan lembur karena ada paket dari luar kota yang datang telat karena mobil pengirimannya mogok dalam perjalanan.
Ada 5 orang yang menunggu di kantor, termasuk aku. Sepertinya malam ini aku menginap.
Di tengah-tengah kesibukan aku sempatkan untuk menelpon Lail,
"Ada apa? Kenapa jam segini belum balik ke rumah? Sekarang sudah jadi orang sibuk lagi ya?" Suaranya meringis di ujung telepon.
"Berikan teleponnya ke Ibu, aku mau bicara." Terdengar desis Lail yang ingin meledekku lagi. "cepat sebelum pulsaku habis. Ini sangat penting."
Aku sedikit memaksa, menutup celah agar Lail mengurungkan niatnya.
Ibu hanya berbicara iya-iya saja saat aku meminta izin untuk tidak pulang dan menginap di kantor karena alasan tadi.
Tambahnya, aku diminta untuk tidak pulang terlalu siang karena besok adalah jadwalku menjaga toko Bu Elis, saudaranya Pak Leo.
Hampir saja aku lupa.
Beberapa jam setelah muatan dari mobil box pengantar paket selesai diturunkan, kantor masih saja ramai.
Kami bermain kartu untuk mengisi malam. Dari saat itu, mulailah beberapa orang di antara kami sering bolak-balik ke kamar mandi.
Awalnya aku biasa saja, hingga aku mengalaminya sendiri, perutku mulas tidak karuan karena kebanyakan makan buah naga.
Mulasnya benar-benar sangat mulas, saking seringnya kami bolak-balik ke toilet.
Paginya, sebelum aku pulang, aku menemukan Mr. Jehian tengah muntah-muntah di wastafel dapur karena melihat lubang kloset yang berwarna keunguan, mirip warna jus buah naga namun dengan warna yang sudah tidak terlalu pekat.
Kira-kira apa penyebabnya? Tidak usah disebutkan, pasti sudah bisa mengerti dengan sendirinya.


 littlemagic
littlemagic









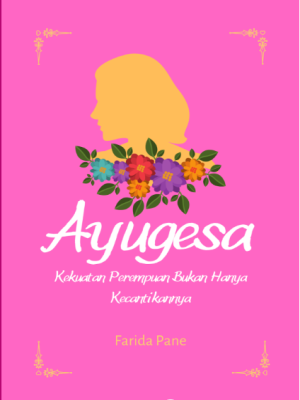

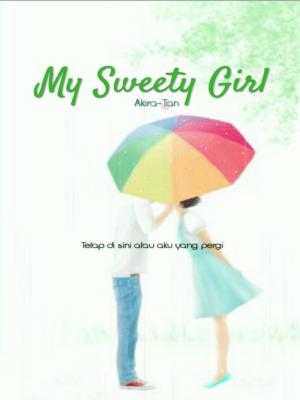
I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog