[Zahwa POV]
Beberapa bulan lagi sakura akan tumbuh dan aku harus melihatnya!
Aku sungguh berharap semoga ia paham jika pergiku bukan untuk meninggalkannya, dan rantauku bukan untuk menemukan hati yang baru.
Meskipun aku sedikit tahu ada yang tidak wajar diantara kami, tapi bagaimana aku harus memperlakukan perasaan ini?
Bukan aku yang meminta untuk diberi perasaan suka padanya, bukan aku pula yang merangkai jalan cerita dalam mimpi sehingga ia bisa hadir setiap malamnya.
Aku sungguh tidak meminta.
Mulai September yang lalu, di Jepang sudah berteman dengan musim gugur.
Suhu kota lumayan panas untukku yang sebelumnya terbiasa tinggal di pegunungan, namun aku tetap tak pernah melewatkan syal yang biasa kulingkarkan di leher dan menutupi seluruh permukaannya.
Beruntung pendingin ruangan dalam kereta bekerja dengan baik.
Dari Tokyo, aku akan pergi ke Fukui, 2 jam lagi kemungkinan aku sampai di sana.
Sudah dua bab buku karya Seno Gumira Ajidarma selesai kubaca, membuat mataku terus sibuk berjalan dan menyapu kata-kata dalam setiap barisnya.
Lucu sekali, buku ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang berusaha keras mengirim sepotong senja untuk Alina, pacar dari lelaki tadi.
Ia rela menjadi buronan insan di seluruh kota karena telah mencuri senja.
Aku belum membaca sampai akhir, aku tak tahu apakah senja ini akan sampai pada Alina dengan keadaan utuh atau malah mungkin tidak sampai, aku belum tahu.
Sebulan lebih di tempat baru ini aku belum banyak menemukan teman. Selain karena tertutup, aku belum banyak bertemu orang.
Belum genap seminggu, aku langsung sibuk dengan kuliah dan orang yang kutemui setiap hari hanya mereka-mereka saja.
Aku masih belajar bahasa pribumi di sini.
Satu hal yang sangat berbeda dengan sekolahku dahulu adalah.. di sini tidak semua orang di dalam satu kelas bisa saling mengenal.
Bahkan yang kukira mereka sudah akrab pun masih saling meminta izin ketika ingin meng-follow media sosial satu sama lain.
Jujur, itu cukup mengagetkan untukku, di SMA-ku dahulu, media sosial adalah arena publik di mana orang ke orang bisa bebas terhubung tanpa embel-embel permisi ingin follow.
Dari Fukui Station aku masih harus naik taksi untuk sampai ke rumah seorang teman.
Letaknya agak jauh dari pusat kota, tak sanggup kakiku berjalan sendirian di tempat yang bisa dibilang asing bagiku.
Ia adalah teman baruku yang pertama bahkan saat aku belum genap sehari di Jepang.
Namanya adalah Hiroshi, si manusia silver. Ia bekerja setiap hari di perempatan jalan tempat aku bersekolah.
Perkenalan kami sangat sederhana, aku menjatuhkan dompetku dan ia menemukannya, bahkan mengantarnya sampai ke dorm tempatku tinggal.
Di hari pertama kuliah, bahasa Jepangku masih buruk dan tidak semua orang bisa berbahasa inggris. Hiroshi bisa keduanya.
Ia bilang bahwa dompet coklat milikku sudah lama tertinggal di bangku dekat tempatnya bekerja menjadi manusia silver.
Tak ada yang berminat mengambilnya. Alhasil ia amankan dan ia cari pemiliknya.
Keesokan harinya aku bertemu Hiroshi, ia selalu ada di situ. Apabila ada waktu luang, aku selalu menyempatkan untuk datang atau sekadar lewat menyapanya.
Kebetulan perempatan itu adalah akses terdekat dari dorm ke kampus.
"Ini adalah adalah hari ke sebelas di mana kau terlihat murung." Hiroshi menjemputku di stasiun lokal, katanya rumahnya masih jauh, dan aku harus menunggu angkutan lagi untuk benar-benar sampai ke rumahnya.
"Tidak, aku hanya sedang rindu rumah."
"Kuharap rindu bukan alasan mengapa perasaan jadi menderita." Hiroshi melambaikan tangan pada taksi yang berseliweran, cukup sepi untuk ukuran Jakarta, tapi sangat ramai untuk kota yang mayoritas orangnya adalah pejalan kaki. "Tunggu, bukankah kemarin sudah telepon ibu dan ayahmu?"
"Iya sudah, rinduku sedikit terobati karena mengetahui mereka dalam keadaan baik-baik saja." Taksi membelah jalanan kota dengan kecepatan medium, tak ada kendaraan lain.
"Lalu rindu mana yang kau risaukan?"
Aku diam, bukan mau menjawab, melainkan karena tak paham dengan perasaan sendiri.
"Kau sudah pergi jauh meninggalkan orang-orang yang telah berada di belakang, kau tak akan maju jika sesuatu yang kau tinggal itu terus kau ikat namun tak kaubawa ke mana-mana. Itu hanya menjadi beban bagimu. Lepaskan saja agar langkahmu ringan."
Aku masih diam, tak mengalihkan pandanganku dari jajaran pohon yang ranum dan kecoklatan di pinggiran jalan yang tabah menghadapi teriknya matahari.
"Kau pasti setuju jika lima puluh persen dari hubungan adalah percaya, separuh yang lain adalah macam-macam perasaan, istilah, dan logika yang memang harus ada. Jika harga sebuah percaya tak lebih besar dari rasa curiga, maka ada sesuatu yang salah di antara hubungan itu."
"Ya, mungkin. Aku rasa aku menyukai orang yang hanya dan selalu menganggapku sebagai adiknya," ucapku lirih, sangat lirih.
"Aku hampir tak percaya, dari caramu menceritakannya, kurasa ia sebenarnya menganggapmu lebih."
"Jangan mengucapkan hal yang belum pasti hanya untuk menenangkan atau menyenangkan perasaanku, Hiroshi. Aku tidak mau bersenang-senang dan merasa aman di atas kebohongan."
"Kau terlalu defensif pada dirimu sendiri, padahal perasaan yang seperti itu tadi, selama tidak berlebihan, menurutku, tidak apa-apa. Lagi pula, kita tak pernah tahu mana yang benar jujur atau mana yang benar bohong. Bisa jadi, apa yang kita kira kebohongan ternyata adalah kebenaran, begitu juga sebaliknya, sesuatu yang kita percaya sebagai kejujuran ternyata adalah kebohongan besar. Manusia selalu dipenuhi dengan ketidaktahuan. Jangan sia-siakan perasaanmu untuk merasa tidak bahagia."
Kami telah sampai di sebuah desa dengan tangga berundak yang dibangun di sana sini.
Ini pegunungan! Untuk apa pun alasannya aku lebih suka matahari terbit di punggung bukit, daripada matahari terbit di garis batas cakrawala antara angkasa dan samudra.
Aku lebih suka udara dingin daripada sepoi dan ributnya angin pesisir.
Aku selalu suka udara pegunungan, lengkap dengan kabut, sepi, jauh dari kota dan tersembunyi.
Detak jantungku merasa lebih baik ketika terbangun di sana.
Hiroshi menuntunku masuk ke sebuah halaman yang pelatarannya dipenuhi tanaman tomat, udaranya sejuk, angin bertiup damai dan beberapa makhluk terbang terlihat sejahtera di dataran ini.
Aku menghela napas berkali-kali, apa ini yang aku butuhkan?
Sejak masih di halaman, terdengar ramai suara anak-anak yang tanpa bertanya pun aku sudah tahu suara itu berasal dari mana.
Dan ketika masuk, seketika aku sadar, ini rumah bukan sepenuhnya rumah, tempat ini adalah panti asuhan.


 littlemagic
littlemagic








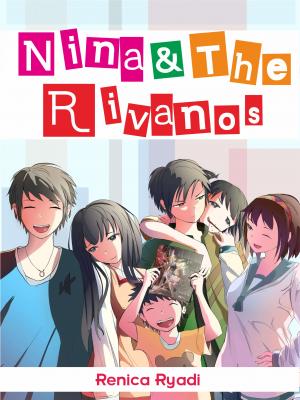



I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog