Matahari sudah lewat dari atas kepala, rumah Pak Bah semakin ramai dengan anak-anak yang gaduh bermain sambil belajar bersama Sena.
Rupanya ia adalah seorang relawan di sebuah panti asuhan di kota besar.
Tak heran mengapa ia mudah sekali mengambil hati anak-anak di sini.
“Bang Nadif, ikannya enak sekali.” Suara teriakannya terdengar riang dari dalam rumah.
Aku ikut tersenyum, Pak Bah juga.
“Bagaimana ceritanya ibumu dengan tiba-tiba membawakan buah tangan kemari? Tak macam biasanya.” Solder dan ragum masih setia berada di dekatnya.
“Kemarin, kuceritakan pada Ibu ke mana pergiku belakangan ini. Dan ia terlihat senang mendengarnya. Aku juga menceritakan sedikit tentang Pak Bah.”
“Kau tidak melebih-lebihkan saat bercerita tentangku, kan?”
Aku menggeleng, mungkin tidak.
“Aku hanya merasa tak ada satu pun orang yang cukup mengenalku dengan baik selain diriku sendiri.”
Kutanya apa fungsi dari alat-alat asing di depanku ini. Ada ragum, jangka bengkok, kikir beragam bentuk, alat pahat, stamp dan masih banyak barang lainnya.
Jujur sejak pertama kali masuk ke bengkel mesin ini, aku tak terlalu banyak tahu dengan perkakas-perkakas yang tersedia.
Kehidupanku beberapa tahun ini banyak kuhabiskan menatap kertas, buku, pensil, penghapus, dan teman-temannya.
“Aku senang pada pemuda yang penasaran sepertimu.” Dengan telaten Pak Bah menjelaskan satu per satu, itu pun tidak semua aku pahami, hanya beberapa.
Rampung semua benda terlihat kutanyakan, giliran Pak Bah yang bertanya.
“Bagaimana dengan kabar gadis yang kau suka itu? Kau masih senang memikirkannya?” Mulutnya terkekeh menampilkan deretan gigi yang tak terlalu putih tapi rapi dan terlihat kekar. “Aku tahu kau tidak sepakat dengan sebutan si matahari terbit, jadi tidak aku gunakan istilah itu lagi.” Entah dari mana ia tahu.
Aku diam, lama. “Tidak tahu, Pak.”
“Bagaimana ceritanya malah tidak tahu. Itu perasaan adalah perasaanmu, kecuali jika itu perasaanku maka wajar bila kau tidak tahu.”
Masalahnya aku benar-benar tidak tahu.
“Nak, perasaan suka di usiamu itu sederhana. Cukup, yakin atau tinggalkan. Tidak bisa ragu-ragu begitu.”
Masalah yang kedua, aku belum tahu bagaimana perasaan Zahwa padaku, aku takut buru-buru menentukan yakin dan bertahan tapi ternyata malah ia meninggalkan.
Begitu juga ketika aku memutuskan untuk pergi, aku takut apabila sejatinya perasaanku bersambut dan kelak ia kembali.
Bagai bisa membaca pikiran, Pak Bah tak perlu menunggu jawabanku. “Kenapa kau tidak menanyakan padanya? Aku tahu perasaanmu itu bukanlah perasaan yang baru. Ia sudah mendekam lama di sana, dan kau biarkan ia tumbuh tanpa pernah memangkasnya.”
Benar! Sudah lama sekali, aku saja yang tidak jujur mengakui, kukira ini hanya perasaan biasa, rasa wajar karena terbiasa bersama.
Tapi setelah sekian lama, ia menjadi berbeda ada ego diri yang membuncah ketika harapan tidak terpenuhi. Ada kecewa yang berbicara ketika sebuah rasa harus berhenti begitu saja.
“Aku tidak punya kesempatan, Pak,” singkatku.
"Benar tidak punya?" tanyanya, "Atau tidak merencanakan?"


 littlemagic
littlemagic




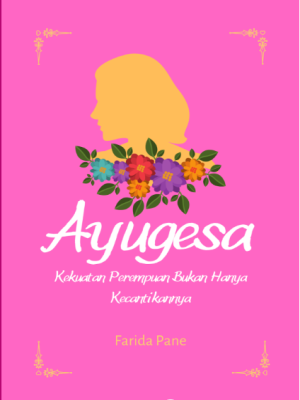



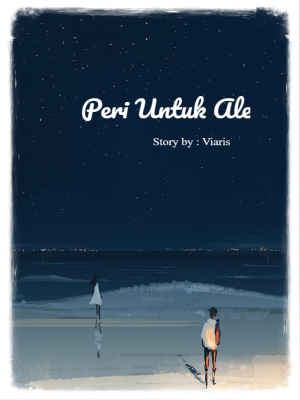



I wish I can meet Nadif & Pak Bah in real life :'
Comment on chapter Epilog